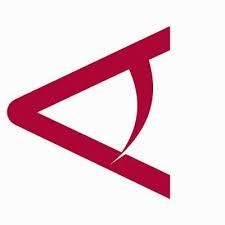Jakarta (ANTARA) - Indonesia hidup di atas lanskap risiko yang terus mendera. Tsunami di sepanjang zona megathrust, hujan ekstrem yang memicu banjir bandang, longsor di wilayah pegunungan, hingga penurunan muka tanah di kota-kota pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut bencana di Sumatera akhir tahun 2025 yang meski menelan korban jauh lebih kecil dari tsunami Aceh 2004, kerusakan tata-ruang wilayahnya yang terdampak jauh lebih luas dan lebih besar.
Ambil contoh lokasi di Sibolga. Banjir bandang yang terjadi di Sibolga dan meluluhlantakkan hingga 1.666 titik infrastruktur, misalnya, pernah terjadi pula pada 25 Juli 1956. Semuanya bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ancaman-ancaman ini berulang, dengan ritme yang sering kali melampaui usia satu generasi manusia.
Banjir bandang di Sibolga yang kembali terjadi setelah hampir tujuh dekade menunjukkan bahwa bahaya alam sering kali memiliki ingatan yang lebih panjang daripada masyarakat yang mengalaminya. Ketika memori kolektif terputus, ruang hidup yang sama kembali dihuni dengan kerentanan yang nyaris serupa, dan sering kali oleh kelompok sosial yang sama.
Tidak hanya di Sibolga, tetapi juga kita bisa melihat di lokasi bekas bencana masa lalu: Aceh, Teluk Babi, Banyuwangi, untuk menyebut beberapa dalam kaitan tsunami.
Ironisnya, justru di situlah letak persoalannya. Ketika jarak waktu antar-bencana terlalu panjang, kesadaran kolektif perlahan memudar terbang. Generasi yang lahir setelah sebuah bencana besar tumbuh di ruang yang sama, tetapi tanpa pengalaman langsung, tanpa trauma, dan sering kali tanpa cerita. Risiko pun menjadi sesuatu yang “tidak hadir” dalam keseharian. Sampai kembali muncul dengan daya rusak yang sama, atau bahkan lebih besar.
Dalam literatur kebencanaan, Fekete (2019) menyebutnya sebagai kurva pelupaan (forgetting curve). Konsepsi kurva pelupaan bermula dari pendekatan psikologis oleh Ebbinghaus (1880 – 1885). Proses penurunan “daya-ingat” seiring dengan bertambahnya waktu.
Dalam konteks kebencanaan, forgetting curve mengingatkan bahwa secara kapasitas ketangguhan kolektif bisa dibangun bersama melalui proses pelatihan dan mengembangkan katalog peristiwa ekstrim. Ingatan sosial kebencanaan membutuhkan “maintenance penguatan”, persis sama dengan infrastruktur fisik.
Sejarah kebencanaan Indonesia juga menunjukkan sisi lain yang membuka peluang dan harapan dari sisi ingatan kolektif. Beberapa komunitas yang selamat dari peristiwa bencana justru bukan karena teknologi modern, tetapi karena ingatan yang dijaga lintas generasi.
Ingatan yang menyelamatkan
Ketika tsunami Aceh 2004 melanda, dunia terkejut oleh besarnya korban jiwa.
Tetapi di Pulau Simeulue, cerita yang berbeda terjadi. Ribuan orang selamat karena satu kata yang diwariskan turun-temurun: Smong. Sebuah pengetahuan lokal yang sederhana; jika gempa besar terjadi dan laut surut, segera lari ke tempat tinggi.
Pengetahuan itu tidak lahir dari buku teks atau simulasi modern, melainkan dari pengalaman tsunami masa lalu yang disimpan dalam cerita, lagu, dan nasihat orang tua kepada anak-anaknya.
Cerita serupa juga ditemukan di Mentawai dengan Simouk Matau (“ke bukit”), di Bima dengan Soromandi Ngalu (“bergerak ke kawasan hutan”) saat banjir bandang, serta dalam struktur sosial dan arsitektur tradisional seperti Tongkonan Layuk di Sulawesi yang terbukti lebih aman terhadap gempa dan likuefaksi.
Semua contoh ini memiliki satu kesamaan penting: ketangguhan tidak dibangun secara instan, melainkan diwariskan. Ia hidup dalam ingatan kolektif, dipelihara melalui praktik sosial, dan diperbarui dari generasi ke generasi.
Dalam literatur kebencanaan, ketangguhan sering dipahami sebagai kemampuan untuk pulih setelah bencana. Namun pengalaman komunitas penyintas di atas menunjukkan bahwa ketangguhan sejati justru bekerja sebelum bencana terjadi melalui pewarisan pengetahuan, nilai, dan respons yang telah teruji oleh waktu.
Inilah esensi ketangguhan antar-generasi. Ketangguhan bukan hanya atribut individu atau hasil intervensi teknis, melainkan proses sosial jangka panjang yang memungkinkan generasi muda “meminjam pengalaman” dari generasi sebelumnya. Dalam konteks ini, orang tua, tetua adat, dan komunitas bukan sekadar penyintas masa lalu, tetapi penyangga dan penjaga memori risiko.
Tanpa proses pewarisan ini, masyarakat berisiko terjebak dalam risk normalization: hidup berdampingan dengan ancaman, tanpa kewaspadaan yang memadai. Adaptasi menjadi reaktif, bukan reflektif, apalagi transformatif yang menjangkau masa depan generasi yang datang kemudian. Ketangguhan menjadi rapuh, tidak tumbuh, dan meluruh.
Ketangguhan lokal
Konteks bencana pada hakikatnya bersifat sangat lokal. Ancaman yang dihadapi masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat lereng gunung, dataran banjir, atau kota yang mengalami penurunan muka tanah. Karena itu, ketangguhan tidak bisa dibangun melalui satu resep universal (one fits for all).
Justru di sinilah unit sosial terkecil: dusun, kampung adat, nagari, kelurahan, menjadi arena kunci. Di tingkat ini relasi antar-generasi berlangsung secara alami, pengetahuan lokal terjaga hidup, dan keputusan kritis saat bencana benar-benar dibuat, diterapkan, dan diuji.
Keberulangan bencana yang tidak diantisipasi secara lintas generasi juga berkontribusi pada terperangkapnya kelompok rentan dalam lingkaran kemiskinan. Masyarakat miskin sering kali tidak memiliki pilihan selain tinggal dan beraktivitas di ruang-ruang berisiko tinggi: bantaran sungai, pesisir rendah, lereng curam.
Setiap kejadian bencana tidak hanya menghancurkan aset fisik, tetapi juga memperlemah kapasitas ekonomi dan sosial lintas generasi (cascading impact). Tanpa mekanisme ketangguhan yang diwariskan, bencana menjadi faktor penguat kemiskinan struktural, bukan sekadar gangguan sementara.
Jika masyarakat pada tingkat paling rentan tetap siaga, sadar risiko, dan memiliki mekanisme pewarisan pengetahuan lintas generasi, maka ketangguhan nasional sesungguhnya sedang terbangun dari bawah. Ketangguhan nasional bukanlah entitas abstrak, melainkan interaksi terakumulasinya secara sosio-kultural ribuan komunitas lokal yang memahami ancaman di sekitarnya dan tahu bagaimana meresponsnya.
Mendukung, tidak menggantikan
Ketangguhan berbasis komunitas tidak dapat dibiarkan tumbuh secara sporadis. Ia memerlukan dukungan ekosistem yang melibatkan berbagai pelaku: akademisi (periset, peneliti, perekayasa), pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas itu sendiri, dalam kerangka penta-helix.
Peran pemangku kepentingan di luar komunitas bukan untuk menggantikan inisiatif lokal, melainkan untuk, antara lain dan tidak terbatas pada upaya: menyediakan kerangka panduan (pedoman, guidance) yang mudah dipahami, memfasilitasi pembelajaran lintas wilayah dan lintas generasi, serta (memastikan bahwa upaya lokal terhubung dengan sistem formal seperti pendidikan, perencanaan wilayah, dan peringatan dini.
Pengalaman negara-negara yang relatif tangguh seperti Jepang, Chili, dan Meksiko menunjukkan bahwa ketangguhan nasional yang kuat selalu bertumpu pada komunitas lokal yang sadar risiko, didukung oleh negara dan pengetahuan ilmiah (berbasis sains dan teknologi), serta tetap berakar pada konteks sosial-budayanya.
Membangun ketangguhan antar-generasi
Bagi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya, ketangguhan bukan soal teknologi canggih, melainkan soal pengetahuan yang tepat, kesiapsiagaan kolektif, dan solidaritas sosial yang diwariskan. Oleh karena itu, panduan di tingkat komunitas menjadi instrumen kunci untuk memutus reproduksi risiko sekaligus kerentanan ekonomi lintas generasi.
Untuk menjembatani refleksi konseptual dengan praktik nyata, ketangguhan antar-generasi dan resiliensi sosial di tingkat komunitas terkecil dapat dibangun melalui tiga langkah awal sederhana.
Pertama, mengenali ancaman lokal. Masyarakat perlu bersama-sama mengidentifikasi ancaman paling nyata di sekitarnya: tsunami, banjir, longsor, gempa, atau penurunan tanah, berdasarkan pengalaman, sejarah lokal, dan pengetahuan ilmiah yang tersedia.
Kedua, menghidupkan kembali memori risiko lintas generasi (institusionalisasi memori). Tutur cerita warga berumur tentang pengalaman masa lalu, penamaan tempat, dan praktik adat perlu diangkat kembali sebagai sumber pembelajaran bersama, sehingga risiko menjadi “hadir” dalam kesadaran generasi muda.
Ketiga, mengubah ingatan menjadi kesepakatan dan praktik kolektif. Pengetahuan dan memori tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kesepakatan komunitas: jalur evakuasi, titik aman, peran keluarga, latihan sederhana, serta integrasi dengan sekolah dan sistem peringatan dini.
Dengan dukungan penta-helix, tiga langkah ini memungkinkan masyarakat membangun ketangguhannya sendiri, sesuai dengan ancaman yang dihadapinya, tanpa kehilangan akar lokalnya.
Dalam era perubahan iklim dan meningkatnya ketidakpastian, ketangguhan tidak lagi cukup dipahami sebagai kemampuan “bangkit kembali lebih baik”. Ia perlu dimaknai sebagai kemampuan untuk terus belajar lintas generasi, beradaptasi lintas waktu, dan hidup berdampingan dengan risiko secara sadar dan bermartabat.
Jika ancaman alam bekerja dalam skala waktu geologis dan klimatologis, maka ketangguhan manusia harus bekerja dalam skala waktu sosio-kultural yang sama panjangnya. Local–indigenous knowledge yang terpelihara di Indonesia menunjukkan bahwa masa depan yang lebih aman sering justru berakar pada ingatan masa lalu yang dijaga dengan baik.
Ketangguhan antar-generasi, dengan demikian, bukan sekadar konsep akademik, tetapi warisan hidup, yang menentukan apakah generasi berikutnya akan kembali menjadi korban, atau justru menjadi generasi yang lebih siap.
Memutus mata rantai bencana dan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan pasca-bencana atau pembangunan fisik semata. Ia harus dimulai dengan memutus kurva pelupaan, yakni terputusnya ingatan, pengetahuan, dan kewaspadaan lintas generasi. Ketangguhan antar-generasi menjadi kunci, karena di sanalah pengalaman masa lalu diubah menjadi modal sosial untuk melindungi kehidupan dan penghidupan generasi yang akan datang.
*) Dr Andi E Sakya M Eng adalah Perekayasa Ahli Utama, Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, anggota CTIS
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut bencana di Sumatera akhir tahun 2025 yang meski menelan korban jauh lebih kecil dari tsunami Aceh 2004, kerusakan tata-ruang wilayahnya yang terdampak jauh lebih luas dan lebih besar.
Ambil contoh lokasi di Sibolga. Banjir bandang yang terjadi di Sibolga dan meluluhlantakkan hingga 1.666 titik infrastruktur, misalnya, pernah terjadi pula pada 25 Juli 1956. Semuanya bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ancaman-ancaman ini berulang, dengan ritme yang sering kali melampaui usia satu generasi manusia.
Banjir bandang di Sibolga yang kembali terjadi setelah hampir tujuh dekade menunjukkan bahwa bahaya alam sering kali memiliki ingatan yang lebih panjang daripada masyarakat yang mengalaminya. Ketika memori kolektif terputus, ruang hidup yang sama kembali dihuni dengan kerentanan yang nyaris serupa, dan sering kali oleh kelompok sosial yang sama.
Tidak hanya di Sibolga, tetapi juga kita bisa melihat di lokasi bekas bencana masa lalu: Aceh, Teluk Babi, Banyuwangi, untuk menyebut beberapa dalam kaitan tsunami.
Ironisnya, justru di situlah letak persoalannya. Ketika jarak waktu antar-bencana terlalu panjang, kesadaran kolektif perlahan memudar terbang. Generasi yang lahir setelah sebuah bencana besar tumbuh di ruang yang sama, tetapi tanpa pengalaman langsung, tanpa trauma, dan sering kali tanpa cerita. Risiko pun menjadi sesuatu yang “tidak hadir” dalam keseharian. Sampai kembali muncul dengan daya rusak yang sama, atau bahkan lebih besar.
Dalam literatur kebencanaan, Fekete (2019) menyebutnya sebagai kurva pelupaan (forgetting curve). Konsepsi kurva pelupaan bermula dari pendekatan psikologis oleh Ebbinghaus (1880 – 1885). Proses penurunan “daya-ingat” seiring dengan bertambahnya waktu.
Dalam konteks kebencanaan, forgetting curve mengingatkan bahwa secara kapasitas ketangguhan kolektif bisa dibangun bersama melalui proses pelatihan dan mengembangkan katalog peristiwa ekstrim. Ingatan sosial kebencanaan membutuhkan “maintenance penguatan”, persis sama dengan infrastruktur fisik.
Sejarah kebencanaan Indonesia juga menunjukkan sisi lain yang membuka peluang dan harapan dari sisi ingatan kolektif. Beberapa komunitas yang selamat dari peristiwa bencana justru bukan karena teknologi modern, tetapi karena ingatan yang dijaga lintas generasi.
Ingatan yang menyelamatkan
Ketika tsunami Aceh 2004 melanda, dunia terkejut oleh besarnya korban jiwa.
Tetapi di Pulau Simeulue, cerita yang berbeda terjadi. Ribuan orang selamat karena satu kata yang diwariskan turun-temurun: Smong. Sebuah pengetahuan lokal yang sederhana; jika gempa besar terjadi dan laut surut, segera lari ke tempat tinggi.
Pengetahuan itu tidak lahir dari buku teks atau simulasi modern, melainkan dari pengalaman tsunami masa lalu yang disimpan dalam cerita, lagu, dan nasihat orang tua kepada anak-anaknya.
Cerita serupa juga ditemukan di Mentawai dengan Simouk Matau (“ke bukit”), di Bima dengan Soromandi Ngalu (“bergerak ke kawasan hutan”) saat banjir bandang, serta dalam struktur sosial dan arsitektur tradisional seperti Tongkonan Layuk di Sulawesi yang terbukti lebih aman terhadap gempa dan likuefaksi.
Semua contoh ini memiliki satu kesamaan penting: ketangguhan tidak dibangun secara instan, melainkan diwariskan. Ia hidup dalam ingatan kolektif, dipelihara melalui praktik sosial, dan diperbarui dari generasi ke generasi.
Dalam literatur kebencanaan, ketangguhan sering dipahami sebagai kemampuan untuk pulih setelah bencana. Namun pengalaman komunitas penyintas di atas menunjukkan bahwa ketangguhan sejati justru bekerja sebelum bencana terjadi melalui pewarisan pengetahuan, nilai, dan respons yang telah teruji oleh waktu.
Inilah esensi ketangguhan antar-generasi. Ketangguhan bukan hanya atribut individu atau hasil intervensi teknis, melainkan proses sosial jangka panjang yang memungkinkan generasi muda “meminjam pengalaman” dari generasi sebelumnya. Dalam konteks ini, orang tua, tetua adat, dan komunitas bukan sekadar penyintas masa lalu, tetapi penyangga dan penjaga memori risiko.
Tanpa proses pewarisan ini, masyarakat berisiko terjebak dalam risk normalization: hidup berdampingan dengan ancaman, tanpa kewaspadaan yang memadai. Adaptasi menjadi reaktif, bukan reflektif, apalagi transformatif yang menjangkau masa depan generasi yang datang kemudian. Ketangguhan menjadi rapuh, tidak tumbuh, dan meluruh.
Ketangguhan lokal
Konteks bencana pada hakikatnya bersifat sangat lokal. Ancaman yang dihadapi masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat lereng gunung, dataran banjir, atau kota yang mengalami penurunan muka tanah. Karena itu, ketangguhan tidak bisa dibangun melalui satu resep universal (one fits for all).
Justru di sinilah unit sosial terkecil: dusun, kampung adat, nagari, kelurahan, menjadi arena kunci. Di tingkat ini relasi antar-generasi berlangsung secara alami, pengetahuan lokal terjaga hidup, dan keputusan kritis saat bencana benar-benar dibuat, diterapkan, dan diuji.
Keberulangan bencana yang tidak diantisipasi secara lintas generasi juga berkontribusi pada terperangkapnya kelompok rentan dalam lingkaran kemiskinan. Masyarakat miskin sering kali tidak memiliki pilihan selain tinggal dan beraktivitas di ruang-ruang berisiko tinggi: bantaran sungai, pesisir rendah, lereng curam.
Setiap kejadian bencana tidak hanya menghancurkan aset fisik, tetapi juga memperlemah kapasitas ekonomi dan sosial lintas generasi (cascading impact). Tanpa mekanisme ketangguhan yang diwariskan, bencana menjadi faktor penguat kemiskinan struktural, bukan sekadar gangguan sementara.
Jika masyarakat pada tingkat paling rentan tetap siaga, sadar risiko, dan memiliki mekanisme pewarisan pengetahuan lintas generasi, maka ketangguhan nasional sesungguhnya sedang terbangun dari bawah. Ketangguhan nasional bukanlah entitas abstrak, melainkan interaksi terakumulasinya secara sosio-kultural ribuan komunitas lokal yang memahami ancaman di sekitarnya dan tahu bagaimana meresponsnya.
Mendukung, tidak menggantikan
Ketangguhan berbasis komunitas tidak dapat dibiarkan tumbuh secara sporadis. Ia memerlukan dukungan ekosistem yang melibatkan berbagai pelaku: akademisi (periset, peneliti, perekayasa), pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas itu sendiri, dalam kerangka penta-helix.
Peran pemangku kepentingan di luar komunitas bukan untuk menggantikan inisiatif lokal, melainkan untuk, antara lain dan tidak terbatas pada upaya: menyediakan kerangka panduan (pedoman, guidance) yang mudah dipahami, memfasilitasi pembelajaran lintas wilayah dan lintas generasi, serta (memastikan bahwa upaya lokal terhubung dengan sistem formal seperti pendidikan, perencanaan wilayah, dan peringatan dini.
Pengalaman negara-negara yang relatif tangguh seperti Jepang, Chili, dan Meksiko menunjukkan bahwa ketangguhan nasional yang kuat selalu bertumpu pada komunitas lokal yang sadar risiko, didukung oleh negara dan pengetahuan ilmiah (berbasis sains dan teknologi), serta tetap berakar pada konteks sosial-budayanya.
Membangun ketangguhan antar-generasi
Bagi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya, ketangguhan bukan soal teknologi canggih, melainkan soal pengetahuan yang tepat, kesiapsiagaan kolektif, dan solidaritas sosial yang diwariskan. Oleh karena itu, panduan di tingkat komunitas menjadi instrumen kunci untuk memutus reproduksi risiko sekaligus kerentanan ekonomi lintas generasi.
Untuk menjembatani refleksi konseptual dengan praktik nyata, ketangguhan antar-generasi dan resiliensi sosial di tingkat komunitas terkecil dapat dibangun melalui tiga langkah awal sederhana.
Pertama, mengenali ancaman lokal. Masyarakat perlu bersama-sama mengidentifikasi ancaman paling nyata di sekitarnya: tsunami, banjir, longsor, gempa, atau penurunan tanah, berdasarkan pengalaman, sejarah lokal, dan pengetahuan ilmiah yang tersedia.
Kedua, menghidupkan kembali memori risiko lintas generasi (institusionalisasi memori). Tutur cerita warga berumur tentang pengalaman masa lalu, penamaan tempat, dan praktik adat perlu diangkat kembali sebagai sumber pembelajaran bersama, sehingga risiko menjadi “hadir” dalam kesadaran generasi muda.
Ketiga, mengubah ingatan menjadi kesepakatan dan praktik kolektif. Pengetahuan dan memori tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kesepakatan komunitas: jalur evakuasi, titik aman, peran keluarga, latihan sederhana, serta integrasi dengan sekolah dan sistem peringatan dini.
Dengan dukungan penta-helix, tiga langkah ini memungkinkan masyarakat membangun ketangguhannya sendiri, sesuai dengan ancaman yang dihadapinya, tanpa kehilangan akar lokalnya.
Dalam era perubahan iklim dan meningkatnya ketidakpastian, ketangguhan tidak lagi cukup dipahami sebagai kemampuan “bangkit kembali lebih baik”. Ia perlu dimaknai sebagai kemampuan untuk terus belajar lintas generasi, beradaptasi lintas waktu, dan hidup berdampingan dengan risiko secara sadar dan bermartabat.
Jika ancaman alam bekerja dalam skala waktu geologis dan klimatologis, maka ketangguhan manusia harus bekerja dalam skala waktu sosio-kultural yang sama panjangnya. Local–indigenous knowledge yang terpelihara di Indonesia menunjukkan bahwa masa depan yang lebih aman sering justru berakar pada ingatan masa lalu yang dijaga dengan baik.
Ketangguhan antar-generasi, dengan demikian, bukan sekadar konsep akademik, tetapi warisan hidup, yang menentukan apakah generasi berikutnya akan kembali menjadi korban, atau justru menjadi generasi yang lebih siap.
Memutus mata rantai bencana dan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan pasca-bencana atau pembangunan fisik semata. Ia harus dimulai dengan memutus kurva pelupaan, yakni terputusnya ingatan, pengetahuan, dan kewaspadaan lintas generasi. Ketangguhan antar-generasi menjadi kunci, karena di sanalah pengalaman masa lalu diubah menjadi modal sosial untuk melindungi kehidupan dan penghidupan generasi yang akan datang.
*) Dr Andi E Sakya M Eng adalah Perekayasa Ahli Utama, Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, anggota CTIS