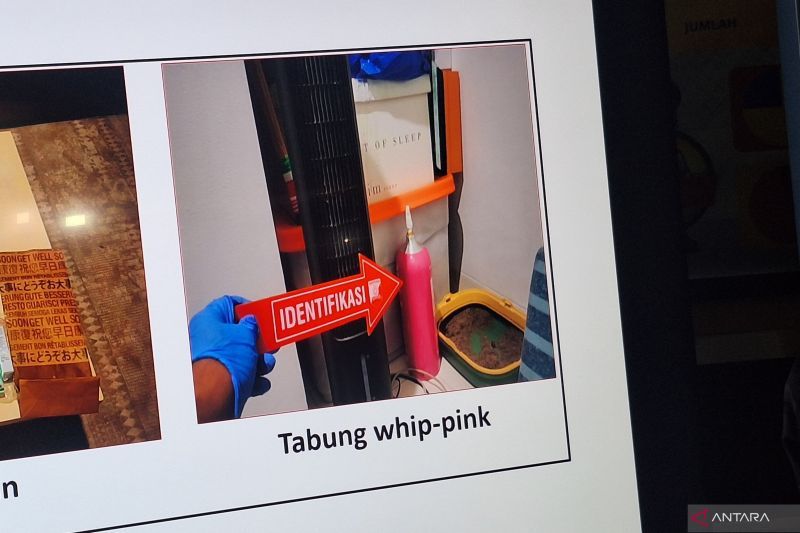Cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi dan musim yang makin tidak menentu menjadi pertanda krisis iklim. Ancamannya pun sudah bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk deretan bencana yang melanda Tanah Air.
Berdasarkan publikasi BPS berjudul Analisis Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Perubahan Iklim di Indonesia 2024 dan 2025, terungkap bahwa 99,34 persen bencana di Indonesia terkait dengan iklim. Salah satunya adalah banjir yang mencapai 1.420 kejadian pada tahun 2024 lalu.
Mengutip situs resmi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), perubahan iklim merupakan satu dari Triple Planetary Crisis yang sedang dihadapi umat manusia. Perubahan iklim ini dipicu emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari aktivitas manusia.
Laporan BPS yang dirilis pada 31 Desember 2025 lalu itu juga membeberkan data jumlah emisi GRK di Indonesia. Sayangnya, tidak ada data 2024 atau bahkan 2025. Datanya yang disajikan terbatas pada data GRK 2005 hingga 2023. Satuan yang dipakai adalah Gigagram Karbon Dioksida Ekuivalen (GG CO2e).
Supaya lebih mudah, 1 Gg CO2e itu setara dengan 1.000 ton emisi karbon dioksida. Jadi, jika dalam laporan BPS tercatat angka jutaan Gg, bisa dibayangkan betapa raksasanya beban emisi yang harus diserap oleh bumi kita.
BPS mencatat bahwa pada 2023, jumlah emisi ERK di Tanah Air mencapai 1,36 juta Gg CO2e. Artinya, jumlah itu setara dengan 1,36 miliar ton karbon dioksida.
Pada 2015, jumlah emisi GRK di Indonesia mencapai titik tertinggi yaitu 2,1 juta Gg CO2e. Menurut catatan BPS, hal tersebut dipicu oleh kebakaran gambut yang menyumbang emisi 410 ribu GG CO2e.
Bila dibuat lebih rinci, jumlah emisi GRK di Indonesia pada 2023 didominasi oleh sektor energi. Ada pula dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Suhu Bumi Sudah Lampaui 1,5° CelsiusErma Yulihastin, Peneliti Ahli Utama Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebut krisis iklim saat ini sudah berada di level gawat. Suhu bumi kini berfluktuasi di batas 1,5° Celsius, sedangkan batas maksimalnya menurut Persetujuan Paris (Paris Agreement) adalah 2° Celsius.
Persetujuan Paris sendiri merupakan traktat internasional terkait mitigasi, adaptasi dan keuangan perubahan iklim yang harus disetujui semua negara. Traktat tersebut mengajak seluruh negara untuk berkomitmen menekan laju suhu bumi di bawah 2° Celsius hingga 2060.
"Ilmuwan itu memproyeksi [suhu bumi] 2029 baru mencapai 1,5° Celsius. Nyatanya [suhu bumi] kita itu sudah melampaui 1,5° Celsius di tahun-tahun ini, bahkan sudah dari tahun 2023," tutur Erma saat dihubungi kumparan pada Senin (26/1).
Menurut Erma, bumi memanas lebih cepat dari yang diperkirakan. Semakin tinggi suhu bumi akan berdampak terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri, kata Erma, bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke titik semula.
Berdasarkan penjelasan Erma, konsekuensi pertama dari perubahan iklim yang bisa kita rasakan adalah intensitas badai yang meningkat secara signifikan. Kemudian dilanjut dengan kerusakan terumbu karang dan es kutub yang mulai mencair.
Selanjutnya, kata dia, musim semakin tidak menentu dan berimbas buruk terhadap pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim berpengaruh terhadap air, makanan, ekosistem, dan cuaca ekstrem.
Erma mengibaratkan iklim bumi saat ini seperti bola di puncak gunung yang jika tersenggol sedikit akan runtuh. Iklim secara sains terdiri dari bumi, darat, udara, dan laut yang harus dijaga. Penekanan laju suhu bumi bertujuan agar iklim yang sudah diujung tanduk ini tidak semakin kacau.
"Jangan sampai [suhu bumi] lebih dari 2° Celsius, itu nanti akan lebih bahaya lagi [dampaknya] bisa dua kali lipat kondisinya," tegas Erma.
Merujuk pada Perjanjian Paris, kata Erma, bentuk mitigasi yang harus dilakukan untuk menekan laju kenaikan suhu bumi adalah dengan Net Zero Emission. Net Zero Emission berarti selisih karbondioksida (CO2) yang dikeluarkan dengan yang diserap adalah 0 (nol).
Menurutnya, Indonesia sebetulnya sudah mulai menyusun strategi pengurangan emisi karbon. Sayangnya, lanjut Erma, hal tersebut masih belum dilaksanakan secara agresif khususnya di bidang penggunaan energi fosil.
"Secara kebijakan kita masih belum ada pembatasan kendaraan bermotor," ungkap Erma.
Meski begitu, Erma menyebut ada upaya lain yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu membuka ruang terbuka hijau. Sektor-sektor yang dianggap menjadi penyumbang emisi karbon terbesar, kata dia, ditekan untuk menanam pohon dengan jumlah target tertentu sebagai bentuk tanggung jawab.
Cara tersebut selaras dengan upaya mengimbangi emisi karbon yang dihasilkan dengan yang diserap dari penggunaan bahan bakar fosil, yaitu dengan memperbanyak hutan. Pepohonan yang terdapat di hutan dapat menyerap CO2 yang menjadi emisi GRK terbanyak di dunia.
"Setiap jenis pohon itu punya hitungan karbon masing-masing, seberapa efektif pohon tersebut menyerap karbon. Itu penting, jadi jangan dianggap semua pohon itu sama," kata Erma.
KLHK Evaluasi Tata RuangKementerian Lingkungan Hidup (KLHK) saat ini tengah mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang di sejumlah provinsi yang dinilai memiliki lanskap rentan. Menurut catatan KLHK, rencana tata ruang di sejumlah daerah sudah tidak lagi memadai untuk menahan dampak bencana yang semakin parah akibat perubahan iklim.
“Kemudian yang terakhir, kami juga sedang melakukan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis tata ruang pada tiga provinsi. Sebenarnya kita lakukan pada empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Bali,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (26/1).
“Sangat ringkih lanskapnya memerlukan kita bertindak cepat untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kajian lingkungan hidup strategis,” tambahnya.
KLH menargetkan hasil analisis KLHS tersebut rampung dalam tiga bulan ke depan dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayahnya, khususnya di daerah dengan tingkat kerentanan lanskap tinggi.
“Karena Indonesia berada di negara tropis, tentu merupakan suatu negara yang sangat rentan dengan perubahan iklim, apalagi dengan bentuk lanskap kita yang merupakan lanskap kepulauan dan bukan kontinen, sehingga sangat mudah sekali mendapat tekanan dari perubahan iklim, baik itu berupa hidrometeorologi maupun kenaikan permukaan air laut,” tutupnya.
Reporter: Safina Azzahra Rona Imani