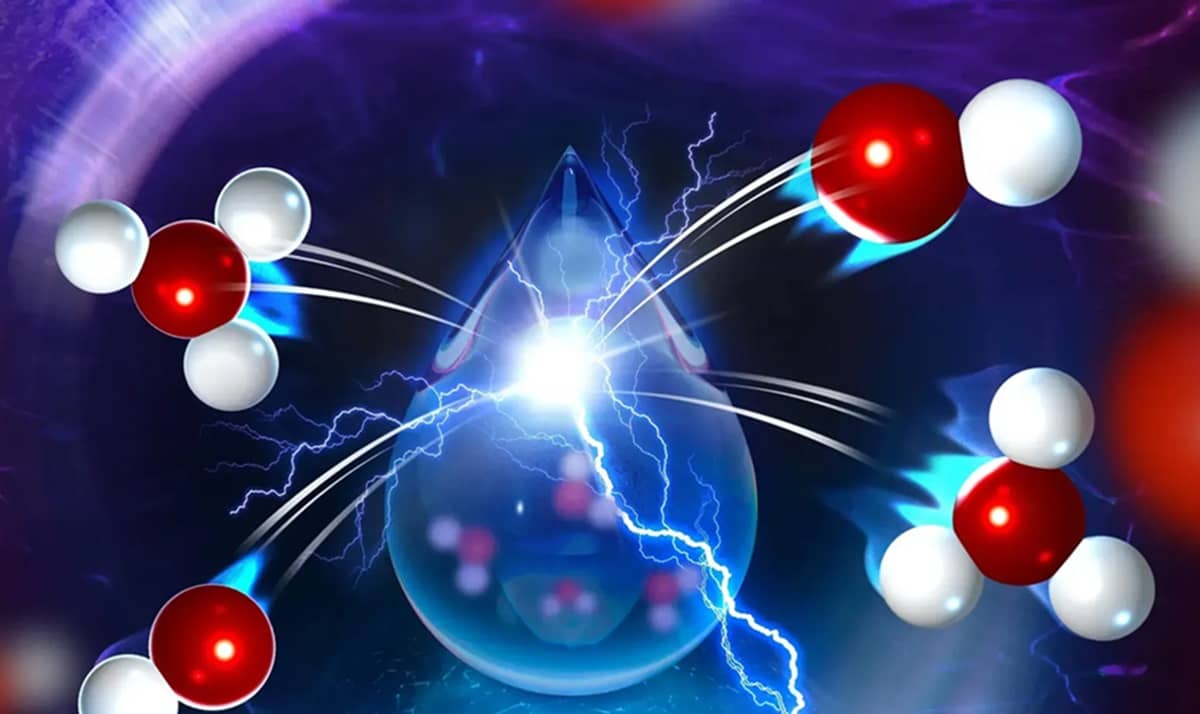Perdebatan polemik keputusan Presiden Prabowo yang membawa Indonesia berhimpun dalam meja perundingan Board of Peace (BoP) tidak bijak jika kita berhenti sekedar pada konklusi 'setuju atau menolak'. Karena Palestina khususnya Gaza, serta Timur Tengah secara keseluruhan, adalah ruang kajian yang mengandung banyak kompleksitas untuk sekedar dibaca dengan sudut pandang moral yang tunggal.
Ketimbang kita bersepakat atau menolak, lebih baik putusan diplomasi ini kita uji, namun sebagai sebuah tindakan, keberanian Indonesia hadir, menggambarkan kemampuan Indonesia membaca medan konflik, dan mengembangkan aneka kemungkinan-kemungkinan menjaga stabilitas perdamaian, Khususnya perdamaian di timur tengah yang penuh lapisan kuasa, sejarah kolonial, dan perang proxy global.
Secara historis, suka atau tidak suka, Timur Tengah bukan sekadar kawasan konflik antarnegara, melainkan sebuah proxy, arena persilangan aneka kepentingan global. Dan percaya atau tidak, hampir tidak ditemukan konflik di kawasan ini yang murni bersifat lokal.
Palestina, Israel, Suriah, Yaman, Lebanon, UEA hingga Irak selalu melibatkan proxy actors yang ikut sponsori negara-negara besar, aliansi regional, milisi ideologis, hingga tentu ada yang menargetkan sumberdaya ekonomi dan energi sebagai salah satu kepentingan.
Dalam kondisi kompleks ini, perlu difahami konflik kadang tidak benar-benar ingin diakhiri, bisa jadi yang terjadi adalah dikelola, dibekukan, atau distabilkan. Maka di tengah konflik Panjang dengan aneka resolusi yang telah diupayakan selama ini (PBB, Pertemuan Regional, sidang-sidang Panjang), yang telah diupayakan namun tidak mencapai stabilitas.
Kenapa tidak kita apresiasi upaya baru? Meski upaya itu belum bisa kita prediksi ke depan, namun dengan adanya gagasan rekonstruksi Gaza contohnya, kenapa tidak dilihat upaya ini sebagai tindakan yang progresif melampaui forum diskusi tapi forum aksi?
Selain faktor geopolitik global, geopolitik dan geostrategi Kawasan Timur Tengah, kita tahu bersama memiliki dimensi yang berbasis kuatnya identitas suku, sektarianisme, dan ego politik yang berakar panjang.
Loyalitas tidak selalu untuk membangun negara-bangsa modern, tetapi pada garis etnis, agama, mazhab dalam agama, dan ingatan kolektif yang saling bertabrakan, dimana masa lalu kadang belum dilupakan, seperti di Prancis meninggalkan dendam masa lalu, kemudian membangun tatanan baru, di timur tengah Masa lalu kadang jadi alat membunuh masa depan.
Karena itu, konflik di kawasan ini sering berhenti, karena sulit diselesaikan sekedar aktor internal mereka. Di sini mediasi pihak luar menjadi keharusan, namun dengan konflik berkepanjangan ini, mediator diperlukan dengan satu syarat penting: mediator tersebut harus memiliki legitimasi moral dan ketulusan politik, di sini kita bisa memaksa Indonesia, menuliskan lembar-lembar komitmen agar tertulis di BoP tanpa tedeng aling aling agar semua memiliki sikap tujuan untuk penciptaan perdamaian, jika melenceng ya bubar.
Di titik inilah kehadiran Indonesia di BoP dapat dibaca sebagai peluang sekaligus risiko. Peluang, karena Indonesia bukan kekuatan kolonial, tidak memiliki beban sejarah penjajahan di Timur Tengah, dan selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Dalam teori resolusi konflik, aktor semacam ini sering dipandang sebagai honest broker, pihak luar yang relatif dapat dipercaya oleh berbagai kubu. Namun, risiko muncul ketika forum mediasi itu sendiri bermasalah secara struktural.
Membaca Board of Peace dengan Kacamata Edward SaidDari perspektif pemikiran Edward Said, khususnya gagasan dia tentang Orientalisme, wacana perdamaian internasional kerap tidak netral. Barat melalui bahasa, institusi, dan narasi memproduksi pengetahuan tentang Timur sebagai wilayah yang "chaotic", "irasional", sehingga membutuhkan pengelolaan dari luar.
Kelirunya dalam kerangka ini, konflik Palestina-Israel sering framing sekedar konflik dua pihak yang setara, dan melupakan relasi kolonial antara penjajah dan yang dijajah, relasi ini bukan untuk menafikan dinamika sejarah bahwa ada upaya penaklukan dan lain-lain, tapi fakta empiris penguasaan wilayah dan upaya genosida.
Kritik ini memiliki relevansi ketika kita sedikit menyoroti Board of Peace.
Yang bahkan tidak melibatkan Palestina secara partisipatif dalam proses awalnya. Meminjam logika Said, ini sebagai bentuk produksi wacana yang mengaburkan ketimpangan struktural, sekaligus menggeser isu dari keadilan dan dekolonisasi menjadi sekadar stabilitas dan manajemen konflik.
Namun ketimbang menyoroti BoP sebagai proyek teknokratis, dan juga membela Palestina sekaligus menihilkan Israel bukanya kita akan mengulangi kegagalan-kegagalan yang pernah diupayakan, maka rekonstruksi, stabilisasi, keamanan tanpa menyentuh akar penjajahan memang harus terus digaungkan dengan tentu pertama mengadili Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan.
Tapi untuk jangka Panjang pemisahan wilayah, mengatur yuridiksi wilayah Israel dan Palestina adalah hal krusial, lalu untuk lebih progresif wajib bertanggung jawab membangun lagi daerah tersebut dan terakhir mengarahkan supremasi hukum yang kuat disana, setidaknya itu alur konstruktif.
Menimbang Teori Hegemoni dan Jalan Tengah yang BersyaratSebagai sebuah upaya melahirkan aneka kemungkinan-kemungkinan sudah kita apresiasi Tindakan Presiden Prabowo, tapi perlu juga kita ingatkan kembali, karena dalam teori hegemoni Antonio Gramsci. Hegemoni bekerja secara smooth karena tidak muncul dengan paksaan, melainkan melalui pembentukan consensus, yang dianggap masuk akal, realistis, dan "normal" oleh komunitas internasional.
Dalam konteks BoP, narasi tentang perdamaian, stabilitas, dan rekonstruksi pasca konflik dapat berfungsi sebagai common sense baru, yang secara halus menggeser tuntutan keadilan substantif Palestina.
Board of Peace, dengan strukturnya yang eksklusif, memiliki potensi berubah menjadi instrumen konsensus global versi dominasi aktor dominan. Yang berbahaya perdamaian dipresentasikan sebagai tujuan universal di atas kertas, tetapi definisinya ditentukan oleh kekuatan besar di lapangan.
Berbahayanya jika diarahkan sebagai alat legitimasi, dimana publik internasional diarahkan menerima stabilitas tanpa kemerdekaan, sebagai sesuatu yang di cap "lebih realistis".
Di sinilah dilema Indonesia harus dapat memutuskan. Agar Partisipasi di BoP tidak diarahkan ke dalam konsensus hegemonik yang justru menormalisasi ketimpangan struktural Palestina.
Maka di sinilah Indonesia menjadi penting, karena menanggung konsekuensi besar. Terlibat di arena realitas politik global, dan tentu ketimbang harus absen, Indonesia terlibat menunjukkan Indonesia sebagai bangsa besar tidak kehilangan ruang pengaruh.
Bayangkan jika Indonesia tidak terlibat, keputusan-keputusan besar tentang Gaza dan Palestina tetap akan diambil, namun tanpa suara dari Indonesia, negara yang secara historis komitmen dan konsisten membela Palestina.
Diplomasi kita haruslah berdiri di jalan tengah, keterlibatan Indonesia di BoP harus bersifat bersyarat. Keaktifan kita adalah secara kritis seperti mazhab politik luar negeri yang bebas aktif. Di mana kita hadir tetapi tidak larut dan penuh kewaspadaan. Terlibat, tetapi tidak tunduk dan penuh kepekaan.
Indonesia harus memaksimalkan forum BoP untuk terus menekan isu krusial khususnya penghentian pendudukan, keadilan bagi korban, dan pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina. Dan saya sepakat, Indonesia harus berani menjadi disturbing voice di dalam forum, bukan sekadar consensus taker.
Karena dukungan kita pada Board of Peace adalah dukungan bersyarat, maka jika forum ini bertransformasi sekadar menjadi alat pengelolaan konflik tanpa keadilan atau bahkan amit-amit menjadi legitimasi baru bagi penindasan, maka konsistensi politik luar negeri bebas aktif kita diperlukan untuk bersikap korektif. Termasuk, jika harus mengambil jarak atau keluar dari forum tersebut.
Dalam konteks Timur Tengah yang sudah kita bahas di awal sebagai kawasan yang sarat ego, proxy, dan luka sejarah, di mana perdamaian sejati di sana, terkadang tidak lahir dari niat baik semata. Ia membutuhkan mediator yang tidak hanya kuat, tetapi juga tulus dan adil.
Di sinilah tantangan terbesar Indonesia: membuktikan bahwa kehadirannya di Board of Peace semata sebagai alat untuk memperbesar peluang keadilan bagi Palestina, meski jalan menuju ke sana penuh risiko dan jebakan-jebakan. Karena bagi kita bangsa Indonesia, membela Palestina bukan soal simbol kehadiran di forum global, tetapi upaya kita memastikan, diplomasi Indonesia tidak kehilangan Nurani sebagai sebuah bangsa Besar.
Ikrama Masloman. Direktur Sintesa Strategi Indonesia (SSI) Alumnus Paramadina Graduate School of Communication (PGSC).
(rdp/tor)