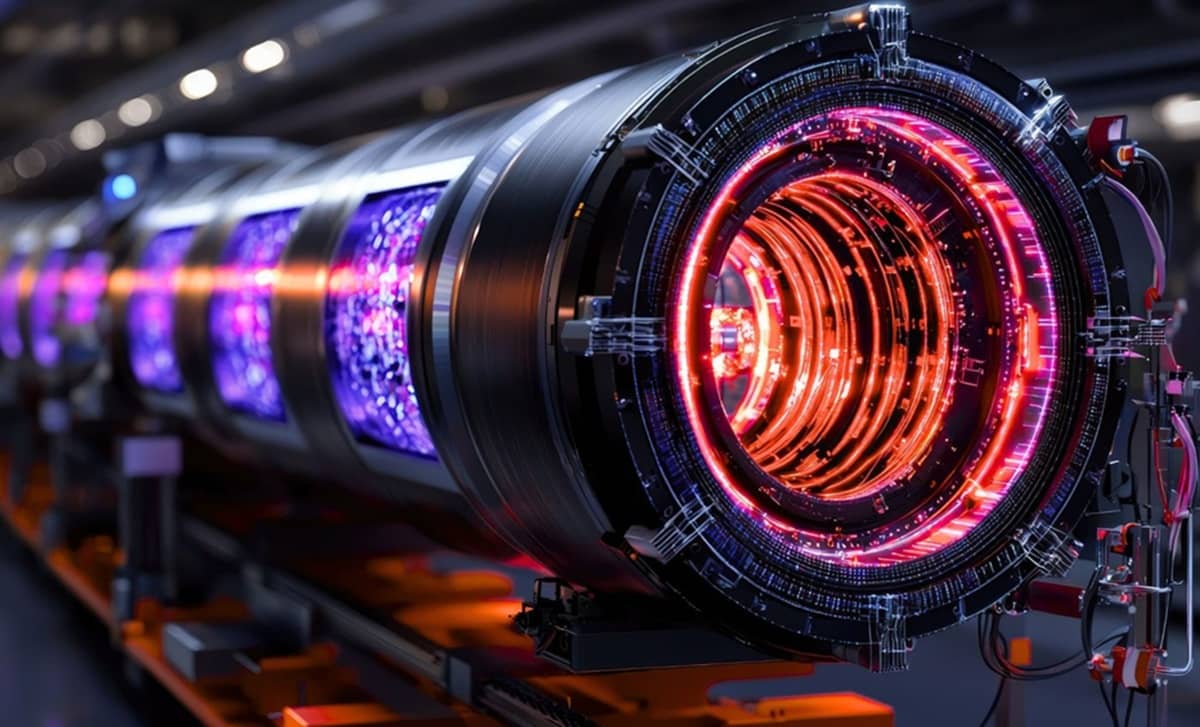Hujan lebat turun sejak Sabtu (31/1/2026) dini hari mengguyur kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menjelang pagi, hujan mereda, menyisakan gerimis ringan yang mengiringi kedatangan ribuan warga Nahdliyin untuk memperingati Hari Ulang Tahun atau Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan.
Di dalam Istora Senayan, ribuan hadirin memadati tribun dan lantai arena. Barisan kursi terisi rapat oleh warga Nahdliyin dari berbagai daerah, didominasi busana putih dan hijau, warna yang sejak lama lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Di sisi panggung, bendera Merah Putih dan bendera NU berjajar berdampingan, menegaskan irisan kuat antara identitas keagamaan dan kebangsaan yang menjadi ciri NU sejak awal.
Namun, peringatan satu abad NU itu berlangsung bukan dalam situasi yang sepenuhnya tenang. Sejak akhir November 2025, dinamika internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencuat ke publik. Meskipun sudah disepakati islah pada akhir Desember lalu, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf tidak tampak hadir di perayaan Harlah ke-100 NU.
“Setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi, dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya, hari ini kita rayakan, kita peringati Harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu,” ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat memberikan pidato harlah.
NU harus dijaga martabatnya, jangan sampai keterlibatan politik merusak integritas dan wibawa organisasi yang selama ini menjadi panutan ilmu dan moral bagi masyarakat.
Pernyataan itu membawa ingatan kembali ke awal kelahiran NU, satu abad silam. Nahdlatul Ulama berdiri pada 31 Januari 1926, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah, di Surabaya. Organisasi ini lahir dari kegelisahan para ulama pesantren menghadapi perubahan sosial-keagamaan yang cepat pada awal abad ke-20. Kala itu, tradisi keislaman lokal berhadapan dengan arus purifikasi, modernisme, dan tekanan kolonialisme Belanda.
Di bawah kepemimpinan KH Hasyim Asy’ari, NU dirumuskan sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah, organisasi keagamaan sekaligus kemasyarakatan. Sejak awal, NU tidak dimaksudkan sebagai partai politik, melainkan sebagai wadah perjuangan umat yang bertumpu pada pesantren, jaringan kiai, dan ikatan kultural dengan masyarakat bawah. Pesantren menjadi pusat transmisi keilmuan, sementara kiai menjadi figur rujukan moral dalam kehidupan sosial.
Sejarah mencatat, Nahdlatul Ulama tidak pernah sepenuhnya berada di luar arus kebangsaan. Peran ulama NU dalam Resolusi Jihad 1945 menjadi salah satu penanda penting keterlibatan NU dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Fatwa tersebut bukan sekadar seruan keagamaan, melainkan legitimasi moral yang memberi dasar etik bagi perlawanan rakyat terhadap kolonialisme, sekaligus menegaskan posisi ulama sebagai penuntun nurani publik pada masa krisis bangsa.
Memasuki fase awal kemerdekaan, NU kemudian terlibat langsung dalam politik praktis. NU menjadi salah satu organisasi Islam pendiri Partai Masyumi pada 7 November 1945, dengan KH Hasyim Asy’ari didapuk sebagai Ketua Majelis Syuro. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Ketegangan politik internal, perbedaan orientasi kebijakan, serta kian termarginalkannya peran kiai dalam pengambilan keputusan mendorong NU keluar dari Masyumi pada April 1952.
NU lantas mendirikan partai politik sendiri pada tahun yang sama. Pilihan memasuki gelanggang politik praktis membawa NU semakin dekat dengan pusat kekuasaan. Namun, pengalaman itu juga membuka ruang ketegangan baru di dalam tubuh organisasi. Energi NU terserap ke dalam dinamika elektoral, persaingan elite, dan logika kekuasaan yang sering kali menjauhkan organisasi dari basis kulturalnya di pesantren dan masyarakat bawah. Sejumlah kiai pesantren mulai merasakan jarak antara NU sebagai organisasi politik dan NU sebagai jam’iyah keagamaan yang mereka rawat sehari-hari.
Situasi itu kian meruncing ketika pada 1973 Partai NU dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam buku Ikhtisar Sejarah NU 1344 H/1926 M karya Ishaq Zubaedi Raqib, fase ini digambarkan sebagai periode ketika NU tidak hanya kehilangan kemandirian politik, tetapi juga menghadapi pembatasan ruang gerak yang membuatnya semakin terikat pada kehendak negara. Hubungan antara ulama, politisi, dan kekuasaan negara menjadi kian rumit, sementara peran NU sebagai kekuatan moral masyarakat sipil melemah.
Pengalaman panjang hampir empat dekade berada dalam politik praktis itu akhirnya melahirkan refleksi mendalam di tubuh NU. Dalam buku Dinamika Sejarah NU dan Tantangannya Kini karya Muhammad Hafiun dan A Yusrianto, keterlibatan langsung NU dalam politik elektoral dinilai tidak sebanding dengan ongkos sosial dan moral yang harus ditanggung organisasi. NU justru kehilangan posisi strategisnya sebagai penengah etis dan penjaga akal sehat publik karena terjebak sebagai pemain dalam arena kekuasaan yang sama.
Refleksi historis itulah yang mengantarkan NU pada keputusan penting dalam Muktamar Situbondo 1984 untuk kembali ke khittah 1926. Keputusan tersebut bukan dimaksudkan sebagai penarikan diri dari urusan kebangsaan, melainkan sebagai koreksi arah perjuangan. NU menegaskan kembali dirinya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah, kekuatan keagamaan dan kemasyarakatan yang bekerja dari luar struktur kekuasaan, namun tetap kritis, peduli, dan berpengaruh dalam kehidupan bangsa.
Pada akhir Orde Baru hingga awal Reformasi, peran tersebut terlihat semakin menonjol. Jaringan pesantren, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial NU berkembang pesat, menjangkau kelompok masyarakat yang kerap luput dari layanan negara. NU hadir sebagai mediator sosial, penjaga kohesi di tengah konflik horizontal, sekaligus penyangga stabilitas sosial pada masa transisi politik yang rawan.
Namun, jarak NU dari politik praktis tidak serta-merta berarti absen dari kekuasaan. Sejumlah tokoh NU terlibat aktif dalam pemerintahan dan partai politik pascareformasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keterlibatan tersebut kerap dipahami sebagai bagian dari tradisi ijtihad kebangsaan NU, yakni ikut memengaruhi arah negara tanpa menjadikan organisasi sebagai kendaraan politik.
Dari pengalaman historis itulah NU membangun pandangan kebangsaannya. Bagi NU, kata Gus Yahya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan sekadar wadah kebangsaan. NKRI dipandang sebagai ruang strategis untuk menjaga cita-cita kemanusiaan sekaligus mendorong lahirnya peradaban yang lebih mulia.
Karena itu, ia mendorong seluruh kader NU menjaga komitmen terhadap NKRI sebagai energi moral dalam pengabdian di tengah masyarakat. Keteguhan orientasi dan kesatuan langkah, menurutnya, merupakan amanat sejarah yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Satu abad perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama, tidak pernah lekang, tidak pernah geser, tidak pernah berubah semangat dan idealismenya. Bahwa Nahdlatul Ulama berjuang dengan membangun kubu perjuangan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Gus Yahya.
Memasuki dua dekade terakhir, tantangan yang dihadapi NU kian kompleks. Menguatnya oligarki politik dan ekonomi, logika transaksional dalam demokrasi elektoral, serta penetrasi kepentingan pasar ke ruang-ruang keagamaan menghadirkan dilema baru bagi NU. Di sejumlah momentum politik, NU diuji oleh tarikan politisasi kiai, komodifikasi otoritas agama, dan godaan kedekatan struktural dengan penguasa.
Tantangan itu bertambah ketika pemerintah memberikan hak pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan. Bagi sebagian kalangan di NU, kebijakan ini dipandang sebagai kesempatan memperkuat kemandirian ekonomi umat. Namun, bagi kalangan lain, langkah tersebut memunculkan kekhawatiran serius tentang risiko konflik kepentingan serta beban ekologis yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap NU sebagai penjaga nilai.
Di tengah dinamika eksternal tersebut, NU juga menghadapi ujian internal. Menjelang peringatan satu abad pada Januari 2026, dinamika kepemimpinan di tingkat elite PBNU mencuat ke ruang publik. Situasi ini menegaskan kembali bahwa besarnya NU menuntut tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan jamaah di akar rumput.
Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Abdul Gaffar Karim, menilai rekam jejak seabad NU menunjukkan peran kebangsaan organisasi itu dalam menjaga Republik Indonesia. NU paling kuat meneguhkan NKRI sejak kembali ke khittah 1926 pada 1984 hingga awal Reformasi, ketika organisasi tampil sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mengedepankan moderasi, pluralisme, dan ijtihad kebangsaan.
Masa paling rentan terjadi saat NU terlibat dalam politik praktis. Periode ini berlangsung ketika NU menjadi partai politik 1952–1973, menjadi bagian dari PPP 1973–1984, maupun ketika patronase negara‑oligarki menguat dalam 10–15 tahun terakhir.
Namun menurut Gaffar, persoalan utama bukan jarak dari kekuasaan, melainkan kemerdekaan NU dari oligarki agar tetap berpihak pada rakyat. Sebab dalam sejarahnya, NU tidak bisa dan tidak pernah jauh dari kekuasaan.
“Kebutuhan NU memang bukan menjaga jarak dari kekuasaan, melainkan menjaga kemampuan untuk turut memengaruhi kekuasaan agar bisa berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Sehingga tantangannya bukan seberapa berjarak NU dari kekuasaan, melainkan seberapa independen NU terhadap oligarki yang mengendalikan kekuasaan politik,” kata Gaffar.
Lebih jauh, Gaffar menilai tantangan NU di abad kedua semakin kompleks. Dari sisi politik, bahaya terbesar muncul dari komersialisasi dan monetisasi otoritas kiai, termasuk praktik endorsement berbayar untuk politisi, serta potensi pesantren menjadi mesin suara. Narasi agama pun kerap dipakai untuk melegitimasi kekuasaan.
Ia menekankan bahwa NU tidak harus apolitis, tetapi yang paling penting adalah menegakkan etika politik yang tegas. Fokus organisasi perlu digeser dari dukungan personal ke agenda kebijakan yang nyata dan relevan bagi kebutuhan umat. Dengan demikian, NU akan terus relevan dalam menjalankan fungsinya mengawal martabat bangsa.
Di sisi lain, lanjutnya, tantangan baru muncul ketika pemerintah memberikan konsesi tambang kepada organisasi. Keterlibatan NU dalam sektor ini membawa risiko moral dan sosial. Konflik kepentingan, erosi wibawa organisasi, polarisasi di akar rumput, serta dampak ekologis menjadi potensi masalah serius.
"Saya paham ada kebutuhan riil yang membuat urusan tambang ini jadi terasa perlu diambil. Jika itu tetap dilakukan, harus ada skema pengelolaan dan pengawasan yang jelas dan transparan," kata Gaffar.
Bahkan dalam beberapa bulan terakhir menjelang usia satu abad, NU tampak sibuk menangani dinamika internal. Fase ini, menurut Gaffar, menjadi pelajaran penting bahwa organisasi sebesar NU membutuhkan tata kelola modern, bukan lagi personalisasi. NU perlu prosedur standar (SOP) untuk keputusan strategis, keterbukaan saat ada konflik kepentingan, serta kaderisasi berbasis merit system.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan data pelayanan yang modern, mulai dari akses sekolah, klinik, hingga jaring pengaman sosial, agar bisa diakses publik. NU juga sebaiknya tidak terlalu terjebak pada perdebatan internal yang bertele-tele, melainkan fokus pada layanan umat dan arah kebangsaan.
Satu abad telah dilalui, dan kini NU menapaki abad kedua dengan tantangan yang tak mudah. Setelah menghadapi berbagai dinamika internal dan eksternal, organisasi perlu kembali meneguhkan fokus pada tujuan besarnya untuk mengawal NKRI.
“Kuncinya adalah memastikan kesejahteraan umat dengan sebaik-baiknya, dan meminimalisir konflik elit agar energi NU tidak habis untuk merekonsiliasi pertikaian yang berulang-ulang,” ujar Gaffar.
Cendekiawan Komaruddin Hidayat menilai, NU tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai pilar masyarakat sipil dan penjaga kohesi sosial. Peran ini membuat NU strategis bagi demokrasi Indonesia karena mampu mendukung negara menjalankan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi pengawas moral bagi praktik kekuasaan.
Di sisi lain, ada risiko yang harus diantisipasi ketika NU bersinggungan ke dunia politik. Kiai dan pesantren jangan dijadikan alat politik oleh elite untuk mencari keuntungan elektoral atau mengamankan suara. “NU harus dijaga martabatnya, jangan sampai keterlibatan politik merusak integritas dan wibawa organisasi yang selama ini menjadi panutan ilmu dan moral bagi masyarakat,” katanya.
Komaruddin menuturkan, pengalaman panjang NU menghadapi turbulensi politik menjadi pelajaran penting. Pengalaman itu mesti membuat NU kembali melakukan konsolidasi internal, menjaga khittah, dan membangun tata kelola yang kuat sehingga NU tetap kritis namun tidak anti-pemerintah. Dengan cara itu, NU bisa menjadi kekuatan masyarakat sipil yang mandiri, menjaga moral publik, dan tetap relevan dalam membimbing umat serta mempertahankan stabilitas sosial.

/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2026%2F01%2F31%2F3b5b99a3aac833a82c4cc68391b4abee-20260131TOK3.jpg)