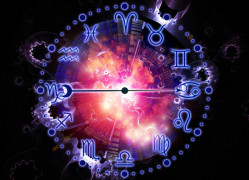Pengakuan Palestina oleh sejumlah negara Barat dalam beberapa bulan terakhir menandai babak baru dalam diplomasi internasional. Langkah itu bukan sekadar simbol politik, tetapi juga pesan moral bahwa kondisi status quo tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, pengakuan diplomatik semata tidak akan otomatis membawa perdamaian. Tanpa rekonsiliasi sosial di level akar rumput—antara warga Palestina dan Israel—perdamaian hanya akan berakhir sebagai proyek elite, yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Mengapa Social Engineering Penting
Sejarah menunjukkan, perjanjian elite tanpa dukungan rakyat seringkali rapuh. Oslo Accords pada 1990-an sempat membuka harapan, tetapi gagal menciptakan rasa percaya karena jurang kebencian di lapangan tidak pernah dijembatani. Kini, dengan semakin banyak negara Barat mengakui Palestina, kebutuhan akan social engineering menjadi mendesak yakni dengan membangun ulang persepsi, narasi, dan hubungan sosial lintas komunitas diantara keduanya.
Di titik ini, social engineering bukan sekadar “kampanye perdamaian”, melainkan upaya membangun prasyarat psikologis dan sosial bagi kompromi politik. Tanpa perubahan di level persepsi publik, setiap konsesi akan dibaca sebagai kekalahan, bukan jalan tengah; setiap gencatan senjata dianggap jeda taktis, bukan pijakan kepercayaan. Social Engineering dibutuhkan untuk menurunkan rasa ancaman, memutus siklus dehumanisasi, dan menciptakan insentif baru agar kerja sama lebih rasional daripada kekerasan—mulai dari kurikulum pendidikan, media arus utama, ruang digital, hingga proyek ekonomi bersama yang memberi manfaat nyata. Dengan kata lain, diplomasi dapat membuka pintu, tetapi hanya transformasi sosial yang membuat pintu itu tetap terbuka.
Program people-to-people diplomacy sebenarnya bukan hal baru. Beberapa inisiatif lintas masyarakat pernah dilakukan, seperti program pertukaran pemuda, proyek pembangunan bersama, hingga kerja sama lintas kampus. Bukti akademis menunjukkan program semacam ini bisa menurunkan stereotip dan meningkatkan empati jangka panjang. Namun, skalanya masih kecil dan sering tidak terintegrasi ke dalam kerangka perdamaian resmi. Tanpa adanya social engineering yang matang pada masyarakat luas, maka yang muncul hanya perdamaian yang sia-sia bahkan pada titik terburuk, kembali pada era perang. Di sisi lain, faksionalisme politik di internal Palestina juga menjadi hambatan: tanpa konsolidasi legitimasi dan agenda bersama, program rekonsiliasi rentan disabotase, dipolitisasi, atau kehilangan representasi di mata publik.
Risiko Infiltrasi dan Manipulasi
Di sinilah paradoks muncul. Upaya rekonsiliasi sosial yang terlalu terbuka juga rawan dimanfaatkan oleh aktor politik dan intelijen. Hamas bisa menyusup ke dalam jaringan masyarakat sipil dengan agenda politis atau bahkan militeristik, sehingga mengubah jalur rekonsiliasi menjadi ruang mobilisasi. Di sisi lain, Mossad dan badan keamanan Israel bisa memanfaatkan inisiatif lintas komunitas sebagai kanal pengumpulan informasi atau pengaruh politik.
Risiko lainnya adalah elite lokal yang mengkapitalisasi proyek rekonsiliasi untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Di Palestina, pengakuan negara berpotensi dipakai oleh Fatah atau Hamas untuk mengklaim otoritas tunggal, sambil menunda reformasi politik internal. Di Israel, pemerintahan yang mengusung narasi “super Sparta” cenderung mengontrol ketat interaksi dengan warga Palestina demi alasan keamanan.
Lebih jauh, infiltrasi dan manipulasi politik juga bisa menimbulkan delegitimasi total terhadap proyek perdamaian itu sendiri. Begitu masyarakat menilai bahwa program lintas komunitas hanyalah alat propaganda atau instrumen intelijen, kepercayaan akan runtuh, bahkan di antara kelompok-kelompok yang tadinya mendukung rekonsiliasi. Ketidakpercayaan ini bisa menjalar cepat melalui media sosial, diperkuat oleh perang narasi dari aktor-aktor radikal. Akibatnya, upaya social engineering justru memperdalam polarisasi, bukannya meruntuhkan sekat yang ada.
Jika pengakuan Palestina dimaknai sebagai koreksi moral atas status quo, maka pekerjaan berikutnya adalah memastikan koreksi itu tidak berhenti sebagai gestur diplomatik. Social engineering perlu menjadi agenda paralel baik secara global , regional maupun domestik. Secara global, aktor internasional harus memfokuskan dukungan pada program lintas masyarakat yang terukur, tahan disinformasi, dan terlindungi dari politisasi. Secara domestik, Palestina dan Israel perlu menata ulang narasi internal untuk mengurangi politik kebencian dan memperluas ruang moderasi. Dalam desain seperti itu, social engineering bukan jebakan, melainkan prasyarat agar perdamaian tidak sekadar diumumkan, tetapi benar-benar dijalani. Pada titik inilah pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak, melainkan siapa yang mengendalikan desainnya dan untuk kepentingan siapa.