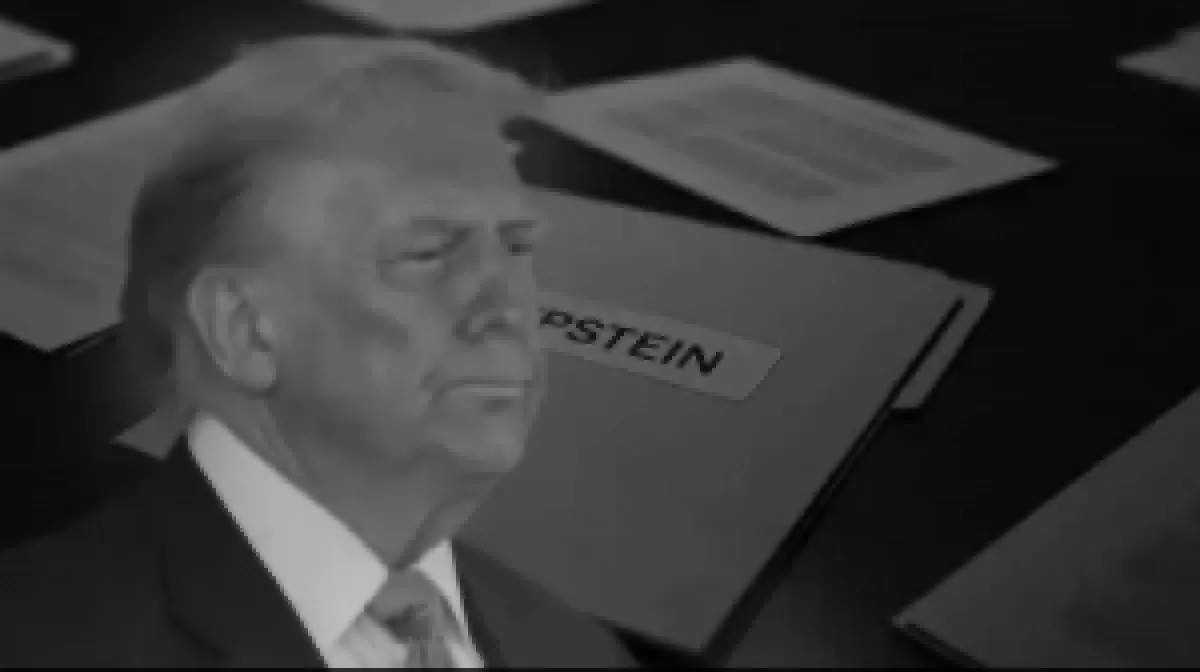Masuknya mekanisme Pengakuan Bersalah (plea bargain) ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai pergeseran penting dalam arah kebijakan penegakan hukum pidana Indonesia.
Untuk pertama kalinya, hukum acara pidana Indonesia mengakui penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah yang dilembagakan secara normatif, diawasi oleh pengadilan, dan ditempatkan dalam kerangka due process of law.
Kebijakan ini lahir dari realitas beban perkara yang tinggi, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta kebutuhan rasionalisasi prosedural agar peradilan pidana lebih efektif dan akuntabel.
Namun, di balik janji efisiensi, muncul pertanyaan mendasar: Apakah Pengakuan Bersalah akan memperkuat kualitas keadilan, atau justru membuka ruang baru bagi tekanan struktural terhadap terdakwa?
Definisi Normatif dan Makna HukumnyaKUHAP Baru mendefinisikan Pengakuan Bersalah sebagai mekanisme bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya secara kooperatif dengan dukungan alat bukti, dengan kemungkinan keringanan pidana sebagai konsekuensi yang bersifat kondisional.
Secara normatif, pengaturan ini menegaskan bahwa pengakuan bersalah bukan negosiasi informal di luar hukum, melainkan institusi prosedural resmi yang tunduk pada standar legalitas, akuntabilitas, dan pengawasan yudisial.
Tiga elemen kunci terkandung dalam definisi tersebut: (i) pengakuan harus merupakan kehendak bebas terdakwa; (ii) pengakuan wajib didukung alat bukti, sehingga tidak berdiri sebagai pengakuan kosong; dan (iii) keringanan pidana tidak otomatis, tetapi bergantung pada penilaian hakim.
Dengan konstruksi ini, Pengakuan Bersalah bukan “jual beli hukuman”, melainkan instrumen rasionalisasi proses yang dibatasi oleh due process of law.
Memahami Tujuan Pengakuan Bersalah: Cepat, tapi Tetap Adil?Pengenalan mekanisme Pengakuan Bersalah sejalan dengan arah kebijakan pemidanaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang memandang pemidanaan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan berlapis, yakni perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan, dan pembinaan pelaku.
Orientasi tersebut membuka ruang bagi diferensiasi respons pidana terhadap pelaku yang kooperatif, tanpa menegasikan prinsip pertanggungjawaban pidana sebagai inti dari sistem hukum pidana.
Secara kebijakan, mekanisme ini dimaksudkan untuk merasionalisasi alur penanganan perkara: perkara dengan kompleksitas pembuktian rendah dapat diselesaikan lebih ringkas, sementara sumber daya peradilan difokuskan pada perkara-perkara yang menuntut pemeriksaan penuh dan mendalam.
Namun demikian, efisiensi yang dilembagakan tersebut harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka keadilan prosedural, dengan menjamin perlindungan hak-hak hukum terdakwa, memastikan peran aktif dan efektif penasihat hukum, serta menegaskan fungsi kontrol yudisial sebagai penentu akhir legitimasi seluruh proses peradilan.
Bagaimana Prosedur Pengakuan Bersalah Diatur dalam KUHAP Baru?KUHAP Baru menempatkan Pengakuan Bersalah sebagai mekanisme berlapis yang hanya menimbulkan akibat hukum final setelah berada dalam kontrol pengadilan.
Pada tahap pra-ajudikasi—khususnya dalam proses penyidikan—Pengakuan Bersalah dari seorang tersangka dapat disampaikan dan dicatat oleh penyidik serta dikoordinasikan dengan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP Baru.
Namun, pada tahap ini pengakuan tersebut belum menimbulkan akibat hukum yang bersifat final dan tidak mengikat pengadilan. Finalisasi hanya terjadi pada tahap ajudikasi melalui sidang khusus sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.
Pengaturan ini mencerminkan pendekatan KUHAP Baru yang membuka ruang bagi pencatatan sikap kooperatif tersangka selama penyidikan, sekaligus menegaskan bahwa finalisasi Pengakuan Bersalah hanya dapat dilakukan dalam kerangka pemeriksaan di pengadilan.
Lebih lanjut, Pasal 78 KUHAP Baru membatasi penerapan Pengakuan Bersalah hanya pada perkara tertentu dan mensyaratkan adanya pendampingan penasihat hukum bagi terdakwa. Kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan diajukan kepada hakim untuk memperoleh persetujuan.
Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kesukarelaan pengakuan, pemahaman terdakwa terhadap konsekuensi hukumnya, dan kecukupan dasar faktual yang mendasari pengakuan tersebut.
Putusan hanya dapat dijatuhkan apabila Pengakuan Bersalah didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sebagaimana disyaratkan Pasal 78 ayat 12 KUHAP Baru. Apabila hakim menilai prasyarat normatif tidak terpenuhi atau terdapat keraguan atas kesukarelaan pengakuan, perkara wajib dilanjutkan dengan mekanisme pemeriksaan biasa.
Dengan desain ini, Pengakuan Bersalah tidak mengunci hasil perkara dan tidak menggantikan pembuktian, tetapi beroperasi sebagai jalur prosedural khusus yang tetap berada dalam kontrol yudisial dan kerangka due process of law.
Pengakuan Bersalah dan “Kesukarelaan” yang SemuSecara normatif, KUHAP Baru menempatkan kesukarelaan sebagai prasyarat mutlak dalam pengakuan bersalah serta secara tegas melarang segala bentuk paksaan. Namun, praktik peradilan pidana di Indonesia kerap menunjukkan kenyataan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan tersebut.
Relasi kuasa antara aparat penegak hukum dan tersangka sering kali bersifat timpang, terutama terhadap tersangka yang berada dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi, serta tidak didampingi oleh penasihat hukum karena keterbatasan biaya.
Dalam kondisi demikian, tekanan selama proses penyidikan—baik dalam bentuk intimidasi, ancaman, maupun kekerasan fisik—masih sangat berpotensi terjadi dan mendorong tersangka untuk mengakui perbuatan pidana yang padahal belum tentu benar-benar dilakukannya.
Dalam konteks ini, konsep “kesukarelaan” berisiko berubah menjadi fiksi prosedural. Situasi yang koersif, penuh tekanan dan ancaman kekerasan dapat mendorong tersangka untuk “memilih” mengaku bersalah sebagai jalan keluar pragmatis, meskipun perkaranya secara yuridis masih dapat diperdebatkan.
Akibatnya, pengakuan yang secara formal tampak sukarela di atas kertas sesungguhnya lahir dari paksaan struktural yang melekat dalam proses penegakan hukum itu sendiri.
Oleh karena itu, pelembagaan mekanisme Pengakuan Bersalah tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi baru atas praktik-praktik tekanan dalam penyidikan.
Sebaliknya, mekanisme ini justru menuntut standar perlindungan yang lebih tinggi bagi tersangka, khususnya melalui pendampingan penasihat hukum yang efektif sejak awal pemeriksaan, larangan absolut terhadap segala bentuk penyiksaan dan intimidasi, serta kewajiban dokumentasi proses pemeriksaan yang transparan dan dapat diuji di persidangan.
Tanpa prasyarat tersebut, Pengakuan Bersalah berisiko melahirkan bentuk baru, yaitu “Pengakuan Terpaksa”: efisien secara prosedural, tetapi rapuh dari perspektif keadilan substantif.
Penting pula ditegaskan bahwa keberadaan mekanisme Pengakuan Bersalah tidak boleh dipahami oleh penyidik, jaksa dan hakim sebagai tolok ukur sikap “kooperatif” atau “tidak kooperatif” tersangka. Hak tersangka untuk diam, menyangkal tuduhan, dan menuntut pembuktian penuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip due process of law.
Menolak mengaku bersalah bukanlah indikator ketidakkooperatifan, melainkan ekspresi sah dari hak konstitusional atas pembelaan diri. Pelabelan negatif terhadap tersangka yang memilih jalur pemeriksaan biasa justru berisiko menggeser mekanisme Pengakuan Bersalah menjadi instrumen tekanan terselubung.
Dengan demikian, pencegahan koersi/paksaan/tekanan tidak cukup bergantung pada perumusan norma dalam undang-undang, tetapi sangat ditentukan oleh implementasinya.
Hal ini menuntut pengawasan yang efektif terhadap praktik penyidikan, jaminan akses bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu, dan peran aktif hakim dalam menguji kesukarelaan pengakuan secara substantif, bukan semata-mata formal.
Tanpa prasyarat tersebut, efisiensi prosedural yang dijanjikan oleh mekanisme Pengakuan Bersalah berpotensi dibayar mahal oleh kelompok yang paling rentan dalam sistem peradilan pidana.
Hakim sebagai Penjaga Terakhir (Judicial Gatekeeper)KUHAP Baru secara tegas menempatkan hakim sebagai pusat legitimasi Pengakuan Bersalah. Prinsip ini tecermin dalam pengaturan bahwa kesepakatan para pihak tidak mengikat pengadilan tanpa persetujuan hakim. Pasal 78 KUHAP Baru mengatur beberapa hal.
1) Pengakuan Bersalah hanya dapat disahkan dalam sidang khusus sebelum pemeriksaan pokok perkara;
2) perjanjian pengakuan bersalah harus mendapat persetujuan hakim;
3) hakim wajib menilai kesukarelaan, pemahaman terdakwa atas konsekuensi pengakuan, serta kecukupan dasar faktual;
4) hakim berwenang menerima atau menolak pengakuan bersalah; dan
5) putusan hanya dapat dijatuhkan apabila pengakuan bersalah didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Konstruksi ini menegaskan bahwa polisi dan jaksa hanya berperan pada tahap inisiasi dan perundingan terbatas, sedangkan otoritas final berada pada pengadilan. Plea bargain dalam KUHAP Baru bukan justice by negotiation, melainkan justice under judicial control.
Untuk mencegah formalisasi semu kesukarelaan, hakim idealnya menerapkan uji kelayakan substantif, antara lain dengan mempertimbangkan durasi penahanan sebelum pengakuan, kualitas akses terdakwa terhadap penasihat hukum, dan rasionalitas kesepakatan dibanding ancaman pidana maksimum.
Tanpa peran aktif hakim sebagai gatekeeper, mekanisme ini berisiko berubah menjadi prosedur cepat yang mereduksi perlindungan terhadap hak-hak hukum terdakwa.
Perbandingan dengan Amerika SerikatDi Amerika Serikat, Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) menjadi cara utama menyelesaikan perkara pidana dengan persentase diperkirakan hingga 80 persen dari seluruh kasus pidana di tingkat federal maupun negara bagian diselesaikan melalui plea bargaining.
Di Amerika, Jaksa memiliki ruang negosiasi yang luas. Diskresi penuntutan jaksa menciptakan insentif struktural bagi tersangka untuk mau mengaku bersalah dibandingkan tetap mengelak dengan konsekuensi ancaman trial penalty, yakni risiko pidana yang jauh lebih berat apabila memilih melanjutkan persidangan dan dinyatakan bersalah.
Pada saat yang sama, praktik penegakan hukum di Amerika Serikat berada dalam kerangka larangan ketat atas intimidasi dan kekerasan oleh aparat.
Pengakuan yang diperoleh melalui paksaan berisiko dikesampingkan oleh pengadilan (exclusionary rule) dan pemeriksaan tersangka dilindungi oleh standar konstitusional—antara lain hak diam dan hak absolut untuk didampingi oleh penasihat hukum.
Meskipun pelanggaran tetap mungkin terjadi, secara institusional terdapat mekanisme penegakan dan sanksi yang relatif lebih kuat terhadap praktik-praktik koersif.
Indonesia memilih desain berbeda. Pengakuan Bersalah dibatasi secara ketat hanya pada jenis perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun (Pasal 78 ayat 1 KUHAP), diformalkan melalui sidang khusus sebelum pemeriksaan pokok perkara, mewajibkan perjanjian tertulis dengan persetujuan hakim, dan mensyaratkan dukungan minimal alat bukti yang sah. Peran hakim bersifat substantif sebagai penjaga legitimasi, bukan sekadar pengesah formil.
Model Pengakuan Bersalah di Indonesia secara normatif lebih selaras dengan prinsip negara hukum dan due process of law karena menempatkan kepentingan efisiensi prosedural di bawah kontrol yudisial yang kuat.
Namun, menurut hemat penulis, keunggulan normatif tersebut hanya akan bermakna apabila disertai dengan pembenahan serius dalam praktik penegakan hukum.
Pembenahan dimaksud mencakup penindakan tegas terhadap praktik intimidasi dan kekerasan dalam proses penyidikan oleh Kepolisian, penyediaan akses bantuan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi tersangka yang tidak mampu, serta keberanian dan independensi hakim untuk menolak Pengakuan Bersalah yang terbukti lahir dari tekanan.
Tanpa prasyarat-prasyarat tersebut, perbedaan desain normatif antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi menyempit dalam praktik, sehingga tujuan perlindungan hak tersangka dan penegakan due process of law menjadi sulit untuk diwujudkan secara nyata.
Efisiensi dengan Syarat KeadilanPengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru merupakan instrumen rasionalisasi peradilan pidana yang berpotensi mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengorbankan kualitas putusan, asalkan dijalankan dalam bingkai ketat due process of law.
Keberhasilan mekanisme ini tidak cukup diukur dari kecepatan semata, tetapi dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif. Ukurannya terletak pada sejauh mana hak-hak hukum seseorang terlindungi, sejak ia dijadikan tersangka hingga menjadi terdakwa di persidangan.
Tantangan implementasinya tetap besar. Asimetri kuasa, risiko koersi/paksaan terselubung, dan kemungkinan penyalahgunaan masih mengintai, terutama jika kontrol yudisial melemah.
Tanpa integritas institusional, pendampingan hukum yang efektif, serta hakim yang aktif menjalankan fungsi gatekeeper, sebagaimana dirancang oleh KUHAP Baru, mekanisme ini berpotensi berubah menjadi cara cepat menutup perkara dengan mengorbankan pihak yang paling rentan dalam sistem peradilan pidana.