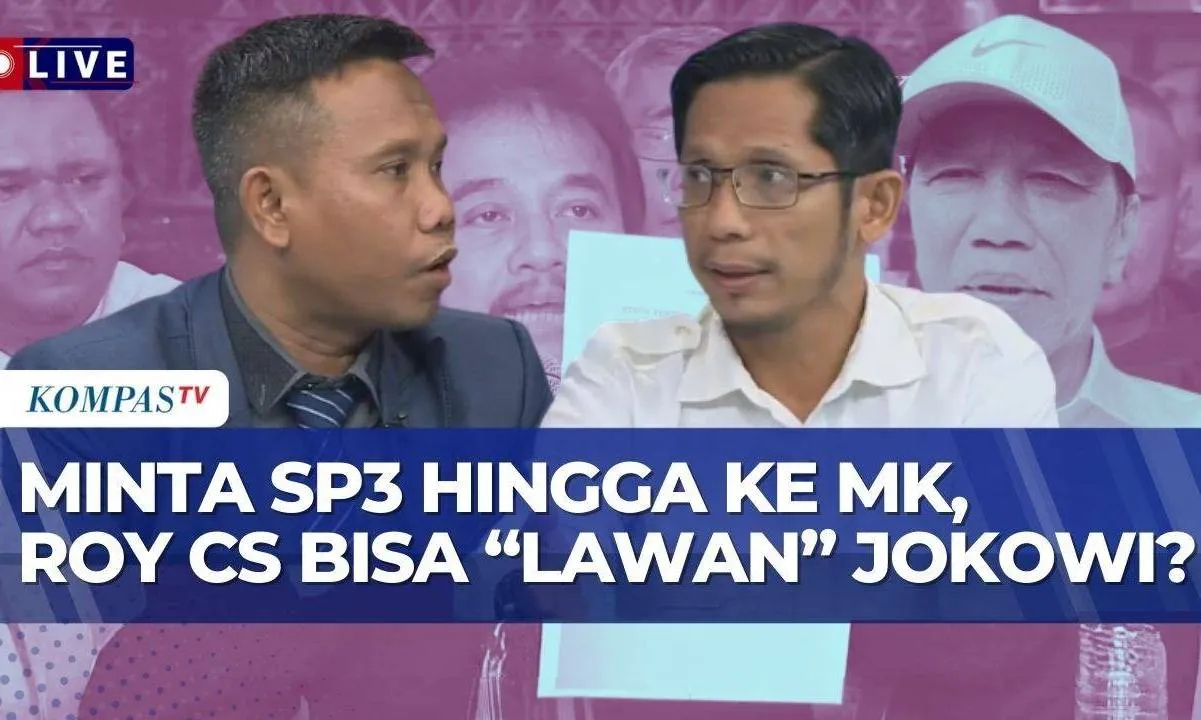Tahun ini, dua tradisi besar keagamaan berjalan hampir beriringan. Umat Muslim bersiap memasuki bulan Ramadhan dan umat Kristiani memulai masa Prapaskah dalam waktu yang hampir bersamaan.
Kamis (19/2/2026), Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai hari pertama puasa. Selanjutnya, selama 30 hari, umat Muslim menjalankan ibadah puasa menuju hari kemenangan di hari raya Idul Fitri.
Sementara itu, sehari sebelumnya, Rabu (18/2/2026), merupakan hari Rabu Abu yang menjadi hari pertama dalam rangkaian masa Prapaskah bagi umat Kristiani.
Dengan tanda abu di dahi, puasa dan pantang akan dijalani selama kurang lebih 40 hari menuju hari raya Paskah yang menjadi hari kebangkitan Yesus Kristus. Dua kalender yang berbeda seakan menemukan satu ritme tahun ini, yakni jeda kolektif dari rutinitas menuju ruang refleksi diri yang lebih hening.
Dalam ritme hidup harian, perubahan terasa nyata mulai dari jam makan bergeser, intensitas ibadah meningkat, hingga percakapan publik yang akan diisi tentang pengendalian diri.
Momentum ini menarik untuk dicermati: di tengah masyarakat modern yang serba cepat, sebuah praktik kuno nan sederhana dijalankan, yaitu menahan lapar dan haus.
Mengapa puasa masih relevan tentu dapat dijawab dengan berbagai penjelasan spiritual berbagai ajaran agama. Namun, pertanyaannya juga, mengapa praktik puasa bertahan begitu lama dalam sejarah manusia, bahkan ketika dunia terus bergerak menuju kemakmuran?
Kendati saat ini puasa sangat dekat dengan praktik dan aturan agama, sejatinya sejarah puasa melampaui batas agama tertentu. Dalam tradisi Yunani Kuno, misalnya, dikenal asketis, yakni upaya melawan nafsu dan kehendak diri. Secara nyata, praktik ini dilakukan dengan menunda keinginan makan dan minum.
Sementara jika mencermati sejarah Mesir Kuno, pantangan makan selalu dijalankan menjelang ritual-ritual sakral. Bergeser ke wilayah Asia Selatan, dalam tradisi Hinduisme dan Buddhisme dikenal praktik tapasya.
Bentuk puasa di dalamnya memuat upaya pengendalian diri yang disengaja untuk meningkatkan kekuatan spiritual demi mencapai pencerahan atau penyucian diri.
Dalam tradisi Nusantara yang dekat dengan bahasa Sanskerta, dikenal pula istilah upawasa. Secara harafiah kurang lebih artinya pendekatan diri kepada Yang Maha Agung. Artinya, menahan lapar dan haus bukan hanya soal fisik, melainkan upaya pendekatan diri terhadap Pencipta.
Kendati puasa senatiasa bernuansa praktik spiritual individu, dengan pendekatan perspektif kebudayaan, dapat ditemukan bahwa praktik ritual pun sejatinya memuat dimensi kolektif. Dalam Ritual Theory, Ritual Practice yang ditulis oleh Catherine Bell, disebutkan dua fungsi ritual.
Pertama, ritual dilakukan demi mempererat hubungan individu dengan yang transenden. Kedua, pembangunan identitas kolektif dalam komunitas.
Dengan demikian, alasan puasa dapat bertahan dalam masyarakat sebab menjadi salah satu strategi sosial. Praktik ini menata ulang relasi antara individu dan komunitasnya.
Dalam cara pandang yang kedua, praktik puasa memiliki sisi sosial yang tak bisa diabaikan apalagi dalam masyarakat modern. Bahkan, puasa dapat dipandang sebagai upaya untuk mereset ritme sosial. Pasalnya, puasa akan mengubah jadwal kolektif.
Ketika jutaan orang sahur dan berbuka pada waktu yang sama, muncul pengalaman kebersamaan, hal yang langka terjadi dalam kehidupan modern individualistis.
Rasa kebersamaan ini berikutnya akan menumbuhkan penguatan solidaritas dengan kesadaran ritual yang dilakukan secara kolektif.
Dalam komunitas, momen puasa yang dilakukan bersama juga akan menjadi saat negosiasi ulang status moral dalam komunitas. Bagi yang menjalankan puasa, dalam diri masing-masing muncul kesadaran untuk lebih sabar, reflektif, dan berhati-hati dalam tindakan.
Hal ini pun akan membuat relasi sosial bergeser. Bahasa dalam percapakan akan lebih santun, konflik cenderung akan ditunda, bahkan ruang publik terasa lebih terkendali. Dengan begitu, kehidupan yang mungkin melenceng dari nilai moral harmoni sosial akan dikembalikan.
Apalagi, di saat yang bersamaan, puasa yang dijalankan pun menjadi bentuk kritik terhadap budaya yang konsumtif. Antropolog Marshall Sahlins dalam Stone Age Economics menggarisbawahi bahwa sejatinya masyarakat tidak selalu mengejar kelimpahan material.
Karenanya, dalam praktik puasa masa kini, setiap individu dipaksa untuk mengevaluasi hubungannya dengan makanan, waktu, dan keinginan.
Bukan hanya perkara spiritual dan sosial, hal yang nyata terjadi dalam diri seorang ketika menjalankan puasa adalah berubahnya ritme biologis, terutama dalam soal makan. Tubuh yang terbiasa dijaga agar tidak kelaparan malah disengaja untuk merasakan haus dan lapar.
Dalam situasi ini puasa memicu adaptasi metabolisme tubuh. Yoshinori Ohsumi, ahli biologi sel asal jepang, dalam penelitiannya menemukan mekanisme autofagi, yakni kondisi sel yang mendaur ulang komponennya sendiri. Kondisi ini akan muncul ketika tubuh sedang dalam kelaparan.
Dalam penelitiannya dijelaskan, kondisi kekurangan nutrisi dapat mendorong sel untuk membersihkan komponen yang rusak. Sejumlah penelitian lain juga menunjukkan jeda makan dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu pengaturan energi.
Tak hanya itu, pengalaman mental yang kerap kali dirasakan oleh orang berpuasa, seperti pikiran yang lebih jernih dan rasa yang muncul pun dibaca sebagai repons adaptif terhadap ritme biologis yang kembali selaras.
Kembali ke pertanyaan, mengapa puasa itu perlu? Dapat ditemukan jawaban bercorak spiritual, sosial, ataupun biologis. Namun, secara praktis, puasa terus bertahan dalam peradaban manusia sebab di tataran paling permukaan sekalipun ia memberikan manfaat.
Orang akan kembali sadar akan pola makan. Dalam relasi sosial, momen berbuka atau beribadah bersama akan mempererat hubungan keluarga ataupun komunitas yang acap kali terlewat dalam rutinitas biasa. Sementara itu, dalam sejarah peradaban modern, puasa akan terus menghadirkan paradoks yang relevan bagi dunia modern.
Dalam masyarakat yang mendewakan kelimpahan, praktik ini justru menawarkan nilai keterbatasan yang dipilih secara sadar.
Kembali pada Sahlins, ia pun menulis, belajar dari masyarakat pemburu-peramu, kelimpahan bukan lahir dari banyaknya barang, melainkan dari kemampuan merasa cukup. (LITBANG KOMPAS)
Serial Artikel
Puasa dan Kedermawanan Otentik
Membantu orang miskin bukan untuk populis dan pencitraan. Lingkungan terdekat dan mikro menjadi kelompok target utama kedermawanan.