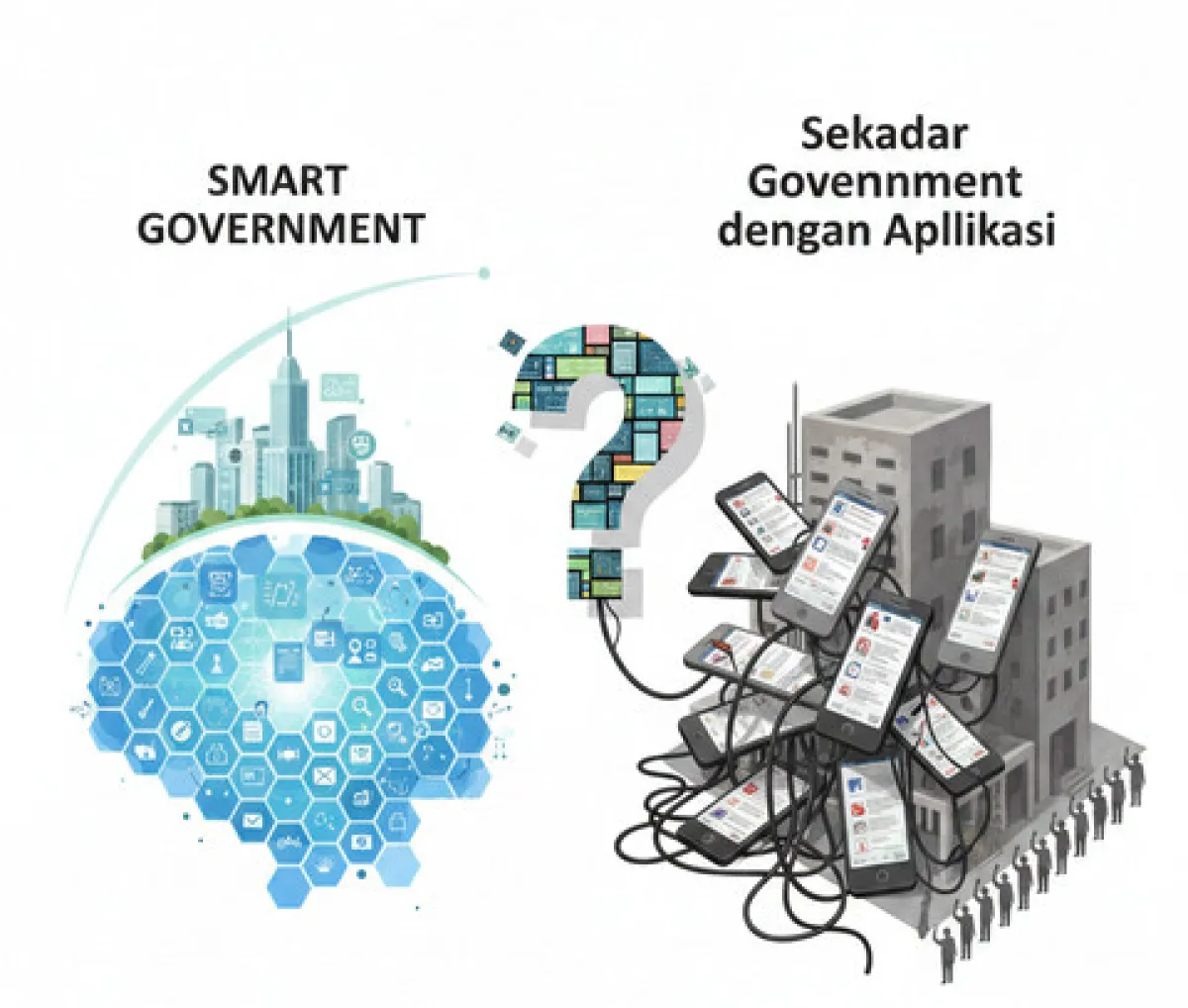SETELAH seperempat abad lebih Reformasi, mengapa praktik bernegara yang dahulu dikutuk dan meruntuhkan rezim Orde Baru justru kembali dinormalisasi?
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kembali dipuja, bahkan dirayakan secara masif. Bersamaan dengan itu suara kritis dibungkam.
Hal tersebut di antaranya ditunjukkan oleh skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 yang turun dibandingkan periode sebelumnya.
Pada 2024, skor Indonesia adalah 37, tetapi pada 2025 angkanya turun menjadi 34, lebih buruk ketimbang Etiopia (38), Suriname (38), dan Sri Lanka (35).
Menurut Transparency International, skor rendah yang terjadi terus-menerus biasanya selaras dengan terkikisnya demokrasi dan buruknya mekanisme pengawasan (akuntabilitas).
Skor yang rendah berkorelasi pula dengan politisasi sistem peradilan, selain mengecilnya ruang kebebasan sipil.
Reformasi ternyata gagal membuahkan peradaban politik baru yang merefleksikan karakter bangsa yang moyangnya pernah gilang-gemilang. Kita seolah tak mampu belajar dari kesalahan masa lalu. Kita kembali terperosok pada lubang yang sama.
Praktik bernegara kita mengalami paradoks. Di satu sisi, prosedur elektoral berjalan relatif baik. Pemilu anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah langsung berjalan tertib dan aman.
Baca juga: Paspor, Amanah Publik, dan Sensitivitas Awardee
Kelembagaan demokrasi yang lain sebagai hasil perjuangan Reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bekerja.
Namun, di sisi lain, praktik KKN tetap marak dalam berbagai bentuk baru, bahkan makin masif dan terang-terangan.
Akibatnya, negara pun kesulitan memenuhi kewajiban konstitusi. Untuk sekadar memberikan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas saja, negara tak mampu.
Kekayaan negara yang semestinya buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mengalir ke kantong sedikit orang. Kemakmuran hanya dinikmati sedikit orang.
Apa masalahnya? Salah satu persoalan mendasar Indonesia sebagai bangsa pascakolonial adalah apa yang oleh Yudi Latif (Kompas, 9 Februari 2026) disebut “jebakan mesianisme”: kecenderungan menggantungkan harapan pada figur penyelamat.
Politik direduksi sekadar urusan tokoh. Seolah-olah, dengan hadirnya seorang pemimpin tertentu, segala persoalan akan otomatis selesai. Sistem, tata kelola, dan partisipasi warga menjadi urusan kedua.
Kecenderungan mesianistik sesungguhnya bukan gejala baru. Dalam konteks era kolonial, imajinasi tentang Ratu Adil berfungsi sebagai simbol pembebasan dari penindasan.