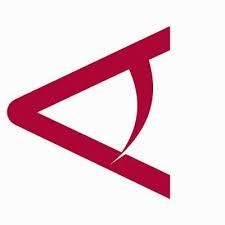Jakarta (ANTARA) - Forum-forum global tentang akal imitasi (AI) makin ramai dan sarat agenda. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut turun tangan dengan gagasan tata kelola dan dana bersama. Semua terdengar ideal dan menjanjikan.
Tetapi, setiap idealisme global selalu bertemu realitas kepentingan nasional masing-masing negara.
Berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AI, di New Delhi, India, baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengapungkan gagasan soal AI yang inklusif dan bisa diakses semua pihak. Guterres mengingatkan bahwa masa depan tak boleh ditentukan segelintir negara atau miliarder teknologi. Pesan moralnya kuat dan menggugah.
Meski demikian, dalam realita, moral global sering kali berbenturan dengan kalkulasi ekonomi politik yang lebih keras. Geopolitik jarang berjalan di atas keindahan retorika, lantaran ia kerap bertumpu pada kepentingan, kekuatan, dan kemampuan membiayai ambisi. Dalam arena seperti ini, siapa yang menguasai teknologi, dialah yang berpeluang menentukan standar global, mengatur arus keuntungan ekonomi, dan membentuk aturan main yang diikuti negara lain.
Tidak ikut blok
Sejak awal berdirinya, Indonesia punya satu pegangan yaitu politik luar negeri bebas aktif. Ia tidak ikut blok mana pun, tetapi juga tidak pasif menunggu siapa yang sedang unggul dalam persaingan global sebelum menentukan sikap. Prinsip ini sudah teruji dalam ketegangan Perang Dingin. Kini ia diuji kembali dalam kontestasi teknologi yang jauh tak kalah menentukan.
Masalahnya, AI dewasa ini bukan sekadar teknologi tambahan di atas model ekonomi lama. Ia adalah infrastruktur kekuasaan baru. Negara yang menguasai data, komputasi, dan talenta bakal menguasai peta produktivitas masa depan. Dari situlah pengaruh ekonomi dan politik akan mengalir deras.
Forum multilateralisme memang memberi ruang dialog yang relatif setara. Negara besar dan negara berkembang bisa duduk di meja yang sama, membahas etika dan standar bersama. Indonesia secara historis nyaman di forum seperti itu karena tradisi diplomasi kolektifnya kuat. Namun, ruang dialog yang setara belum tentu otomatis memberi keuntungan strategis jika tidak diikuti kesiapan ekonomi dan teknologi di dalam negeri.
Realisme mengingatkan bahwa di balik meja bundar, ada meja persegi panjang tempat keputusan bisnis besar ditentukan. Di sana, investasi dan kontrol teknologi menjadi bahasa utama. Artinya, kekuatan finansial sering kali lebih berpengaruh daripada legitimasi normatif. Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap fakta ini.
Jika Indonesia terlalu normatif, ia bisa kehilangan momentum ekonomi. Jika terlalu pragmatis, ia bisa kehilangan konsistensi kebijakan luar negerinya. Di sinilah keseimbangan menjadi seni yang rumit.
Dihitung sejak awal
Dana AI global yang diusulkan PBB terdengar memang menjanjikan bagi negara berkembang. Ada harapan untuk membangun kapasitas, melatih talenta dan sekaligus menyediakan komputasi terjangkau. Akan tetapi, bantuan selalu datang dengan ekosistem dan standar teknologinya sendiri. Itu berarti ada struktur ketergantungan yang perlu dihitung sejak awal.
Dalam hal ini, ekosistem berarti perangkat lunak tertentu, penyedia cloud tertentu, bahkan arsitektur keamanan tertentu. Standar berarti arah pengembangan yang mungkin tidak sepenuhnya fleksibel. Adapun ketergantungan berarti ruang negosiasi yang menyempit dalam jangka panjang. Indonesia perlu membaca ini dengan kepala dingin.
Suka atau tidak, kerja sama global tetap penting dan tak bisa dihindari. Tanpa kolaborasi, kita bisa tertinggal dalam riset dan pengembangan. Sungguhpun demikian, kerja sama harus dirancang sebagai kemitraan setara, bukan relasi pemasok dan pelanggan. Perbedaan keduanya bakal sangat menentukan masa depan industri nasional.
Indonesia tak pelak punya pasar besar dengan jutaan pengguna digital aktif. Juga punya bonus demografi yang bisa menjadi tenaga kerja digital produktif. Selain itu, punya pula ekosistem startup yang mulai menemukan model bisnis berkelanjutan. Semua itu adalah modal tawar, bukan sekadar angka-angka dalam laporan tahunan.
Di forum global, Indonesia perlu lebih dari sekadar memberikan dukungan pada resolusi normatif. Ia perlu pula membawa agenda ekonomi yang terukur dan konkret. Alih teknologi, pengembangan pusat data domestik, dan pelatihan talenta harus menjadi bagian dari negosiasi.
AI bukan hanya perkara regulasi dan standar etika. Ia juga menyangkut investasi miliaran dolar dan kontrak jangka panjang, menyangkut pula soal siapa yang membangun pusat data dan siapa yang menyuplai energinya, serta soal siapa yang memegang lisensi model dan siapa yang membayar biaya langganan.
Multilateralisme memberi legitimasi internasional. Adapun realisme memberi daya tahan dalam persaingan. Indonesia perlu memadukan keduanya secara cerdas. Bukan memilih salah satu, tetapi menjahit keduanya dalam strategi yang koheren.
Memainkan peran penyeimbang
Dalam beberapa periode sejarah -- terutama pada era awal Perang Dingin dan dalam dinamika geopolitik Asia Tenggara -- Indonesia pernah memainkan peran penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar. Ia bukan pemimpin blok, tetapi penghubung yang dipercaya. Peran itu agaknya relevan kembali dalam tata kelola AI global. Namun kali ini, sebagai penghubung, Indonesia harus juga kuat secara ekonomi.
Indonesia, misalnya, bisa mendorong prinsip keadilan akses dan perlindungan untuk negara berkembang. Tetapi, pada saat yang sama, ia harus pula memastikan industri dalam negerinya naik kelas. Jangan sampai kita hanya menjadi reseller teknologi global dengan margin tipis. Maka, transformasi harus terjadi di dalam negeri.
Forum global tetap penting sebagai arena pembentukan norma. Tanpa norma, pasar bisa berjalan liar dan tidak adil. Namun demikian, norma tanpa kapasitas domestik hanya akan menjadi arsip diplomatik. Kekuatan nyata tetap terletak pada kesiapan nasional.
Untuk itu, setiap komitmen internasional harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di dalam negeri, mulai dari insentif fiskal hingga regulasi perlindungan data, dari pendidikan vokasi hingga riset universitas. Diplomasi yang baik selalu punya ekor kebijakan di ranah domestik.
Indonesia perlu waspada terhadap fragmentasi digital dunia ketika ekosistem teknologi, standar data, dan infrastruktur siber terbelah ke dalam blok-blok eksklusif yang saling bersaing. Jika dunia terpolarisasi dalam kubu teknologi yang kaku, ruang pilihan akan menyempit dan biaya strategis akan meningkat.
Negara seperti Indonesia, yang tidak memiliki kepentingan untuk memusuhi salah satu pihak, justru akan dirugikan oleh dikotomi semacam itu. Karena itu, fleksibilitas bukan sekadar sikap, melainkan kebutuhan strategis agar ruang manuver tetap terbuka.
Bebas aktif di era AI berarti fleksibel dalam memilih mitra, tetapi tegas dalam menetapkan kepentingan. Tidak alergi terhadap investasi asing, tetapi juga tidak menyerahkan kendali strategis. Ini bukan soal nasionalisme emosional, melainkan manajemen risiko jangka panjang.
Lapangan kerja berkualitas
Memelihara kepentingan nasional di era AI sebenarnya sederhana, yaitu kedaulatan data harus dijaga, produktivitas ekonomi harus meningkat, dan lapangan kerja berkualitas harus tercipta.
Tiga hal ini perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret di panggung global. Indonesia perlu hadir dalam forum internasional dengan proposal yang terukur: angka investasi yang realistis, peta talenta digital yang transparan, serta rencana pembangunan pusat data nasional yang kredibel.
Artinya, bukan sekadar menyetujui teks deklarasi bersama, melainkan menunjukkan kesiapan yang bisa dihitung dan dievaluasi. Dunia bisnis di mana pun menghargai kesiapan dan kepastian, bukan hanya niat baik.
Indonesia bisa ikut mendukung tata kelola global yang etis dan aman, tetapi juga harus menegosiasikan insentif bagi pelaku usaha nasional. Ruang fiskal dan kebijakan industri tidak boleh tergerus oleh komitmen yang terlalu umum. Diplomasi ekonomi harus berjalan seiring diplomasi politik.
Tentu saja, realisme bukan berarti sinis terhadap kerja sama global. Ia berarti sadar posisi dan kapasitas diri. Sadar bahwa teknologi adalah arena kompetisi yang nyata dan sadar bahwa kedaulatan hari ini sebagian besar ditentukan oleh kemampuan ekonomi digital.
Di sisi lain, multilateralisme berarti percaya bahwa kolaborasi bisa menciptakan stabilitas dan kepastian. Tanpa aturan bersama, ketidakpastian pasar bisa merugikan semua pihak. Karena itu, Indonesia tidak boleh absen dari forum-forum yang merumuskan aturan tentang AI ekonomi digital global.
Di saat yang sama, setiap perubahan lanskap teknologi harus direspons dengan penyesuaian strategi. Pasalnya, tidak ada posisi yang statis dalam ekonomi digital.
Forum AI global akan terus berkembang dan penuh tarik-menarik kepentingan. Standar akan berubah seiring meningkatnya inovasi. Kompetisi akan makin tajam dan mahal. Indonesia harus hadir bukan sekadar sebagai peserta, tetapi juga ikut sebagai perancang masa depan digitalnya sendiri.
Pilihan strategis Indonesia yaitu memastikan bahwa dalam setiap kesepakatan global, kepentingan nasional tetap terjaga. Bebas aktif di era AI berarti pula berani bekerja sama tanpa kehilangan kendali. Dengan kata lain, kerja sama boleh luas, tapi keputusan akhir tetap senantiasa ditimbang berdasarkan manfaat bagi rakyat, bukan berdasar tekanan eksternal.
*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Tetapi, setiap idealisme global selalu bertemu realitas kepentingan nasional masing-masing negara.
Berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AI, di New Delhi, India, baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengapungkan gagasan soal AI yang inklusif dan bisa diakses semua pihak. Guterres mengingatkan bahwa masa depan tak boleh ditentukan segelintir negara atau miliarder teknologi. Pesan moralnya kuat dan menggugah.
Meski demikian, dalam realita, moral global sering kali berbenturan dengan kalkulasi ekonomi politik yang lebih keras. Geopolitik jarang berjalan di atas keindahan retorika, lantaran ia kerap bertumpu pada kepentingan, kekuatan, dan kemampuan membiayai ambisi. Dalam arena seperti ini, siapa yang menguasai teknologi, dialah yang berpeluang menentukan standar global, mengatur arus keuntungan ekonomi, dan membentuk aturan main yang diikuti negara lain.
Tidak ikut blok
Sejak awal berdirinya, Indonesia punya satu pegangan yaitu politik luar negeri bebas aktif. Ia tidak ikut blok mana pun, tetapi juga tidak pasif menunggu siapa yang sedang unggul dalam persaingan global sebelum menentukan sikap. Prinsip ini sudah teruji dalam ketegangan Perang Dingin. Kini ia diuji kembali dalam kontestasi teknologi yang jauh tak kalah menentukan.
Masalahnya, AI dewasa ini bukan sekadar teknologi tambahan di atas model ekonomi lama. Ia adalah infrastruktur kekuasaan baru. Negara yang menguasai data, komputasi, dan talenta bakal menguasai peta produktivitas masa depan. Dari situlah pengaruh ekonomi dan politik akan mengalir deras.
Forum multilateralisme memang memberi ruang dialog yang relatif setara. Negara besar dan negara berkembang bisa duduk di meja yang sama, membahas etika dan standar bersama. Indonesia secara historis nyaman di forum seperti itu karena tradisi diplomasi kolektifnya kuat. Namun, ruang dialog yang setara belum tentu otomatis memberi keuntungan strategis jika tidak diikuti kesiapan ekonomi dan teknologi di dalam negeri.
Realisme mengingatkan bahwa di balik meja bundar, ada meja persegi panjang tempat keputusan bisnis besar ditentukan. Di sana, investasi dan kontrol teknologi menjadi bahasa utama. Artinya, kekuatan finansial sering kali lebih berpengaruh daripada legitimasi normatif. Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap fakta ini.
Jika Indonesia terlalu normatif, ia bisa kehilangan momentum ekonomi. Jika terlalu pragmatis, ia bisa kehilangan konsistensi kebijakan luar negerinya. Di sinilah keseimbangan menjadi seni yang rumit.
Dihitung sejak awal
Dana AI global yang diusulkan PBB terdengar memang menjanjikan bagi negara berkembang. Ada harapan untuk membangun kapasitas, melatih talenta dan sekaligus menyediakan komputasi terjangkau. Akan tetapi, bantuan selalu datang dengan ekosistem dan standar teknologinya sendiri. Itu berarti ada struktur ketergantungan yang perlu dihitung sejak awal.
Dalam hal ini, ekosistem berarti perangkat lunak tertentu, penyedia cloud tertentu, bahkan arsitektur keamanan tertentu. Standar berarti arah pengembangan yang mungkin tidak sepenuhnya fleksibel. Adapun ketergantungan berarti ruang negosiasi yang menyempit dalam jangka panjang. Indonesia perlu membaca ini dengan kepala dingin.
Suka atau tidak, kerja sama global tetap penting dan tak bisa dihindari. Tanpa kolaborasi, kita bisa tertinggal dalam riset dan pengembangan. Sungguhpun demikian, kerja sama harus dirancang sebagai kemitraan setara, bukan relasi pemasok dan pelanggan. Perbedaan keduanya bakal sangat menentukan masa depan industri nasional.
Indonesia tak pelak punya pasar besar dengan jutaan pengguna digital aktif. Juga punya bonus demografi yang bisa menjadi tenaga kerja digital produktif. Selain itu, punya pula ekosistem startup yang mulai menemukan model bisnis berkelanjutan. Semua itu adalah modal tawar, bukan sekadar angka-angka dalam laporan tahunan.
Di forum global, Indonesia perlu lebih dari sekadar memberikan dukungan pada resolusi normatif. Ia perlu pula membawa agenda ekonomi yang terukur dan konkret. Alih teknologi, pengembangan pusat data domestik, dan pelatihan talenta harus menjadi bagian dari negosiasi.
AI bukan hanya perkara regulasi dan standar etika. Ia juga menyangkut investasi miliaran dolar dan kontrak jangka panjang, menyangkut pula soal siapa yang membangun pusat data dan siapa yang menyuplai energinya, serta soal siapa yang memegang lisensi model dan siapa yang membayar biaya langganan.
Multilateralisme memberi legitimasi internasional. Adapun realisme memberi daya tahan dalam persaingan. Indonesia perlu memadukan keduanya secara cerdas. Bukan memilih salah satu, tetapi menjahit keduanya dalam strategi yang koheren.
Memainkan peran penyeimbang
Dalam beberapa periode sejarah -- terutama pada era awal Perang Dingin dan dalam dinamika geopolitik Asia Tenggara -- Indonesia pernah memainkan peran penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar. Ia bukan pemimpin blok, tetapi penghubung yang dipercaya. Peran itu agaknya relevan kembali dalam tata kelola AI global. Namun kali ini, sebagai penghubung, Indonesia harus juga kuat secara ekonomi.
Indonesia, misalnya, bisa mendorong prinsip keadilan akses dan perlindungan untuk negara berkembang. Tetapi, pada saat yang sama, ia harus pula memastikan industri dalam negerinya naik kelas. Jangan sampai kita hanya menjadi reseller teknologi global dengan margin tipis. Maka, transformasi harus terjadi di dalam negeri.
Forum global tetap penting sebagai arena pembentukan norma. Tanpa norma, pasar bisa berjalan liar dan tidak adil. Namun demikian, norma tanpa kapasitas domestik hanya akan menjadi arsip diplomatik. Kekuatan nyata tetap terletak pada kesiapan nasional.
Untuk itu, setiap komitmen internasional harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di dalam negeri, mulai dari insentif fiskal hingga regulasi perlindungan data, dari pendidikan vokasi hingga riset universitas. Diplomasi yang baik selalu punya ekor kebijakan di ranah domestik.
Indonesia perlu waspada terhadap fragmentasi digital dunia ketika ekosistem teknologi, standar data, dan infrastruktur siber terbelah ke dalam blok-blok eksklusif yang saling bersaing. Jika dunia terpolarisasi dalam kubu teknologi yang kaku, ruang pilihan akan menyempit dan biaya strategis akan meningkat.
Negara seperti Indonesia, yang tidak memiliki kepentingan untuk memusuhi salah satu pihak, justru akan dirugikan oleh dikotomi semacam itu. Karena itu, fleksibilitas bukan sekadar sikap, melainkan kebutuhan strategis agar ruang manuver tetap terbuka.
Bebas aktif di era AI berarti fleksibel dalam memilih mitra, tetapi tegas dalam menetapkan kepentingan. Tidak alergi terhadap investasi asing, tetapi juga tidak menyerahkan kendali strategis. Ini bukan soal nasionalisme emosional, melainkan manajemen risiko jangka panjang.
Lapangan kerja berkualitas
Memelihara kepentingan nasional di era AI sebenarnya sederhana, yaitu kedaulatan data harus dijaga, produktivitas ekonomi harus meningkat, dan lapangan kerja berkualitas harus tercipta.
Tiga hal ini perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret di panggung global. Indonesia perlu hadir dalam forum internasional dengan proposal yang terukur: angka investasi yang realistis, peta talenta digital yang transparan, serta rencana pembangunan pusat data nasional yang kredibel.
Artinya, bukan sekadar menyetujui teks deklarasi bersama, melainkan menunjukkan kesiapan yang bisa dihitung dan dievaluasi. Dunia bisnis di mana pun menghargai kesiapan dan kepastian, bukan hanya niat baik.
Indonesia bisa ikut mendukung tata kelola global yang etis dan aman, tetapi juga harus menegosiasikan insentif bagi pelaku usaha nasional. Ruang fiskal dan kebijakan industri tidak boleh tergerus oleh komitmen yang terlalu umum. Diplomasi ekonomi harus berjalan seiring diplomasi politik.
Tentu saja, realisme bukan berarti sinis terhadap kerja sama global. Ia berarti sadar posisi dan kapasitas diri. Sadar bahwa teknologi adalah arena kompetisi yang nyata dan sadar bahwa kedaulatan hari ini sebagian besar ditentukan oleh kemampuan ekonomi digital.
Di sisi lain, multilateralisme berarti percaya bahwa kolaborasi bisa menciptakan stabilitas dan kepastian. Tanpa aturan bersama, ketidakpastian pasar bisa merugikan semua pihak. Karena itu, Indonesia tidak boleh absen dari forum-forum yang merumuskan aturan tentang AI ekonomi digital global.
Di saat yang sama, setiap perubahan lanskap teknologi harus direspons dengan penyesuaian strategi. Pasalnya, tidak ada posisi yang statis dalam ekonomi digital.
Forum AI global akan terus berkembang dan penuh tarik-menarik kepentingan. Standar akan berubah seiring meningkatnya inovasi. Kompetisi akan makin tajam dan mahal. Indonesia harus hadir bukan sekadar sebagai peserta, tetapi juga ikut sebagai perancang masa depan digitalnya sendiri.
Pilihan strategis Indonesia yaitu memastikan bahwa dalam setiap kesepakatan global, kepentingan nasional tetap terjaga. Bebas aktif di era AI berarti pula berani bekerja sama tanpa kehilangan kendali. Dengan kata lain, kerja sama boleh luas, tapi keputusan akhir tetap senantiasa ditimbang berdasarkan manfaat bagi rakyat, bukan berdasar tekanan eksternal.
*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran