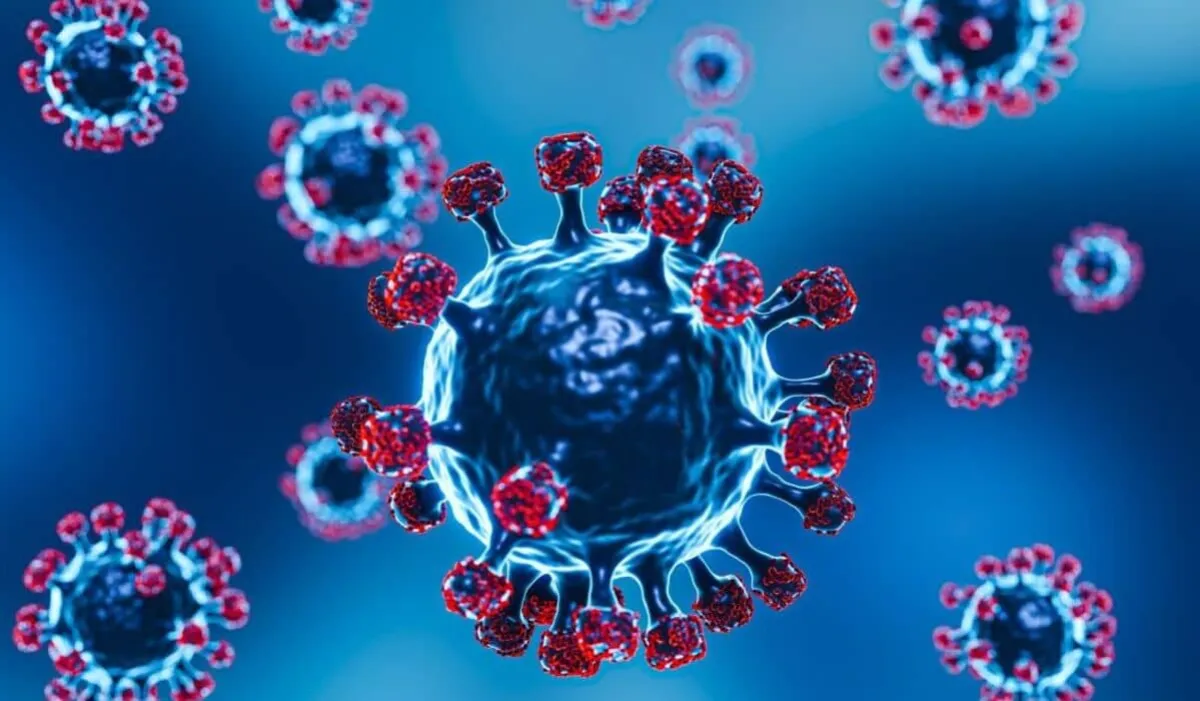Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (PP 48/2025) merupakan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah demi kepentingan umum, pemerataan ekonomi, serta penataan ruang yang berkelanjutan. Regulasi ini pada dasarnya merupakan instrumen korektif terhadap praktik penguasaan tanah yang tidak produktif, spekulatif, atau menyimpang dari peruntukan tata ruang.
Di tengah tujuan normatif tersebut, muncul kegelisahan di masyarakat. Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan, ketidakjelasan kriteria “tanah terlantar”, hingga ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, pendekatan legal sosiologis menjadi penting untuk memahami isi PP 48/2025 sehingga tidak hanya dipahami sebagai teks hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berdampak langsung pada relasi negara dan masyarakat.
Dalam kerangka normatif, secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah mengandung fungsi sosial.
Dalam kerangka tersebut, PP 48/2025 memberikan dasar operasional bagi negara untuk:
1. Mengidentifikasi tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
2. Memberikan peringatan dan pembinaan kepada pemegang hak;
3. Menetapkan tanah sebagai tanah terlantar apabila tidak ada itikad baik;
4. Mengambil langkah administratif lanjutan sesuai ketentuan hukum.
Secara normatif, langkah ini sah dan sejalan dengan asas keadilan distributif. Tanah sebagai sumber daya terbatas tidak boleh dikuasai secara pasif tanpa kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, legitimasi normatif saja tidak cukup. Hukum yang efektif bukan hanya hukum yang tertulis dengan baik, tetapi hukum yang diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat.
Dalam perspektif legal sosiologis, yaitu: antara teks hukum dan realitas sosial, terdapat pandangan bahwa hukum sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan nilai, struktur ekonomi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks PP 48/2025, terdapat beberapa realitas sosial yang perlu dicermati:
Pertama, ketimpangan informasi dan literasi hukum. Ketimpangan informasi dan literasi hukum menjadi salah satu akar persoalan dalam kebijakan penertiban tanah. Tidak semua pemegang hak atas tanah memahami secara utuh bahwa hak atas tanah dalam sistem hukum nasional tidak saja bersifat privat, melainkan juga mengandung dimensi sosial dan kewajiban tertentu terkait pemanfaatannya.
Dalam konstruksi hukum agraria, hak atas tanah pada dasarnya melekat dengan kewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai peruntukan, menjaga fungsi sosialnya, serta tidak menelantarkannya. Namun, norma ini sering kali berhenti pada teks peraturan dan tidak terinternalisasi secara efektif di tingkat masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah pinggiran, memegang tanah sebagai aset warisan keluarga atau sebagai bentuk tabungan jangka panjang. Tanah dipandang sebagai “jaminan masa depan” yang sewaktu-waktu dapat dijual, diagunkan, atau diwariskan kembali.
Dalam konteks sosial-ekonomi tertentu, tidak memanfaatkan tanah secara aktif bukanlah bentuk pelanggaran yang disengaja, melainkan strategi bertahan hidup. Minimnya akses terhadap informasi hukum, keterbatasan penyuluhan agraria, serta rendahnya literasi mengenai tata ruang dan kewajiban pemanfaatan tanah membuat masyarakat tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari pembiaran tersebut. Ketika negara kemudian hadir dengan kebijakan penertiban misalnya terhadap tanah yang dinilai terlantar atau tidak sesuai peruntukan. Masyarakat kerap merasakan tindakan tersebut sebagai bentuk “hukuman” yang datang secara tiba-tiba. Dari sudut pandang warga, mereka merasa memiliki alas hak yang sah dan tidak pernah diberi peringatan atau pendampingan yang memadai sebelumnya.
Di sinilah terjadi benturan persepsi antara pendekatan normatif negara dan realitas sosial masyarakat. Negara memandang penertiban sebagai penegakan aturan, sementara warga memaknainya sebagai pencabutan hak tanpa proses edukasi yang cukup. Situasi ini menunjukkan adanya kegagalan komunikasi hukum (legal communication gap) antara pemerintah dan masyarakat. Prinsip negara hukum tidak hanya menuntut adanya aturan yang jelas, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut dapat dipahami dan diakses secara setara oleh seluruh warga negara. Literasi hukum yang timpang menciptakan relasi yang tidak seimbang: negara berada dalam posisi mengetahui dan menguasai instrumen regulasi, sementara masyarakat berada dalam posisi pasif dan reaktif.
Dalam kondisi demikian, penertiban berpotensi kehilangan legitimasi sosial karena tidak didahului oleh upaya pembinaan, penyuluhan, atau pemberian kesempatan untuk melakukan penyesuaian.
Oleh karena itu, sebelum melakukan penertiban, negara seharusnya memperkuat program edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban pemanfaatan tanah, termasuk konsekuensi hukum atas penelantaran atau ketidaksesuaian peruntukan. Pendekatan persuasif dan preventif harus didahulukan dibandingkan pendekatan represif. Penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya soal ketegasan sanksi, melainkan juga tentang memastikan bahwa setiap warga memahami secara sadar hak dan kewajibannya. Tanpa itu, penertiban tanah akan terus dipersepsikan sebagai tindakan sepihak yang memperlebar jarak antara negara dan rakyatnya, alih-alih sebagai instrumen penataan ruang yang berorientasi pada kepentingan bersama.
Kedua, ketidakselarasan antara kondisi faktual dan rencana tata ruang. Kritik utama yang perlu ditegaskan adalah adanya ketidakselarasan antara norma perencanaan ruang dan kondisi faktual di lapangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik antara masyarakat dan pemerintah.
Dalam praktik, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering kali tidak tersosialisasi secara luas dan efektif, sehingga masyarakat tidak memahami secara utuh perubahan peruntukan ruang yang terjadi. Ketika kemudian negara menggunakan dokumen tersebut sebagai dasar penertiban, muncul kesan bahwa pemerintah secara sepihak mengubah “aturan main” tanpa memberikan ruang partisipasi yang memadai. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Lebih jauh, perubahan zonasi yang fluktuatif dan kerap mengikuti dinamika kebijakan sektoral atau kepentingan investasi memperlihatkan inkonsistensi dalam perencanaan ruang. Dalam banyak kasus, kawasan yang sebelumnya berkembang sebagai permukiman atau area usaha dengan toleransi pemerintah, bahkan disertai pelayanan administratif seperti pemungutan pajak, tiba-tiba dinyatakan tidak sesuai peruntukan berdasarkan revisi RTRW. Penertiban terhadap kondisi tersebut tanpa mekanisme transisi yang adil berpotensi melanggar asas perlindungan terhadap harapan yang sah (legitimate expectation) masyarakat. Negara tidak dapat mengabaikan fakta bahwa pembiaran atau kelalaian pengawasan selama bertahun-tahun turut membentuk realitas pemanfaatan ruang yang ada.
Selain itu, ketidaksinkronan antara RTRW dan kebijakan pertanahan maupun perizinan memperparah persoalan tersebut. Tidak jarang tanah yang telah memiliki dasar penguasaan atau legalitas administratif justru dinyatakan bertentangan dengan rencana tata ruang terbaru. Dalam situasi demikian, penertiban yang dilakukan secara represif tanpa skema relokasi, kompensasi, atau penyesuaian hak mencerminkan lemahnya koordinasi kebijakan serta kurangnya perlindungan terhadap hak atas tanah. RTRW seharusnya menjadi instrumen pengendalian yang progresif dan korektif, bukan alat legitimasi tindakan administratif yang bersifat mendadak dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan penertiban tanah sesungguhnya tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran tata ruang oleh warga atau masyarakat belaka, melainkan juga menyangkut kualitas perencanaan, transparansi revisi RTRW, serta akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian ruang. Tanpa partisipasi publik yang bermakna dan kebijakan transisi yang berkeadilan, penertiban berpotensi dipandang sebagai tindakan sepihak yang mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum.
Ketiga, trauma historis terhadap konflik agraria. Trauma historis terhadap konflik agraria merupakan faktor psikologis dan sosiologis yang tidak dapat diabaikan dalam setiap kebijakan penertiban tanah. Indonesia memiliki sejarah panjang sengketa dan konflik tanah yang melibatkan masyarakat, korporasi, dan negara, mulai dari masa kolonial dengan praktik domein verklaring, kebijakan konsesi perkebunan skala besar, hingga dinamika pembangunan era modern yang kerap berorientasi pada investasi dan proyek strategis.
Dalam lintasan sejarah tersebut, tanah tidak sekadar dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup, sumber identitas, dan simbol keberlanjutan generasi. Karena itu, setiap intervensi negara atas tanah selalu menyentuh dimensi yang sangat sensitif. Memori kolektif masyarakat mengenai konflik agraria: penggusuran, pencabutan hak, kriminalisasi, hingga ketimpangan penguasaan lahan membentuk persepsi yang bertahan lama. Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat kecil merasa berada pada posisi yang paling lemah ketika berhadapan dengan negara atau korporasi besar yang memiliki akses terhadap modal, kekuasaan, dan perangkat hukum yang lebih kuat. Pengalaman-pengalaman tersebut, baik yang dialami langsung maupun yang diwariskan melalui narasi sosial, menumbuhkan rasa curiga terhadap setiap kebijakan yang berkaitan dengan penataan atau penertiban tanah. Akibatnya, kebijakan penertiban yang secara normatif dimaksudkan untuk menegakkan tata ruang atau mengoptimalkan pemanfaatan lahan sering kali diasosiasikan dengan potensi perampasan atau peminggiran.
Masyarakat cenderung melihatnya bukan semata sebagai penegakan aturan, tetapi sebagai kelanjutan dari pola relasi yang timpang antara negara dan rakyat kecil. Ketika proses penertiban tidak disertai dialog yang transparan, jaminan perlindungan hak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, trauma historis tersebut kembali mengemuka dan memperkuat resistensi. Dari perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formalnya, tetapi juga oleh legitimasi sosialnya. Negara tidak dapat mengabaikan konteks historis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan agraria. Pendekatan yang semata-mata legalistik—berbasis pada norma dan sanksi—berisiko menghidupkan kembali luka lama dan memperdalam ketidakpercayaan publik.
Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan rekognisi terhadap hak masyarakat, transparansi proses, partisipasi yang bermakna, serta perlindungan terhadap kelompok rentan akan lebih mampu meredam trauma kolektif tersebut. Dengan demikian, penertiban tanah di Indonesia harus dibaca bukan hanya sebagai persoalan administrasi atau tata ruang, melainkan sebagai isu yang sarat dimensi historis dan emosional. Mengabaikan sejarah konflik agraria berarti menutup mata terhadap faktor yang justru sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Jika negara ingin membangun tata kelola pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka pengakuan terhadap trauma historis serta upaya membangun kembali kepercayaan publik menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar.
Apabila dimensi sosiologis ini tidak dikelola dengan baik, PP 48/2025 berpotensi menimbulkan resistensi sosial, sengketa hukum, dan delegitimasi kebijakan publik. Maka kepastian hukum dan keadilan prosedural sebagai kunci.
Untuk menjembatani norma dan realitas, terdapat dua prinsip fundamental yang harus dijaga:
1. Kepastian hukum (legal certainty) Kriteria tanah terlantar harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan tidak multitafsir. Prosedur peringatan, pembinaan, hingga penetapan harus transparan dan terdokumentasi.
2. Keadilan prosedural (procedural justice) Pemegang hak harus diberikan kesempatan yang nyata untuk didengar (right to be heard), mengajukan keberatan, serta memperoleh akses terhadap upaya hukum.
Tanpa dua prinsip ini, kebijakan penertiban mudah dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan semata, bukan sebagai upaya penegakan fungsi sosial tanah.
Sehingga sangat diperlukan adanya RTRW yang transparan dan berkeadilan. Mengingat bahwa salah satu akar persoalan dalam penertiban tanah adalah lemahnya akses publik terhadap informasi tata ruang dan wilayah. Padahal, tata ruang merupakan “peta hukum” yang menentukan boleh atau tidaknya suatu tanah dimanfaatkan untuk tujuan tertentu.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu:
1. Membangun Sistem RTRW Digital Terbuka (Open Spatial Plan System).
Seluruh dokumen RTRW dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) harus tersedia secara daring, mudah diakses, dan dilengkapi peta interaktif berbasis koordinat. Masyarakat harus dapat memeriksa status peruntukan tanahnya secara mandiri. Karena Indonesia menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
2. Menjamin partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Penyusunan dan revisi tata ruang tidak boleh bersifat elitis. Konsultasi publik harus dilakukan secara substantif, bukan formalitas administratif. Mengingat keperluan terhadap penyusunan RTRW ini bukan hanya merupakan hajat penguasa, melainkan adalah hajat rakyat sebagai amanat dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, maka sudah seyogyanya masyarakat turut memberikan sumbangsihnya terhadap penyusunan RTRW ini.
3. Mengintegrasikan data pertanahan dan tata ruang. Sinkronisasi antara data hak atas tanah dan rencana tata ruang akan meminimalkan konflik normatif dan administratif. Selain itu, urgensi dari sinkronsasi data ini juga untuk menjamin kredibilitas dan kapabilitas penyelenggara negara atau Lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya.
4. Menyediakan mekanisme koreksi dan keberatan yang efektif. Apabila terdapat perubahan peruntukan ruang yang berdampak signifikan terhadap masyarakat, harus tersedia mekanisme keberatan yang cepat, adil, dan tidak mahal. Selain untuk menjamin hak, mekanisme koreksi dan keberatan yang efektif ini merupakan Langkah agar tercipta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program kerja perancangan RTRW dan RDTR ini.
5. Mengedepankan asas keadilan sosial. Penertiban tanah hendaknya memprioritaskan redistribusi untuk kepentingan publik, reforma agraria, dan pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata membuka ruang konsesi baru bagi kepentingan ekonomi berskala besar.
Menata Tanah, Menata KepercayaanPP 48/2025 pada dasarnya adalah instrumen untuk memastikan tanah tidak menjadi objek “spekulasi” yang menghambat pembangunan dan pemerataan. Namun, keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, melainkan oleh kualitas tata kelola dan sensitivitas sosial negara.
Penertiban kawasan dan tanah terlantar harus dipahami sebagai upaya menata keadilan ruang, bukan sekadar menata administrasi pertanahan. Negara perlu hadir dan memastikan bahwa setiap langkah penertiban dilandasi transparansi, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Hukum agraria yang baik bukan hanya yang mampu menertibkan tanah, tetapi juga yang mampu menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan hanya lahir dari kebijakan yang transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Sehingga falsafah bangsa Indonesia yang termuat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai amanat kepada negara dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan senyata-nyatanya.