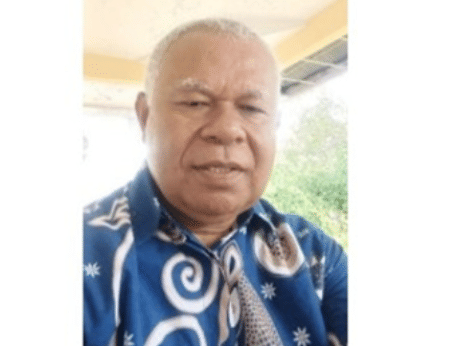SUMATRA kembali menjadi panggung duka. Di bawah langit kelabu yang diguyur hujan tanpa jeda, tanah yang dulu subur kini berubah menjadi kuburan massal. Siklon Senyar bukan sekadar badai; 'lidah angin yang melumat hutan' itu adalah amarah alam yang meletup setelah sekian lama manusia yang bermartabat khalifah fi al-ard (wakil Allah dan/atau pemimpin yang diberi amanah untuk merawat bumi) mengabaikan peringatannya.
Data BNPB mencatat angka yang mencengangkan: hampir seribu nyawa melayang, ratusan masih hilang, dan lebih dari sejuta manusia terusir dari rumah yang mereka sebut 'tempat pulang'. Ribuan sekolah, jembatan, dan rumah hanyut bersama mimpi yang tak sempat selesai.
Lokasi bencana jadi panggung pencitraanHelikopter berputar di langit kelabu, kapal rumah sakit berlayar di sungai yang berubah menjadi lautan lumpur, dan sinyal Starlink dipasang agar suara-suara dari daerah terisolasi tak lenyap ditelan sunyi. Namun, di balik heroisme ini, ada pertanyaan yang mengiris: mengapa kita selalu menunggu bencana untuk bertindak? Mengapa mitigasi selalu tak berdaya di hadapan retorika politis yang sarat dengan kepalsuan?
Kritik publikpun mengemuka. Di media sosial, warganet menyorot bagaimana lokasi bencana kerap berubah menjadi panggung pencitraan. Foto pejabat berseragam lengkap,berpose di tengah puing, lebih cepat beredar daripada rencana aksi nyata. Padahal, para korban lebih membutuhkan solusi, bukan selfie.
Fenomena ini menegaskan jurang antara simbol dan substansi: ketika tragedi menjadi latar drama politik, korban tetap menunggu uluran tangan yang sesungguhnya. Seperti suara Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan, seorang Imam dari Ordo Capusin, Romo Aleks Silaen, dari Medan berkicau: “Bencana bukan panggung untuk pencitraan, melainkan panggilan untuk solidaritas sejati. Jika penderitaan dijadikan latar foto, kita sedang mengkhianati Injil yang mengajarkan kasih yang nyata, bukan kasih yang dipoles kamera.”
Paus Fransiskus juga mengingatkan dalam Evangelii Gaudium: “Pemimpin sejati adalah mereka yang menghidupi pelayanan, bukan mencari kehormatan. Mereka berjalan di tengah umat, bukan di atas panggung” (EG 31). Kutipan ini menegaskan, bahwa kepemimpinan sejati lahir dari kerendahan hati dan keberpihakan kepada warga atau umat yang menderita, bukan sebaliknya, dari pencitraan yang mengorbankan martabat para korban.
Akar masalah: dosa struktural terhadap alamSorotan tajam kini mengarah pada akar persoalan: deforestasi yang rakus, pembalakan liar yang tak pernah benar-benar kita hentikan. Hutan yang dulu menjadi perisai kini tinggal cerita, digantikan oleh ambisi yang menebang tanpa nurani. Kerusakan hutan di Sumatra bukan sekadar angka statistik; kejahatan ekologis tersebut adalah bom waktu yang menelan banyak korban.
Dalam terang iman Katolik, tragedi ini bukan hanya soal alam, tetapi soal moral. Paus Fransiskus dalam Laudato Si' mengingatkan: “Bumi, rumah kita bersama, semakin rusak karena dosa manusia yang mengabaikan tanggung jawab ekologis” (LS .2). Kitab Suci pun bersuara: “Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu” (Kejadian 2:15).
Manusia diberikan mandat ilahi yang clear and clean, yakni bukan untuk mengeksploitasi, tetapi untuk merawat. Ketika sang khalifah merusak ciptaan, kita merusak harmoni yang Allah tetapkan.
Bencana sebagai cermin pertobatanBencana ini adalah cermin retak yang memantulkan wajah kita sendiri-wajah yang abai, serakah, dan tak belajar dari luka yang berulang. Gereja mengajak semua pihak untuk melakukan pertobatan ekologis: mengubah cara pandang dari eksploitasi menuju pemeliharaan.
Paus Fransiskus menulis: “Pertobatan ekologis menuntut kita untuk mengakui kesalahan, dosa, dan kelalaian terhadap ciptaan, serta mengubah gaya hidup menuju kesederhanaan dan tanggung jawab” (LS. 219).
Pertanyaannya sederhana namun menohok: sampai kapan kita akan menulis berita duka, tanpa pernah menulis babak perubahan? Pertobatan ekologis bukan hanya ide, tetapi aksi nyata.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh umat Katolik.
Pertama, doa lingkungan dan katekese hijau. Setiap paroki dapat mengadakan doa khusus untuk korban bencana dan refleksi tentang tanggung jawab ekologis. Misalnya, mengintegrasikan tema ciptaan dalam homili dan katekese.
Kedua, gerakan hijau paroki. Membentuk tim lingkungan di paroki untuk menanam pohon, mengurangi plastik, dan mengelola sampah. Ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi wujud iman yang hidup.
Ketiga, hari doa untuk alam. Mengikuti seruan Paus Fransiskus, paroki dapat menetapkan satu hari khusus untuk doa dan aksi nyata bagi bumi, misalnya pada Hari Doa Sedunia untuk Ciptaan yang jatuh pada setiap tanggal 1 September.
Keempat, advokasi dan edukasi. Mengajak umat untuk mendukung kebijakan yang melindungi hutan dan menolak praktik deforestasi. Ikhtiar untuk mengedukasi publik itu bisa melalui seminar,media sosial,dan komunitas basis.
Selain keempat langkah tersebut, di atas segalanya, lilin solidaritas untuk korban mesti dinyalakan. Menggalang dana dan bantuan untuk korban bencana, bukan hanya sebagai aksi karitatif, tetapi sebagai bentuk kasih yang menghidupkan iman. Mazmur mengingatkan kita:“Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya"(Mazmur 24:1).
Alarm pertobatan ekologisJika bumi adalah milik Tuhan, maka merawatnya bukan sekadar pilihan, melainkan ibadah yang nyata. Tragedi Sumatra bukan hanya kisah tentang banjir dan longsor; air mata duka para korban adalah lonceng yang berdentang keras, mengingatkan kita bahwa pembangunan tanpa etika ekologis adalah jalan pintas menuju kehancuran.
Setelah menyingkap bagaimana lokasi bencana berubah menjadi panggung pencitraan, menelusuri akar persoalan yang berakar pada dosa struktural terhadap alam, dan merenungkan bencana sebagai cermin pertobatan, satu pesan tak terbantahkan: empati saja tidak cukup.
Kita tidak bisa berhenti pada rasa iba. Kita dipanggil untuk melangkah lebih jauh, yakni bertobat, mengubah cara pandang yang eksploitatif, dan menjadikannya aksi nyata berbasis kemanusiaan dan/atau kekhalifahan.
Pertobatan ekologis bukan sekadar jargon teologis, tetapi revolusi moral yang menuntut keberanian: keberanian untuk melawan keserakahan, menolak pencitraan kosong, dan memilih solidaritas yang hidup. Jika kita gagal menjawab panggilan ini, kita sedang menulis undangan untuk tragedi berikutnya.
Mari bertafakur sejenak: apakah kita akan terus menjadi penonton di panggung bencana, atau bangkit sebagai khalifah fi al-ard, sebagai pengelola bumi yang setia pada amanah Sang Pencipta?