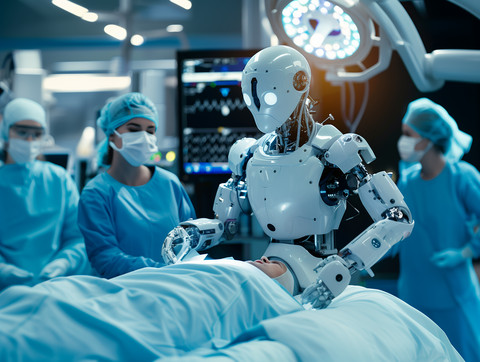Terlintaslah di depan mata kami satu adegan. Sangat menyebalkan. Ada rombongan truk polisi dan barakuda melintas. Dari arah timur. Mungkin sedang dalam proses evakuasi. Saya tidak tahu. Truknya diisi oleh para anggota kepolisian. Memang agak padat. Tapi, tak tampak petugas polisi ini sedang membantu masyarakat.
Di depan mata, saya menyaksikan adegan yang menyebalkan. Sepasang suami-istri yang tampak kelelahan berjalan kaki, minta tolong menumpang ke rombongan polisi tadi. Dari bawaannya, kelihatannya sedang berusaha menuju Banda Aceh juga.
Sang suami minta tolong seraya membuka pintu bak truk yang berhenti. Para polisi melarangnya. Suami-istri itu hanya termangu. Kecewa. Kunci pintu bak truk yang sudah dibuka, ditutup kembali. Oleh salah satu polisi, badannya tegap.
Pak Polisi, bukankah sudah tugasmu melindungi dan melayani?
Pak Polisi, bukankah rakyat membayar pajak untuk membiayaimu?
Dalam keadaan banjir besar dan kesulitan pun, rakyat belanja di mana-mana tetap bayar pajak. Tapi, ketika tiba saat rakyat minta tolong, karena mereka memang benar-benar butuh pertolongan, kok diabaikan begitu saja?
Sekadar intermezzo, setiba di Banda Aceh, ketika sinyal nongol, di Tiktok tersiar video “Ikrar Ksatria Polri”: mau jadi polisi yang melindungi dan melayani. Ikrar dipimpin oleh Pak Kapolri. Diikuti oleh para perwira tinggi. Dihiasi dekorasi obor bambu dan minyak. Mirip seperti persami (perkemahan sabtu-minggu) zaman pramuka kami ketika SD. Ironis. Budaya verbalisme makin menguat. Seolah-olah sudah mengerjakan sesuatu ketika mengatakannya.
Coba cermati isi ikrar tersebut. Perhatikan baik-baik kata demi katanya. Tidak ada satu pun kata bertenaga, mengentak kesadaran internal untuk melakukan koreksi total, atau meyakinkan publik bahwa suatu pembenahan fundamental sedang ditempuh. Bahkan Tim Reformasi yang dipimpin oleh Prof Jimly Asshiddiqie pun seperti tenggelam. Wallahua’lam.
Selera Asal Tak Bisa Jauh-JauhSudah cukup lama menahan-nahan untuk buang air kecil, akhirnya saya minta izin masuk kantor Koramil. Numpang ke toilet. Ternyata kantor itu sudah tiga hari terendam banjir. Di depan, ada pos jaga. Agak tinggi. Digunakan mengungsi warga sekitar.
Di dalam ruangan, genangan air masih ada. Tingginya 5 sampai 10 sentimeter. Menjelang kamar mandi, di halaman belakang ada beberapa istri prajurit tengah memasak untuk para suaminya. Rupanya ada beberapa anggota yang tinggal di mess.
Selesai dari toilet, ada tiga orang yang sedang makan. Di meja ada seonggok gorengan yang hangat. Tempe, bakwan, dan tahu goreng. Dalam keadaan basah dan dingin mendung, tentu gorengan sangat memancing selera. Tanpa rasa malu, saya minta izin ke tentara yang sedang makan.
“Pak, boleh minta satu gorengan?”
“Ya, Silakan. Silakan!”
Selera asal memang tak bisa jauh-jauh.
Rakyat Memang HebatKerumunan di depan kantor Koramil 20/Bandar Dua mulai ramai. Cuaca tidak segelap jam-jam sebelumnya. Rupanya ada pejabat Dinas Sosial dan politisi Partai Gerindra. Saya menemui mereka yang sedang bersama sama beberapa anggota Koramil.
Ada yang langsung menyapa, karena mengenali. Kami berbincang-bincang soal bantuan kepada warga. Anggota DPRD Gerindra (lupa namanya) bercerita, bahwa dua hari ini stok SPPG dialokasikan semua ke warga yang terkena musibah. Tapi, dapur memang tidak beroperasi. Karena banjir.
Pak Kepala Dinas Sosial menyampaikan, Dinas Sosial sudah menyiapkan stok bahan makanan. Untuk dibagi. Beras, mi, dan lain-lain. Telur sudah tidak ada di pasaran. Pasar beberapa hari tutup karena pedagangnya juga kena banjir.
Kesulitan Dinas Sosial adalah soal membagi logistik dan mengetahui di mana pusat-pusat pengungsian berada. Karena tidak ada jalur komunikasi.
Saya tanya pada kerumunan, “Bapak-Bapak di Koramil dan Pemda tidak ada handytalkie? Atau sistem komunikasi emergency?”
“Putus semua, Pak. Handytalkie tak ada baterai karena listrik mati,” jawab mereka.
Saya merenung dalam-dalam. Betapa lemahnya sistem kedaruratan kita. Mungkin ini perlu kita tanyakan kepada para pengurus negara yang membidanginya. Dalam masygul, tetiba ada penghibur suasana batin. Satu truk dump melintas. Di atasnya, menumpanglah sejumlah warga. Truk dihentikan oleh satu anggota Koramil, dan minta agar sopir mengangkut beberapa orang yang terlihat kelelahan.
“Bang, nitip. Ini kawan-kawan. Jalannya masih jauh. Arah Aceh Besar,” pesannya.
Si sopir dengan suka-cita menyahut, “Ayo, naik, naik!”
Rakyat memang top!
Pak Kadis Menjaga SSPak Kadis Sosial, dengan rompi Satgana, rupanya juga pengurus PMI Pidie Jaya. Saya lupa namanya. Ia tengah beraksi di lapangan. Dibantu beberapa stafnya. Begitu kami bersiap naik kendaraan, dan pamit, Pak Kadis minta nomor kontak saya.
Sejurus kemudian, beliau menghentikan truk besar, dan meminta sopir truk untuk memberi ruang bagi kendaraan kami. Bila diawali oleh truk besar, memang lebih aman. Seperti dibukakan jalan. Dan air jadi tidak begitu dalam.
Abang pengemudinya langsung merapatkan mobil di belakang truk besar. Ya Tuhan, di bagian belakang truk kontainer itu, ada tulisan mencolok sekali.
“Jaga SS. SS Jaga Jarak.”
Pak Kadis yang sesama pegiat kemanusiaan, rupanya telah membuka jalan untuk menjaga rombongan kami. Truk melaju perlahan. Melintasi wilayah paling dalam. Kami tengah mengikutinya dengan penuh kehati-hatian. Semoga jalan keluar ke Banda Aceh segera terbuka.
Solidaritas yang BeraniDi beberapa titik, ada warga yang mau numpang. Dan, berhenti dengan seketika. Mempersilakan warga numpang melintasi genangan yang dalam.
Tadi pagi, 07.00 WIB, Ketua Ansari Muhammad mengambil keputusan yang mengharukan. Satu mobil tidak bisa di-starter. Tapi, kami bersepakat dengan keputusan Bung Ansari Muhammad. Semua penumpang harus bersama. Tidak ada yang boleh tinggal. Bung Furqan, pengemudi mobil sewa, harus menunggu kendaraannya diambil dengan ditarik, atau naik truk. Jadilah satu mobil Fortuner kami dimuati delapan penumpang.
Saya dan Bung Zulfan di depan. Jok belakang, dua orang. Jok tengah, empat orang. Jok belakang dikosongkan satu. Karena harus mengangkut serta tas dan perlengkapan bawaan.
Saya di depan, memangku koper.
Seharian, setahap demi setahap halangan dilewati.
Setiap merasa capai karena duduk berdesakan, kami pun beristirahat. Meluruskan kaki. Sambil cari toilet. Atau makanan dan minuman. Jam menunjukkan pukul 15.46 WIB. Harapan kami semakin membuncah untuk bisa melewati titik-titik paling rawan.
Di depan, terlihat ada satu tanjakan. Menikung dan cukup curam. Sehingga, genangan airnya paling ekstrem. Alhamdulillah bisa kami lalui. Seorang petugas berseragam jas hujan bertuliskan “Polisi”, dibantu sejumlah warga, membantu mengatur arus kendaraan. Supaya bisa naik satu per satu melewati titik paling rawan.
Alhamdulillah, keputusan Bung Ansari Muhammad untuk menjaga solidaritas agar seluruh anggota tim terbawa, sungguh berarti. Saya sudah 30 tahun lebih belajar dan mengajar kepemimpinan. Juga menyebarluaskan nilai-nilai kepemimpinan. Kepemimpinan (dalam krisis) Bung Ansari Muhammad sungguh kaya makna. Saya berniat untuk mengundangnya bercerita perjalanan menempuh krisis ini pada sesi TSLB Angkatan ke-10.
Betapa Bahagianya MerekaRupanya, truk “Jaga SS” membuka kontainernya dan memberi keselamatan kepada siapa pun yang akan menumpang.
Serombongan santri dayah (pesantren) menyetop truk. Katanya, mereka telah berjalan kaki sejak pukul 13.00 WIB.
Beramai-ramai mereka naik truk di tengah genangan. Ah, betapa bahagianya anak-anak itu.
Listrik dan Telepon Mati Lama, Masih Adakah BUMN Kita?Bung Ansari Muhammad benar. Dulu, ketika tsunami, listrik mati. Beberapa gardu induk tumbang. Kapal PLTD sedemikian besarnya yang tengah bersandar di Pantai Ulee Lheue sampai terlempar masuk 6 kilometer ke pemukiman warga. Listrik Banda Aceh padam, tapi tak sampai berhari-hari. Mengapa ketika keadaan jauh lebih baik, sistem kelistrikan kok bisa drop dan berhari-hari tak kunjung solusi? Apa yang salah dengan manajemen PLN?
Saya menerawang jauh ke belakang, ketika BUMN-BUMN yang vital dipimpin oleh orang-orang berdedikasi penuh dan integritas nircela. Pada masa lalu, ada manusia-manusia model Kuntoro Mangkusubroto, Arie Soemarno, atau Dahlan Iskan.
Ada juga Ignatius Jonan yang membereskan kereta api. Sofyan Djalil yang menahkodai Kementerian BUMN dengan profesional. Atau bankir setara Robby Djohan yang membereskan Garuda.
Di Telkom, kita mengenal Cacuk Sudarjanto yang mereformasi PT Telkom besar-besaran. Sekarang, BUMN Telkom malah dijadikan bancakan, dicuri dari segala sisi oleh para profesional fakir malu.
Pembangunan BTS-nya digarong oleh para politisi, pejabat negara, hingga pengusaha culas yang tidak mengerjakan kewajibannya. Merger dan akuisisinya dibantu oleh lawyer dan penasihat keuangan serakah. Dibuat bangkrut. Terus, memungut pulsa ke rakyat. Tapi, ketika terjadi kelumpuhan massal telekomunikasi, satu suara pun tiada mengemuka, apalagi muka mereka.
Dalam satu dekade belakangan, BUMN kita diurus oleh para pemain salon. Kinclong. Berkilau-kilau. Gemar nian pada upacara, flexing. Akan tetapi, ketika krisis benar-benar datang menimpa rakyat, gagap dan gagal.
Sepanjang empat hari berlalu-lalang di Aceh, mulai dari Banda Aceh, Pidie, Sigli, Bireuen, Takengon, Bener Meriah, hingga kembali ke Banda Aceh, tak satu kali pun kami bertemu petugas PLN atau Telkom yang sedang berupaya mencari solusi. Atau menemani rakyat. Maaf, tidak ada!
Ending: Di Banda AcehMelintasi tiga genangan terberat merupakan perjuangan penuh risiko. Mau menunggu, sayang. Karena perjalanan sudah makin mengarah ke Barat. Alias sudah separuh jalan dari Bireuen memasuki Pidie Jaya dan Pidie.
Di satu genangan yang cukup tinggi dan deras airnya, mobil kami sempat berpapasan dengan pengendara motor, anak muda. Ia terpeleset. Motornya terbawa arus ke arah kanan kami yang memang terlihat seperti laut lepas dengan arus tanpa kendali.
Di titik genangan berikutnya, kendaraan di depan kami memotong antrean dan mendahului kami. Kendaraan pemotong antrean itu body-nya rendah. Jadi, ketika masuk genangan dalam, mesinnya nyaris mati dan mobil melambat.
Kami khawatir sekali ikut berhenti dan mesin mati, sesuatu yang pernah kami alami di Peudada, sehari sebelumnya. Beruntung, ada tanjakan dan mobil di depan kami minggir ke tanjakan, membuka jalan bagi kami untuk kembali bergerak lebih cepat.
Di tanjakan titik terberat di Meureudu, iringan mobil harus ditata, hanya bisa naik satu per satu. Jalannya lumayan curam, menyebabkan genangan sebelum tanjakan itu lebih dalam dibanding seluruh genangan yang pernah kami lewati.
Dengan bantuan seorang petugas berjas hujan dengan grafir "POLISI", kami dibimbing dengan ketat agar tidak masuk lubang. Beberapa hari tergenang air menyebabkan sebagian jalan lepas aspalnya. Juga menciptakan lubang-lubang. Bila roda terjebak di lubang jalan yang rusak berat, bisa celaka. Bukannya mentas naik, malah makin amblas.
Alhamdulillah, tanjakan Meureudu kami lewati dengan mulus. Sampailah ke kota Pidie. Wah, macetnya bukan main.
Semua yang baru lepas dari kubangan raksasa, seperti ingin melepas tegang dan lelah sambil mengistirahatkan mobil. Yang akan masuk ke “kubangan” besar Meureudu harus antre dan siap-siap. Karena macet, kami dibelokkan ke kanan, masuk lewat samping Masjid Besar, melewati jalan di depan pasar. Ternyata kemacetan panjang ada di depan, berlawanan arah. Mobil kami harus melipir di bagian kanan. Harus ekstra hati-hati, karena di bagian kanan, jalan beberapa titik ada got yang terbuka. “Hati-hati Pak, di depan sekolah ada got.”
Saya dan Bung Ansari memutuskan turun, diikuti Audi. Kami turun itu untuk membimbing mobil sembari memintajalan dari mobil-mobil yang merayap dari arah berlawanan. Padahal genangannya setengah meter. Dalam tempo setengah jam, kami berhasil keluar dari genangan air. Lalu masuk ke jalan yang relatif kering. Sebenarnya ada bekas genangan, tapi tampaknya telah mulai surut. Banyak mobil berhenti karena pengendaranya kelelahan. Setengah jam perjalanan, tiba-tiba ada suara ponsel menerima pesan. Kami semua serentak mengecek ponsel. Dan, benar. Rupanya ada sinyal masuk lumayan besar.
Tanpa buang-buang waktu, saya segera menelepon istri, Astried, dan video call dengan anak-anak yang sedang berkumpul. Saya juga mengirim pesan untuk semua kolega yang saya kirimi pesan—siapa tahu setelah ini sinyal mati. Tanpa sadar, air mata mengalir. Campur aduk. Bersyukur, bahagia, tapi juga membayangkan teman-teman lain yang masih tertinggal, termasuk Yuki Yusuf, Pak Murdani, 50-an kawan yang kabarnya belum bisa keluar dari Takengon. Perjalanan berikutnya adalah tiga jam menuju Banda Aceh, pukul 16.00 WIB dan seterusnya.
Tampaknya, listrik masih padam. Sinyal sesekali saja muncul, tapi kebanyakan masih hilang. Menjelang magrib, Sigli sudah tampak di depan. Kami berhenti di masjid besar, menjamak salat. Di Masjid tersedia penerangan lampu. Tapi energinya dari genset. Di masjid, sinyal cukup besar. Saya menyempatkan diri untuk menelepon satu-dua anggota keluarga dan kolega.
Pada 21.30 WIB, kami melewati Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh besar. Lanjut ke jalan tol yang sudah berfungsi sepotong, masuklah kami ke Kota Banda Aceh. Tentu saja penuh syukur. Saya menelepon Pak Taqwallah, memberi kabar. Pak Taqwa menyusul ke tempat minum kopi. Kami sedang beriung di “BTJ Kopi,” di belakang Kejaksaan Tinggi Aceh, Gampong Lampeuneurut.
Setelahnya, kami masuk penginapan di sebuah hotel dekat Pantai Ulee Lheue. Yang menarik, listrik PLN masih padam. Perkampungan gelap-gulita. Tapi hotel, restoran, dan kedai kopi, penuh manusia. Rupanya, banyak warga mengungsi ke hotel karena tidak ada listrik dan tak bisa masak. Mereka duduk di warung-warung kopi yang jumlahnya ratusan. Sambil mengudap serta mengisi baterai ponsel dan mendapatkan sinyal.
Saya membatin, sebanyak-banyaknya warga yang bisa menginap di hotel dan makan di restoran berhari-hari, pastilah itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar, ya di rumah, menunggu ketidakpastian. Mendekam dalam kegelapan. Tanpa pasokan air bersih. Tanpa sinyal telekomunikasi. “Ini orang kebanyakan, siapa yang menolong mereka ya?” gumam saya kepada teman-teman.
Jakarta MeresponsSaya mengontak beberapa teman di pemerintahan. Termasuk seorang perwira tinggi aktif yang tugasnya mengurus pusat kendali sebuah instansi strategis. Saya jelaskan detail-detail cerita berikut suasananya. Cerita itu saya lengkapi dengan mengirimkan foto dan video yang berhasil direkam oleh Audi bersama Tim PMI. Yang bersangkutan terperanjat, “Saya akan segera membuat laporan detail untuk mendapat atensi para pimpinan. Terima kasih, Pak”.
Kepada seorang sahabat, Mas Hendri Satrio, cerita yang sama saya jelaskan berikut fotonya. Dia merespons cepat, mengirimkan kepada berbagai media. Dalam beberapa waktu, sejumlah media menghubungi saya, minta penjelasan keadaan lapangan. Alhamdulillah, beberapa wawancara langsung ditayangkan.
Harapannya, semoga bisa menggugah kesadaran bahwa keadaan Aceh jauh lebih serius daripada yang dimamah dan dipahami oleh otoritas di Jakarta. Saya meminta izin kepada Sekjen PMI, Pak Abdurrahman Mohammad Fachir, untuk terus memberi informasi kepada media. Dengan maksud agar suasana di lapangan bisa diceritakan lebih akurat, bukan sekadar pernyataan pers. Sejak Kamis (27/11) malam, hingga Jumat (28/11) siang, saya terus menerima permintaan wawancara radio, media cetak, media daring, maupun televisi.
Hari Jumat (28/11), seharian, mulai tampak gerakan dari Pengurus Negara di Jakarta. Mulai bergeliat. PMI rupanya diikutsertakan dalam mobilisasi bantuan penyelamatan dan pengelolaan logistik nasional. Ini tentu pertanda bagus— meski diselingi pernyataan blunder Kepala BNP, bahwa bencana ini seolah hanya ramai di media sosial.
Saya enggak bisa berkomentar lagi. Betapa seorang pimpinan tertinggi institusi penanggulangan bencana kok sampai bisa mengambil posisi meremehkan skala dan keseriusan suatu bencana. Bukankah yang harus dilakukan adalah mengajak semua masyarakat agar terus waspada, bersiaga, dan saling bantu?
Belakangan, orang ini meminta maaf kepada publik. Satu hal yang saya cermati: dari pilihan katanya dan bahasa tubuhnya, tampak jelas bahwa yang bersangkutan tidak menghayati betul tugasnya. Dia melihat kedudukannya sebagai pekerjaan semata, semacam jenjang atau jalan karier. Jadi, ketika dihadapkan pada tantangan nyata, bencana besar mencekam, ia kehilangan kata-kata. Jangankan bertindak tepat, berpikir dan berkata tepat saja tidak mampu. Pantaslah kalau warga marah tiada terkira.
Rakyat, Siapa yang Menolongnya?Nyaris tengah malam, saya masuk hotel. Mata sulit terpejam karena pikiran terasa penuh. Hati pun campur-campur. Bersyukur, tentu saja, karena saya penyintas yang selamat dari genangan. Tapi, ada juga kecewa, sedih, dan bahkan marah. Marah karena, mengapa berhari-hari keadaan yang sedemikian mencekam itu kok seperti tak ada aksi sat-set kedaruratan dari pengurus negara? Pak Taqwallah bercerita, sore tadi (27/11) Pemerintah Aceh baru saja mengumumkan keadaan bencana.
Di Jakarta ada beberapa penjelasan, berita TV cukup mencekam sebenarnya, tetapi belum tampak ada gerakan yang didorong oleh sense of urgency. Jumat (28/11) subuh-subuh, saya diantar ke Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang. Saya diantar oleh seorang relawan PMI yang baru pulang ke rumah tepat tengah malam tadi sesudah mengendarai mobil selama tiga hari tanpa bergantian. Bang Zulfan, namanya. Saya tanya, “Bang Zul, di rumah, semalam lampu menyala?”
“Enggak, Pak,” jawabnya pendek.
“Di rumah pakai penerangan apa,” tanya saya lagi.
“Tidak ada. Gelap-gelapan saja. Sesekali kami nyalakan lilin, takut kehabisan. Berhari-hari sejak Selasa (25/11), istri dan anak saya menunggu di rumah dalam gelap. Enggak ada komunikasi. Enggak ada air bersih,” tuturnya.
Batin saya bergumam, “Jadi, rakyat kita, yang menolongnya siapa? Saat menunggu boarding, seorang sahabat, pengusaha, melayangkan pesan di ponsel saya.
Begini tulisnya, “Pak, saya kemarin bertemu seorang pengusaha besar, dan ada kalimat yang cukup memohon. Negara meminta rakyatnya bekerja keras, namun tidak di-reward secara pantas. Kalau seorang pengusaha tingkat dewa saja merasa begitu, bagaimana dengan rakyat kebanyakan?” Ya, saya sependapat dengan sahabat saya itu. “Jadi, sebenarnya, siapa yang menolong rakyat kita?” Pertanyaan itu terngiang-ngiang terus. Menyertai saya mengawang-awang di angkasa raya menuju Jakarta.