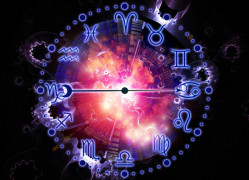Hidup di Jawa Barat berarti hidup berdampingan dengan risiko. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini berdiri di atas patahan aktif, dikelilingi daerah aliran sungai yang rapuh, serta semakin tertekan oleh krisis iklim. Memasuki periode 2025–2026, cuaca ekstrem tidak lagi hadir sebagai peristiwa langka, melainkan sebagai bagian dari rutinitas yang tak bisa diprediksi.
Dalam konteks ini, Tas Siaga Bencana (TSB) bukan sekadar perlengkapan darurat. Ia adalah simbol perubahan cara berpikir masyarakat dari pasrah menjadi siap, dari menunggu menjadi bertindak. TSB menandai lahirnya etika baru bertahan hidup di wilayah rawan bencana.
Dari Ketergantungan Menuju Kesiapsiagaan MandiriSelama bertahun-tahun, narasi kebencanaan di Indonesia cenderung menempatkan masyarakat sebagai pihak yang menunggu. Menunggu peringatan, menunggu evakuasi, menunggu bantuan datang. Padahal, pada menit-menit awal bencana, negara sering kali belum mampu hadir secara penuh.
Di wilayah Jawa Barat yang padat dan kompleks, jarak antara bencana dan bantuan bisa menjadi jurang berbahaya. Banjir bandang, longsor, atau gempa tidak memberi waktu panjang untuk berunding. Dalam kondisi seperti itu, TSB menjadi alat transisi penting dari ketergantungan total menuju kesiapsiagaan mandiri.
Dengan TSB, warga memiliki ruang kendali atas keselamatan dirinya sendiri, setidaknya dalam fase awal ketika sistem belum pulih.
72 Jam Pertama: Waktu yang Tidak Bisa DitawarDalam manajemen kebencanaan, 72 jam pertama pasca-kejadian adalah fase paling menentukan. Pada masa ini, listrik sering padam, jaringan komunikasi lumpuh, dan jalur transportasi terputus. Kekacauan bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis.
TSB dirancang untuk menjembatani fase genting ini. Isinya bukan sekadar barang, melainkan strategi bertahan hidup. Air minum, makanan siap konsumsi, senter, obat-obatan, uang tunai, peluit, pakaian, hingga dokumen penting yang disimpan kedap air adalah bentuk antisipasi terhadap kegagalan sistem.
Tanpa TSB, individu berada dalam posisi paling rentan bingung, bergantung, dan tidak berdaya. Dengan TSB, peluang bertahan meningkat secara signifikan.
Mitigasi Bukan Ketakutan, Melainkan Literasi RisikoMasih ada anggapan bahwa menyiapkan TSB adalah tindakan berlebihan atau cerminan rasa takut berlebih. Pandangan ini menunjukkan rendahnya literasi risiko. Di wilayah seperti Jawa Barat, mitigasi justru merupakan ekspresi rasionalitas.
Menyiapkan TSB bukan berarti mengundang bencana, tetapi mengakui realitas geografis dan iklim. Sama seperti memakai helm saat berkendara, TSB adalah perlindungan dasar yang logis, bukan paranoia.
Ketika masyarakat terbiasa menyiapkan TSB, budaya keselamatan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada instruksi darurat, melainkan tumbuh dari kesadaran kolektif.
Keselamatan Dimulai dari RumahPemerintah dapat menetapkan status siaga, membangun sistem peringatan dini, dan menyiapkan tim respons cepat. Namun, keselamatan sejati tidak pernah sepenuhnya terpusat. Ia dimulai dari rumah, dari keputusan kecil yang konsisten.
TSB yang diletakkan dekat pintu keluar rumah adalah pernyataan diam-diam bahwa keluarga tersebut siap menghadapi kemungkinan terburuk tanpa panik. Ia adalah bentuk partisipasi warga dalam sistem kebencanaan yang lebih besar.
Di tengah ancaman iklim dan geologi yang semakin nyata, Tas Siaga Bencana bukan lagi sekadar rekomendasi. Ia adalah etika hidup baru bagi masyarakat Jawa Barat agar sadar risiko, siap bertindak, dan bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri.
Karena dalam situasi bencana, kesiapan bukan soal keberanian, melainkan soal pilihan yang dibuat jauh sebelum sirene pertama berbunyi.