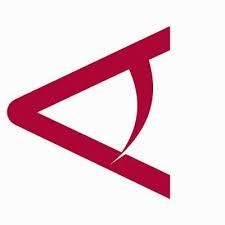Jakarta (ANTARA) - Baru-baru ini, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria melontarkan gagasan yang sekilas terdengar teknokratis, tetapi sesungguhnya menyimpan implikasi besar bagi masa depan perguruan tinggi Indonesia: membuka opsi jabatan fungsional peneliti di kampus.
Gagasan ini dimaksudkan untuk memperkuat riset perguruan tinggi, sekaligus memberi ruang karier bagi para peneliti yang selama ini tak sepenuhnya tertampung dalam skema dosen. Di tengah stagnasi riset kampus dan obsesinya pada angka akreditasi, wacana ini patut dibaca sebagai sinyal perubahan arah.
Selama ini, perguruan tinggi di Indonesia lebih sering diperlakukan sebagai teaching university ketimbang universitas riset. Riset memang dilakukan, publikasi memang dikejar, tetapi kerap hanya menjadi instrumen administratif: syarat kenaikan pangkat, pemenuhan borang (daftar isian), atau formalitas hibah.
Dalam struktur seperti itu, peneliti non-dosen nyaris tak memiliki ruang hidup yang layak, mereka ada, bekerja, tetapi tak benar-benar diakui.
Ketika BRIN membuka kemungkinan lahirnya jabatan fungsional peneliti di perguruan tinggi, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya soal jenjang karier, melainkan arah epistemik kampus itu sendiri: apakah universitas sungguh-sungguh ingin menjadi pusat produksi pengetahuan, atau sekadar pabrik ijazah yang dibalut jargon riset.
Kendati demikian, harapan ini tentu tidak datang tanpa tanda tanya. Apakah kebijakan tersebut akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya ekosistem universitas riset yang otonom dan berdaya, atau justru membuka babak baru sentralisasi riset di bawah logika birokrasi negara?
Apakah peneliti kampus akan berdiri sebagai subjek akademik yang merdeka atau hanya perpanjangan tangan institusi riset negara di ruang universitas? Pada posisi inilah, gagasan BRIN tak cukup dipuji sebagai terobosan, tetapi perlu diuji secara kritis, agar janji era baru universitas riset tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar menjelma sebagai transformasi.
Belajar dari dunia
Wacana menjadikan kampus sebagai universitas riset, sesungguhnya, bukan hal baru di tingkat global. Di Jerman, misalnya, universitas tidak hanya diisi oleh profesor dan dosen, tetapi juga oleh peneliti full-time yang memiliki status, jenjang karier, dan pengakuan profesional yang jelas.
Pelbagai lembaga, seperti Max Planck Society dan Fraunhofer Society, menunjukkan bagaimana peneliti dapat bekerja di persimpangan antara universitas, negara, dan industri, tanpa harus dibebani kewajiban mengajar. Di sana, riset bukan aktivitas sampingan, melainkan inti dari kerja akademik yang dilindungi dan dihargai.
Contoh lain dapat dilihat di Inggris, yang sejak lama memisahkan jalur karier teaching-focused academic dan research-focused academic. Melalui skema research-only contracts, banyak peneliti universitas bekerja penuh waktu untuk riset dan publikasi, dengan pembiayaan yang terhubung langsung ke lembaga nasional, seperti UK Research and Innovation (UKRI).
Model ini membuat universitas tidak lagi bergantung pada "dosen serba bisa", melainkan membangun ekosistem riset berbasis kolaborasi dan spesialisasi. Dampaknya terlihat jelas: riset kampus di Inggris relatif stabil, kompetitif, dan berpengaruh secara global.
Sementara itu, di Korea Selatan, transformasi universitas menjadi institusi penggerak riset berlangsung seiring dengan kebijakan negara yang agresif mendukung riset. Banyak universitas riset memiliki profesor riset atau research fellow yang tidak diwajibkan mengajar, tetapi difokuskan pada inovasi, paten, dan kolaborasi industri.
Negara memastikan bahwa peneliti kampus tidak terjebak dalam birokrasi administratif, melainkan diberi ruang kebebasan akademik untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi strategis.
Dari pengalaman pelbagai negara tersebut, satu pelajaran penting dapat ditarik: universitas riset tidak lahir dari slogan, melainkan dari pengakuan struktural bahwa peneliti adalah profesi otonom.
Dorongan universitas riset juga dipertegas oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie yang menilai bahwa universitas tidak bisa lagi berhenti sebagai ruang pengajaran semata.
Dalam pernyataannya, Stella mengingatkan bahwa negara-negara yang mampu melompat secara ekonomi, seperti Jerman, Amerika Serikat, dan China, lebih dahulu menata universitasnya sebagai pusat riset dan inovasi, meski dampaknya baru terasa puluhan tahun kemudian.
Pesan ini penting: riset bukan jalan pintas, melainkan investasi jangka panjang yang menuntut konsistensi kebijakan dan keberanian negara.
Maka, ketika negara meminta kampus bertransformasi menjadi universitas riset, tanggung jawabnya tidak bisa dibebankan sepihak kepada universitas; negara juga harus memastikan ekosistem riset yang adil, peneliti yang diakui secara struktural, serta kebebasan akademik yang dijaga agar inovasi tidak lahir dari tekanan, melainkan dari kemerdekaan berpikir.
Jika Indonesia, melalui BRIN, serius membuka jabatan fungsional peneliti di perguruan tinggi, maka kebijakan ini semestinya diarahkan bukan hanya sebagai penataan administratif, melainkan sebagai fondasi perubahan paradigma. Tanpa itu, universitas akan terus terjebak pada riset simbolik; sebaliknya, dengan desain yang tepat, kampus dapat benar-benar menjelma sebagai ruang produksi pengetahuan yang merdeka dan berdampak.
Risiko birokratisasi
Di sinilah tantangan paling krusial dari agenda universitas riset Indonesia bermula: memastikan bahwa penguatan riset tidak justru menjelma menjadi perluasan kendali birokrasi atas kampus.
Kala negara, melalui BRIN, masuk semakin dalam ke ruang universitas, selalu ada risiko bahwa riset direduksi menjadi instrumen kebijakan, diukur semata oleh target luaran, serapan anggaran, dan kepentingan jangka pendek.
Dalam situasi seperti ini, riset mudah tergelincir menjadi aktivitas administratif yang patuh, bukan praktik intelektual yang kritis dan merdeka.
Padahal, sejarah universitas modern justru memperlihatkan hal sebaliknya. Pengetahuan yang paling berpengaruh sering lahir dari kebebasan akademik, dari riset yang tidak selalu "laku" secara ekonomi, dan bahkan dari kerja ilmiah yang pada masanya dianggap tidak relevan.
Jika universitas riset dibangun dengan logika kontrol berlebihan, kampus berisiko kehilangan watak dasarnya sebagai ruang pencarian kebenaran. Kampus akan sibuk memenuhi indikator kinerja, tetapi "miskin" keberanian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang justru menjadi motor kemajuan ilmu pengetahuan.
Maka, menanti era baru universitas riset, semestinya juga berarti menagih kedewasaan negara dalam mengelola riset. Negara perlu hadir sebagai penopang, bukan pengendali; sebagai fasilitator, bukan "sutradara tunggal".
Tanpa keseimbangan antara dukungan kebijakan dan penghormatan terhadap otonomi akademik, agenda "universitas riset" berisiko berhenti sebagai perubahan "kosmetik", mengganti istilah dan struktur, tetapi gagal melahirkan transformasi intelektual yang sesungguhnya.
*) Raihan Muhammad adalah pegiat hak asasi manusia, pemerhati kebijakan publik, politik, dan hukum
Gagasan ini dimaksudkan untuk memperkuat riset perguruan tinggi, sekaligus memberi ruang karier bagi para peneliti yang selama ini tak sepenuhnya tertampung dalam skema dosen. Di tengah stagnasi riset kampus dan obsesinya pada angka akreditasi, wacana ini patut dibaca sebagai sinyal perubahan arah.
Selama ini, perguruan tinggi di Indonesia lebih sering diperlakukan sebagai teaching university ketimbang universitas riset. Riset memang dilakukan, publikasi memang dikejar, tetapi kerap hanya menjadi instrumen administratif: syarat kenaikan pangkat, pemenuhan borang (daftar isian), atau formalitas hibah.
Dalam struktur seperti itu, peneliti non-dosen nyaris tak memiliki ruang hidup yang layak, mereka ada, bekerja, tetapi tak benar-benar diakui.
Ketika BRIN membuka kemungkinan lahirnya jabatan fungsional peneliti di perguruan tinggi, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya soal jenjang karier, melainkan arah epistemik kampus itu sendiri: apakah universitas sungguh-sungguh ingin menjadi pusat produksi pengetahuan, atau sekadar pabrik ijazah yang dibalut jargon riset.
Kendati demikian, harapan ini tentu tidak datang tanpa tanda tanya. Apakah kebijakan tersebut akan menjadi pintu masuk bagi lahirnya ekosistem universitas riset yang otonom dan berdaya, atau justru membuka babak baru sentralisasi riset di bawah logika birokrasi negara?
Apakah peneliti kampus akan berdiri sebagai subjek akademik yang merdeka atau hanya perpanjangan tangan institusi riset negara di ruang universitas? Pada posisi inilah, gagasan BRIN tak cukup dipuji sebagai terobosan, tetapi perlu diuji secara kritis, agar janji era baru universitas riset tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar menjelma sebagai transformasi.
Belajar dari dunia
Wacana menjadikan kampus sebagai universitas riset, sesungguhnya, bukan hal baru di tingkat global. Di Jerman, misalnya, universitas tidak hanya diisi oleh profesor dan dosen, tetapi juga oleh peneliti full-time yang memiliki status, jenjang karier, dan pengakuan profesional yang jelas.
Pelbagai lembaga, seperti Max Planck Society dan Fraunhofer Society, menunjukkan bagaimana peneliti dapat bekerja di persimpangan antara universitas, negara, dan industri, tanpa harus dibebani kewajiban mengajar. Di sana, riset bukan aktivitas sampingan, melainkan inti dari kerja akademik yang dilindungi dan dihargai.
Contoh lain dapat dilihat di Inggris, yang sejak lama memisahkan jalur karier teaching-focused academic dan research-focused academic. Melalui skema research-only contracts, banyak peneliti universitas bekerja penuh waktu untuk riset dan publikasi, dengan pembiayaan yang terhubung langsung ke lembaga nasional, seperti UK Research and Innovation (UKRI).
Model ini membuat universitas tidak lagi bergantung pada "dosen serba bisa", melainkan membangun ekosistem riset berbasis kolaborasi dan spesialisasi. Dampaknya terlihat jelas: riset kampus di Inggris relatif stabil, kompetitif, dan berpengaruh secara global.
Sementara itu, di Korea Selatan, transformasi universitas menjadi institusi penggerak riset berlangsung seiring dengan kebijakan negara yang agresif mendukung riset. Banyak universitas riset memiliki profesor riset atau research fellow yang tidak diwajibkan mengajar, tetapi difokuskan pada inovasi, paten, dan kolaborasi industri.
Negara memastikan bahwa peneliti kampus tidak terjebak dalam birokrasi administratif, melainkan diberi ruang kebebasan akademik untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi strategis.
Dari pengalaman pelbagai negara tersebut, satu pelajaran penting dapat ditarik: universitas riset tidak lahir dari slogan, melainkan dari pengakuan struktural bahwa peneliti adalah profesi otonom.
Dorongan universitas riset juga dipertegas oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie yang menilai bahwa universitas tidak bisa lagi berhenti sebagai ruang pengajaran semata.
Dalam pernyataannya, Stella mengingatkan bahwa negara-negara yang mampu melompat secara ekonomi, seperti Jerman, Amerika Serikat, dan China, lebih dahulu menata universitasnya sebagai pusat riset dan inovasi, meski dampaknya baru terasa puluhan tahun kemudian.
Pesan ini penting: riset bukan jalan pintas, melainkan investasi jangka panjang yang menuntut konsistensi kebijakan dan keberanian negara.
Maka, ketika negara meminta kampus bertransformasi menjadi universitas riset, tanggung jawabnya tidak bisa dibebankan sepihak kepada universitas; negara juga harus memastikan ekosistem riset yang adil, peneliti yang diakui secara struktural, serta kebebasan akademik yang dijaga agar inovasi tidak lahir dari tekanan, melainkan dari kemerdekaan berpikir.
Jika Indonesia, melalui BRIN, serius membuka jabatan fungsional peneliti di perguruan tinggi, maka kebijakan ini semestinya diarahkan bukan hanya sebagai penataan administratif, melainkan sebagai fondasi perubahan paradigma. Tanpa itu, universitas akan terus terjebak pada riset simbolik; sebaliknya, dengan desain yang tepat, kampus dapat benar-benar menjelma sebagai ruang produksi pengetahuan yang merdeka dan berdampak.
Risiko birokratisasi
Di sinilah tantangan paling krusial dari agenda universitas riset Indonesia bermula: memastikan bahwa penguatan riset tidak justru menjelma menjadi perluasan kendali birokrasi atas kampus.
Kala negara, melalui BRIN, masuk semakin dalam ke ruang universitas, selalu ada risiko bahwa riset direduksi menjadi instrumen kebijakan, diukur semata oleh target luaran, serapan anggaran, dan kepentingan jangka pendek.
Dalam situasi seperti ini, riset mudah tergelincir menjadi aktivitas administratif yang patuh, bukan praktik intelektual yang kritis dan merdeka.
Padahal, sejarah universitas modern justru memperlihatkan hal sebaliknya. Pengetahuan yang paling berpengaruh sering lahir dari kebebasan akademik, dari riset yang tidak selalu "laku" secara ekonomi, dan bahkan dari kerja ilmiah yang pada masanya dianggap tidak relevan.
Jika universitas riset dibangun dengan logika kontrol berlebihan, kampus berisiko kehilangan watak dasarnya sebagai ruang pencarian kebenaran. Kampus akan sibuk memenuhi indikator kinerja, tetapi "miskin" keberanian untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang justru menjadi motor kemajuan ilmu pengetahuan.
Maka, menanti era baru universitas riset, semestinya juga berarti menagih kedewasaan negara dalam mengelola riset. Negara perlu hadir sebagai penopang, bukan pengendali; sebagai fasilitator, bukan "sutradara tunggal".
Tanpa keseimbangan antara dukungan kebijakan dan penghormatan terhadap otonomi akademik, agenda "universitas riset" berisiko berhenti sebagai perubahan "kosmetik", mengganti istilah dan struktur, tetapi gagal melahirkan transformasi intelektual yang sesungguhnya.
*) Raihan Muhammad adalah pegiat hak asasi manusia, pemerhati kebijakan publik, politik, dan hukum