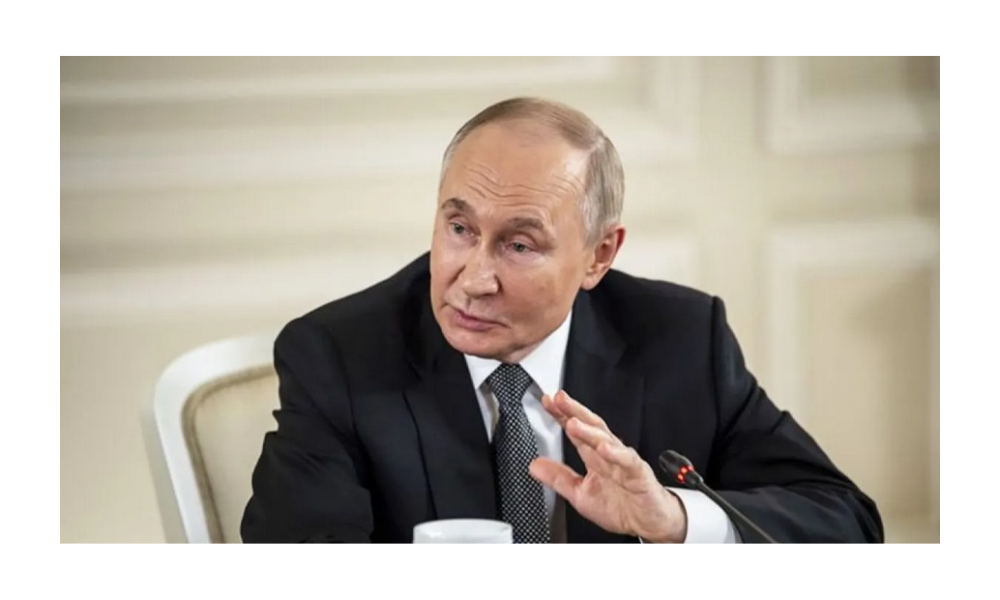Prof. Mohamad Sadli adalah salah satu ekonom pertama yang secara sistematis menunjukkan adanya pasang surut peran teknokrat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi di Indonesia selama Orde Baru. Dalam berbagai tulisan dan refleksinya—yang juga menjadi rujukan utama Prof. Iwan Azis dalam Political Economy of Policy Reform (Institute for International Economics)—Prof. Sadli menggambarkan dinamika ini sebagai sebuah tug-of-war game, atau permainan tarik tambang, antara rasionalitas ekonomi dan kepentingan politik.
Pola yang berulang ini dapat dirumuskan secara sederhana: peran teknokrat menguat ketika krisis ekonomi terjadi, dan melemah ketika ekonomi membaik. Mengikuti istilah yang dipopulerkan oleh kolumnis Rizal Mallarangeng, fenomena ini layak disebut sebagai “Hukum Sadli.”
Teknokrat dan Krisis: Awal DominasiHukum Sadli mulai tampak jelas ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi terbesar dalam sejarahnya pada 1966. Pada periode ini, teknokrat menjadi aktor utama dalam proses stabilisasi ekonomi. Dominasi mereka sangat kuat, didukung kewibawaan almarhum Sultan Hamengkubuwono IX. Hampir seluruh posisi strategis dalam kementerian ekonomi—atau setidaknya pada tingkat sekretaris jenderal—diisi kalangan teknokrat.
Keberhasilan stabilisasi ini secara bertahap mengurangi inflasi dan memulihkan kepercayaan ekonomi. Namun, justru keberhasilan inilah yang menjadi awal dari melemahnya peran teknokrat.
Oil Boom dan Munculnya Pemikiran TandinganPenurunan peran teknokrat mulai terasa pada periode 1973–1974, setelah Indonesia berhasil keluar dari tekanan inflasi tinggi. Oil boom pertama menyediakan limpahan dana pembangunan yang besar dan memicu munculnya pemikiran-pemikiran alternatif di luar kerangka teknokratis.
Kelompok nasionalis dan teknisi mulai mendorong strategi “lompatan ke depan” melalui pembangunan industri besar dan teknologi tinggi. Pusat pemikiran tandingan ini berkembang di sekitar Ali Moertopo, Soejono Hoemardani, serta di lingkungan Pertamina melalui Divisi Teknologi yang kelak menjelma menjadi BPPT. Beberapa proyek besar lahir dari gagasan ini, seperti Krakatau Steel generasi pertama dan sejumlah pabrik pupuk. Namun, sebagian besar proyek tersebut tidak didukung oleh analisis biaya-manfaat yang memadai dan akhirnya terbengkalai.
Krisis Pertamina dan Kembalinya TeknokratKrisis Pertamina tahun 1975, yang diperparah oleh peristiwa Malari setahun sebelumnya, kembali menggeser bandul kekuasaan ke arah teknokrat. Pemerintah memberikan mandat lebih besar kepada mereka untuk merumuskan strategi pembangunan yang berorientasi pemerataan. Hasilnya tercermin dalam berbagai proyek Inpres yang kemudian diakui berperan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
Namun, pola lama kembali terulang. Oil boom kedua pada 1978 membuat disiplin anggaran kembali mengendur. Pemerintah memberi ruang lebih luas kepada kelompok nasionalis dan teknisi, yang menduduki posisi strategis seperti BKPM dan Departemen Perindustrian, dengan dukungan dua pusat kekuatan baru: Sekretariat Negara dan BPPT. Industri-industri strategis kembali diperluas, tetapi—kecuali Krakatau Steel—sebagian besar tetap bergantung pada dukungan keuangan dan proteksi pemerintah hingga hari ini.
Deregulasi 1980-an: Puncak Peran TeknokratResesi global awal 1980-an dan penurunan tajam harga migas memaksa pemerintah meninjau ulang strategi pembangunan. Sekali lagi, teknokrat dipanggil sebagai “juru selamat.” Kelompok ini mendorong deregulasi ekonomi yang dimulai pada 1983, mencakup liberalisasi sektor keuangan, peningkatan daya saing, dan upaya sistematis menekan ekonomi biaya tinggi.
Salah satu kebijakan paling radikal adalah pengalihan fungsi pemeriksaan Bea Cukai kepada SGS, yang secara nyata memperlancar arus barang di pelabuhan dan meningkatkan penerimaan negara meskipun tarif bea masuk diturunkan. Deregulasi lanjutan pada 1986–1990 bersifat struktural, meningkatkan transparansi transaksi ekonomi melalui peralihan dari tataniaga non-tarif ke sistem tarif. Proses ini secara bertahap mengalihkan rente ekonomi dari swasta ke pemerintah dan kemudian menguranginya.
Yang lebih penting, deregulasi ini berhasil menumbangkan sejumlah kelompok pencari rente yang sebelumnya dianggap “kebal,” seperti penguasa tataniaga plastik dan bungkil kedelai. Dampaknya tercermin pada pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi—lebih dari 6% per tahun—serta kontribusi TFP yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan studi IMF oleh Michael Sarel (1997).
Krisis 1997/98 : Kemunduran, Distorsi, dan Krisis KredibilitasSayangnya, keberhasilan deregulasi ini ternodai oleh munculnya berbagai tataniaga baru—cengkeh, rotan, jeruk, dan lainnya—yang berada di luar kendali teknokrat. Dalam banyak kasus, teknokrat terpaksa membela kebijakan tersebut di hadapan publik meskipun tidak sejalan dengan prinsip efisiensi yang mereka yakini.
Memasuki tahun 1990-an, ketika ekonomi kembali membaik, proses deregulasi praktis berhenti. Praktik monopoli dan oligopoli yang dilegalkan oleh kebijakan pemerintah justru semakin meluas, sering kali dibungkus dengan retorika “nasional” dan “kerakyatan.” Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya menciptakan inefisiensi, tetapi juga merusak kredibilitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan.
Erosi kredibilitas inilah yang membuat stabilisasi ekonomi menghadapi guncangan regional—termasuk krisis rupiah—menjadi sangat mahal. Biaya bunga SBI melonjak, suku bunga perbankan melambung, dan beban ekonomi akhirnya ditanggung oleh dunia usaha serta kelompok menengah dan bawah.
Apakah Hukum Sadli Masih Berlaku?Keadaan ekonomi dewasa ini tentu tidak sama dengan situasi menjelang krisis 1998. Nilai tukar rupiah memang mengalami pelemahan—sebagian di antaranya justru merupakan penyesuaian yang necessary untuk memulihkan keseimbangan internal dan eksternal perekonomian secara makro. Laju pertumbuhan potensial Indonesia memang telah menurun ke kisaran 4,5–5% per tahun, namun laju pertumbuhan aktual masih bertahan di sekitar 5%. Dalam konteks ketidakpastian global yang tinggi, capaian ini relatif memadai.
Namun, respons kebijakan yang muncul sejauh ini cenderung belum cukup kuat. Di balik pelonggaran likuiditas yang dilakukan pemerintah, peningkatan unused approved credit justru memberikan indikasi awal menurunnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek perekonomian. Fenomena institutional decay yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir juga belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan, dan tampaknya masih dibiarkan berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Banyak pihak berharap Presiden Prabowo akan mengadopsi kembali semangat deregulasi yang secara konsisten disuarakan oleh almarhum Prof. Soemitro Djojohadikusumo pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Namun pengalaman historis menunjukkan bahwa deregulasi ekonomi–politik bergerak seperti bandul: pada tahap awal, kebijakan menyasar kelompok pinggiran, tetapi setelah satu dekade, hambatan utama justru berada pada “lingkaran inti” yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan.
Pada tahap ini, deregulasi menuntut pengorbanan langsung dari kelompok inti tersebut. Tanpa figur yang memiliki kapasitas intelektual sekaligus posisi politik untuk menjelaskan urgensi pengorbanan ini kepada pengambil keputusan tertinggi, proses reformasi cenderung menemui jalan buntu. Dari komposisi teknokrat yang tersisa saat ini, hampir tidak ada yang memiliki political standing untuk memainkan peran strategis tersebut.
Lebih jauh, kelompok teknokrat yang dahulu relatif solid kini terfragmentasi dan gagal melahirkan gagasan-gagasan baru yang segar. Kegagalan kaderisasi inilah yang menjadi salah satu kelemahan mendasar kepemimpinan teknokrat di masa lalu. Akibatnya, deregulasi pasca-1993 merosot menjadi sekadar penurunan tarif impor, sementara berbagai bentuk proteksi baru dan pembebasan pajak secara diam-diam justru diberikan kepada kelompok rente inti—sebagaimana tercermin dalam kebijakan impor gula kasar, berbagai produk pertanian dan mineral, serta kecenderungan yang kini kembali menjalar ke sektor tekstil melalui mekanisme kuota.
Dari “Hukum Sadli” ke Hukum Sadli+Dilihat dari perspektif pasca-Reformasi, Hukum Sadli tidak hanya bertahan, tetapi justru mengalami transformasi dalam bentuk dan mekanismenya. Jika pada masa Orde Baru tarik-menarik antara teknokrat dan kekuatan politik berlangsung relatif terbuka dan terpersonalisasi, maka dalam era Reformasi kontestasi tersebut menjadi lebih terselubung, terfragmentasi, dan kerap dilembagakan melalui regulasi, penugasan, serta desain institusi itu sendiri.
Episode kembalinya Sri Mulyani Indrawati dari posisinya sebagai Managing Director Bank Dunia untuk memimpin kembali Kementerian Keuangan merupakan ilustrasi konkret dari bekerjanya Hukum Sadli Plus. Pemanggilan tersebut terjadi dalam konteks meningkatnya tekanan ekonomi dan kebutuhan akan pemulihan kredibilitas kebijakan fiskal, baik di mata pasar domestik maupun internasional. Seperti pola historis yang berulang, krisis menciptakan ruang politik bagi figur teknokrat dengan reputasi global dan otoritas profesional yang kuat untuk kembali mengambil peran sentral dalam stabilisasi dan penguatan disiplin kebijakan.
Krisis 1997/98 kembali mengonfirmasi bekerjanya hukum ini. Pada fase awal krisis, teknokrat memperoleh ruang yang luas: stabilisasi makroekonomi, reformasi sektor keuangan, restrukturisasi utang, serta penguatan institusi moneter dan fiskal dijalankan dengan disiplin yang relatif tinggi. Independensi Bank Indonesia, disiplin fiskal, dan kerangka kebijakan makro yang kredibel menjadi warisan penting periode tersebut. Namun, sebagaimana pola yang berulang dalam sejarah ekonomi Indonesia, seiring membaiknya kondisi ekonomi, ruang gerak teknokrat kembali menyempit.
Perbedaannya, dalam era Reformasi, penyempitan ini tidak lagi terjadi melalui konfrontasi langsung antara teknokrat dan kekuatan non-teknokrat, melainkan melalui mekanisme policy layering: penambahan mandat, penugasan khusus, dan pembentukan entitas baru yang secara gradual menggerus prinsip-prinsip tata kelola yang sebelumnya diperjuangkan. Dalam konteks ini, BUMN—kini melalui Danantara—kembali memainkan peran sentral sebagai wahana kompromi antara logika ekonomi dan kepentingan politik, sebuah gema langsung dari pengalaman nasionalisasi dan industrialisasi negara di masa lalu.
Danantara memang diisi oleh profesional domestik maupun diaspora yang secara individual memiliki kapasitas yang memadai. Namun, gelagat dalam enam bulan terakhir memberikan indikasi yang tidak lebih baik dibandingkan pengalaman pada era Pertamina (1970-an) maupun BPPT (1990-an). Proyek-proyek raksasa dengan kelayakan ekonomi dan finansial yang lemah tampak tetap melaju mengikuti preferensi penguasa. Proyek gasifikasi batubara—yang telah lama menggantung—misalnya, kembali mencuat dan berpotensi lolos meskipun secara analisis ekonomi maupun finansial sangat tidak layak. Lebih jauh, risiko lingkungan dan dampak kesehatan dari proyek semacam ini secara langsung akan masuk ke “dapur” rumah tangga, terutama rumah tangga berpendapatan rendah di perkotaan dengan kualitas hunian dan ventilasi yang buruk.
Refleksi yang lebih mendalam menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan semata-mata melemahnya posisi teknokrat, melainkan ketiadaan mekanisme institusional yang mampu “mengunci” rasionalitas ekonomi setelah krisis berlalu. Selama rasionalitas kebijakan bergantung pada situasi darurat dan figur tertentu, Hukum Sadli akan terus berulang. Ketika krisis usai, legitimasi teknokrat ikut surut, dan arah kebijakan kembali ditarik oleh kepentingan jangka pendek, simbolisme politik, serta distribusi rente.
Di sinilah letak pelajaran terpenting dari tulisan ini: kegagalan kaderisasi dan pembaruan gagasan teknokrat bukan semata persoalan generasi, melainkan persoalan kelembagaan. Tanpa institusi yang mampu menjaga policy discipline secara berkelanjutan, teknokrat—betapapun kompeten—akan selalu berada dalam posisi defensif. Mereka dipanggil sebagai pemadam kebakaran, bukan sebagai arsitek pembangunan jangka panjang.
Lebih jauh, pengalaman dua dekade terakhir menunjukkan bahwa Hukum Sadli kini tidak hanya berlaku bagi teknokrat negara, tetapi juga mencerminkan relasi yang lebih luas antara negara dan pasar. Negara cenderung ekspansif ketika ruang fiskal dan politik terbuka, namun kembali mencari disiplin ketika tekanan muncul. Tanpa refleksi historis yang memadai, pola ini berisiko mengulang kesalahan lama dengan justifikasi baru: industrialisasi berbasis negara tanpa evaluasi biaya-manfaat yang ketat, penugasan BUMN tanpa hard budget constraint, serta regulasi yang menciptakan rente atas nama stabilitas atau nasionalisme ekonomi.
Dalam konteks demokrasi elektoral, Hukum Sadli tidak lagi bekerja secara diskrit, melainkan kontinu, dan karenanya sering kali lebih tidak stabil secara kebijakan.” Peran teknokrat tidak “datang dan pergi” secara tajam mengikuti siklus krisis, tetapi mengalami gradasi yang dipengaruhi oleh fragmentasi kekuasaan politik, dinamika koalisi, serta tekanan opini publik. Jika dalam sistem otokratis teknokrat berhadapan dengan satu pusat keputusan, maka dalam demokrasi mereka harus bernegosiasi dengan banyak veto players yang masing-masing memiliki horizon politik dan insentif berbeda. Akibatnya, kebijakan ekonomi yang dihasilkan bukan sekadar refleksi dari rasionalitas teknokratik atau kepentingan politik semata, melainkan hasil kompromi berlapis yang seringkali mengorbankan koherensi kebijakan jangka panjang.
Sebagai penutup reflektif, Hukum Sadli seharusnya tidak dibaca secara fatalistik, melainkan sebagai sebuah peringatan institusional. Ia mengingatkan bahwa rasionalitas ekonomi tidak pernah menang secara permanen; rasionalitas tersebut harus terus diperjuangkan, dilembagakan, dan diperbarui agar tidak tergerus oleh dinamika politik dan kepentingan jangka pendek.
Dengan demikian, Hukum Sadli tetap relevan secara analitis, namun tidak lagi memadai jika dipahami semata sebagai hukum siklus krisis. Dalam konteks kontemporer, ia lebih tepat dibaca sebagai hukum institusional tentang bagaimana rasionalitas ekonomi mengalami erosi yang berbeda-beda, tergantung pada struktur kekuasaan dan konfigurasi sistem politik yang melingkupinya.
Tantangan ke depan, oleh karena itu, bukan sekadar melahirkan teknokrat yang cerdas dan berintegritas, melainkan membangun sistem politik-ekonomi yang mampu menjaga keberlanjutan kebijakan rasional—bahkan ketika krisis telah berlalu dan tekanan politik kembali menguat.