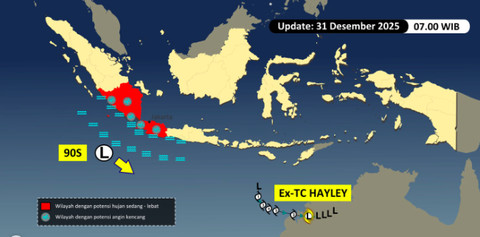EtIndonesia. Pertemuan itu terjadi kembali—setelah tujuh tahun berlalu—di sebuah musim dingin. Di kota kecil di utara, hujan malam turun rintik-rintik, membasahi wajah, terasa dingin menusuk kulit.
Dia menutup pintu mobil, melihat cipratan lumpur yang terlempar ke bodi kendaraan, lalu mengeluh dalam hati mengapa suaminya tidak mengingatkannya membawa payung di hari hujan seperti ini. Bibir kecilnya mengerucut tanpa sadar, tanda rasa kesal yang samar.
Sementara itu, dia—pria itu—berputar cukup lama mencari tempat parkir. Hujan deras mengaburkan pandangan. Setelah berputar-putar di antara arus kendaraan, akhirnya dia menemukan celah sempit yang pas-pasan—cukup untuk badan mobil saja. Bahkan membuka pintu dan menurunkan kaki pun terasa sulit. Saat akhirnya berhasil melangkah keluar, kakinya justru menginjak genangan air.
Dia menggeleng pelan dan menghela napas tipis.
Dia hendak kembali menggerutu—orang macam apa ini, memarkir mobil terlalu dekat, nanti bagaimana aku keluar? Namun kata-kata itu tertahan di bibirnya. Otot wajahnya menegang sedikit.
Di saat yang sama, pria itu membelalakkan mata. Pandangannya terpaku pada wajahnya.
Dia terdiam sejenak. Ingatan melesat seperti lari sprint seratus meter—kembali ke tujuh tahun silam. Senyum hangat itu. Tatapan yang tenang. Isyarat yang lembut. Bahkan sepatu yang basah seolah kembali terasa hangat.
Mereka masuk ke sebuah kafe bernama “Pertemuan.” Di malam hujan, sudut ruangan terasa hangat dan sunyi.
Dia menatap pria di hadapannya dengan saksama. Saat alunan lagu “Semoga Kau Baik-baik Saja” terdengar, riak emosi muncul di matanya. Tatapan itu—pria itu—masih terasa begitu akrab. Dia adalah sosok yang pernah lama berkelana dalam mimpinya, dan juga seseorang yang dia rindukan dalam kesepian malam-malam panjang.
Matanya menyimpan kesedihan lembut. Jari-jarinya pucat. Garis wajahnya tegas. Hanya saja, rambut panjangnya telah dipotong pendek, dan di matanya kini ada kedewasaan serta ketenangan yang tak ada dulu.
Dia memesan segelas susu vanila, lalu memberi isyarat kepadanya. Pria itu masih refleks mengernyitkan dahi.
“Kalau masih ingat kebiasaanku, tolong pesan untukku,” katanya.
Dia berkata pada pelayan : “Untuk Tuan ini, satu gelas Cinta Setan.”
Dia mengangkat bahu dan tersenyum pahit.
“Aku tak bisa menyetir sambil mabuk.”
Dia menjawab pelan : “Waktu tak pernah berhenti. Di tengah hiruk-pikuk usia, kita memang harus mengubah banyak kebiasaan.”
Dia tersenyum tanpa suara, mengangkat gelas hitam yang dinamai setan, dan meneguknya perlahan.
“Bertahun-tahun berlalu, tapi satu hal yang tak berubah darimu—kebiasaan mengernyitkan dahi. Di antara alismu, selalu ada bayangan yang tak pernah bisa kuterobos.”
Dia menjawab : “Orangnya mungkin sama, tapi zaman telah berganti. Seperti minuman yang kamu pesan untukku ini—aku tahu, di hatimu, kamu selalu menyimpan rasa tak rela terhadapku.”
“Bukan kebencian,” katanya lirih. “Aku hanya tak sanggup kalah oleh waktu, tak mampu bertarung melawan kenangan. Waktu diam-diam mengikis ketajamanku. Aku tak lagi sekeras dan seegois dulu. Tapi kamu pergi begitu saja… dan sepanjang hidup ini, kamu masih berutang satu penjelasan padaku.”
Dia menyalakan rokok. Tatapannya tenggelam seperti terperosok ke rawa. Gelas berkaki tinggi terus diputar di antara jemarinya. Lama dia terdiam.
“Sebenarnya, tahun ujian masuk perguruan tinggi itu, aku seharusnya bisa melangkah bersamamu ke masa depan yang sama. Tapi di saat terakhir, aku terpaksa berhenti.”
“Kamu berasal dari keluarga baik-baik. Kamu punya masa depan cerah. Sedangkan aku… hanya pemuda miskin yang bahkan kesulitan membayar uang kuliah. Di saat bersamaan, kakek—satu-satunya keluarga yang kupunya—jatuh sakit parah. Aku terpaksa berbohong, mengatakan bahwa aku gagal ujian, hanya demi menenangkan harapannya.”
“Musim panas itu, ibumu datang ke restoran tempatku bekerja. Dia ingin berbicara. Dia menawarkan sejumlah uang—sebagai bantuan, atau mungkin kompensasi. Syaratnya satu: aku harus berpisah darimu atas inisiatifku sendiri.”
“Aku menolak uang itu. Tapi aku mendengar baik-baik kalimat ‘harus sepadan.’ Sampai hari ini, aku tak pernah membencinya. Mungkin dia benar. Saat itu, aku memang tak mampu memberimu apa pun.”
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, isaknya berkali-kali memutus kalimat.
Dia berkata lirih : “Aku masih ingat hari kamu meninggalkan kota kecil itu. Kamu mengenakan gaun merah muda. Itu hadiah terakhir dariku. Aku berdiri di sudut peron, melihatmu perlahan menghilang dari pandanganku.”
“Aku ingat ruang kelasmu—di belokan tangga. Tahun kedua kuliah, kamu menjadi penyiar radio kampus. Dan setiap siaranmu selalu diakhiri dengan lagu Qi Qin kesukaanku.”
“Aku ingat tahun ketiga, saat kamu punya pacar. Suatu malam di lapangan basket terbuka, kamu menangis dalam pelukannya. Hari itu ulang tahunmu—juga hari kalian resmi bersama.”
“Aku ingat menjelang kelulusan, kamu sering mengenakan setelan kerja biru tua, syal biru muda di leher, dan bros kristal berbentuk kupu-kupu. Suatu sore, sepulang magang, kamu turun dari bus nomor 24 yang penuh sesak. Tumit sepatu hakmu terkilir. Pria itu mengantarmu ke rumah sakit dengan sepeda. Sebelumnya kamu jongkok menangis di halte, tak berdaya… lalu tersenyum bahagia saat duduk di belakang sepedanya.”
“Mungkin kamu heran, mengapa aku tahu semua ini. Sebenarnya, selama tahun-tahun kuliahmu, aku tak pernah benar-benar pergi. Kita hidup di kota yang sama. Aku hanya berdiri di sudut-sudut jalan sebagai penjaga diam—berpapasan denganmu, lagi dan lagi.”
Dia menangis tersedu, menghabiskan semua tisu. Dia memesan kopi—tanpa gula—seperti dulu.
Saat berpisah, dia mengeluarkan dua keping CD dari mobil. Bungkusnya hitam polos, tanpa tulisan.
“Ini kami temukan tiga tahun lalu, saat aku dan suamiku bulan madu di Lijiang. Aku tahu… kamu pasti menyukainya.”
Dia mengeluarkan sebuah foto dari dompetnya dengan sangat hati-hati. Gambar itu membeku pada masa kuliahnya—rok yang berkibar, tubuh anggun.
“‘Dirimu’ yang pernah kusimpan di saku ranselku, menemaniku ke banyak tempat… kini harus kukembalikan. Maafkan aku atas semua keterpaksaan di masa lalu.”
Dia memundurkan mobil dari arus kendaraan, menyalakan lampu untuk meneranginya.
Dia membuka CD itu.
Di dalamnya, tertulis tangan: “Malam datang dan pagi berlalu, yang pergi—tak pernah kembali.”(jhn/yn)