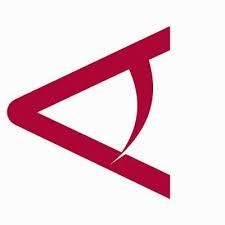Jakarta (ANTARA) - Dua puluh tahun pilkada langsung berjalan, tetapi kesejahteraan daerah tetap sangat ditentukan oleh pusat. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun ruang fiskal dan kewenangan kebijakannya justru makin menyempit.
Inilah paradoks demokrasi lokal Indonesia. Legitimasi politik diperluas, tetapi kapasitas ekonomi tidak pernah benar-benar didesentralisasikan.
Polemik mekanisme pilkada kembali mengemuka, ditandai dengan menguatnya usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan ini memperoleh dukungan mayoritas partai politik parlemen dengan argumen klasik yang nyaris tak berubah sejak satu dekade lalu.
Pilkada langsung dianggap mahal, rawan korupsi, melelahkan, dan memicu konflik. Komposisi aktor pendukung perubahan ini pun menunjukkan kemiripan mencolok dengan situasi pada 2014.
Ironisnya, di tengah dorongan mengakhiri pilkada langsung, hampir tidak terlihat upaya serius untuk memperbaiki dampak negatifnya. Pengetatan aturan pembiayaan politik, penegakan hukum terhadap politik uang, atau kebijakan untuk menurunkan biaya kontestasi elektoral, jarang menjadi agenda utama.
Padahal, jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, kualitas demokrasi lokal justru berpotensi meningkat tanpa memangkas hak pilih warga.
Selama ini, pilkada langsung kerap diposisikan sebagai tonggak demokrasi lokal yang diyakini mampu mendorong kesejahteraan. Logikanya sederhana. Pemimpin yang dipilih langsung akan lebih akuntabel, lebih responsif, dan pada akhirnya lebih efektif memperbaiki layanan publik.
Namun setelah hampir dua dekade, klaim ini tidak pernah terbukti secara konsisten. Kepercayaan politik memang meningkat di sejumlah daerah, tetapi dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi warga jauh dari seragam. Bahkan kerap mengecewakan.
Di sinilah problem mendasarnya. Demokrasi terlalu sering dinilai dari prosedur pemilihan, bukan dari kapasitas institusi yang menopang hasil pilihan tersebut. Pilkada langsung menjadi pusat perdebatan, sementara struktur fiskal, desain kewenangan, dan relasi kekuasaan lokal dibiarkan nyaris tak berubah. Demokrasi akhirnya berhenti sebagai ritual elektoral, bukan sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan.
Baca juga: Yusril: Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional
Ambiguitas akuntabilitas politik
Pendukung pilkada langsung berargumen bahwa pemilihan langsung menciptakan insentif kuat bagi kepala daerah untuk bekerja lebih baik karena bergantung pada suara rakyat. Secara teori, argumen ini koheren.
Namun bukti empiris menunjukkan kenyataan yang jauh lebih ambigu. Banyak daerah dengan kontestasi pilkada kompetitif tetap mencatat stagnasi kualitas layanan publik. Di sejumlah kabupaten dan kota, belanja pendidikan dan kesehatan meningkat secara nominal, tetapi mutu layanan tidak bergerak signifikan karena terserap belanja rutin dan birokrasi.
Masalahnya bukan pada absennya akuntabilitas elektoral, melainkan pada rapuhnya akuntabilitas kebijakan. Kepala daerah memang bertanggung jawab kepada pemilih, tetapi ruang fiskal dan kewenangan kebijakannya sangat terbatas.
Di sebagian besar daerah, lebih dari separuh APBD bersumber dari transfer pusat, terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam konstruksi seperti ini, janji kampanye kerap terputus dari realitas anggaran. Pemimpin dipilih langsung, tetapi tidak memegang kendali penuh atas sumber daya yang menentukan keberhasilan kebijakan.
Kegagalan pilkada langsung dalam menghasilkan perbaikan kesejahteraan bukanlah kegagalan pilihan elektoral, melainkan kegagalan desain ekonomi-politik. Mandat politik yang diperoleh melalui pemilihan langsung tidak diiringi kontrol sepadan atas sumber daya fiskal dan instrumen kebijakan.
Dalam sistem desentralisasi yang sangat bergantung pada transfer pusat, kepala daerah lebih berperan sebagai agen distribusi anggaran nasional ketimbang aktor otonom pembangunan lokal. Kontestasi elektoral menghasilkan legitimasi politik tanpa kapasitas ekonomi, sementara hasil kebijakan tetap dikunci oleh struktur fiskal terpusat dan relasi kekuasaan antar-elite.
Baca juga: Populi Center ungkap survei mayoritas warga ingin Pilkada langsung
Elite capture dan biaya demokrasi
Kelemahan struktural ini diperparah oleh fenomena elite capture. Biaya politik pilkada yang tinggi menciptakan kebergantungan kepala daerah pada sponsor politik dan jaringan oligarki lokal, bahkan nasional. Kemenangan elektoral kemudian dibayar melalui konsesi proyek, distribusi rente, atau kebijakan yang bias pada kepentingan sempit.
Dalam konteks ini, pilkada langsung tidak otomatis memperluas keadilan sosial, melainkan sering kali hanya memperluas arena kompetisi elite.
Fenomena ini bukan anomali Indonesia semata. Berbagai studi komparatif di negara berkembang menunjukkan pola serupa ketika desentralisasi politik tidak diiringi reformasi fiskal dan tata kelola. Demokrasi prosedural berjalan, partisipasi meningkat, tetapi distribusi kesejahteraan tetap timpang karena dikunci oleh relasi kuasa yang tidak demokratis.
Kesalahan terbesar dalam debat pilkada adalah menganggap pemilihan sebagai tujuan, bukan alat. Demokrasi direduksi menjadi peristiwa lima tahunan. Sementara kapasitas negara di tingkat daerah, baik itu perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, sering kali diabaikan. Dalam kerangka ini, pilkada langsung memang meningkatkan legitimasi, tetapi legitimasi tanpa kapasitas hanya melahirkan ekspektasi publik yang tak pernah terpenuhi.
Jika tujuan akhirnya adalah kesejahteraan, maka debat pilkada perlu diarahkan ulang. Pertanyaannya bukan “langsung atau tidak langsung”, melainkan apakah institusi lokal memiliki daya untuk menerjemahkan mandat politik menjadi kebijakan publik yang efektif.
Reformasi yang dibutuhkan justru terletak pada perbaikan desain perimbangan keuangan pusat–daerah, penguatan kapasitas fiskal lokal, transparansi pembiayaan politik, dan profesionalisasi birokrasi daerah.
Polemik ini muncul di tengah agenda yang jauh lebih mendesak; Revisi UU Pemilu. Revisi tersebut semestinya diselesaikan sebelum dimulainya seleksi penyelenggara Pemilu 2029 pada Agustus 2026.
Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pilkada berpotensi baru digelar pada 2031. Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk pembenahan struktural, bukan sekadar mengulang perdebatan prosedural.
Tanpa pembenahan struktural tersebut, mempertahankan pilkada langsung sambil berharap kesejahteraan meningkat hanyalah bentuk policy wishful thinking.
Momentum revisi UU Pemilu pasca-putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dimanfaatkan untuk memperbaiki desain kekuasaan ekonomi dan kapasitas institusi lokal, bukan sekadar mengulang perdebatan prosedural.
Tanpa kekuasaan fiskal dan institusi yang benar-benar bekerja, demokrasi hanya memindahkan legitimasi politik. Sementara kesejahteraan tetap dikunci oleh struktur kekuasaan.
Baca juga: Megawati sebut wacana Pilkada melalui DPRD pengkhianatan reformasi
*) Kusfiardi adalah Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute
Inilah paradoks demokrasi lokal Indonesia. Legitimasi politik diperluas, tetapi kapasitas ekonomi tidak pernah benar-benar didesentralisasikan.
Polemik mekanisme pilkada kembali mengemuka, ditandai dengan menguatnya usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan ini memperoleh dukungan mayoritas partai politik parlemen dengan argumen klasik yang nyaris tak berubah sejak satu dekade lalu.
Pilkada langsung dianggap mahal, rawan korupsi, melelahkan, dan memicu konflik. Komposisi aktor pendukung perubahan ini pun menunjukkan kemiripan mencolok dengan situasi pada 2014.
Ironisnya, di tengah dorongan mengakhiri pilkada langsung, hampir tidak terlihat upaya serius untuk memperbaiki dampak negatifnya. Pengetatan aturan pembiayaan politik, penegakan hukum terhadap politik uang, atau kebijakan untuk menurunkan biaya kontestasi elektoral, jarang menjadi agenda utama.
Padahal, jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, kualitas demokrasi lokal justru berpotensi meningkat tanpa memangkas hak pilih warga.
Selama ini, pilkada langsung kerap diposisikan sebagai tonggak demokrasi lokal yang diyakini mampu mendorong kesejahteraan. Logikanya sederhana. Pemimpin yang dipilih langsung akan lebih akuntabel, lebih responsif, dan pada akhirnya lebih efektif memperbaiki layanan publik.
Namun setelah hampir dua dekade, klaim ini tidak pernah terbukti secara konsisten. Kepercayaan politik memang meningkat di sejumlah daerah, tetapi dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi warga jauh dari seragam. Bahkan kerap mengecewakan.
Di sinilah problem mendasarnya. Demokrasi terlalu sering dinilai dari prosedur pemilihan, bukan dari kapasitas institusi yang menopang hasil pilihan tersebut. Pilkada langsung menjadi pusat perdebatan, sementara struktur fiskal, desain kewenangan, dan relasi kekuasaan lokal dibiarkan nyaris tak berubah. Demokrasi akhirnya berhenti sebagai ritual elektoral, bukan sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan.
Baca juga: Yusril: Pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama konstitusional
Ambiguitas akuntabilitas politik
Pendukung pilkada langsung berargumen bahwa pemilihan langsung menciptakan insentif kuat bagi kepala daerah untuk bekerja lebih baik karena bergantung pada suara rakyat. Secara teori, argumen ini koheren.
Namun bukti empiris menunjukkan kenyataan yang jauh lebih ambigu. Banyak daerah dengan kontestasi pilkada kompetitif tetap mencatat stagnasi kualitas layanan publik. Di sejumlah kabupaten dan kota, belanja pendidikan dan kesehatan meningkat secara nominal, tetapi mutu layanan tidak bergerak signifikan karena terserap belanja rutin dan birokrasi.
Masalahnya bukan pada absennya akuntabilitas elektoral, melainkan pada rapuhnya akuntabilitas kebijakan. Kepala daerah memang bertanggung jawab kepada pemilih, tetapi ruang fiskal dan kewenangan kebijakannya sangat terbatas.
Di sebagian besar daerah, lebih dari separuh APBD bersumber dari transfer pusat, terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam konstruksi seperti ini, janji kampanye kerap terputus dari realitas anggaran. Pemimpin dipilih langsung, tetapi tidak memegang kendali penuh atas sumber daya yang menentukan keberhasilan kebijakan.
Kegagalan pilkada langsung dalam menghasilkan perbaikan kesejahteraan bukanlah kegagalan pilihan elektoral, melainkan kegagalan desain ekonomi-politik. Mandat politik yang diperoleh melalui pemilihan langsung tidak diiringi kontrol sepadan atas sumber daya fiskal dan instrumen kebijakan.
Dalam sistem desentralisasi yang sangat bergantung pada transfer pusat, kepala daerah lebih berperan sebagai agen distribusi anggaran nasional ketimbang aktor otonom pembangunan lokal. Kontestasi elektoral menghasilkan legitimasi politik tanpa kapasitas ekonomi, sementara hasil kebijakan tetap dikunci oleh struktur fiskal terpusat dan relasi kekuasaan antar-elite.
Baca juga: Populi Center ungkap survei mayoritas warga ingin Pilkada langsung
Elite capture dan biaya demokrasi
Kelemahan struktural ini diperparah oleh fenomena elite capture. Biaya politik pilkada yang tinggi menciptakan kebergantungan kepala daerah pada sponsor politik dan jaringan oligarki lokal, bahkan nasional. Kemenangan elektoral kemudian dibayar melalui konsesi proyek, distribusi rente, atau kebijakan yang bias pada kepentingan sempit.
Dalam konteks ini, pilkada langsung tidak otomatis memperluas keadilan sosial, melainkan sering kali hanya memperluas arena kompetisi elite.
Fenomena ini bukan anomali Indonesia semata. Berbagai studi komparatif di negara berkembang menunjukkan pola serupa ketika desentralisasi politik tidak diiringi reformasi fiskal dan tata kelola. Demokrasi prosedural berjalan, partisipasi meningkat, tetapi distribusi kesejahteraan tetap timpang karena dikunci oleh relasi kuasa yang tidak demokratis.
Kesalahan terbesar dalam debat pilkada adalah menganggap pemilihan sebagai tujuan, bukan alat. Demokrasi direduksi menjadi peristiwa lima tahunan. Sementara kapasitas negara di tingkat daerah, baik itu perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, sering kali diabaikan. Dalam kerangka ini, pilkada langsung memang meningkatkan legitimasi, tetapi legitimasi tanpa kapasitas hanya melahirkan ekspektasi publik yang tak pernah terpenuhi.
Jika tujuan akhirnya adalah kesejahteraan, maka debat pilkada perlu diarahkan ulang. Pertanyaannya bukan “langsung atau tidak langsung”, melainkan apakah institusi lokal memiliki daya untuk menerjemahkan mandat politik menjadi kebijakan publik yang efektif.
Reformasi yang dibutuhkan justru terletak pada perbaikan desain perimbangan keuangan pusat–daerah, penguatan kapasitas fiskal lokal, transparansi pembiayaan politik, dan profesionalisasi birokrasi daerah.
Polemik ini muncul di tengah agenda yang jauh lebih mendesak; Revisi UU Pemilu. Revisi tersebut semestinya diselesaikan sebelum dimulainya seleksi penyelenggara Pemilu 2029 pada Agustus 2026.
Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pilkada berpotensi baru digelar pada 2031. Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk pembenahan struktural, bukan sekadar mengulang perdebatan prosedural.
Tanpa pembenahan struktural tersebut, mempertahankan pilkada langsung sambil berharap kesejahteraan meningkat hanyalah bentuk policy wishful thinking.
Momentum revisi UU Pemilu pasca-putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dimanfaatkan untuk memperbaiki desain kekuasaan ekonomi dan kapasitas institusi lokal, bukan sekadar mengulang perdebatan prosedural.
Tanpa kekuasaan fiskal dan institusi yang benar-benar bekerja, demokrasi hanya memindahkan legitimasi politik. Sementara kesejahteraan tetap dikunci oleh struktur kekuasaan.
Baca juga: Megawati sebut wacana Pilkada melalui DPRD pengkhianatan reformasi
*) Kusfiardi adalah Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute