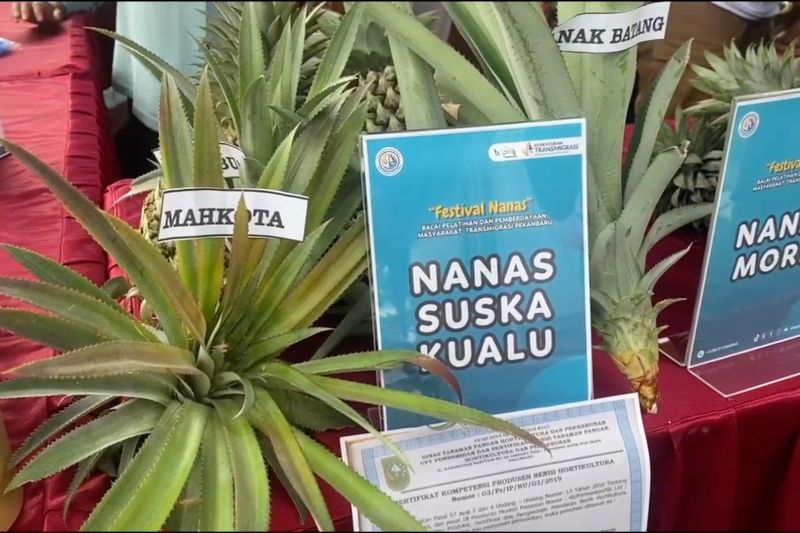Dalam ruang publik hari-hari ini, kritik semakin jarang diperlakukan sebagai praktik intelektual yang wajar. Ia kerap dipersepsikan sebagai ancaman dan gangguan yang tidak diharapkan.
Kritik tidak lagi dinilai dari argumen yang diajukan, tetapi direduksi menjadi persoalan "niat", afiliasi politik, atau dugaan agenda tersembunyi. Pergeseran ini menandai kemunduran serius dalam kehidupan demokratis.
Kritik adalah upaya rasional untuk menguji klaim, kebijakan, dan wacana yang berkembang di ruang publik. Ia bukan ekspresi kebencian. Justru sebaliknya, kritik adalah mekanisme koreksi, sarana refleksi kolektif, dan bentuk ekspresi rasional warga negara dalam mengawasi kekuasaan.
Albert O. Hirschman, dalam Exit, Voice, and Loyalty (1970), menyebut kritik sebagai bentuk voice—saluran partisipasi warga yang memilih tetap terlibat daripada meninggalkan sistem. Dalam kerangka ini, kritik adalah tanda keterikatan, bukan pembangkangan.
Dengan demikian, kritik justru lahir dari kepedulian dan harapan akan perbaikan, bukan dari niat merusak. Ia bekerja sebagai alarm sosial—penanda bahwa ada masalah yang perlu diperiksa.
Kritik berangkat dari kesadaran bahwa tidak ada kekuasaan yang sempurna. Karena itu, dalam sistem demoktratis, kritik berfungsi sebagai mekanisme checks and balances. Ia memungkinkan kebijakan diuji secara terbuka, kesalahan diakui, dan perbaikan dilakukan.
Jurgen Habermas—dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1962)—menempatkan kritik sebagai jantung dari ruang publik modern. Ruang publik menurut Habermas adalah arena di mana warga menggunakan rasionalitas komunikatif untuk menilai tindakan negara dan memungkinkan kontrol demokratis atas kekuasaan.
Tanpa kritik, ruang publik kehilangan fungsi deliberatifnya dan berubah menjadi ruang afirmasi—tempat kebijakan hanya dirayakan, bukan dipertanyakan. Dalam kondisi semacam itu, demokrasi merosot menjadi sekadar prosedur tanpa substansi.
Ketika kritik disampaikan melalui argumen, data, dan pertimbangan etis, ia menjadi energi konstruktif bagi negara dan institusi sosial. Negara yang matang tidak memusuhi kritik, tetapi menggunakannya sebagai sumber pembelajaran.
Antikritik: Dari Ancaman ke DelegitimasiMasalah muncul ketika kritik tidak lagi diperlakukan sebagai masukan, tetapi sebagai ancaman. Di titik inilah muncul fenomena antikritik. Antikritik bukanlah bantahan rasional terhadap argumen, melainkan upaya delegitimasi terhadap pengkritik.
Polanya relatif konsisten: pelabelan kritikus sebagai musuh negara, tidak nasionalis, tidak tahu diri, atau bagian dari kepentingan asing; pengaburan substansi kritik dengan serangan personal (ad hominem); serta penggunaan hukum atau sentimen publik untuk membungkam suara yang berbeda.
Ironisnya, kelompok atau rezim yang paling alergi terhadap kritik justru sering mengeklaim diri sebagai pihak yang paling memahami kepentingan rakyat. Antikritik sering dibungkus dengan narasi stabilitas. Kritik dianggap mengganggu ketertiban, merusak persatuan, atau melemahkan wibawa pemimpin.
Padahal, stabilitas yang dibangun di atas pembungkaman hanyalah ketenangan semu. Di bawah permukaannya, kekecewaan dan ketidakpercayaan terus menumpuk.
Ketika kritik dibungkam, yang hilang bukan hanya kebebasan bicara, melainkan juga kemampuan kolektif untuk belajar dan mengakui kekeliruan. Akibatnya, kesalahan terus diulang, kebijakan gagal dipertahankan, dan jarak antara penguasa dan rakyat semakin melebar.
Dalam jangka panjang, budaya antikritik melahirkan masyarakat yang apatis atau sinis. Warga berhenti berbicara karena takut, atau berbicara dengan nada sarkastik tanpa harapan. Kepercayaan sosial runtuh, digantikan oleh kepatuhan palsu. Kondisi ini mengingatkan apa yang disinyalir Hannah Arendt—dalam The Human Condition (1958)—sebagai "membusuknya politik" (decay of politics).
Politik tidak lagi menjadi sarana bagi kebebasan dan inisiatif manusia yang pada akhirnya mengarah pada dehumanisasi kehidupan publik.
Rezim Paranoid: Ketika Kekuasaan Hidup dalam KecurigaanAntikritik—jika dilembagakan dan dinormalisasi—berkembang menjadi apa yang dapat disebut sebagai rezim paranoid. Rezim paranoid bukan semata soal bentuk pemerintahan otoriter. Ia bisa hadir dalam sistem yang secara formal demokratis, tetapi secara mentalitas anti-demokrasi.
Ciri utamanya adalah kecurigaan berlebih. Alih-alih membantah kritik dan membuka ruang dialog, rezim paranoid memilih membangun narasi ancaman permanen. Pola ini mencerminkan apa yang oleh Carl Schmitt—dalam The Concept of the Political (1996)—sebut sebagai reduksi politik ke dalam logika kawan-lawan. Ketika kritik ditempatkan di sisi "lawan", dialog menjadi mustahil dan yang tersisa hanyalah kecurigaan.
Kritik kemudian dibaca sebagai ancaman besar: diskusi intelektual dianggap konspirasi dan perbedaan pendapat dicurigai sebagai upaya menjatuhkan kekuasaan. Dalam rezim paranoid, kesetiaan lebih dihargai daripada kebenaran dan ketenangan lebih penting daripada kejujuran. Yang diproduksi bukan dialog, melainkan pembungkaman simbolik: intimidasi, kriminalisasi selektif, dan penciptaan efek jera.
Dalam konteks Indonesia hari ini, gejala rezim paranoid terlihat dalam respons terhadap kritik publik, khususnya yang datang dari media sosial, komedi, dan ruang intelektual. Polanya berulang, aktornya beragam, tetapi logikanya sama: kritik diposisikan sebagai masalah.
Kasus pelaporan Pandji Pragiwaksono menjadi contoh kasat mata. Kritiknya—yang disampaikan melalui komedi—tidak ditanggapi dengan klarifikasi data atau adu argumen terbuka, tetapi dibawa ke ranah hukum. Persoalannya bukan soal setuju atau tidak setuju dengan isi kritik, melainkan mengapa komedi harus dipersoalkan menjadi perkara pidana.
Komedi sejak lama adalah bahasa kritik yang sah. Ia menyederhanakan persoalan rumit agar dapat diakses publik. Dalam banyak demokrasi matang, kemampuan menertawakan kekuasaan justru dianggap indikator kesehatan politik. Ketika komedi diperlakukan sebagai ancaman stabilitas, yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan seniman, melainkan kedewasaan demokrasi itu sendiri.
Hal serupa tampak dalam pembatalan diskusi buku Reset Indonesia. Tanpa kekerasan terbuka dan larangan resmi, ruang diskusi ditutup atas nama "keamanan" dan "kondusivitas".
Jika ruang diskusi intelektual—yang paling jinak dalam demokrasi—saja dianggap berbahaya, pertanyaannya sederhana: Apa yang sebenarnya ditakuti? Gagasan, atau publik yang mulai berpikir di luar narasi resmi?
Peringatan moral terhadap kritik—agar tidak provokatif, tidak menyesatkan, dan tidak memperkeruh suasana—sering kali terdengar masuk akal. Namun, karena frasa-frasa ini sangat lentur, ia mudah digunakan untuk membungkam kritik apa pun yang tidak nyaman. Pada titik ini, yang dijaga bukan ketertiban publik, melainkan ketenangan kekuasaan.
Kita tidak hidup dalam rezim yang secara terang melarang kritik, tetapi dalam atmosfer yang membuat kritik melelahkan, berisiko, dan penuh konsekuensi personal. Ini bukan pembungkaman melalui larangan tegas, melainkan melalui efek jera. Pesannya implisit, tetapi jelas: silahkan berbicara, tetapi bersiaplah menanggung akibatnya.
Merawat Kritik, Menghindari ParanoiaMembela kritik bukan berarti membenarkan semua kritik. Kritik tetap harus diuji, dibantah, bahkan ditolak jika keliru. Namun penolakan harus dilakukan dengan argumen, bukan dengan paranoia.
Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu membedakan kritik dari ancaman dan perbedaan dari permusuhan. Kekuasaan yang percaya diri tidak sibuk mengawasi komika, influencer, atau diskusi buku. Ia sibuk menjawab kritik dengan argumen dan kinerja.
Pada akhirnya, kritik adalah cermin relasi antara kekuasaan dan warga negara. Ketika kritik dibungkam dan dianggap masalah, kita patut bertanya: Apa yang sebenarnya sedang dipertahankan? Ketertiban dan kepentingan bersama? Atau sekadar citra, legitimasi rapuh, dan kenyamanan kekuasaan yang enggan dikoreksi?
Dalam ruang publik yang dewasa, kritik tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dirawat—karena hanya dengan cara itulah kekuasaan, apa pun bentuknya, bisa tetap waras.