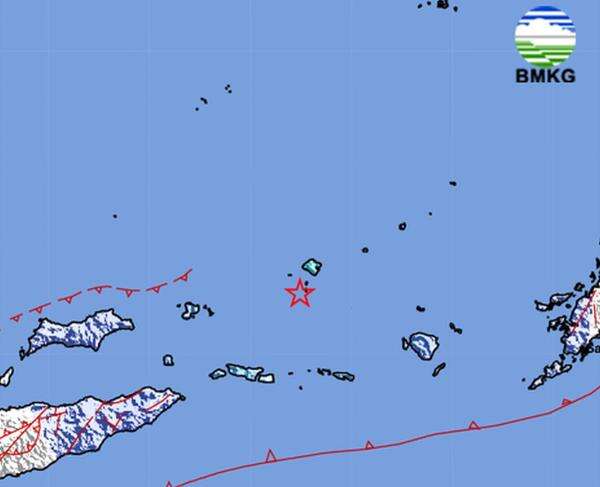Asap tipis di angkringan mengepul dari sebuah teko logam yang menghitam akibat jelaga arang. Di bawah temaram lampu jalan yang mulai menguning, aroma jahe bakar menyeruak, beradu dengan wangi nasi kucing yang terbungkus rapi dalam daun pisang. Suara denting sendok yang beradu dengan gelas kaca menjadi musik latar di sebuah sudut trotoar yang sempit. Di sini, di atas bangku kayu panjang yang sudah mulai melapuk, sebuah ruang sosial tercipta. Tidak ada sekat, tidak ada protokol, dan yang terpenting: tidak ada kasta.
Angkringan, sebuah entitas kuliner yang sederhana, rupanya menyimpan kekuatan magis yang melampaui sekadar tempat pengisi perut. Ia adalah rahim bagi ribuan narasi yang lahir setiap malamnya. Di balik uap kopi panas yang disajikan, tersimpan denyut nadi kehidupan masyarakat yang mencari pelarian, kawan, hingga sekadar pendengar bagi keluh kesah yang tak tersampaikan di rumah atau kantor.
Bagi Basuki Tohari (55), seorang pemilik angkringan yang telah bertahun-tahun menghabiskan malamnya di balik gerobak kayu, pekerjaannya bukan soal meracik minuman, Basuki menjadi saksi bisu dari banyaknya kata yang terlontar di atas meja dagangannya. Dengan kopiah yang dipakainya, ia mengamati bagaimana angkringannya bertransformasi menjadi panggung cerita kehidupan.
"Angkringan itu bukan cuma jualan gorengan, kopi, wedang jahe, ataupun nasi kucing," ujar Basuki sembari menata sate usus di atas nampan plastik. Baginya, ada komoditas lain yang tidak tertulis di daftar menu, namun selalu habis terjual setiap malam; empati.
"Kalau ditanya yang dicari orang apa, ya bukan cuma kenyang. Di sini itu tempat orang berkeluh kesah. Setiap hari saya denger cerita yang berbeda-beda. Ada yang bahas politik sampai debat panjang, ada yang bahas kerjaan, ada yang juga yang bercanda. Pokoknya banyak macam ragamnya," tambahnya dengan nada suara yang tenang.
Basuki juga menambahkan bahwa angkringan sebagai ‘ruang tamu bersama’. Sebuah analogi yang cerdas untuk menggambarkan sebuah tempat di mana siapa pun boleh masuk tanpa perlu merasa terintimidasi oleh kemewahan.
"Siapa pun boleh datang, duduk, dan bicara tanpa jaga muka," tegasnya. Di hadapan Basuki, seorang pejabat dan seorang buruh bisa menjadi sama-sama "telanjang"—melepaskan atribut sosial mereka demi menyesap segelas kopi yang sama.
Ketertarikan masyarakat terhadap angkringan dirasakan betul oleh Ratna Ningsih (47). Sebagai ibu rumah tangga yang kerap merasa penat dengan rutinitas rumah, angkringan adalah tempat berteduhnya.
"Saya datang hampir tiap malam. Biasanya ya cuma buat beli wedang jahe atau teh panas. Tapi juga saya sering makan di sini. Hitung-hitung mengobati rasa capek," tutur Ratna. Penampilannya sangat kontras dengan pengunjung kafe-kafe kekinian di pusat kota. Ia hanya mengenakan daster batik sederhana dan sandal jepit. Namun, justru itulah poin utamanya.
"Wah, saya malah enggak suka sama kafe-kafe begitu. Mending di sini, bisa duduk pakai sandal jepit, pakai daster, sambil ngerokok, dan ngobrol sama siapa saja," katanya sambil tertawa kecil. Bagi Ratna, angkringan menawarkan kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dengan kehangatan antar manusia yang spontan.
Ia sering membawa tetangganya sebagai teman bicara, namun tak jarang pula ia justru terlibat percakapan mendalam dengan orang asing yang kebetulan duduk di sebelahnya.
"Nggak kenal, tapi tiba-tiba sudah ngobrol saja. Menurut saya obrolan di sini ataupun hubungan di sini hangat, jujur tanpa dibuat-buat sama sekali," pungkas Ratna.
Fenomena angkringan sebagai ruang sosial juga menarik minat generasi muda yang seharusnya lebih akrab dengan coffee shop estetik dan koneksi Wi-Fi kencang. Dhaniswara Ahmad (20), seorang mahasiswa, memberikan sudut pandang menarik.
"Saya suka banget sama kafe, bahkan sering juga ke kafe. Tapi angkringan itu vibes-nya beda banget, kayak ada ketenangan sendiri di situ," jelas Dhaniswara.
Ia melihat sebuah perbedaan yang ironis antara kafe modern dan angkringan. Di kafe, orang seringkali terjebak dalam kesunyian individual, sibuk dengan gawai atau laptop masing-masing. Namun di angkringan, orang antusias mendengarkan cerita orang lain.
Dhaniswara menceritakan sebuah pengalaman yang menurutnya sangat membekas. Suatu malam, saat ia sedang buntu mengerjakan tugas kuliah di atas meja angkringan, seorang pria paruh baya di sebelahnya memberikan ide yang segar.
"Terus malah dibantuin kasih ide sama bapak-bapak yang kebetulan lagi ngopi di sebelahku. saya merasa ada suasana hidup sama vibes kekeluargaan yang nggak saya temuin di tempat yang serba minimalis dan estetik," kenangnya.
Kehadiran mahasiswa seperti Dhaniswara membuktikan bahwa angkringan adalah ruang yang sangat inklusif. Di sini, status akademik atau usia tidak menjadi pembatas. "Kita bisa duduk bareng orang yang beda-beda, kadang sama delman, tukang parkir, dosen, mahasiswa, semua setara," imbuhnya.
Saat kota mulai sunyi dan sebagian besar jendela rumah sudah tertutup rapat, angkringan mencapai puncak perannya sebagai "penyelamat". Bagi mereka yang bekerja di gelapnya malam, seperti Andriyono Aprianto (29), seorang driver ojek online, angkringan adalah terminal pemberhentian terakhir sebelum kembali ke ‘tempat pulang’.
"Bagi saya, angkringan itu terminal istirahat. Kalau jam 3 pagi mata sudah sepet, narik orderan mulai sepi, pelariannya ya ke sini," ujar Andriyono sembari menyeruput kopi hitamnya. Di saat dunia luar terasa keras dengan tuntutan target dan algoritma aplikasi, meja kayu angkringan menawarkan jeda.
Di sini, Andriyono menemukan ekosistem dukungan dari sesama pekerja malam. "Biasanya saya juga ketemu teman seprofesi, ngobrol tentang ‘spot’ ramai, atau cuma sekadar bercanda, ya hitung-hitung pelepas penat atau penghilang stres," ungkapnya.
Menariknya, bagi Andriyono, sosok penjual seperti Basuki seringkali menjadi terapis dadakan. "Sesekali ngobrol juga sama yang punya angkringan, enggak kenal tapi beliau mau mendengar," ujarnya.
Angkringan adalah bukti bahwa, seberapa pun majunya teknologi, manusia tetaplah makhluk sosial yang membutuhkan sentuhan narasi nyata. Ia menjadi katup pengaman sosial di tengah hiruk pikuk tekanan ekonomi dan politik. Di atas bangku kayunya, demokrasi tidak perlu diperdebatkan di atas mimbar; ia dipraktikkan secara alami melalui segelas teh manis dan sepiring nasi kucing.
Angkringan, dengan segala kesederhanaannya, memperlihatkan bahwa ruang publik tidak selalu harus megah atau berteknologi tinggi. Ia justru hidup karena kedekatan, kehangatan, dan keterbukaan. Di balik kopi panas dan lampu temaram, angkringan menjadi panggung kecil bagi cerita-cerita tentang manusia, tentang kebutuhan untuk didengar, dan tentang kebersamaan yang lahir tanpa syarat. Di sanalah ruang sosial rakyat terus bertahan, menyimpan percakapan, tawa, dan harapan yang tak pernah benar-benar padam.
Hingga fajar menyingsing, angkringan akan tetap ada. Bukan hanya sebagai unit usaha kecil menengah, melainkan sebagai monumen kehidupan rakyat. Ia adalah tempat di mana kopi panas tidak hanya menghangatkan kerongkongan, tetapi juga menghangatkan jiwa-jiwa yang haus akan cerita dan keberadaan manusia lainnya. Selama orang masih butuh didengar, selama itu pula angkringan tak akan pernah kehilangan ceritanya.



/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2026%2F01%2F20%2F1fa2c81acdbded3a605112db259cc496-FAK_0437.jpg)