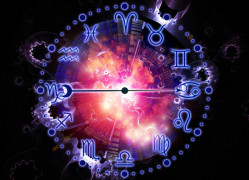Bukti ilegal akhir-akhir ini menjadi satu permasalahan yang hangat di media sosial. Hal tersebut membuka sebuah pertanyaan bagaimana kedudukan bukti ilegal jika digunakan untuk menjerat seseorang ke dalam proses pemidanaan? Hukum pidana sejatinya tidak hanya berbicara tentang benar dan salah dalam arti sempit normatif. Ia adalah cermin tentang bagaimana negara memaknai keadilan, martabat manusia, dan batas kekuasaannya sendiri. Ketika hukum terlalu sibuk mengejar ketertiban formal, ia kerap lupa pada satu prinsip mendasar: keadilan tidak boleh lahir dari cara yang tidak adil.
Dalam konteks itulah perdebatan mengenai bukti ilegal menjadi relevan. Alat bukti bukan sekadar instrumen teknis dalam pembuktian, melainkan fondasi legitimasi dari seluruh proses peradilan pidana. Jika fondasi itu cacat, maka putusan seadil apa pun akan kehilangan maknanya.
Bukti dan Moralitas ProsesHukum acara pidana mengajarkan bahwa pembuktian adalah jantung dari proses peradilan. Namun jantung itu hanya akan memompa keadilan apabila darah yang mengalir di dalamnya bersih. Bukti yang diperoleh secara melawan hukum baik melalui pelanggaran hak cipta, penyadapan ilegal, perolehan tanpa hak, maupun pelanggaran privasi adalah darah yang tercemar, yang sejak awal merusak legitimasi proses peradilan pidana.
Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).
Dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP Baru ditegaskan bahwa:
Penegasan tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 235 ayat (3) KUHAP Baru, yang menyatakan bahwa:
Dengan demikian, legalitas cara perolehan bukti merupakan syarat esensial, bukan sekadar formalitas administratif. Bukti yang isinya relevan tetapi diperoleh melalui cara yang melanggar hukum kehilangan kekuatan pembuktiannya secara hukum acara.
Sejalan dengan itu, dalam doktrin hukum pidana modern dikenal prinsip exclusionary rule, yakni bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak boleh digunakan sebagai dasar pemidanaan. Prinsip ini bukan dimaksudkan untuk melindungi pelaku kejahatan, melainkan untuk membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Negara tidak boleh menjadi pelanggar hukum atas nama penegakan hukum.
Hukum yang baik tidak hanya menghukum perbuatan yang salah, tetapi juga mendidik pelaksananya agar taat pada caranya sendiri. Sebab ketika hukum membenarkan pelanggaran prosedur demi mencapai putusan, maka yang runtuh bukan hanya satu perkara, melainkan martabat keadilan itu sendiri.
Ketika Kasus Konkret Menguji Prinsip UmumPerdebatan ini menjadi nyata ketika hukum berhadapan dengan perkara yang melibatkan ekspresi seni, kritik, dan satire. Dalam salah satu perkara yang belakangan mencuat di ruang publik—yang melibatkan seorang komedian dan pertunjukan berjudul Mens Rea—muncul persoalan serius mengenai alat bukti berupa rekaman pertunjukan yang diperoleh tanpa hak dari platform berlangganan.
Terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadap isi pertunjukan tersebut, pertanyaan hukumnya tetap sama: apakah negara boleh menghukum seseorang dengan menggunakan bukti yang lahir dari pelanggaran hukum lain? Jika jawabannya iya, maka hukum telah kehilangan batasnya sendiri.
Pertunjukan tersebut adalah karya berhak cipta yang distribusinya berada di bawah kendali platform resmi, yakni Netflix. Mengunduh, merekam, menggandakan, lalu menyerahkannya sebagai alat bukti tanpa hak dan izin, pada dasarnya adalah tindakan ilegal. Maka, sejak awal, bukti itu telah berdiri di atas pelanggaran hukum lain.
Di sinilah ironi hukum muncul:
Bagaimana mungkin hukum menuntut kepatuhan warga, jika ia sendiri membenarkan pelanggaran sebagai jalan menuju penghukuman?
Hukum tidak boleh menjadi mesin otomatis yang hanya bekerja berdasarkan tombol pasal. Hukum harus berani bertanya: untuk siapa ia ditegakkan? dan dengan cara apa ia bekerja?.
Dalam konteks ini, menolak barang bukti ilegal bukan berarti membela isi materi, melainkan membela proses hukum yang bermartabat. Keadilan prosedural adalah prasyarat keadilan substantif.
Ketika Hukum Harus BercerminTulisan ini ingin mengajak kita semua untuk menegaskan bahwa hukum pidana bukan alat moral policing, bukan pula instrumen balas dendam kultural. Ia adalah jalan terakhir (ultimum remedium) yang harus dijalankan dengan kehati-hatian ekstrem.
Bukti ilegal tidak boleh dijadikan bukti, bukan karena hukum terlalu lunak, tetapi karena hukum terlalu berharga untuk dikotori oleh cara-cara yang tidak sah. Jika hukum kehilangan integritas prosedurnya, maka yang runtuh bukan hanya satu perkara, melainkan kepercayaan publik terhadap keadilan itu sendiri. Dan pada titik itulah, hukum berhenti menjadi penjaga keadilan ia berubah menjadi sekadar kekuasaan yang bersuara.