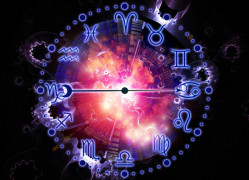Sebelum pembaca membaca artikel ini lebih lanjut, penulis merasa perlu untuk memberikan pengantar untuk tulisan ini. Jadi artikel ini ditulis dalam rangka membahas menurunnya jumlah simpatisan Muhammadiyah yang pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada tahun 2023.
Hasil temuan survei LSI Denny JA menyatakan pada tahun 2005 jumlah umat Muslim yang menyatakan dirinya berafiliasi kepada Muhammadiyah sekitar 9,4% dan pada tahun 2023 menjadi 5,7%. Dalam hasil survei yang diulas di akun Youtube Orasi Denny JA, tidak dijelaskan secara detail dan hanya menjelaskan problemnya hanya masalah perkaderan. Namun penulis memotret analisa yang jauh lebih mendalam daripada itu, dan masalahnya tidaklah sesederhana masalah metode perkaderan yang ketinggalan zaman terdapat sejumlah masalah eksistensial di dalam tubuh Muhammadiyah. Semua itu penulis ulas tuntas dalam artikel ini.
Tentu ironis sekali ormas Islam terbesar no.2 di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama (NU), kemudian mengalami masalah penurunan jumlah massa yang signifikan. Sedangkan hasil survei LSI Denny JA menunjukkan NU mengalami jumlah kenaikan simpatisan drastis dari tahun 2005 yang hanya 27,5% menjadi 56,9% pada tahun 2023.
Artikel ini adalah esai penulis untuk media Stratsea.com, sebuah media dan think tank khusus kajian wilayah Asia Tenggara yang berbasis di Singapura. Penulis tahun 2025 terpilih bersama 5 orang peneliti untuk menulis "Political Islam Series - Stratsea.com" lewat kurasi yang sangat ketat, saat itu penulis mengajukan sebuah artikel penelitian yang penulis tulis dalam bahasa Inggris berjudul: "Understanding Muhammadiyah's Waning Influence" yang dimuat pada tanggal 31 Juli 2025.
Menulis sebuah artikel penelitian yang ringkas namun mendalam dalam bahasa Inggris merupakan tantangan tersendiri, yang memerlukan beberapa kali revisi; untuk memastikan kedalaman analisis, ketepatan fakta, dan kesesuaian dengan standar ilmiah. Semuanya dalam batasan ruang yang ditentukan. Publikasi tulisan ini, pada akhirnya, adalah berkat arahan dan masukan konstruktif dari Muhammad Sinatra, Pemimpin Redaksi Stratsea.com. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus.
Sayangnya setelah tulisan itu diterbitkan, tulisan ini hanya beredar di kalangan internasional dan tidak menjangkau banyak pihak di Indonesia, terutama warga dan para elite Muhammadiyah yang penulis mengharapkan membaca tulisan ini, supaya dapat menjadi sarana perbaikan bagi organisasi Muhammadiyah ke depannya. Atas saran dari kawan penulis yang kebetulan seorang jurnalis yakni Reynaldi Adi Surya, ia menyarankan agar artikel ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dimuat di media berbahasa Indonesia agar dapat menjangkau audiens lebih luas, khususnya warga dan para petinggi Muhammadiyah.
Untuk memperluas jangkauan dan dampaknya, khususnya bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan warga Muhammadiyah di Indonesia, artikel tersebut kemudian penulis terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian konteks seperlunya agar mudah dipahami pembaca Indonesia. Judul dan sub-judul hingga substansi utama tetap dipertahankan.
Berikut adalah artikel "Memahami Melemahnya Pengaruh Muhammadiyah (Understanding Muhammadiyah's Waning Influence)" - silakan dibaca:
Muhammadiyah dalam Era PostmodernismeMuhammadiyah, yang berdiri pada 1912 dengan semangat modernisasi Islam dan pemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah sejak awal hadir sebagai proyek pembaruan yang menentang kolonialisme Belanda, sekaligus praktik keagamaan yang dianggap tidak rasional seperti takhayul, bid’ah, dan khurafat (churofat), yang populer disebut “TBC” dalam percakapan sehari-hari.
Perkembangan pesat Muhammadiyah di awal berdirinya dan juga wacana segar di awal berdirinya yakni “modernitas dan pemurnian ajaran Islam” membuat Muhammadiyah berdiri seperti mercusuar keislaman modern: tegak, tajam, dan penuh keyakinan. Wajar bila setelah berdirinya Muhammadiyah memperoleh banyak dukungan dan anggota, sehingga membuatnya menjadi salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia.
Selama puluhan tahun, Muhammadiyah tumbuh menjadi raksasa civil society Indonesia. Namun kini, angka-angka yang sunyi tetapi jujur menampakkan kenyataan lain.
Sebuah survei yang dilakukan pada 2023 oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa jumlah orang yang “menyebut dirinya warga Muhammadiyah” menurun drastis. Survei yang sama pada 2005 menunjukkan 9,4% responden mengaku berafiliasi sebagai warga Muhammadiyah, tetapi angka ini turun menjadi 7,8% pada 2014 dan kemudian 5,7% pada 2023.
Sementara itu dalam survei LSI Denny JA di rentang tahun yang sama; Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebuah organisasi yang dulu dianggap tradisionalis justru berkembang drastis dari 27,5% menjadi 56,9% dalam kurun yang sama.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah detak pelan perubahan zaman di mana Muhammadiyah harus bercermin pada dirinya sendiri.
Tulisan ini berupaya menjelaskan merosotnya pengaruh Muhammadiyah dengan menyoroti dua fondasi utamanya (raison d’etre): modernisme Islam dan pemurnian ajaran Islam.
Tulisan ini mencoba menjelaskan penurunan Muhammadiyah dengan menyoroti persoalan-persoalan yang mempengaruhi dua prinsip utama organisasi tersebut.
Tidak Lagi Cukup Modern?Pilar kemodernan Islam Muhammadiyah yang telah lama dipegang tampaknya semakin tidak selaras dengan iklim intelektual dan sosio-religius Indonesia saat ini. Dulu wacana modernitas merupakan wacana menarik bagi kaum terdidik pra-Reformasi karena pendekatannya yang dianggap rasional dan sangat menekankan kemurnian agama dengan berbasis teks-teks otoritatif agama. Kini kerangka modernis Muhammadiyah kini menghadapi kritik dan tantangan epistemis dari pemikiran postmodern dan postkolonial yang mengungkap asumsi-asumsi modernitas yang pada dasarnya berpusat pada Barat dan eksklusif serta “bias kolonial.” Cara pandang modernisme sendiri sudah semakin dipertanyakan di negara-negara Barat sendiri, tempat asal modernisme berasal. Apalagi di negara-negara berkembang yang kita sebut kini sebagai “Global South.”
Perubahan wacana intelektual dari modernisme ke posmodernisme kini telah membentuk ulang wacana Islam global. Posmodernisme Islam kini telah menggantikan modernisme Islam dan Islamisme yang mulai digantikan oleh post-Islamisme: sebuah wacana yang menekankan pluralisme, refleksivitas, dan hak-hak individual.
Di Indonesia, tren ini mengangkat Nahdlatul Ulama, yang dulu dianggap tradisionalis dan hanya menang secara basis massa serta dianggap gagap ketika berbicara soal modernisme. Kini NU menjadi organisasi yang lincah secara intelektual dalam menghadapi isu-isu posmodernisme. Di bawah Abdurrahman Wahid, banyak pemuda NU dikirim untuk belajar di Barat dan kembali dengan pola pikir kritis.
Para intelektual NU tersebut dipengaruhi oleh berbagai pemikiran mutakhir seperti hermeneutika feminis, dekonstruksi, posmodernisme, post-islamisme, teori post-kolonialisme, dan ekoteologi, yang kini membentuk wacana dominan Islam Indonesia. NU hadir bukan saja besar mulai dari gender hingga keadilan lingkungan. NU kini menang secara basis massa dan juga dalam menguasai wacana keislaman di publik. Walhasil NU bukan lagi sebagai kelompok tradisionalisme Islam, melainkan post-tradisionalisme Islam.
Sementara itu, Muhammadiyah tetap berpegang pada paradigma modernis-rasionalis abad 20 yang semakin sulit menginspirasi generasi baru. Sebab landasan berpikir modernitas yang berlandaskan pada oposisi-biner, serta pandangan dunia (world view) modernisme sudah banyak dikritisi serta didekonstruksi baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis oleh banyak pemikir dan filsuf posmodernis. Sehingga modernisme, bukan lagi menjadi kajian serta wacana intelektual yang seksi di dunia akademik.
Meski kuat secara kelembagaan di bidang pendidikan dan kesehatan, relevansi ideologis Muhammadiyah semakin memudar.
Munculnya kerangka post-Islamist dan post-traditionalist juga membuka jalan bagi aktor lain untuk memimpin dalam membentuk lanskap keagamaan Indonesia, semakin meminggirkan Muhammadiyah.
Di tingkat akar rumput, masyarakat pun kesulitan memahami komitmen Muhammadiyah terhadap modernitas karena kecenderungannya melihat masalah kompleks melalui perspektif yang satu dimensi.
Contoh yang sering disebut adalah kegaduhan tentang sikap Muhammadiyah terhadap rokok dan air mineral, yang mencerminkan posisi organisasi yang dipertanyakan.
Banyak pengikut Muhammadiyah adalah pemilik warung kelontong dan toko sembako, tempat rokok dan air mineral dalam kemasan dijual bebas. Banyak orang Indonesia merokok, dan sebagai negara tropis, masyarakat sangat bergantung pada air mineral kemasan ketika cuaca panas. Artinya, pemilik toko yang berafiliasi Muhammadiyah mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan dua komoditas ini.
Namun, fatwa Muhammadiyah mengenai kedua barang tersebut tampak mengabaikan realitas ekonomi anggotanya. Pada 2010, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang menyatakan rokok haram, menyebutnya tidak sehat dan pemborosan. Fatwa ini mengesampingkan ketergantungan ekonomi petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik rokok serta asbak, karyawan perusahaan rokok, SPG rokok, dan distributor.
Fatwa tersebut menimbulkan konflik batin bagi anggota Muhammadiyah yang merokok, membuat mereka mempertanyakan tidak hanya fatwa tetapi juga organisasi. Bahkan kader Muhammadiyah yang sudah lama pun banyak yang mengabaikan fatwa ini dan tetap merokok, sehingga memperumit hubungan mereka dengan organisasi.
Pada 2014 mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin tampaknya menentang apa yang ia sebut sebagai eksploitasi monopolistik atas sumber air oleh perusahaan swasta dan asing yang memproduksi air mineral kemasan di Indonesia. Dengan alasan bahwa air adalah sumber daya alam yang semestinya dikelola oleh negara untuk hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945. Din bahkan mendorong organisasi Muhammadiyah mengeluarkan fatwa agar mengharamkan produk tersebut. Walaupun faktanya ia sendiri masih minum air mineral.
Namun langkah drastis ini berdampak negatif pada ribuan bahkan jutaan orang serta bisnis yang terlibat dalam ekosistem produk tersebut. Bagi pedagang kaki lima atau warung, tidak penting apakah produsennya asing atau lokal selama mereka bisa bertahan hidup.
Jika fatwa semacam itu dikeluarkan, hal ini menempatkan pemilik usaha, penjual, dan konsumen, termasuk pengikut Muhammadiyah dalam posisi sulit, karena menjual dan mengonsumsi air mineral kemasan dianggap dosa.
Dua episode ini menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah mempromosikan prinsip modernitas, organisasi ini juga terlibat dalam kontroversi yang mempertanyakan kedalaman pemahaman mereka terhadap konsep modernitas maupun akar intelektualnya. Akibatnya, baik pengikut Muhammadiyah maupun publik menjadi tidak yakin terhadap organisasi ini.
Kurangnya Gairah GerakanKedua, selama dalam perjalanan sejarahnya Muhammadiyah memiliki misi suci (mission sacre) untuk memurnikan praktek keberislaman di Indonesia dari pengaruh TBC. Selama dalam lintasan sejarah, Muhammadiyah mendapatkan reaksi yang tidak kalah keras atas upayanya terutama dari kalangan Islam tradisionalis yang masih mempertahankan praktek keberagamaan yang dianggap TBC.
Belakangan terjadi pergerseran paradigma dalam tubuh Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah sudah mulai mengalami moderasi serta kehilangan gairah (missionary zeal) untuk memberantas pengaruh TBC. Walhasil Muhammadiyah yang semula hadir secara raison d’etre untuk memurnikan ajaran Islam dari praktek TBC kini melunak dan tidak lagi menjadi fokus utama. Orientasi organisasi kini beralih pada pelayanan sosial seperti pengelolaan rumah sakit, sekolah, universitas, panti asuhan, dan lembaga wakaf.
Ini menunjukkan perubahan pandangan dunia (worldview) Muhammadiyah. Muhammadiyah masih secara resmi di internal organisasinya hingga institusi pendidikannya masih mengajarkan bahwa cabang praktek-praktek peribadatan (furu’iyah) yang seperti qunut, tahlil, tawasul, barzanji, sebagai praktek TBC. Dalam hal ini Muhammadiyah masih berbagi pandangan tentang hal apa yang disebut sebagai praktek TBC dengan organisasi Islam modernis lain seperti Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Tetapi juga tidak secara terbuka menentang kelompok Islam tradisional yang masih mempraktikkannya, seperti qunut, tahlil, tawasul, maulid, barzanji, dan tabarruk.
Kini Muhammadiyah memilih untuk hidup berdampingan dengan seluruh komunitas Islam, dan bahkan menghindari pelabelan sesat terhadap para pelaku TBC. Kurang lebih sikapnya dapat diringkas begini: “Kami memahami bahwa tahlilan, qunut, tawasul, dan praktik sejenisnya termasuk TBC. Namun kami tidak mengafirkan atau menyesatkan siapa pun yang melakukannya. Silahkan, monggo, kami hanya memilih tidak ikut.”
Sikap yang lebih lunak dan tidak lagi konfrontatif terhadap praktik-praktik TBC ini perlahan membuat Muhammadiyah kehilangan “daya pikat” bagi kalangan yang masih tertarik pada isu pemurnian agama. Kekosongan itulah yang kemudian diisi oleh gerakan-gerakan Islam transnasional. Kelompok-kelompok ini berasal dari luar negeri—terutama Timur Tengah—tetapi telah menemukan pijakan yang kokoh di tengah sebagian umat Islam Indonesia. Di antaranya adalah Wahhabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia (yang kini dibubarkan namun pernah berpengaruh besar), hingga jaringan Salafi-jihadi seperti Al-Qaeda dan ISIS.
Gerakan-gerakan tersebut bergerak dengan gairah keagamaan yang menyala (divine fervor) dan semangat dakwah yang menggebu (missionary zeal), sebuah tenaga ideologis yang membuat mereka lebih militan dalam agenda pemurnian Islam, khususnya terhadap praktek-praktek yang mereka anggap sebagai TBC. Mereka tampil jauh lebih tegas dan meyakinkan, ketimbang Muhammadiyah yang kini lebih hati-hati dan kurang berfokus pada isu ini. Hal ini membuat kelompok-kelompok Islam transnasional tampil sebagai pewaris baru semangat pemurnian Islam yang dahulu menjadi ciri khas gerakan modernisme Islam di Indonesia.
Melemahnya dorongan Muhammadiyah untuk memimpin agenda pemurnian Islam kemudian memberi ruang luas bagi kelompok-kelompok Islam transnasional untuk menyebarkan ajaran dan pengaruhnya. Dinamika ini akan dibahas lebih jauh pada bagian berikutnya.
Pengaruh yang TenggelamSementara itu, kelompok Islam transnasional giat menentang dan memerangi praktik TBC, mengkritiknya secara militan dengan penuh gairah dakwah melalui media sosial dan kajian. Dari interaksi penulis dengan para simpatisan Muhammadiyah, semangat kelompok Islam transnasional itu pun turut memikat mereka. Terlihat di berbagai tempat di Indonesia kelompok Islam transnasional itu disambut oleh tangan terbuka, terutama oleh kalangan akar rumput (grassroot) dan fungsionaris Muhammadiyah karena kesamaan ajaran. Hal ini dapat dipahami, karena kesamaan ajaran teologis antara Muhammadiyah dengan kelompok Islam transnasional ini yang sama-sama memerangi TBC, hal ini turut memikat simpatisan Muhammadiyah.
Sehingga tidak sedikit orang-orang Muhammadiyah yang turut membaca karya-karya pemikiran Islam transnasional, bahkan mendengar dakwah para pendakwah dari kelompok-kelompok Islam transnasional. Terlebih lagi beberapa dari mereka, mulai merasa organisasi Muhammadiyah kini menjauh dari agenda pemurnian Islam.
Ketika dulu Muhammadiyah mendominasi agenda ini, kini kelompok-kelompok transnasional menjadi wajah utamanya, sehingga mengurangi daya tarik Muhammadiyah. Bagi orang awam yang tidak mendalami Islamologi, tentunya sulit sekali membedakan antara simpatisan Muhammadiyah dengan kelompok Islam transnasional.
Hal yang menjadikan kelompok Islam transnasional dianggap memiliki legitimasi dan dianggap lebih berhak memimpin agenda ini. Karena berasal dari Timur Tengah, Islam mereka dianggap lebih murni, otentik, dan militan. Dibandingkan itu, ajaran Muhammadiyah telah yang telah disesuaikan agar sesuai kondisi sosial Indonesia, membuat klaim otentisitasnya lebih lemah.
Semua ini diperkuat oleh dukungan negara kaya minyak (petrodollar) dari Timur Tengah; khususnya Arab Saudi dan Qatar, serta donor simpatisan di kawasan. Meskipun belakangan Arab Saudi telah kehilangan gairah dalam menyebarkan ajaran Wahhabisme ke seluruh dunia dan lebih berhati-hati akhir-akhir ini, setelah adanya Reformasi Pangeran Muhammad bin Salman. Namun tidak menutup fakta bahwa selama puluhan tahun Arab Saudi berperan besar menyebarkan ajaran Wahhabi dan jaringan dana dari sana tetap besar. Sekarang peran tersebut lebih dimainkan oleh Qatar yang masih menjadi “patron” terutama bagi gerakan Ikhwanul Muslimin di dunia.
Adanya jaringan ke luar negeri ini sangat memikat banyak orang yang tertarik untuk menjadi aktivis gerakan Islam transnasional. Para aktivis gerakan-gerakan ini juga dibina melalui beasiswa studi ke Timur Tengah, yang menjadi daya tarik besar. Tidak ada ideologi yang dapat berkembang cepat tanpa dana dan jaringan yang kuat. Intinya logika tanpa logistik, anarkis. Sebab kita tahu umat manusia lebih takut lapar dari mati, makanya ada istilah: “pasukan berani mati, takut lapar.”
Bangkitnya kelompok-kelompok ini lebih mengancam Muhammadiyah daripada NU. NU memiliki perbedaan hukum dan praktik yang tajam, sehingga pengikutnya cenderung menolak ajaran kelompok transnasional. Sebaliknya, Muhammadiyah berbagi akar teologis, sehingga lebih mudah bagi kelompok tersebut menjangkau pengikut Muhammadiyah.
Hal ini memicu perlawanan dari dalam Muhammadiyah sendiri. Kekhawatiran muncul lantaran masjid-masjid dan basis massa Muhammadiyah diambil alih kelompok transnasional. Barulah Muhammadiyah mulai sadar dan mulai melawan pengaruh kelompok Islam transnasional, sudah mulai ada tulisan hingga video ceramah di Youtube yang melawan pengaruh kelompok Islam transnasional di tubuh Muhammadiyah, sayangnya semua sudah terlambat. Kekhawatiran akan direbutnya basis massa Muhammadiyah oleh kelompok Islam transnasional diperkuat oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sebuah partai politik yang secara historis dianggap berafiliasi secara kultural dengan Muhammadiyah. Zulkifli Hasan dalam sebuah pernyataan yang penulis kutip dari Kompas.com, tertanggal 5 Februari 2018:
Hari Raya Indonesia atau Hari Raya Muhammadiyah?Menurunnya jumlah massa Muhammadiyah, disadari atau tidak, turut dipengaruhi oleh seringnya organisasi ini berbeda dengan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hal ini menimbulkan dilema khusus bagi warga Muhammadiyah yang bekerja sebagai PNS, guru, dosen, maupun pejabat birokrasi; kalangan yang sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru memang menjadi basis sosial utama Muhammadiyah. Setiap kali terjadi perbedaan tanggal, mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak nyaman: mengikuti ketentuan pemerintah sebagai institusi tempat mereka bekerja, atau mengikuti organisasi tempat mereka bernaung secara ideologis.
Sedikit sekali masyarakat memahami alasan teologis dan metodologis di balik perbedaan ini, sehingga perbedaan tersebut kerap dipersepsikan sekadar sebagai “keanehan” Muhammadiyah.
Dalam soal penetapan hari raya, perbedaan utama Muhammadiyah dengan kelompok Islam transnasional terutama kelompok Salafi, justru sangat tajam. Salafi meyakini bahwa rukyatul hilal dengan mata telanjang adalah metode paling sahih karena dicontohkan Rasulullah SAW dan para Sahabat. Penggunaan teleskop baru diterima pada abad ke-20 sebagai alat bantu, namun tetap dianggap sekunder dibanding penglihatan langsung. Paradoksnya, dalam hal ini pandangan Salafi beririsan dengan Syi’ah, yang juga menekankan rukyat mata telanjang; hanya saja Syi’ah baru menerima penggunaan teleskop sebagai alat bantu secara umum setelah fatwa Imam Khomeini pasca-Revolusi 1979.
Bagi kalangan Salafi, hisab adalah bid’ah karena tidak dilakukan pada masa Nabi. Selain itu, mereka menilai bahwa penetapan hari raya adalah hak Ulil Amri; sehingga umat wajib mengikuti pemerintah apa pun metode yang digunakan. Karena hampir semua negara Muslim kini memakai "hisab imkanur rukyat"—gabungan hisab dan rukyat yang merupakan jalan tengah antara hisab dan rukyat—Salafi menerima hal itu selama keputusan datang dari otoritas negara.
Di titik inilah terlihat paradoks yang lebih dalam: Muhammadiyah sebagai organisasi yang lebih dari satu abad menjadikan pemberantasan bid’ah sebagai misi sucinya (mission sacre) justru dianggap sebagai pelaku bid’ah terbesar oleh kelompok-kelompok transnasional. Bagi mereka, penggunaan hisab murni (hisab haqiqi wujudul hilal) adalah inovasi keagamaan yang sama sekali tidak memiliki preseden pada masa Nabi dan para Sahabat. Ironisnya, metode inilah yang membedakan Muhammadiyah secara fundamental dari seluruh arus purifikasi Islam lain di dunia Muslim.
Perbedaan ini menjadi garis pemisah paling mendasar antara Muhammadiyah dan mayoritas arus Islam lainnya. Hizbut Tahrir, misalnya, meski menolak negara dan menyerukan khilafah, tetap bersikap bahwa umat tidak boleh berbeda tanggal demi persatuan. Ikhwanul Muslimin yang memiliki partai politik terafiliasi seperti PKS cenderung mengikuti pemerintah demi stabilitas politik. Bahkan Ahmadiyah—golongan yang ditolak banyak kelompok—setuju dengan Salafi dalam hal ketaatan kepada ulil amri dan keharusan rukyatul hilal.
Akhirnya, perdebatan hisab versus rukyat justru menyatukan kelompok-kelompok yang biasanya saling bertentangan: NU, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathan, Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, Al-Khairaat, LDII, Salafi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Syi’ah, hingga Ahmadiyah, hal ini menjadikan Muhammadiyah “sendirian” dengan metode hisab murninya. Tak ada satu pun negara Muslim yang memakai hisab haqiqi wujudul hilal seperti Muhammadiyah; perdebatan serius soal ini pun hanya terjadi di Indonesia.
Pemerintah RI sendiri menggunakan metode hisab imkanur rukyat, yang kini disepakati juga oleh forum MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura). Dalam metode ini, hisab dan teropong berfungsi sebagai alat bantu, sementara penetapan final tetap melalui pengamatan hilal. Sebaliknya, Muhammadiyah memakai hisab haqiqi wujudul hilal, yaitu metode astronomi murni tanpa memerlukan konfirmasi rukyat.
Akibat perbedaan ini, banyak warga Muhammadiyah—terutama PNS dan kelompok yang masih memegang agenda pemurnian Islam—akhirnya berpindah ke kelompok Islam transnasional yang mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan hari raya. Keunggulan kelompok-kelompok ini dalam menyerukan ketaatan kepada Ulil Amri, terutama di kalangan Salafi, menjadi daya tarik tambahan bagi warga Muhammadiyah yang bekerja sebagai PNS. Tidak sedikit mantan warga Muhammadiyah yang kemudian beralih menjadi Salafi atau kelompok modernis transnasional lainnya.
Sementara itu mayoritas Muslim yang tidak terafiliasi dengan ormas apa pun, sering disebut non-denominational Muslim atau ghairi mazhab—secara alami mengikuti pemerintah dan tidak tertarik memperdebatkan soal ini. Begitu pula kelompok Islam abangan ataupun Islam KTP, kebanyakan generasi milenial, Gen-Z, hingga Gen-Alpha yang tidak akrab dengan isu hisab dan rukyat; bagi mereka, Muhammadiyah tampak sebagai organisasi yang “berbeda sendiri”, sehingga tidak lagi menjadi pilihan identitas keagamaan yang menarik.
Realitas LapanganTerakhir, Muhammadiyah juga memiliki masalah kaderisasi.
Meski memiliki jaringan sekolah dan universitas yang luas, tidak semua alumninya otomatis menjadi kader atau anggota inti Muhammadiyah. Beberapa tidak menjadi anggota, dan sebagian justru ada yang pindah ke ormas Muslim lain seperti NU. Tercatat banyak juga orang-orang dari keluarga berlatarbelakang NU, namun sekolah atau kuliah di lembaga pendidikannya Muhammadiyah.
Mahasiswa dari keluarga Muhammadiyah atau lulusan sekolah Muhammadiyah sering bergabung dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK), di mana para murobbi sering kali berasal dari Ikhwanul Muslimin. Karena akar teologis Muhammadiyah dan Ikhwanul Muslimin mirip, perpindahan ideologis ini menjadi lebih mudah.
Muhammadiyah juga tertinggal di ruang digital. Dalam dakwah media sosial, upayanya tidak secanggih organisasi lain. NU dan kelompok transnasional memiliki banyak pendakwah online populer, sementara Muhammadiyah hanya punya satu yang benar-benar dikenal: Ustaz Adi Hidayat.
Ada pula kritik bahwa pendakwah Muhammadiyah kurang mampu tampil secara menarik secara online, karena banyak yang lebih memilih seminar formalistik atau menulis makalah ilmiah yang sulit diakses khalayak umum.
KesimpulanMuhammadiyah tetap menjadi salah satu organisasi Islam paling berpengaruh di Indonesia, dengan warisan lebih dari satu abad di bidang pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat. Perannya dalam membentuk identitas Muslim modern Indonesia tak terbantahkan.
Namun kekuatan institusional jangka panjang ini tampaknya juga menumbuhkan rasa puas diri dan menyebabkan kejumudan dalam tubuh Muhammadiyah.
Meski infrastrukturnya besar, Muhammadiyah kehilangan relevansi—khususnya di generasi muda dan kelas menengah Muslim perkotaan yang selama ini menjadi basis massanya—yang kini tertarik pada wacana yang lebih reflektif, kontekstual, dan melek digital.
Penurunan ini bukan hanya akibat kompetisi eksternal, tetapi juga stagnansi internal. Keterikatan Muhammadiyah pada visi modernitas awal abad ke-20 membuatnya kurang adaptif terhadap arus posmodernimse dan post-Islamisme yang kini membentuk pemikiran Islam kontemporer.
Sebagaimana terlihat dari bangkitnya pemikir post-tradisionalis NU dan meningkatnya daya tarik kelompok Islam transnasional, medan wacana telah berubah. Rasionalisme dan pemurnian Islam dari praktik TBC, yang selama ini dijunjung Muhammadiyah kini dianggap kaku dan jauh dari realitas hidup umat Muslim Indonesia.
Lebih jauh, respons Muhammadiyah terhadap isu moral dan ekonomi—seperti fatwa haram rokok dan air mineral—menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap realitas sosial ekonomi akar rumput. Keterputusan dari budaya digital, regenerasi kader yang lambat, dan kurangnya tokoh intelektual publik juga mengikis posisi simboliknya.
Untuk bangkit kembali, Muhammadiyah harus memperkuat kehadiran digitalnya, memperbarui strategi komunikasi, dan mengevaluasi kembali fondasi epistemologisnya. Ini mungkin mencakup keterlibatan lebih dalam dengan pendekatan pluralis, kontekstual, dan interdisipliner tanpa menghilangkan semangat reformisnya.
Hanya dengan cara itu Muhammadiyah dapat tetap relevan sebagai kekuatan moral dan aktor strategis dalam lanskap keagamaan dan sosial-politik Indonesia yang terus berubah.