jpnn.com, JAKARTA - Demokrasi semestinya menjadi panggung adu ide, bukan arena adu ejekan fisik.
Namun belakangan, politik kita justru gemar bermain di wilayah paling remeh, yakni tubuh manusia mulai wajah, cara berjalan, hingga ekspresi.
BACA JUGA: Detektif Jubun Bicara soal Body Shaming dan Dampaknya
Semuanya bisa dijadikan senjata untuk menutupi kemiskinan argumen.
Dalam catatan pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli, fenomena body shaming politik disebutkan sebagai gejala serius menurunnya etika dan nalar elite.
BACA JUGA: Atikoh Ajak Santriwati Ponpes KHAS Stand Out Melawan Body Shaming & Bullying
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan ketika kritik kehilangan data dan gagasan, ejekan fisik menjadi jalan pintas yang tampak lucu, tetapi sesungguhnya berbahaya bagi kualitas demokrasi dan kecerdasan publik.Berikut ini catatan lengkapnya.
Bagi Pieter Zulkifli, demokrasi idealnya adalah arena adu gagasan, bukan lomba mencela raga.
BACA JUGA: Aurel Hermansyah Curhat Begini Setelah Jadi Korban Body Shaming
Namun yang belakangan kita saksikan justru sebaliknya, politik Indonesia kerap tergelincir ke wilayah paling dangkal, yaitu tubuh manusia.
“Dari perubahan kulit wajah Presiden Joko Widodo yang dipelintir menjadi 'karma', ejekan atas cara berjalan dan postur Prabowo Subianto, hingga olok-olok terhadap raut wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Body shaming politik menjelma senjata murah dalam pertarungan kekuasaan,” kata Pieter Zulkifi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Pieter Zulkifli menyebut fenomena ini bukan sekadar soal etika komunikasi, melainkan cermin telanjang kemiskinan intelektual elite dan partai politik.
Ketika argumen habis, data mentok, dan prestasi sulit dibantah, tubuh lawan dijadikan sasaran.
“Kulit, gestur, usia, bahkan ekspresi wajah diperlakukan seolah indikator kepemimpinan. Di titik ini, politik kehilangan martabatnya sebagai ruang rasional,” katanya.
Dia mencontohkan kasus yang paling gamblang, yakni Jokowi pascakunjungan luar negeri.
Alih-alih mendiskusikan substansi kebijakan atau warisan infrastrukturnya, kata dia, sebagian elite justru sibuk merangkai narasi metafisik tentang 'karma'.
"Ini bukan kritik; ini pengalihan isu yang dibungkus takhayul. Mengaitkan kondisi biologis dengan legitimasi moral adalah praktik purba yang seharusnya sudah lama ditinggalkan oleh demokrasi modern," kata dia.
Tak hanya itu, Pieter Zulkifli melanjutkan pola serupa sebelumnya juga menimpa Prabowo, yang kerap direduksi dari cara berjalan dan kondisi fisik, seolah kepemimpinan diukur dari kelincahan tubuh, bukan ketajaman visi geopolitik dan kapasitas pengambilan keputusan.
"Gibran pun tak luput dari sasaran. Raut wajah yang dianggap 'ngantukan' dijadikan alat delegitimasi, seakan ekspresi sesaat lebih penting daripada tanggung jawab konstitusional seorang wakil presiden. Tubuh menjadi medan tempur, sementara kebijakan dibiarkan luput dari perdebatan serius,” ucapnya.
Menurutnya, dalam tradisi filsafat dan logika, praktik semacam ini dikenal sebagai argumentum ad hominem, yakni cara berdebat dengan menyerang pribadi atau kondisi personal lawan alih-alih menguji gagasan dan kebijakannya.
“Immanuel Kant mengingatkan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat," katanya.
Pieter Zulkifli menekankan ketika tubuh seseorang dijadikan amunisi politik, yang terjadi bukan kritik, melainkan perendahan martabat manusia.
Dia lantas menyinggung Hannah Arendt yang pernah memperingatkan, hilangnya kejujuran faktual dan penghormatan terhadap martabat manusia di ruang publik akan menyeret demokrasi ke dalam banalitas: riuh, emosional, tetapi miskin makna.
Pieter Zulkifli menyatakan body shaming politik bekerja efektif karena ia visual, emosional, dan mudah dicerna.
Body shaming bahkan tidak menuntut literasi kebijakan, tidak memerlukan data, apalagi keberanian intelektual, namun justru di situlah racunnya.
“Publik digiring untuk menertawakan kulit, bukan menguliti kebijakan; mengejek gestur, bukan menimbang langkah strategis. Demokrasi pun terjerumus menjadi apa yang bisa disebut sebagai politik kosmetik," katanya.
Dia berpandangan fenomena ini tak bisa dilepaskan dari problem yang lebih struktural, yakni penegakan hukum yang setengah hati.
Praktik hukum yang tebang pilih, tidak konsisten, dan kurang tegas—yang kerap menghukum pelanggar kecil tetapi ragu menyentuh pihak kuat telah menciptakan preseden buruk dalam kehidupan bernegara.
Dia mengingatkan ketika negara tampak permisif terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk intimidasi simbolik dan kekerasan verbal di ruang publik, maka budaya merendahkan martabat manusia pun dibiarkan tumbuh.
“Sikap ragu-ragu negara bukan hanya memperpanjang rantai pelanggaran, tetapi juga menggerus kepercayaan publik dan melanggengkan ketidakadilan," ucap dia.
Pieter Zulkifi mengatakan masalah profesionalisme penegak hukum serta adanya pembiaran negara terhadap berbagai pelanggaran mencerminkan ketidaksungguhan membangun politik, ekonomi, dan hukum yang bermartabat.
Padahal, peradaban bangsa adalah puncak perkembangan kebudayaan dan perilaku kolektif yang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, semuanya berlandaskan nilai luhur, adab, dan akhlak.
Menurut dia, peradaban yang kokoh hanya mungkin dibangun oleh sumber daya manusia yang unggul, bermoral, dan memiliki nilai kebangsaan yang kuat.
Dalam pengertian ini, peradaban juga terkait dengan kemampuan manusia mengendalikan dorongan-dorongan dasar demi kualitas hidup yang lebih tinggi.
“Di sinilah peran negara menjadi krusial dan tak tergantikan,” katanya.
Di sisi lain, Pieter Zulkifi menegaskan partai politik (parpol) seharusnya menjadi benteng pertama melawan kemerosotan ini.
Sayangnya, kader kerap dibiarkan atau bahkan didorong menjadi pasukan sorak yang lihai mencemooh, tetapi gagap berargumen.
“Padahal partai adalah sekolah politik, bukan pabrik provokator. Tanpa kaderisasi yang menekankan etika debat dan kecakapan berpikir, partai hanya akan memperpanjang polusi verbal di ruang publik,” kata dia.
Pieter Zulkifi kembali mengungkit pernyataan Eleanor Roosevelt yang pernah berkata, 'Great minds discuss ideas; small minds discuss people'.
Dia menyebut kutipan ini terasa relevan sekaligus menohok.
“Ketika elite sibuk membahas wajah dan tubuh lawan, sesungguhnya mereka sedang membuka aib sendiri: ketidakmampuan berpikir pada level ide," katanya.
“Pada akhirnya, tanggung jawab juga ada di tangan publik. Demokrasi tidak akan naik kelas jika pemilih terus membeli dagangan narasi murahan. Kritiklah kebijakan Jokowi, bedah visi Prabowo, uji kapasitas Gibran tetapi biarkan tubuh mereka tetap menjadi wilayah kemanusiaan, bukan medan tempur politik," timpalnya.
Di akhir pernyataannya, Pieter Zulkifi menyatakan body shaming politik bukan tanda keberanian, melainkan kepanikan. Dia juga menganggap body shaming bukan kecerdikan, melainkan kemalasan berpikir.
"Dan, selama elite terus menjajakan politik kulit, rakyat dituntut lebih cerdas: menolak yang remeh, dan menuntut yang substansial. Demokrasi yang beradab hanya tumbuh di atas intelektualitas, bukan di atas ejekan," tegas Pieter Zulkifli.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari


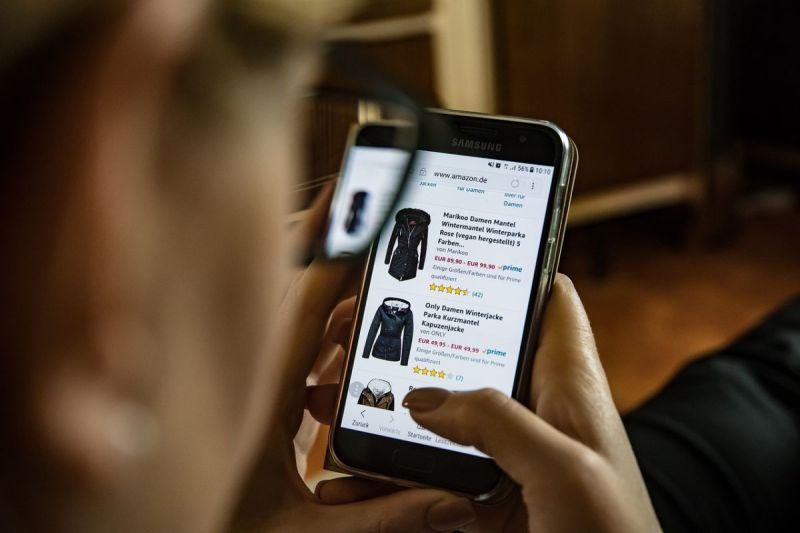


:strip_icc()/kly-media-production/medias/5417976/original/049724300_1763555921-InShot_20251119_193350409.jpg)
