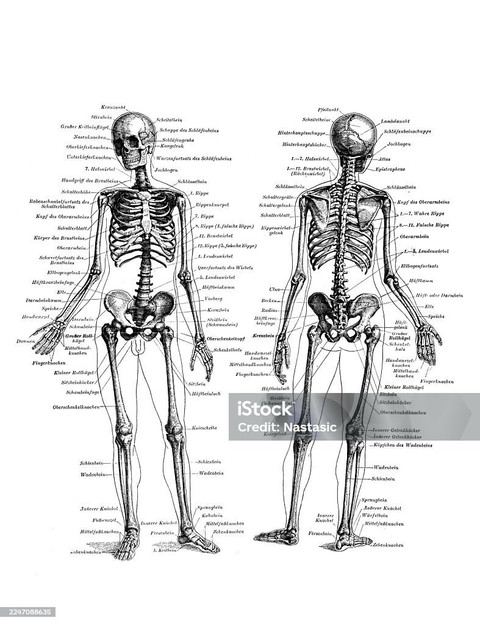Mengikuti kabar bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian buatan Amerika Serikat, membuat saya diliputi perasaan yang bercampur antara heran, cemas, dan resah. Bukan semata karena nama besar Donald Trump di balik inisiatif tersebut, melainkan karena konfigurasi moral dan politik yang melekat di dalamnya. Dewan Perdamaian ini diklaim bertujuan mempercepat terciptanya perdamaian sekaligus mendorong rekonstruksi Gaza setelah kehancuran masif akibat agresi militer Israel.
Namun, sejak awal, komposisi dan pendekatan forum tersebut memunculkan pertanyaan mendasar. Israel diundang sebagai bagian dari proses “perdamaian”, sementara Palestina sebagai pihak yang wilayah dan rakyatnya menjadi korban utama justru tidak diundang. Saya merasa ada keganjilan etis dan historis yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari posisi dan identitas politik luar negeri Indonesia.
Hubungan Indonesia dan Palestina bukanlah hubungan yang lahir dari kepentingan pragmatis jangka pendek. Hubungan kedua negara tersebut memiliki akar sejarah yang panjang dan sarat makna politik. Palestina, melalui tokoh-tokohnya, telah memberikan dukungan moral dan politik terhadap kemerdekaan Indonesia sejak 1944, jauh sebelum banyak negara lain memberikan pengakuan serupa.
Sebaliknya, Indonesia, secara konsisten menjadikan perjuangan Palestina sebagai bagian integral dari komitmen anti-kolonialisme, baik dalam forum bilateral maupun multilateral. Kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah membentuk solidaritas yang tidak semata emosional, tetapi berlandaskan prinsip hukum dan keadilan internasional.
Dalam perspektif hukum internasional, konflik Palestina–Israel bukan hanya persoalan sengketa teritorial, melainkan juga menyangkut pelanggaran serius terhadap hukum humaniter. Cassese (2003) menegaskan bahwa kejahatan perang dan genosida merupakan norma hukum internasional yang bersifat mengikat secara absolut dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan politik apa pun.
Argumen ini diperkuat oleh Schabas (2016) yang menyatakan bahwa proses perdamaian yang mengabaikan tanggung jawab hukum pelaku kekerasan justru berpotensi melemahkan tatanan hukum internasional itu sendiri. Tuduhan genosida terhadap Israel bukanlah opini emosional semata. Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), dalam putusan sementara tahun 2024, menyatakan adanya dasar yang masuk akal (plausible case) bahwa tindakan Israel berpotensi melanggar Konvensi Genosida 1948.
Ketika Dewan Perdamaian dibentuk tanpa melibatkan Palestina, sementara Israel diberi ruang sebagai aktor setara di dalam keanggotaan Dewan tersebut, muncul persoalan legitimasi yang serius. Perdamaian, dalam kerangka seperti ini, cenderung direduksi menjadi proyek stabilisasi pascakonflik yang berorientasi pada kepentingan geopolitik aktor kuat.
Akhavan (2019) mengingatkan bahwa pendekatan semacam ini sering melahirkan apa yang disebut sebagai perdamaian semu, yakni kondisi tanpa kekerasan terbuka tetapi tetap menyisakan ketidakadilan struktural dan trauma kolektif. Dalam situasi demikian, rekonstruksi fisik dapat berjalan, tetapi rekonsiliasi yang adil dan berkelanjutan justru absen.
Di sinilah posisi Indonesia menjadi krusial sekaligus rawan. Dengan bergabung ke dalam Dewan Perdamaian yang tidak melibatkan Palestina, Indonesia berisiko terjebak dalam kontradiksi antara identitas normatif dan praktik diplomatiknya. Secara simbolik, kehadiran Indonesia dapat ditafsirkan sebagai legitimasi terhadap forum yang mengesampingkan korban utama konflik.
Padahal, menurut Galtung (1996), perdamaian sejati bukan hanya ketiadaan kekerasan (negative peace), melainkan kehadiran keadilan struktural (positive peace). Tanpa suara Palestina, sulit membayangkan bahwa Dewan Perdamaian tersebut mampu melampaui sekadar pengaturan ulang kekuasaan pascakonflik.
Saya tidak menutup mata bahwa diplomasi sering kali menuntut keterlibatan dalam forum yang tidak ideal. Ada argumen realistis yang menyatakan bahwa kehadiran Indonesia justru dapat digunakan untuk menyuarakan kepentingan Palestina dari dalam.
Namun, argumen ini mensyaratkan prasyarat penting, yaitu keberanian untuk bersikap kritis dan konsisten, bahkan jika sikap itu harus berseberangan dengan “arsitek utama” forum tersebut. Dalam sebuah risetnya, Nye (2004) mengemukakan bahwa soft power sebuah negara justru terletak pada kredibilitas moralnya, bukan semata pada akses ke meja perundingan.
Jika Indonesia memilih untuk tetap berada dalam Dewan Perdamaian tersebut, maka kehadiran itu harus bersifat kondisional dan berprinsip. Indonesia perlu secara terbuka mendorong pelibatan Palestina sebagai aktor utama, menegaskan pentingnya akuntabilitas hukum internasional, serta menolak normalisasi hubungan dengan pihak yang belum mempertanggungjawabkan dugaan kejahatan perang. Jika tidak, keputusan untuk bergabung justru berpotensi menggerus posisi historis Indonesia sebagai pembela konsisten perjuangan anti-kolonialisme.
Saya percaya bahwa perdamaian bukan sekadar soal duduk bersama, melainkan tentang mekanisme yang menentukan suara mana yang dianggap sah dan kepentingan mana yang diabaikan. Membahas perdamaian bersama pelaku kejahatan perang, tanpa kehadiran korban, bukan hanya persoalan diplomasi yang keliru, tetapi juga cermin dari kegagalan etis. Indonesia, dengan seluruh modal sejarah dan moralnya, seharusnya berhati-hati agar tidak salah memilih meja dalam memperjuangkan perdamaian yang adil dan bermartabat.