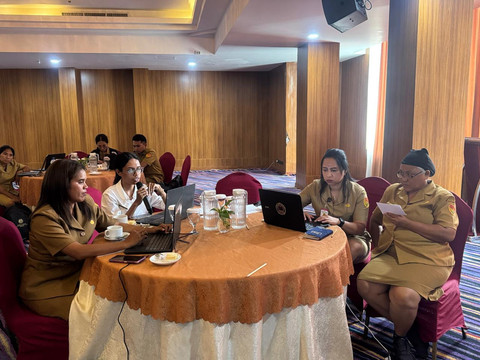Angka-angka resmi terlihat menjanjikan. Indeks Ketimpangan Gender Indonesia terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun bagi banyak perempuan, kemajuan itu lebih sering hadir di laporan tahunan ketimbang dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, di tempat kerja, dan di ruang pengambilan keputusan, ketimpangan masih menjadi pengalaman nyata.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Ketimpangan Gender, dari 0,459 pada 2022 menjadi 0,421 pada 2024. Dalam narasi pembangunan, capaian ini kerap dibaca sebagai sinyal positif bahwa kesetaraan gender di Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik. (BPS, Indeks Ketimpangan Gender 2022–2024)
Namun, statistik tersebut menyimpan ironi. Di balik angka yang membaik, banyak perempuan masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi, beban kerja domestik yang tidak berimbang, serta minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Perbaikan indikator belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perubahan struktur sosial.
Paradoks paling nyata terlihat di sektor ketenagakerjaan. Pada 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada di kisaran 56 persen. Angka ini memang menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih terpaut jauh dari tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai sekitar 84 persen. (BPS, Sakernas 2024)
Kesenjangan ini bukan hanya soal kesempatan kerja, melainkan juga kualitas pekerjaan. Banyak perempuan terserap di sektor informal dengan upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan minim perlindungan kerja. Bahkan, ketika memiliki tingkat pendidikan yang setara, perempuan kerap menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki. (BPS, 2024)
Di ranah politik, persoalan serupa muncul. Keterwakilan perempuan di DPR RI setelah Pemilu 2024 masih berada di kisaran 22 persen, jauh dari target ideal 30 persen (Bappenas, Indonesia VNR 2025). Lebih dari itu, keberadaan perempuan di parlemen sering kali bersifat simbolik. Tidak sedikit yang terpinggirkan dari posisi strategis dan proses pengambilan keputusan penting.
Situasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia masih banyak berhenti pada level program dan angka. Pelatihan keterampilan, kampanye kesadaran, atau kuota formal memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi perubahan struktur yang lebih mendasar.
Akar persoalannya terletak pada ketimpangan struktural yang belum disentuh secara serius. Pembagian kerja berbasis gender masih membebani perempuan dengan pekerjaan domestik dan kerja perawatan tanpa pengakuan ekonomi. Kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial belum sepenuhnya responsif gender, terutama bagi pekerja perempuan di sektor informal dan pedesaan.
Selain itu, banyak program pemberdayaan masih berorientasi pada output jangka pendek—yaitu jumlah peserta pelatihan, sertifikat, atau laporan kegiatan—tanpa memastikan dampak jangka panjang berupa akses modal, pasar, dan posisi tawar perempuan. Akibatnya, statistik program meningkat, tetapi kehidupan perempuan tidak banyak berubah.
Jika pemberdayaan perempuan ingin bergerak melampaui statistik, pendekatannya harus bergeser dari sekadar administratif menjadi transformatif. Negara perlu memastikan kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, dan politik benar-benar membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dan bermakna.
Langkah konkret bisa dimulai dari penguatan perlindungan sosial bagi pekerja perempuan, kebijakan upah yang adil, dukungan terhadap kerja perawatan melalui layanan publik, dan reformasi internal partai politik agar perempuan bukan hanya hadir sebagai pemenuh kuota, melainkan juga sebagai aktor pengambil keputusan.
Pemberdayaan perempuan sejatinya bukan tentang seberapa indah angka di laporan, melainkan tentang seberapa nyata perubahan yang dirasakan dalam hidup sehari-hari. Selama kemajuan hanya tecermin di statistik, selama itu pula kesetaraan gender masih menjadi janji yang belum sepenuhnya ditepati.