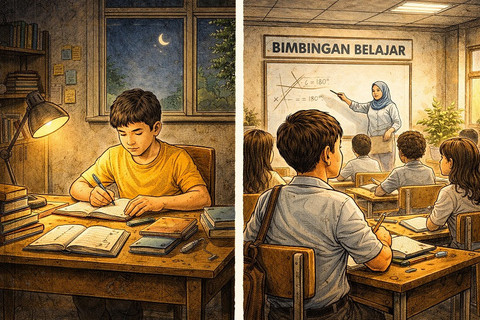Setiap tahun, jutaan siswa SMA di Indonesia terjebak dalam kompetisi kolosal. Medan tempurnya bukan di lapangan luas, melainkan di ruang-ruang sempit pusat bimbingan belajar (bimbel). Di sana, mereka melatih kecepatan menjawab soal pilihan ganda hingga larut malam demi satu tujuan: menembus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit.
Fenomena ini, yang dalam studi sosio-pendidikan disebut sebagai Shadow Education (Pendidikan Bayangan), telah menjadi lumrah. Di baliknya, terdapat retakan besar dalam filosofi pendidikan kita: siswa dimanjakan dengan fasilitas instan untuk lulus tes, namun kehilangan ketangguhan mental dan rasa ingin tahu yang dibutuhkan untuk bertahan di bangku kuliah.
Keberadaan bimbel yang masif di Indonesia seolah menjadi sinyal ketidakpercayaan publik terhadap sekolah formal. Orang tua merasa kurikulum sekolah tidak cukup untuk membekali anak menghadapi ujian seleksi yang standarnya seringkali jauh di atas materi harian di kelas. Akibatnya, pendidikan tidak lagi tentang pendalaman ilmu, melainkan tentang investasi strategi.
Lebih jauh, ada pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan: Jika seorang siswa memang memiliki passion atau minat mendalam pada suatu jurusan—katakanlah Teknik Sipil atau Hukum—, bukankah seharusnya rasa ingin tahu intelektualnya mendorong dia untuk belajar mandiri? Bukankah kandidat yang paling layak adalah mereka yang mampu menaklukkan materi melalui eksplorasi sendiri, bukan melalui trik cepat yang dibeli di tempat les?
Realitasnya, banyak bimbel menjual efisiensi, bukan kedalaman. Mereka mengajarkan cara membedah pola soal, bukan cara mencintai ilmu. Dampaknya, kita berisiko melahirkan "generasi karbitan": siswa yang sangat mahir masuk ke universitas, namun gegar budaya saat harus menyelesaikannya. Perlu kita sadari, kemampuan menjawab soal pilihan ganda dalam waktu 60 detik tentu sangat berbeda dengan kemampuan riset, berpikir kritis, dan literasi mendalam yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi atau menghadapi dunia kerja.
Di sisi lain, obsesi terhadap kampus-kampus elit menciptakan beban psikologis yang toksik. Di negara seperti Finlandia, sekolah terbaik adalah sekolah terdekat. Tidak ada kasta antar institusi karena kualitasnya merata. Namun di Indonesia, seorang siswa yang diterima di jurusan berakreditasi "Unggul" pada kampus lapis kedua seringkali merasa sebagai 'produk gagal' hanya karena nama kampusnya tidak mentereng.
Pengejaran gengsi ini kemudian membutakan siswa dari hal yang lebih esensial: akreditasi program studi, kurikulum yang relevan, serta kemitraan industri yang ditawarkan kampus tersebut. Kebutaan tersebut bukan tanpa alasan. HRD berbagai perusahaan di Indonesia kerap malas menyaring skill riil dan lebih memilih menggunakan nama besar almamater sebagai gatekeeping mechanism yang dinilai lebih menghemat waktu alih-alih portofolio keterampilan. Tanpa pengubahan di bagian ini, sulit bagi kita mengharapkan kegilaan akan bimbel dan kampus elit seperti ini akan usai.
Diperlukan perspektif baru dalam memandang kelulusan masuk PTN sebagai gerbang awal dan bukan garis finis. Orang tua dan pendidik harus mulai memikirkan dan melakukan berbagai cara demi membangun citra diri anak berdasarkan kompetensi dan adaptabilitas, bukan sekadar merek almamater. Jika kita terus-menerus tergantung pada bimbel, kita mungkin akan mengisi universitas-universitas terbaik kita dengan para penghafal pola soal yang hebat, namun akan merasa tersesat ketika dihadapkan pada masalah nyata di dunia luar yang tidak memiliki pilihan jawaban A, B, C, atau D, yang kemudian mungkin turut menjadi penyebab mengapa integritas dan kualitas penelitian pendidikan tinggi kita acapkali masuk dalam kategori rapor merah. ●