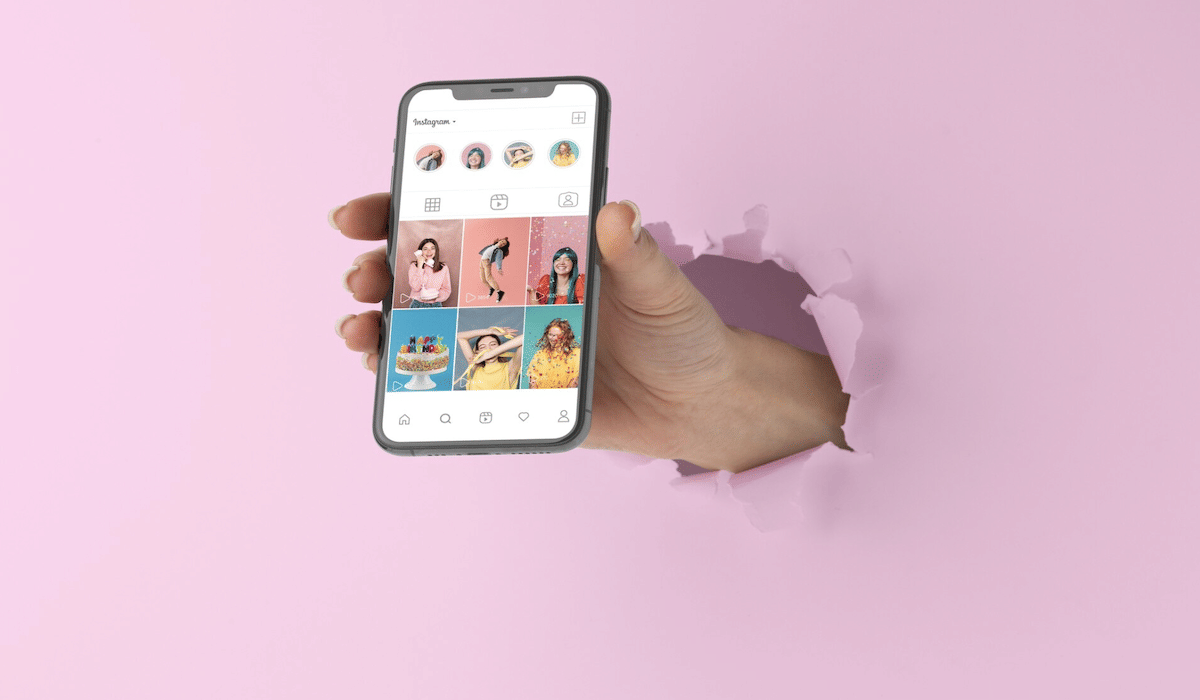Bisnis.com, JAKARTA — China semakin mendominasi rantai pasok perdagangan internasional Indonesia, yang tampak dari meningkatnya pangsa pasar impor dari Negeri Panda.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor nonmigas RI dari China sepanjang 2025 menembus US$86,99 miliar atau melonjak 21,4% secara tahunan (year-on-year/YoY). Lonjakan ini membuat pangsa pasar produk China di Tanah Air membengkak drastis dari 36,29% pada 2024 menjadi 41,60% pada 2025.
Kondisi ini kontras dengan peran mitra dagang tradisional lain seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Asia Tenggara (Asean) yang justru menyusut.
Saat impor China meroket, impor RI dari Jepang justru turun dari US$14,86 miliar pada 2024 menjadi US$14,42 miliar pada 2025 (pangsa pasar turun dari 7,53 ke 6,90%).
Pada saat yang sama, penurunan juga terjadi pada impor dari Korea Selatan dari US$8,67 menjadi US$7,61 miliar (pangsa pasar turun dari 3,36% ke 4,10%), Asean dari US$34,60 miliar ke angka US$32,46 miliar (pangsa pasar turun dari 17,50 ke 15,53%), dan Uni Eropa dari US$14,01 miliar menjadi US$12,63 miliar (pangsa pasar turun dari 5,93% ke 6,40%).
Ketergantungan itu memicu lampu kuning dari kalangan ekonom hingga think-tank pemerintah. Ketergantungan rantai pasok yang terlalu dalam pada satu negara dinilai tidak hanya meningkatkan kerentanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal, tetapi juga berisiko menggerus kedaulatan kebijakan luar negeri Indonesia secara de facto.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai bahwa fenomena ini terjadi secara natural akibat struktur industri nasional yang mengalami hollow middle atau kekosongan di sektor industri antara.
"Industri kita hollow middle, tidak ada di tengahnya. Karena kita tidak punya manufaktur yang dalam dan saling terkait, kita rely on komoditas. Jadi mau tidak mau kita akan mengimpor dari negara lain," ujar Deni kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, pilihan logis bagi industri domestik saat ini jatuh pada China. Pasalnya, barang modal maupun bahan baku dari Jepang dan Korea Selatan relatif lebih mahal. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) kini lebih fokus pada jasa dan teknologi, sedangkan perkembangan industri Uni Eropa dinilai lambat.
Kendati demikian, Deni memperingatkan risiko besar di balik 'kenyamanan' harga murah tersebut. Ketergantungan pada satu poros kekuatan membuat ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap guncangan di Negeri Tirai Bambu.
"Kalau ekonomi China melambat karena masalah properti dan excess supply atau over production, ya kita jadinya akan sangat tergantung itu. Kalau China turun, mau tidak mau kita ikut turun," tegasnya.
Selain risiko ekonomi, Deni juga menyoroti potensi tergerusnya fleksibilitas Indonesia dalam mengambil sikap di panggung global.





/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F12%2F26%2F3c59fea1dc50fc0c468c8dd4a464b229-WhatsApp_Image_2025_12_26_at_16.53.46.jpeg)