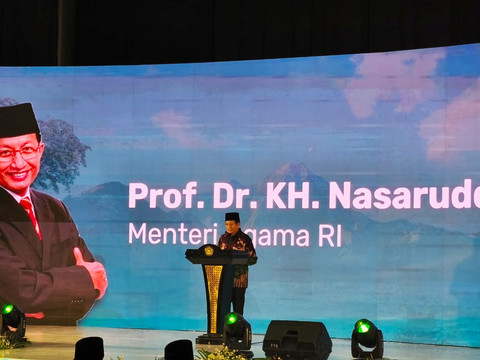SETELAH Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginisiasi Board of Peace (BoP) per Januari 2026, sebagai tindak lanjut atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, yang menyambut kerangka kerja 20 poin mediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza, momentumnya terjadi signifikan per 22 Januari 2026.
Saat itu, ketika Trump, dan terutama Presiden kita, Prabowo Subianto, secara resmi menandatangani piagam Dewan tersebut dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos.
Maka, dalam hemat penulis dari sisi komunikasi publik, sejak saat itu kita harus membaca bahwa tatanan internasional saat ini tidak semata digerakkan pertimbangan etika semata.
Hubungan antarnegara berlangsung dalam medan yang ditentukan oleh kalkulasi kekuatan, irisan kepentingan, serta negosiasi yang sarat kompromi.
Negara yang bersandar hanya pada kemurnian idealisme kerap kehilangan tempat dalam percakapan global dan terlempar dari proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks seperti itu, Indonesia tidak berada pada posisi memilih sikap serba tunggal. Justru sebaliknya, Indonesia dituntut mampu berpijak pada dua landasan sekaligus menjaga komitmen moral, sembari cermat membaca dan mengelola kepentingan strategisnya.
Dukungan terhadap Palestina merupakan sikap historis yang berakar kuat secara konstitusional. Namun, keberlangsungan pengaruh Indonesia di panggung dunia menuntut kecakapan diplomasi realistis dan terukur.
Baca juga: Board of Peace: Antara Mimbar Ulama dan Meja Diplomasi (Bagian I)
Keputusan Indonesia bergabung BoP dalam konteks dua kaki macam itu, karenanya wajar memantik perdebatan publik.
Sebagian kalangan menilai langkah tersebut sebagai bentuk pragmatisme berlebihan, bahkan dicurigai sinyal melunaknya posisi Indonesia terhadap Israel.
Namun, membaca langkah diplomatik semata dari permukaan berisiko menyederhanakan realitas hubungan internasional.
Dalam praktik diplomasi, ketidakhadiran sering kali justru membawa konsekuensi lebih serius ketimbang kehadiran.
Absen berarti membiarkan arah pembicaraan, kerangka perdamaian, dan bahasa kebijakan sepenuhnya ditentukan aktor lain.
Sebaliknya, dengan berada di dalam forum, negara memperoleh peluang untuk memengaruhi proses, meski ruangnya terbatas dan penuh risiko politik.
Jadi, di mata penulis, kehadiran Indonesia tidak dapat dibaca sebagai penghapusan sikap moral ke Palestina, melainkan upaya memastikan bahwa prinsip keadilan dan pengakuan hak politik Palestina tetap memiliki saluran dalam proses yang nyata.
Tanpa keterlibatan aktor seperti Indonesia, forum perdamaian berisiko menyempit menjadi sekadar arena teknokratis yang mengutamakan stabilitas jangka pendek tanpa sentuh akar persoalan.


:strip_icc()/kly-media-production/medias/5426450/original/037517400_1764306006-Screenshot_2025-11-28_113148.png)