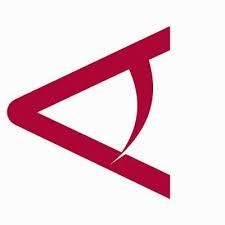Jakarta (ANTARA) - Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) pada prinsipnya dirancang untuk menegakkan keadilan fiskal: mereka yang berpenghasilan lebih tinggi membayar tarif pajak lebih besar.
Namun, struktur tarif yang berlapis (bracket) ini ternyata memiliki efek samping yang subtansial. Layaknya seorang pendaki gunung yang memilih bermalam di pos tertentu karena langkah berikutnya terasa berat, wajib pajak pun kerap memutuskan “berhenti” di titik penghasilan tertentu yang secara tidak langsung dapat mengurangi beban pajaknya.
Inilah yang dikenal dalam literatur perpajakan sebagai bunching effect, yaitu penumpukan pelaporan penghasilan tepat di bawah ambang batas tarif atas suatu lapisan pajak sebagai respons terhadap lonjakan tarif.
Fenomena ini dijelaskan oleh Saez (2001) sebagai kecenderungan wajib pajak untuk terkonsentrasi di ujung atas dari lapisan tarif yang lebih rendah sebagai sebuah strategi rasional untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dalam menghadapi sistem tarif yang berjenjang.
Ketika setiap tambahan rupiah penghasilan membuat seseorang terseret ke tarif yang lebih tinggi, respons yang paling hemat secara ekonomi adalah menunda atau menyesuaikan pelaporan pendapatan agar tetap berada di lapisan tarif yang lebih rendah.
Dalam desain PPh OP, ambang batas ini bertindak seperti “pos” yang ingin dihindari oleh banyak wajib pajak. Setiap kali seseorang mendekati posisi batas atas suatu tarif, terdapat motivasi ekonomi untuk berhenti bukan karena ia tidak mampu menghasilkan lebih banyak dengan produktif, tetapi karena tarif pajak yang tajam membuat tambahan pendapatan menjadi kurang menarik secara bersih setelah dipotong pajak.
Desain tarif yang demikian, meskipun dibangun atas dasar keadilan progresif, mengandung distorsi perilaku. Ketika keputusan ekonomi wajib pajak dipengaruhi oleh struktur tarif, itu berarti kebijakan pajak tidak hanya memungut penerimaan, tetapi justru membentuk pola perilaku pelaporan pendapatan. Analisis ini penting karena ia membuka perspektif bahwa tarif pajak bukan sekadar soal angka, tetapi juga sinyal perilaku.
Baca juga: Dunia usaha dinilai perlu perkuat sistem kepatuhan usai implementasi Coretax
Ketimpangan dalam Pungutan
Salah satu temuan menarik dari studi internasional adalah bahwa bunching effect sangat bergantung pada karakteristik wajib pajak, terutama kemampuan mereka untuk mengatur waktu dan jumlah penghasilan yang dilaporkan. Studi Adam et al. (2020) di Britania Raya menunjukkan bahwa penumpukan pelaporan penghasilan lebih kuat terjadi pada kelompok wajib pajak yang memiliki keleluasaan tinggi untuk mengatur pendapatan mereka, seperti wiraswasta, pengusaha, dan pemilik perusahaan.
Logika di balik ini sederhana: seorang pengusaha atau pekerja lepas bisa menunda penerbitan faktur, menunda pencatatan pendapatan, atau mempercepat pembelian sebagai biaya dalam periode yang menguntungkan secara pajak. Pada kelompok ini, keputusan ekonomi bisa diarahkan untuk “menghindari” tarif pajak yang lebih tinggi. Respons seperti ini bukan sekadar trik akuntansi; ia merupakan respon rasional terhadap struktur tarif yang ada.
Hal ini kontras dengan kondisi yang dihadapi pegawai karyawan. Gaji karyawan bersifat tetap, dipotong langsung oleh pemberi kerja melalui mekanisme withholding tax, dan hampir tidak dapat dimanipulasi oleh pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, kelompok karyawan menunjukkan distribusi pelaporan penghasilan yang lebih merata/tersebar dan jarang menunjukkan pola bunching.
Data Indonesia menunjukkan realitas yang menarik. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, realisasi penerimaan dari PPh Pasal 21 (karyawan) mencapai Rp240 triliun, atau sekitar 12,8% dari total penerimaan pajak. Sementara itu, realisasi penerimaan dari PPh Pasal 25/29 orang pribadi (non-karyawan) hanya Rp14,74 triliun, atau sekitar 0,8% saja dari total penerimaan. Dengan kata lain, penerimaan dari karyawan hampir 16 kali lebih besar dibandingkan dari non-karyawan yang umumnya mencakup wiraswasta dan pekerja bebas.
Ironinya, kelompok non-karyawan secara ekonomis memiliki basis penghasilan yang berpotensi jauh lebih besar daripada pekerja bergaji tetap. Namun kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak tetap jauh lebih kecil. Ketimpangan ini memicu pertanyaan serius tentang efektivitas struktur PPh OP yang saat ini dipakai dan potensi adanya distorsi perilaku termasuk bunching effect yang mengurangi penerimaan negara dari segmentasi yang secara modal dan potensi ekonomi besar ini.
Baca juga: IKPI dorong kepatuhan wajib pajak nasional lewat kegiatan strategis
Paradoks Keadilan Fiskal
Berbeda dengan pelaku usaha, karyawan pada umumnya tidak memiliki fleksibilitas ajustasi penghasilan yang sama. Gaji mereka sudah ditetapkan dan pajaknya dipotong secara otomatis melalui mekanisme pemotongan/penyetoran oleh pemberi kerja setiap bulan. Sistem ini menutup ruang untuk manipulasi waktu pelaporan atau penyesuaian jumlah pendapatan yang dilaporkan. Efeknya, karyawan cenderung terhindar dari fenomena bunching effect baik karena struktur pemotongan yang terotomasi maupun karena kurangnya kendali atas waktu penerimaan penghasilan.
Berdasarkan hal tersebut, pola pelaporan penghasilan karyawan cenderung mengikuti struktur alami distribusi pendapatan tanpa konsentrasi tajam di sekitar ambang batas tarif. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kelompok ini memberi kontribusi penerimaan yang relatif besar (Rp240 triliun dari PPh Pasal 21), namun bukan karena tarif progresifnya lebih adil, melainkan karena mekanisme withholding yang membatasi ruang perilaku responsif terhadap ambang tarif.
Dalam konteks keadilan fiskal, hal ini menciptakan paradoks. Kelompok yang paling patuh secara struktural karena tidak punya opsi penyesuaian yang justru menanggung bagian beban pajak yang lebih pasti. Sementara kelompok dengan basis ekonomi lebih besar memiliki ruang untuk mengatur pelaporan penghasilan mereka agar tidak terangkat ke tarif yang lebih tinggi, sehingga kontribusi mereka terhadap penerimaan cenderung lebih kecil.
Baca juga: Paradigma baru kepatuhan pajak
Perbaikan Desain Kebijakan
Fenomena bunching effect ini memberikan pelajaran penting bagi perancang kebijakan fiskal. Bahwa tarif progresif meskipun dimaksudkan untuk keadilan, dapat menciptakan distorsi perilaku dalam sistem pemajakan yang justru menurunkan efisiensi dan basis pajak. Bunching effect menjadi sebuah indikator perilaku ekonomi yang rasional dalam menghadapi struktur tarif pajak yang tajam.
Untuk itu, beberapa pendekatan kebijakan dapat diusulkan untuk menjadi perbaikan desain kebijakan ke depan.
Pertama, penyederhanaan sistem dan administrasi perpajakan, karena struktur yang rumit tidak hanya memicu bunching, tetapi juga memperkuat peluang ketidaktahuan atau penyesuaian perilaku yang tidak diinginkan.
Kedua, pengurangan jumlah lapisan tarif, karena semakin sedikit lapisan berarti semakin kecil lonjakan tarif antar level yang bisa memicu perilaku konsentrasi pelaporan.
Ketiga, melakukan penataan ulang threshold (ambang batas) agar desainnya lebih selaras dengan kenyataan distribusi pendapatan masyarakat untuk mengurangi keuntungan ekonomis dari penyesuaian pelaporan yang rasional.
Selain itu, ada pula opsi yang kerap dibahas dalam studi internasional, yaitu struktur flat tax rate dengan dasar penghasilan yang luas dan kombinasi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Negara seperti Estonia menerapkan sistem pajak tunggal 22% dengan PTKP, yang dinilai mampu mempertahankan kesederhanaan sekaligus keadilan. Namun hal ini bukan satu-satunya formula yang ideal, karena desain terbaik sering kali adalah yang paling tepat membaca konteks ekonomi, administratif, dan perilaku pelaku pajak di setiap negara.
Pada akhirnya bunching effect bukan sekadar istilah akademik; ia adalah cermin nyata bagaimana struktur tarif memengaruhi perilaku ekonomi wajib pajak. Ketika struktur pajak dianggap terlalu tajam, banyak wajib pajak terutama mereka yang fleksibel dalam mengatur penghasilan akan menyesuaikan pelaporan mereka untuk menghindari lonjakan tarif. Ini bukan sekadar manipulasi, tetapi respons rasional terhadap sistem yang ada.
Memahami fenomena ini membantu kita melihat bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal moral atau penegakan hukum, tetapi juga tentang desain kebijakan yang memahami perilaku manusia.
Pajak yang efektif adalah pajak yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga cerdas dalam merespons perilaku ekonomi nyata.
Baca juga: Sinergi meningkatkan kepatuhan pajak melalui Single Profile Policy
*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik
Namun, struktur tarif yang berlapis (bracket) ini ternyata memiliki efek samping yang subtansial. Layaknya seorang pendaki gunung yang memilih bermalam di pos tertentu karena langkah berikutnya terasa berat, wajib pajak pun kerap memutuskan “berhenti” di titik penghasilan tertentu yang secara tidak langsung dapat mengurangi beban pajaknya.
Inilah yang dikenal dalam literatur perpajakan sebagai bunching effect, yaitu penumpukan pelaporan penghasilan tepat di bawah ambang batas tarif atas suatu lapisan pajak sebagai respons terhadap lonjakan tarif.
Fenomena ini dijelaskan oleh Saez (2001) sebagai kecenderungan wajib pajak untuk terkonsentrasi di ujung atas dari lapisan tarif yang lebih rendah sebagai sebuah strategi rasional untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dalam menghadapi sistem tarif yang berjenjang.
Ketika setiap tambahan rupiah penghasilan membuat seseorang terseret ke tarif yang lebih tinggi, respons yang paling hemat secara ekonomi adalah menunda atau menyesuaikan pelaporan pendapatan agar tetap berada di lapisan tarif yang lebih rendah.
Dalam desain PPh OP, ambang batas ini bertindak seperti “pos” yang ingin dihindari oleh banyak wajib pajak. Setiap kali seseorang mendekati posisi batas atas suatu tarif, terdapat motivasi ekonomi untuk berhenti bukan karena ia tidak mampu menghasilkan lebih banyak dengan produktif, tetapi karena tarif pajak yang tajam membuat tambahan pendapatan menjadi kurang menarik secara bersih setelah dipotong pajak.
Desain tarif yang demikian, meskipun dibangun atas dasar keadilan progresif, mengandung distorsi perilaku. Ketika keputusan ekonomi wajib pajak dipengaruhi oleh struktur tarif, itu berarti kebijakan pajak tidak hanya memungut penerimaan, tetapi justru membentuk pola perilaku pelaporan pendapatan. Analisis ini penting karena ia membuka perspektif bahwa tarif pajak bukan sekadar soal angka, tetapi juga sinyal perilaku.
Baca juga: Dunia usaha dinilai perlu perkuat sistem kepatuhan usai implementasi Coretax
Ketimpangan dalam Pungutan
Salah satu temuan menarik dari studi internasional adalah bahwa bunching effect sangat bergantung pada karakteristik wajib pajak, terutama kemampuan mereka untuk mengatur waktu dan jumlah penghasilan yang dilaporkan. Studi Adam et al. (2020) di Britania Raya menunjukkan bahwa penumpukan pelaporan penghasilan lebih kuat terjadi pada kelompok wajib pajak yang memiliki keleluasaan tinggi untuk mengatur pendapatan mereka, seperti wiraswasta, pengusaha, dan pemilik perusahaan.
Logika di balik ini sederhana: seorang pengusaha atau pekerja lepas bisa menunda penerbitan faktur, menunda pencatatan pendapatan, atau mempercepat pembelian sebagai biaya dalam periode yang menguntungkan secara pajak. Pada kelompok ini, keputusan ekonomi bisa diarahkan untuk “menghindari” tarif pajak yang lebih tinggi. Respons seperti ini bukan sekadar trik akuntansi; ia merupakan respon rasional terhadap struktur tarif yang ada.
Hal ini kontras dengan kondisi yang dihadapi pegawai karyawan. Gaji karyawan bersifat tetap, dipotong langsung oleh pemberi kerja melalui mekanisme withholding tax, dan hampir tidak dapat dimanipulasi oleh pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, kelompok karyawan menunjukkan distribusi pelaporan penghasilan yang lebih merata/tersebar dan jarang menunjukkan pola bunching.
Data Indonesia menunjukkan realitas yang menarik. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, realisasi penerimaan dari PPh Pasal 21 (karyawan) mencapai Rp240 triliun, atau sekitar 12,8% dari total penerimaan pajak. Sementara itu, realisasi penerimaan dari PPh Pasal 25/29 orang pribadi (non-karyawan) hanya Rp14,74 triliun, atau sekitar 0,8% saja dari total penerimaan. Dengan kata lain, penerimaan dari karyawan hampir 16 kali lebih besar dibandingkan dari non-karyawan yang umumnya mencakup wiraswasta dan pekerja bebas.
Ironinya, kelompok non-karyawan secara ekonomis memiliki basis penghasilan yang berpotensi jauh lebih besar daripada pekerja bergaji tetap. Namun kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak tetap jauh lebih kecil. Ketimpangan ini memicu pertanyaan serius tentang efektivitas struktur PPh OP yang saat ini dipakai dan potensi adanya distorsi perilaku termasuk bunching effect yang mengurangi penerimaan negara dari segmentasi yang secara modal dan potensi ekonomi besar ini.
Baca juga: IKPI dorong kepatuhan wajib pajak nasional lewat kegiatan strategis
Paradoks Keadilan Fiskal
Berbeda dengan pelaku usaha, karyawan pada umumnya tidak memiliki fleksibilitas ajustasi penghasilan yang sama. Gaji mereka sudah ditetapkan dan pajaknya dipotong secara otomatis melalui mekanisme pemotongan/penyetoran oleh pemberi kerja setiap bulan. Sistem ini menutup ruang untuk manipulasi waktu pelaporan atau penyesuaian jumlah pendapatan yang dilaporkan. Efeknya, karyawan cenderung terhindar dari fenomena bunching effect baik karena struktur pemotongan yang terotomasi maupun karena kurangnya kendali atas waktu penerimaan penghasilan.
Berdasarkan hal tersebut, pola pelaporan penghasilan karyawan cenderung mengikuti struktur alami distribusi pendapatan tanpa konsentrasi tajam di sekitar ambang batas tarif. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kelompok ini memberi kontribusi penerimaan yang relatif besar (Rp240 triliun dari PPh Pasal 21), namun bukan karena tarif progresifnya lebih adil, melainkan karena mekanisme withholding yang membatasi ruang perilaku responsif terhadap ambang tarif.
Dalam konteks keadilan fiskal, hal ini menciptakan paradoks. Kelompok yang paling patuh secara struktural karena tidak punya opsi penyesuaian yang justru menanggung bagian beban pajak yang lebih pasti. Sementara kelompok dengan basis ekonomi lebih besar memiliki ruang untuk mengatur pelaporan penghasilan mereka agar tidak terangkat ke tarif yang lebih tinggi, sehingga kontribusi mereka terhadap penerimaan cenderung lebih kecil.
Baca juga: Paradigma baru kepatuhan pajak
Perbaikan Desain Kebijakan
Fenomena bunching effect ini memberikan pelajaran penting bagi perancang kebijakan fiskal. Bahwa tarif progresif meskipun dimaksudkan untuk keadilan, dapat menciptakan distorsi perilaku dalam sistem pemajakan yang justru menurunkan efisiensi dan basis pajak. Bunching effect menjadi sebuah indikator perilaku ekonomi yang rasional dalam menghadapi struktur tarif pajak yang tajam.
Untuk itu, beberapa pendekatan kebijakan dapat diusulkan untuk menjadi perbaikan desain kebijakan ke depan.
Pertama, penyederhanaan sistem dan administrasi perpajakan, karena struktur yang rumit tidak hanya memicu bunching, tetapi juga memperkuat peluang ketidaktahuan atau penyesuaian perilaku yang tidak diinginkan.
Kedua, pengurangan jumlah lapisan tarif, karena semakin sedikit lapisan berarti semakin kecil lonjakan tarif antar level yang bisa memicu perilaku konsentrasi pelaporan.
Ketiga, melakukan penataan ulang threshold (ambang batas) agar desainnya lebih selaras dengan kenyataan distribusi pendapatan masyarakat untuk mengurangi keuntungan ekonomis dari penyesuaian pelaporan yang rasional.
Selain itu, ada pula opsi yang kerap dibahas dalam studi internasional, yaitu struktur flat tax rate dengan dasar penghasilan yang luas dan kombinasi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Negara seperti Estonia menerapkan sistem pajak tunggal 22% dengan PTKP, yang dinilai mampu mempertahankan kesederhanaan sekaligus keadilan. Namun hal ini bukan satu-satunya formula yang ideal, karena desain terbaik sering kali adalah yang paling tepat membaca konteks ekonomi, administratif, dan perilaku pelaku pajak di setiap negara.
Pada akhirnya bunching effect bukan sekadar istilah akademik; ia adalah cermin nyata bagaimana struktur tarif memengaruhi perilaku ekonomi wajib pajak. Ketika struktur pajak dianggap terlalu tajam, banyak wajib pajak terutama mereka yang fleksibel dalam mengatur penghasilan akan menyesuaikan pelaporan mereka untuk menghindari lonjakan tarif. Ini bukan sekadar manipulasi, tetapi respons rasional terhadap sistem yang ada.
Memahami fenomena ini membantu kita melihat bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal moral atau penegakan hukum, tetapi juga tentang desain kebijakan yang memahami perilaku manusia.
Pajak yang efektif adalah pajak yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga cerdas dalam merespons perilaku ekonomi nyata.
Baca juga: Sinergi meningkatkan kepatuhan pajak melalui Single Profile Policy
*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik