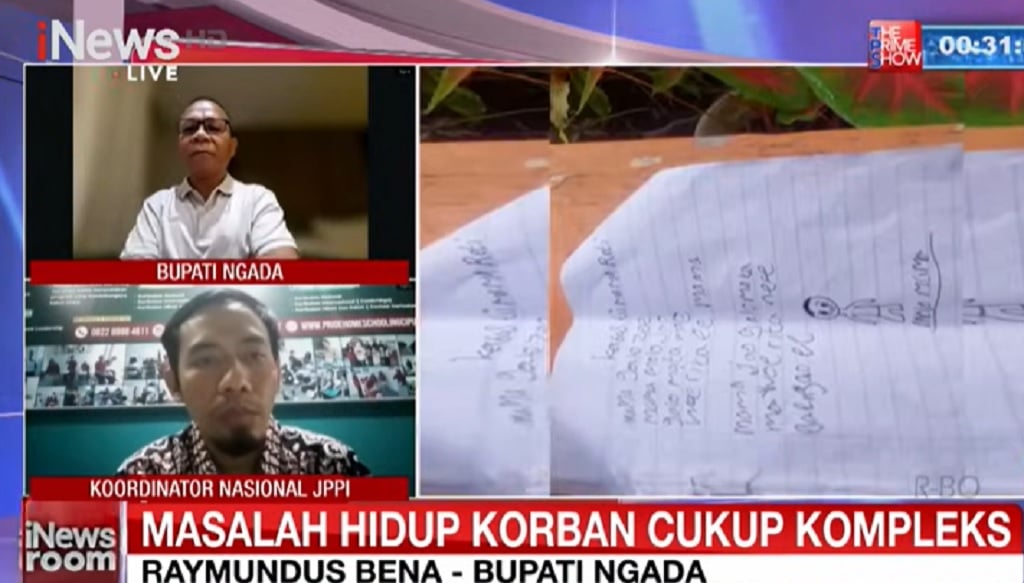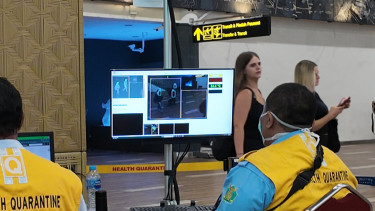JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah banyaknya pekerja yang berlomba mengejar promosi, titel, dan kursi manajerial, semakin banyak pekerja muda yang justru memilih berjalan pelan.
Bukan karena tak mampu, melainkan karena sadar akan harga yang harus dibayar.
Bagi Naya (25), Content and Social Media Officer di sebuah startup digital di Jakarta Pusat, naik jabatan bukanlah tujuan utama dalam kariernya.
“Buat aku, naik jabatan itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab besar. Tekanannya besar, aturannya banyak, hidup makin dikontrol kantor,” ujar Naya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/2/2026).
Bekerja sejak tiga tahun lalu, Naya mengaku tidak pernah mengejar posisi struktural. Ia memilih bekerja profesional, tetapi tetap menjaga jarak agar hidupnya tidak sepenuhnya tersedot oleh pekerjaan.
“Kerja ya kerja, hidup ya hidup. Jangan sampai dicampur sampai stres sendiri,” kata dia.
Menurut Naya, di lingkungan kerjanya, karyawan yang terlalu menonjol justru sering menjadi “langganan” pekerjaan tambahan.
Mereka yang rajin, responsif, dan cepat menyelesaikan tugas, kerap dibebani lebih banyak tanggung jawab tanpa kompensasi sepadan.
“Kalau kelihatan rajin, semua dilempar ke kita. Darurat, kita yang dicari. Lembur, kita yang disuruh. Tapi gajinya tetap segitu-gitu aja,” ujar dia.
Pengalaman itu membuat Naya memilih memasang batas. Ia tetap menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi tidak ingin bekerja melampaui kapasitas.
“Bukan males. Aku tetap tanggung jawab. Cuma aku enggak mau over,” tutur Naya.
Baca juga: Saat Buruh Suarakan Masalah PT Pakerin, Desak Prabowo Selamatkan 2.500 Pekerja dari PHK
Takut kehilangan diriBagi Naya, ketakutan terbesar dari naik jabatan bukan soal kemampuan, melainkan konsekuensinya.
“Naik posisi berarti waktu makin sedikit, tekanan makin besar, urusan makin ribet. Harus standby terus, harus mikirin banyak orang. Kayak kehilangan diri sendiri,” ujar Naya.
Ia melihat banyak senior yang kariernya menanjak, tetapi hidupnya semakin terikat pekerjaan.
Pesan dari kantor masuk tengah malam. Libur tetap buka laptop. Pikiran tidak pernah benar-benar lepas dari target.
“Kami enggak mau hidup cuma buat profit perusahaan,” katanya.
Menurut Naya, Gen Z lebih berani bicara soal batasan dibanding generasi sebelumnya.
“Kalau capek, kami bilang. Kalau kebebanan, kami protes. Bukan manja, tapi biar enggak numpuk di kepala,” ujar Naya.
Pengalaman tertekan oleh target tinggi juga pernah Naya alami. Ia sempat mengalami gangguan tidur karena terus memikirkan pekerjaan.
“Dari situ aku sadar, kalau aku terus nurutin semua, yang rusak ya aku sendiri. Perusahaan tetap jalan tanpa aku,” kata Naya.
Sukses versi baruBagi Naya, makna sukses kini jauh dari sekadar jabatan.
“Sukses itu bisa tidur nyenyak, bisa liburan tanpa mikirin laptop, bisa bilang ‘enggak’ tanpa rasa bersalah,” ujar Naya.
Ia menilai, banyak anak muda saat ini melihat teman-temannya yang hidup sederhana tetapi bahagia sebagai bentuk kesuksesan baru.
“Ngapain jabatan tinggi tapi tiap hari stres?” ungkap dia.
Karena itu, ia berharap perusahaan mulai menghargai pilihan karier yang beragam.
“Enggak semua orang mau jadi bos. Dan itu harusnya enggak dianggap gagal,” ujar Naya.
Baca juga: Dilema Ibu Pekerja Jakarta: Menanggung Lelah di Kantor dan Rumah
Pandangan serupa disampaikan Raka (27), Digital Marketing Specialist di perusahaan e-commerce Jakarta Selatan. Empat tahun bekerja membuatnya mengubah pandangan tentang karier.