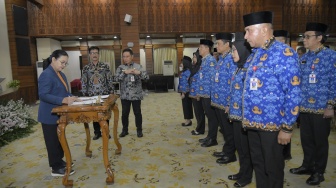Saya beberapa kali mendapati diri saya tertarik tapi sekaligus curiga ketika mendengar istilah pasar karbon disebut sebagai sebuah terobosan. Tertarik, karena gagasannya terdengar elegan, yaitu emisi diberi harga, lalu aktor ekonomi terdorong memilih teknologi yang lebih bersih.
Namun di saat bersamaan juga menyeruak perasaan curiga, karena di banyak negara, bahkan di pasar yang relatif stabil, harga karbon sering terlalu rendah, cakupan sektor terbatas, dan terkadang terjadi distori tata kelola yang memungkinkan terjadinya reduksi emisi semu, di mana emisi tampak menurun dalam laporan, tetapi tidak benar-benar berkurang secara riil di atmosfer.
Dari sisi prospek, Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol. Secara kebijakan nasional, fondasi utamanya adalah Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang secara eksplisit memasukkan perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan pengendalian emisi dalam pembangunan nasional.
Di tingkat tata kelola pasar, OJK kemudian menerbitkan POJK 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yang menjadi rambu operasional bagi perdagangan unit karbon melalui penyelenggara bursa. Ketika perangkat regulasi dan kelembagaan ini disatukan, Indonesia pada dasarnya sedang menata prasyarat minimum yang jika konsisten, dapat membuat pasar karbon tidak berhenti sebagai jargon.
Indikator awalnya terlihat dari jalannya bursa karbon Indonesia (IDXCarbon) yang beroperasi sejak 26 September 2023. Dari sisi “denyut transaksi”, nilainya memang belum sebesar yang sering dibayangkan publik (karena imajinasi orang tentang pasar biasanya langsung melompat ke triliunan).
Namun tren partisipasi dan aktivitasnya memberi sinyal bahwa mekanisme ini mulai menemukan pelaku dan kebutuhannya. Hingga 22 Agustus 2025, IDXCarbon melaporkan nilai transaksi kumulatif sekitar Rp78,37 miliar dengan volume sekitar 1,604 juta tCO2e.
Angka tersebut menurut keyakinan saya akan bersamaan memunculkan dua perasaan, optimis dan kritis. Dalam hal perasaan optimis, akan mengatakan angka tersebut merupakan permulaan yang wajar karena pasar baru membutuhkan pembentukan kepercayaan, kurva belajar Measurement, Reporting, and Verification (MRV), dan penyesuaian pelaku sedangkan dari sudut sikap kritis, akan mengatakan bahwa tanpa pendorong kepatuhan yang kuat dan sinyal harga yang memadai, pasar bisa ramai tetapi tidak cukup “menggigit” perilaku emisi.
Manfaat yang paling sering dikutip dan menurut saya paling masuk akal adalah potensi mobilisasi pembiayaan iklim. Indonesia sudah menaikkan target penurunan emisi dalam Enhanced NDC menjadi 31,89% (tanpa bantuan internasional) dan 43,20% (dengan dukungan internasional) pada 2030 dibanding baseline Business As Usual (BAU).
Target ini, apa pun perdebatan tentang kecukupannya, secara implisit menuntut pendanaan, teknologi, dan perubahan praktik pada sektor energi, industri, kehutanan, limbah, hingga pertanian. Dalam konteks global, Bank Dunia mencatat pendapatan dari instrumen penetapan harga karbon di dunia pada 2023 mencapai rekor sekitar US$104 miliar. Hal tersebut membuktikan bahwa ketika desain dan kepatuhan berjalan, penetapan harga karbon bisa menghasilkan sumber daya fiskal dan pembiayaan program iklim.
Namun, saya justru menilai tantangan Indonesia ada pada tiga simpul yang bila tidak diselesaikan, bisa mengubah solusi menjadi sekadar ilusi. Pertama adalah integritas lingkungan (environmental integrity). Pasar karbon hanya bermakna jika satu unit benar-benar mewakili penurunan/penyerapan emisi yang tambahan (additional), terverifikasi, permanen, dan tidak bocor (leakage).
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI sudah disiapkan sebagai pusat data dan registri nasional. Tantangannya bukan sekadar “punya sistem”, melainkan memastikan sistem itu menjadi sumber kebenaran yang diakui dan dipakai secara konsisten oleh semua rezim (bursa, kepatuhan sektor, dan klaim korporasi).
Kedua adalah kepastian regulasi dan keterhubungan dengan pasar internasional. Kebijakan domestik harus tegas memisahkan mana unit untuk klaim NDC (menghindari double counting), mana unit yang bisa diperdagangkan lintas batas dengan pengaturan penyesuaian (corresponding adjustment) sesuai prinsip Paris Agreement. Tanpa kejelasan tersebut, pasar bisa berjalan, tetapi nilainya cenderung tertekan karena pembeli ragu terhadap legitimasi dan penggunaan klaimnya.
Ketiga adalah dimensi keadilan sosial dan tata kelola lahan, khususnya pada kredit berbasis alam (nature-based credits) seperti REDD+ atau pengelolaan hutan. Potensi kehutanan Indonesia sangat besar dan memiliki peluang besar jika tata kelolanya kuat. Tetapi pengalaman banyak negara menunjukkan risiko “green grabbing” di mana ketika nilai karbon menaikkan nilai lahan, sementara hak masyarakat adat/lokal tidak cukup terlindungi, konflik dan ketidakadilan distribusi manfaat bisa meningkat.
Kredit karbon tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hutan adat dan hak masyarakat, karena pada akhirnya konflik sosial akan merusak reputasi kredit dan meruntuhkan kepercayaan pasar. Integritas lingkungan dan integritas sosial bukan dua hal terpisah.
Saya lebih memilih cara pandang yang tidak sinis, tetapi juga tidak naif. Pasar karbon Indonesia saat ini terus berproses. Fondasinya sudah ada dan dituangkan dalam Perpres 98/2021. Perangkat pasar dipandu POJK 14/2023, registri nasional tersedia, dan aktivitas bursa sudah menunjukkan banyak tanda kehidupan awal.
Yang akan menentukan apakah ia menjadi solusi atau ilusi adalah keberanian untuk menjaga kualitas, bukan sekadar kuantitas, serta kesediaan menempatkan perlindungan sosial dan integritas ekologis sebagai prasyarat, bukan aksesori. Jika itu dilakukan, pasar karbon bisa menjadi salah satu instrumen yang masuk akal untuk membantu Indonesia memenuhi Enhanced NDC 2030. Jika tidak, ia akan menjadi pasar yang sibuk mencatat transaksi, tetapi gagal menurunkan emisi dan dalam kondisi demikian, publik wajar bertanya: “yang kita jual sebenarnya apa?”