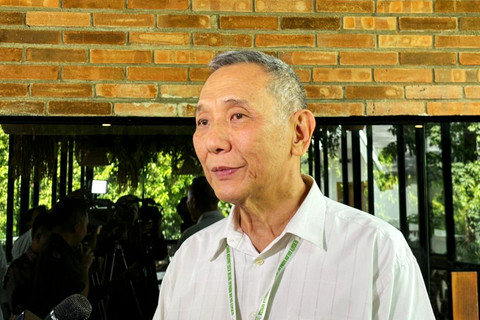Maraknya kasus kejahatan seksual dewasa ini—baik di lingkungan pendidikan, tempat kerja, hingga komunitas keagamaan—menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata soal individu pelaku.
Di balik setiap kasus, hampir selalu terdapat jejaring sosial yang lebih luas: teman, kelompok, organisasi, atau komunitas yang memilih untuk diam. Dalam konteks ini, diam bukanlah ketiadaan komunikasi, melainkan bentuk komunikasi itu sendiri.
Dalam kajian komunikasi, kejahatan seksual dapat dipahami sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh dinamika komunikasi kelompok.
Cara kelompok berinteraksi—baik berbicara, bercanda, menilai, bahkan mengabaikan isu kekerasan seksual—berkontribusi besar dalam membentuk iklim sosial yang memungkinkan kejahatan tersebut terus berulang. Oleh karena itu, permasalahan tersebut naik takhta menjadi masalah yang harus dipandang serius oleh kita semua.
Diam sebagai Pesan SosialMengenai kebutuhan berkomunikasi (hubungan sosial), Paul Watzlawick dalam Pragmatics of Human Communication (1967) menyatakan, "One cannot not communicate" (manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi).
Ketika sebuah kelompok memilih untuk tidak merespons candaan seksual, pelecehan verbal, atau laporan korban, sikap tersebut sesungguhnya adalah pesan yang jelas: perilaku itu dapat ditoleransi. Hal tersebut justru menjadi penyebab suburnya (legitimate) kejahatan seksual terjadi di kalangan masyarakat.
Diam kolektif sering kali berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kelompok. Pelaku dilindungi demi menjaga reputasi institusi, nama baik organisasi, atau “harmoni” sosial. Dalam praktiknya, nilai harmoni ini justru memakan korban dan memperpanjang siklus kekerasan.
Norma Kelompok dan Tekanan SosialTeori normative social influence dari Solomon Asch (1951) menjelaskan bahwa individu cenderung beradaptasi dengan norma kelompok agar diterima secara sosial.
Dalam konteks kejahatan seksual, anggota kelompok sering kali memilih diam bukan karena tidak tahu, melainkan karena takut dikucilkan, disalahkan, atau dianggap merusak solidaritas, bahkan mendapatkan tindakan kekerasan, baik fisik maupun mental.
Tekanan ini diperkuat oleh fenomena groupthink yang diperkenalkan Irving Janis (1972). Groupthink terjadi ketika keinginan menjaga kesepakatan kelompok lebih diutamakan daripada evaluasi moral dan rasional. Akibatnya, peringatan dini diabaikan, suara kritis dibungkam, dan kejahatan seksual dianggap sebagai “urusan pribadi” atau “kesalahpahaman”.
Normalisasi Melalui Komunikasi Sehari-hariKomunikasi kelompok tidak selalu berlangsung dalam forum resmi. Justru, normalisasi sering terjadi lewat obrolan santai, candaan, dan bahasa simbolik sehari-hari.
George Herbert Mead (1934) melalui teori symbolic interactionism menekankan bahwa makna dibentuk melalui interaksi sosial. Ketika candaan seksis atau objektifikasi tubuh dibiarkan tanpa koreksi, kelompok secara tidak sadar membentuk makna bahwa pelecehan adalah hal lumrah.
Lebih jauh, Albert Bandura dalam teori social learning (1977) menjelaskan bahwa individu belajar perilaku melalui observasi dan peniruan. Ketika pelaku tidak mendapat sanksi sosial, anggota lain belajar bahwa tindakan tersebut aman untuk ditiru. Kejahatan seksual pun menjadi produk dari proses belajar sosial, bukan semata penyimpangan personal.
Hal tersebut dikuatkan kembali oleh Elisabeth Noelle-Neumann (1974) melalui teori spiral of silence yang menjelaskan bahwa individu cenderung bungkam ketika merasa pendapatnya berada di posisi minoritas. Dalam kasus kejahatan seksual, korban sering kali memilih diam karena narasi dominan kelompok lebih berpihak pada pelaku, terutama jika pelaku memiliki status, kuasa, atau kedekatan emosional dengan kelompok.
Komunikasi kelompok yang tidak empatik menciptakan iklim ketakutan di mana korban khawatir tidak dipercaya, disalahkan, atau distigmatisasi. Diam dari korban kemudian ditafsirkan sebagai ketiadaan masalah, padahal justru menandakan kegagalan komunikasi yang paling serius.
Menggeser Budaya Diam Menjadi Budaya PeduliJika kejahatan seksual sebagian besar dipelihara oleh komunikasi kelompok yang keliru, pencegahannya pun harus dimulai dari pembenahan komunikasi.
Kelompok sosial perlu membangun norma komunikasi yang jelas: berani menegur, membuka ruang aman untuk bersuara, dan menempatkan empati sebagai nilai bersama. Bukan hanya masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang harus mulai berani “menegur”, melainkan juga aparat yang bersikap tegas terhadap kejahatan seksual—bahwa kejahatan seksual adalah sebuah perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum.
Dalam perspektif communication ethics (Johannesen, 2002), komunikasi tidak hanya dinilai dari efektivitasnya, tetapi juga dari tanggung jawab moralnya. Diam yang melanggengkan kekerasan adalah bentuk komunikasi yang tidak etis.
Kejahatan seksual bukan hanya kegagalan hukum, melainkan juga kegagalan komunikasi kelompok. Selama diam terus dianggap sebagai sikap aman, dan solidaritas dipahami sebagai perlindungan terhadap pelaku, kejahatan seksual akan terus menemukan ruang hidupnya.
Sudah saatnya kelompok sosial menyadari bahwa setiap respons, termasuk diam, memiliki makna. Dalam konteks ini, berbicara bukan sekadar pilihan, melainkan juga tanggung jawab sosial.