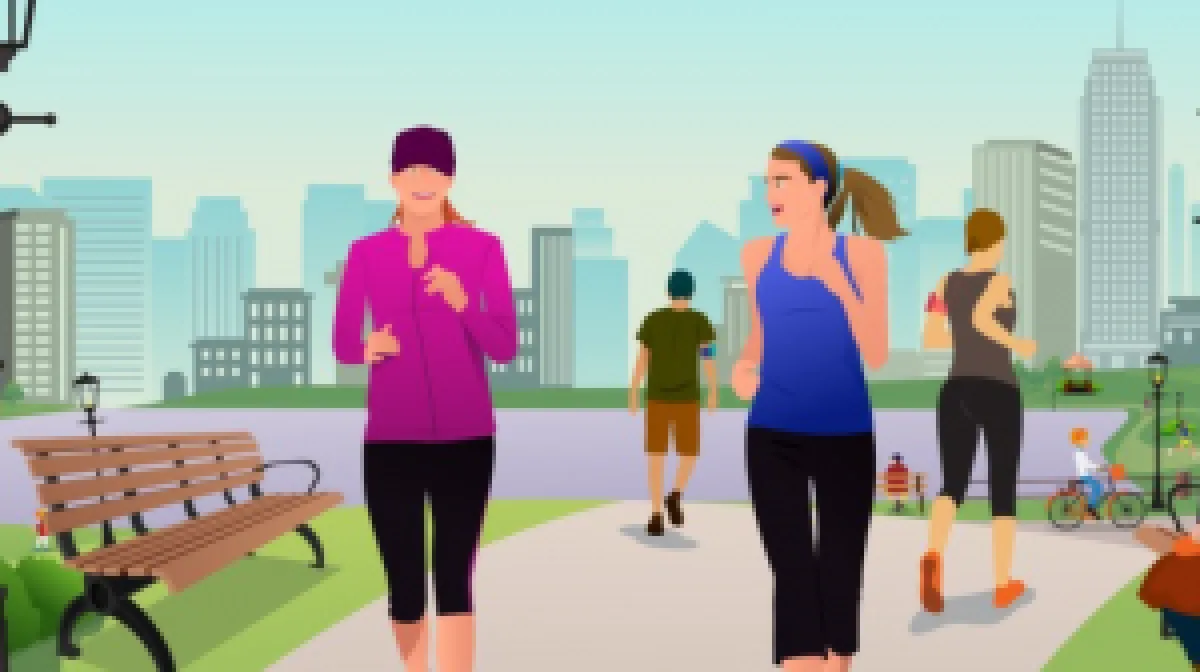Saya baru saja bertemu dengan seorang ibu yang hendak mengurut istri saya. Saya menjemputnya ke rumah. Perjalanan kami singkat, namun percakapannya bergerak jauh. Entah bagaimana, obrolan ringan tentang keluarga berbelok ke kisah rumah tangga anaknya. Kami memang sudah pernah bertemu sebelumnya, sehingga percakapan mengalir tanpa sekat.
Ibu itu berusia sekitar enam puluh tahun. Dengan nada lelah dan pasrah, ia bercerita bahwa menantunya, seorang perempuan, pergi meninggalkan rumah karena tidak lagi akur dengan suaminya. Konflik yang berlarut-larut membuat rumah tangga itu berada di ambang perceraian. Di ujung ceritanya, sang ibu menyimpulkan dengan satu kalimat yang ia ucapkan seolah sebagai kebenaran umum: perempuan harus mengalah.
Kalimat itu membuat saya diam. Bukan karena menghormati usia semata, tetapi karena saya tidak setuju. Diam saya bukan persetujuan, melainkan kegelisahan.
Nasihat yang Diwariskan, Beban yang DiturunkanNasihat itu tidak lahir dari niat buruk. Ia lahir dari pengalaman hidup sebuah generasi. Namun persoalannya, pengalaman personal yang dibingkai sebagai kebenaran universal sering kali berubah menjadi warisan sunyi yang menekan generasi berikutnya, terutama perempuan.
Dalam banyak keluarga Indonesia, konflik rumah tangga masih sering disederhanakan menjadi soal kesabaran perempuan. Ketika relasi retak, yang diminta menahan diri lebih dulu hampir selalu perempuan. Ketika komunikasi buntu, yang dinasihati untuk mengalah adalah perempuan. Sementara perubahan sikap, tanggung jawab emosional, dan refleksi diri jarang dituntut secara setara dari laki-laki.
Kalimat perempuan harus mengalah terdengar lembut, bahkan bijak. Namun di balik kelembutan itu tersembunyi ketimpangan yang telah lama dinormalisasi.
Patriarki yang Hidup dalam Kalimat Sehari-hariBudaya patriarki tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan atau larangan terbuka. Ia justru paling kuat ketika hadir sebagai petuah, nasihat, dan nilai yang diwariskan dari orang tua ke anak. Mengalah dipuji sebagai kebajikan perempuan, sementara keutuhan rumah tangga diposisikan sebagai tanggung jawab utamanya.
Akibatnya, relasi dalam keluarga tidak dibangun di atas kesetaraan, melainkan hierarki. Jika rumah tangga gagal, perempuan sering kali menanggung beban moral yang lebih berat. Ia dianggap kurang sabar, kurang kuat, atau kurang berkorban.
Padahal, rumah tangga adalah perjumpaan dua manusia dewasa. Mengalah hanya bermakna jika lahir dari kesadaran bersama, bukan tuntutan sepihak.
Keluarga sebagai Sekolah KebangsaanPersoalan ini tidak berhenti di ruang privat. Keluarga adalah sekolah pertama kebangsaan. Di sanalah anak belajar tentang keadilan, penghormatan, dan relasi kuasa. Ketika anak tumbuh dengan menyaksikan ibunya terus diminta mengalah, ia belajar bahwa ketimpangan adalah hal wajar.
Anak laki-laki belajar bahwa ia tidak perlu banyak berubah. Anak perempuan belajar bahwa bertahan lebih penting daripada didengar. Dari rumah seperti inilah nilai ketidakadilan kemudian terbawa ke ruang publik, tempat kita masih berjuang mewujudkan kesetaraan.
Tidak mengherankan jika upaya negara membangun keadilan gender sering tersendat. Undang-undang dan kurikulum bisa bicara tentang kesetaraan, tetapi jika nilai di rumah bertolak belakang, kebijakan akan selalu kalah oleh kebiasaan.
Menghormati Pengalaman, Mengkritisi WarisanPengalaman hidup ibu yang saya temui hari itu patut dihormati. Namun penghormatan tidak harus berarti penerimaan tanpa kritik. Bertahan di masa lalu sering kali bukan pilihan bebas, melainkan keterpaksaan akibat kondisi sosial dan budaya.
Ketika pengalaman itu diwariskan sebagai nasihat mutlak, yang diturunkan bukan kebijaksanaan, melainkan luka yang belum sempat disembuhkan.
Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling pandai menyuruh warganya mengalah, tetapi bangsa yang berani menata ulang relasi agar lebih adil. Dan keberanian itu harus dimulai dari ruang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga.
Sebab tidak semua nasihat lama layak dipertahankan. Sebagian justru perlu dipertanyakan, demi masa depan yang lebih setara dan beradab.