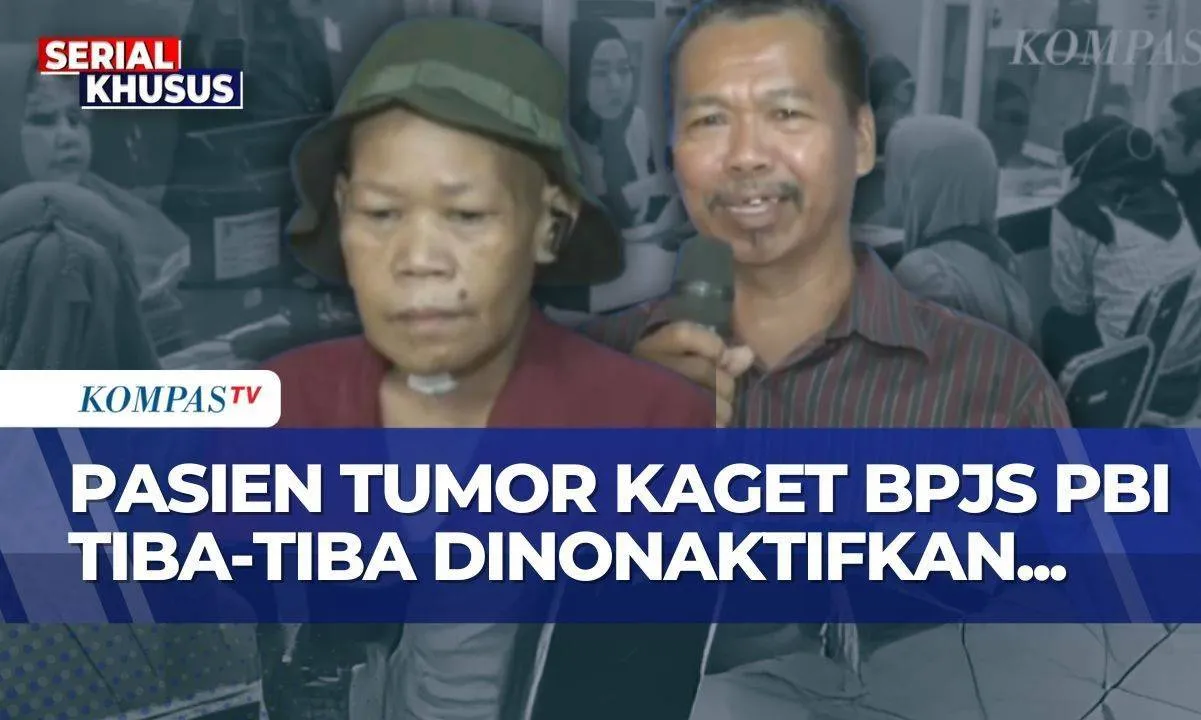Oleh: Nanda Yuniza Eviani
Mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Di pasar Indonesia, tabung nitrous oxide beredar dalam berbagai merek dagang, salah satunya dikenal publik dengan nama Whippink. Produk ini secara formal dipasarkan sebagai cream charger untuk kebutuhan industri makanan, terutama sebagai propelan dalam pembuatan whipped cream. Secara kimia, zat di dalamnya adalah nitrous oxide, senyawa yang tersusun dari dua atom nitrogen dan satu atom oksigen, tidak berwarna, dan dalam praktik medis digunakan sebagai anestesi ringan. Di tingkat internasional, nitrous oxide lebih populer dengan sebutan laughing gas karena efek euforia singkat yang ditimbulkannya ketika dihirup.
Persoalan muncul ketika fungsi medis dan kuliner tersebut bergeser menjadi konsumsi rekreasional. Laughing gas tidak lagi semata alat dapur, melainkan dihirup untuk menghasilkan sensasi melayang yang berisiko pada sistem saraf dan pernapasan. Pergeseran fungsi ini bukan isu moral, melainkan isu kesehatan publik yang nyata. Ketika praktik inhalasi menjadi pengetahuan umum, negara tidak bisa lagi berpura-pura bahwa zat ini sekadar komoditas industri makanan yang netral secara sosial.
Secara normatif, nitrous oxide memang tidak tercantum dalam daftar narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam klasifikasi psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dari perspektif hukum pidana khusus, ia bukan barang terlarang. Asas legalitas tetap menjadi fondasi negara hukum dan tidak boleh dikesampingkan. Namun asas legalitas tidak dapat dijadikan alasan untuk pembiaran kebijakan. Tidak tercantum dalam lampiran undang-undang bukan berarti negara bebas dari tanggung jawab pengawasan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban negara untuk mengendalikan zat yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Hak atas kesehatan adalah mandat konstitusional yang menuntut kebijakan preventif. Ketika suatu zat secara faktual telah digunakan secara luas untuk tujuan yang berisiko, negara tidak dapat menunggu sampai muncul korban untuk menyusun respons. Hukum yang hanya bekerja setelah tragedi terjadi adalah hukum yang kehilangan fungsi perlindungannya.
Dimensi lain yang turut memperlihatkan lemahnya respons regulasi adalah praktik periklanan dan pemasaran. Produk laughing gas kerap dipromosikan secara daring dengan narasi yang ambigu, menonjolkan legalitas dan kemudahan akses sebagai produk dapur, tetapi menggunakan gaya komunikasi yang secara implisit dapat diasosiasikan dengan penggunaan rekreasional. Iklan semacam ini tidak selalu memuat pernyataan yang salah secara eksplisit, namun berpotensi membangun persepsi keliru mengenai keamanan dan tujuan penggunaan. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik promosi yang menyesatkan atau tidak memberikan informasi yang jelas mengenai risiko dapat dipersoalkan secara hukum.
Namun inti persoalannya bukan hanya semata pada pelaku usaha, melainkan pada keberanian negara dalam menutup celah regulasi. Pemerintah memiliki ruang diskresi dalam hukum administrasi untuk membatasi peredaran barang yang berpotensi mengganggu kesehatan publik. Pembatasan usia, kewajiban pelabelan risiko, pengawasan distribusi daring, hingga pengaturan kuantitas pembelian adalah instrumen yang secara hukum dapat ditempuh tanpa melanggar asas legalitas. Ketiadaan langkah progresif menunjukkan bahwa negara masih bersikap reaktif, bukan preventif.
Jika suatu hari penyalahgunaan laughing gas menimbulkan kematian atau kerusakan neurologis permanen, Pasal 359 dan 360 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pihak yang lalai. Namun pendekatan ini datang setelah kerusakan terjadi. Negara yang progresif tidak menunggu sampai risiko berubah menjadi krisis untuk bertindak. Negara yang responsif membaca perubahan sosial lebih cepat daripada tekanan publik dan sorotan media.
Isu laughing gas pada akhirnya bukan sekadar persoalan peredaran suatu zat, melainkan ukuran tentang sejauh mana pemerintah menjalankan mandat perlindungan yang melekat pada negara hukum. Ketika suatu produk yang memiliki risiko kesehatan nyata beredar luas dan penyalahgunaannya berlangsung secara terbuka, respons yang lambat tidak dapat terus-menerus dibingkai sebagai kehati-hatian regulatif. Dalam konteks perlindungan kesehatan publik, kehati-hatian yang berlarut justru dapat berubah menjadi kelambanan kebijakan.
Diamnya negara dalam situasi seperti ini bukanlah netralitas administratif. Ia adalah bentuk pilihan kebijakan, baik disadari maupun tidak. Negara yang memilih menunggu sampai risiko itu bermetamorfosis menjadi krisis publik sesungguhnya sedang menempatkan fungsi pencegahan di posisi sekunder. Padahal dalam paradigma negara kesejahteraan, fungsi utama hukum bukan hanya menghukum akibat, melainkan mengantisipasi sebab.
Dalam negara hukum, setiap tindakan dan setiap penundaan memiliki implikasi normatif. Menunda regulasi yang tegas dan proporsional dengan alasan belum adanya klasifikasi formal atau belum adanya tekanan sosial yang cukup kuat berpotensi menggeser orientasi perlindungan menjadi sekadar respons situasional. Kebijakan yang progresif semestinya lahir dari pembacaan risiko yang objektif, bukan dari eskalasi opini publik.
Jika pemerintah terus memilih langkah yang lambat dalam menghadapi risiko yang telah nyata di depan mata, maka persoalannya bukan lagi pada kekosongan regulasi, melainkan pada keberanian mengambil keputusan. Negara tidak dinilai dari kemampuannya menyusun norma setelah krisis terjadi, tetapi dari ketegasannya bertindak sebelum risiko berubah menjadi kerugian publik yang tak terpulihkan. Apabila perlindungan kesehatan warga negara selalu menunggu tekanan atau korban sebagai pemicu, maka yang patut dipertanyakan bukan sekadar efektivitas kebijakan, melainkan kesungguhan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya sendiri.