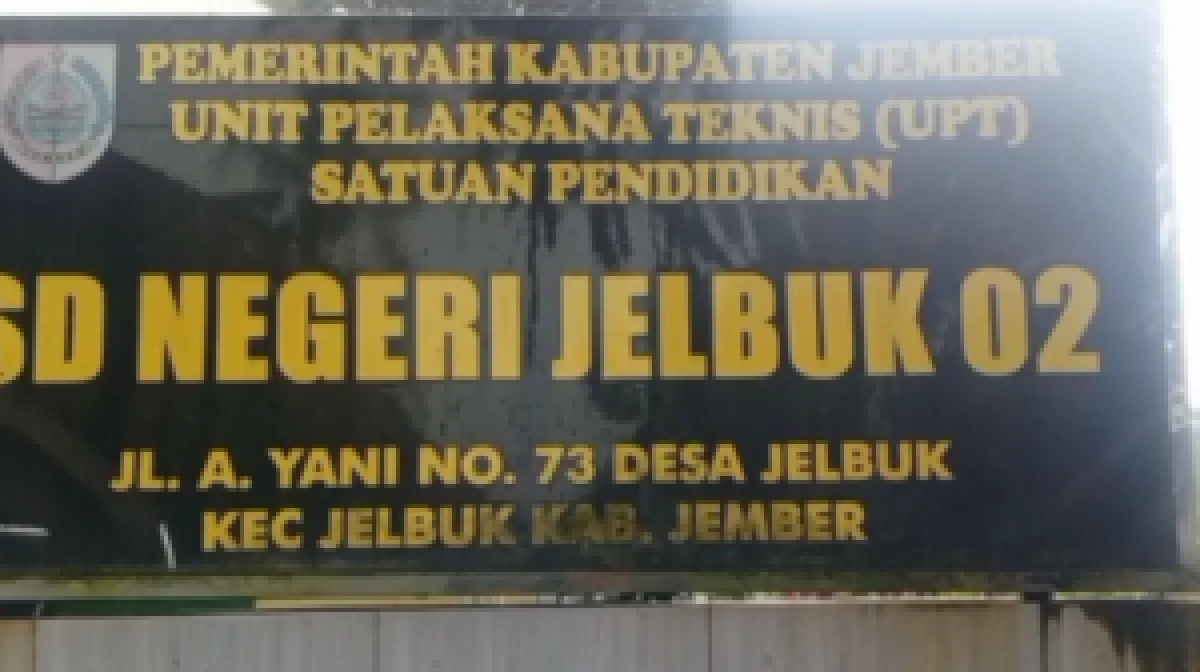Ada dosa yang tidak sempat kita istighfari karena ia tak tampak di cermin. Dosa itu menempel di udara, masuk ke paru-paru, mengendap pelan-pelan, lalu menjadi “normal” dalam hidup kota. Kita menyebutnya macet. Kita menyebutnya polusi. Kita menyebutnya harga kemajuan. Padahal sering kali itu hanya satu nama lain dari kelalaian. Kelalaian menjaga amanah paling dekat yakni napas kita.
Lalu Car Free Day (CFD) setiap Minggu pagi datang seperti jeda rahmat. Sehari, jalan raya kembali menjadi ruang manusia. Sehari, Jakarta seperti bisa bernapas. Sehari, kita merasakan sesuatu yang seharusnya tidak langka, udara yang lebih ringan, bising yang berkurang, wajah yang lebih tenang, dan tubuh yang bergerak tanpa harus “berperang” dengan knalpot.
Tetapi justru di situlah pertanyaan yang harus dijawab, kalau sehari saja bisa, mengapa kita rela membiarkan enam hari lain menjadi rutinitas menyiksa?
CFD adalah CerminCFD membongkar mitos paling nyaman seakan-akan polusi adalah takdir kota besar. Padahal CFD menunjukkan polusi itu bisa diturunkan saat sumbernya dikurangi. Maka akar masalahnya bukan semata “warga kurang sadar”, melainkan arah kebijakan yang terlalu lama memanjakan kendaraan pribadi dan menghukum pejalan kaki.
Kita perlu jujur bahwa Jakarta dan banyak kota besar lain sering dibangun dengan logika mobil, bukan logika manusia. Trotoar sempit, terputus, dan rawan. Bersepeda sering diperlakukan seperti gangguan, bukan hak. Transportasi publik sudah membaik, namun integrasi, kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan masih harus terus ditingkatkan agar benar-benar bisa menggantikan ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Kalau CFD hanya menjadi “panggung Minggu pagi”, ia akan berubah menjadi sedekah sehari untuk menebus dosa setahun, ramai sebentar, lalu kembali menebar asap; tertib sebentar, lalu kembali saling serobot; sehat sebentar, lalu kembali menganggap sesak sebagai kewajaran. CFD seharusnya menjadi alat ukur dan pemantik debat public, kebijakan apa yang membuat udara bersih menjadi peristiwa langka?
Dari Jeda Menjadi SistemJika CFD serius dipahami sebagai kampanye lingkungan dan kualitas hidup, maka ia harus menuntut kelanjutan yang konkret. Bukan sekadar ajakan moral, tetapi desain kebijakan yang berani dan tentu saja memancing perdebatan, karena menyentuh kepentingan.
Pertama, penegakan emisi yang tidak basa-basi. Uji emisi tidak boleh menjadi formalitas musiman. Kendaraan yang tidak layak emisi harus benar-benar dibatasi ruang geraknya. Kalau sebuah kendaraan merusak kesehatan publik, itu bukan “urusan pribadi”. Itu sudah masuk wilayah mudarat sosial.
Kedua, perluasan ruang aman untuk berjalan kaki dan bersepeda, bukan jalur simbolik. Kota yang waras tentu memudahkan orang bergerak tanpa mesin. Jika warga dipaksa memilih antara “naik kendaraan” atau “berisiko di jalan”, maka kita sedang gagal sebagai perancang peradaban.
Ketiga, manajemen pembatasan kendaraan pribadi secara tegas, pembatasan parkir yang lebih rasional, pengendalian kendaraan di kawasan padat pada jam tertentu. Ini selalu kontroversial tetapi kota-kota besar yang serius mengejar kualitas hidup memang harus berani memprioritaskan kesehatan publik di atas kenyamanan segelintir orang.
Keempat, menguatkan transportasi publik sebagai bentuk keadilan ekologis. Jangan biarkan angkutan umum menjadi pilihan “terakhir”. Ia harus menjadi pilihan “terbaik”, terintegrasi, aman, nyaman, dan terjangkau. Jika tidak, CFD akan seperti khotbah tanpa tindak lanjut, indah didengar, miskin dalam implementasi.
Kelima, disiplin kebersihan dan pengendalian sampah dalam setiap ruang publik. CFD yang meninggalkan sampah adalah ironi yang memalukan. Kita mengaku mencintai bumi, tetapi meninggalkan kotoran di jalan. Inilah yang pertanyaan yang harus dijawab, apakah kita ingin kota yang “lancar untuk mobil”, atau kota yang “sehat untuk manusia”?
Green Sufisme: Udara, Tanah, dan Air Bukan Benda MatiGreen Sufisme mengajarkan sesuatu yang sederhana namun menggetarkan. Alam bukan semata panggung atau latar. Alam adalah sahabat spiritual. Udara, tanah, dan air bukan barang habis pakai. Mereka makhluk yang menunaikan tugasnya dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kita memperlakukannya. Al-Qur’an menampar dengan kalimat yang terlalu jelas untuk dibantah:
Ini bukan sekadar ayat untuk dibaca. Ini diagnosis. Kerusakan bukan misteri tapi akibat. Lalu ada peringatan yang lebih tajam:
Bumi “diperbaiki”, ditata, diseimbangkan, diberi ukuran. Kita datang, lalu mengacak-acaknya atas nama kemajuan. Bahkan dalam urusan konsumsi, Allah menyebut akar bencana dengan satu kata yang sering kita remehkan: israf (berlebihan).
Kita biasa mengaitkan israf dengan makanan. Padahal boros energi, boros BBM, boros perjalanan yang tidak perlu—itu juga israf. Dan israf selalu punya biaya: dibayar oleh udara yang kotor, dibayar oleh kesehatan publik, dibayar oleh generasi berikutnya. Lalu Allah menegakkan prinsip kosmik yang sering dilupakan para pembuat kebijakan: mizan—timbangan, keseimbangan.
Ketika keseimbangan dilanggar, bencana bukan “hukuman jatuh dari langit” semata. Ia juga konsekuensi dari batas yang kita tabrak sendiri.
Hadis Nabi mengancam sisi paling praktis dari hakikat iman; “Kebersihan adalah sebagian dari iman.” (HR. Muslim). Kalau iman hanya kuat di simbol, tetapi lemah di kebersihan udara, kebersihan air, kebersihan ruang public, maka yang rapuh bukan kota saja, melainkan cara kita beriman.
Bahkan Nabi kita mengingatkan; “Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Gangguan di jalan hari ini bukan hanya batu atau duri. Gangguan terbesar justru asap, kebisingan, perilaku berkendara yang membahayakan, dan sistem yang membuat jalan tak ramah bagi pejalan kaki.
Jika menyingkirkan duri saja sedekah, lalu bagaimana dengan menyingkirkan sebab-sebab sesak napas? Demikian pula ajaran Nabi yang menjadi fondasi etika public, “Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya.” (HR. Ibn Majah, juga diriwayatkan dalam banyak jalur). Polusi yang merusak kesehatan orang lain bukan “hak individu”. Itu bahaya yang wajib dihentikan.
PenutupCFD memberi kita optimisme bahwa Jakarta bisa lebih sehat, lebih hening, lebih sejuk, lebih manusiawi. Maka jangan biarkan ia menjadi sekadar foto Minggu pagi. Jika kita serius, CFD adalah pintu tobat social, tobat dari kebijakan yang memanjakan kendaraan pribadi, tobat dari gaya hidup yang boros energi, tobat dari cara beragama yang cuma rajin bicara surga tetapi abai menjaga bumi.
Kota yang mampu bernapas adalah kota yang memberi kesempatan warganya untuk hidup lebih panjang, lebih tenang, lebih waras. Dalam kacamata Green Sufisme, kota yang waras adalah kota yang kembali beradab kepada manusia, kepada alam, dan kepada Tuhan. Sehari bernapas itu indah. Tetapi lebih indah dan lebih wajib jika kita berani menjadikannya sebuah sistem. Karena kelak, kita bukan hanya ditanya berapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi juga amanah bumi ini kita kembalikan dalam keadaan seperti apa nantinya.