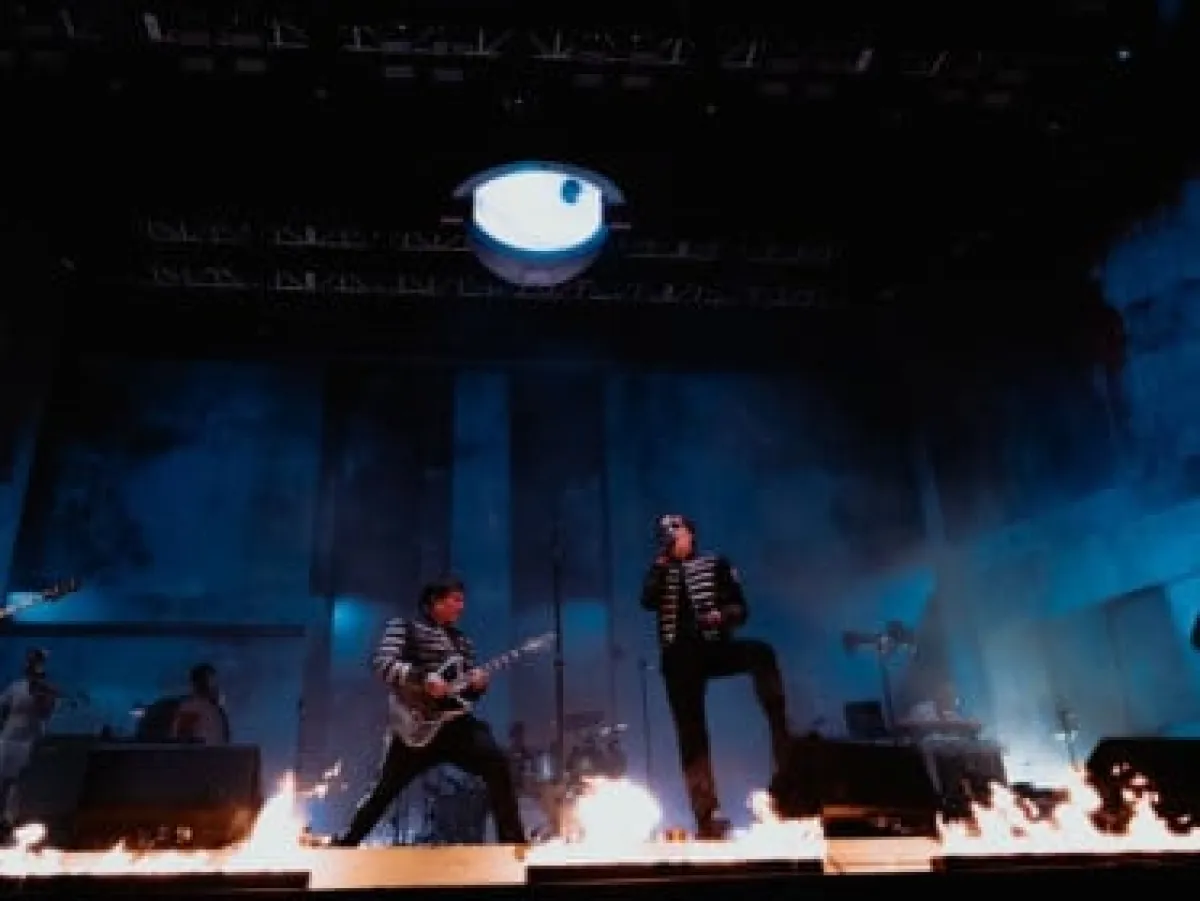Perempuan hari ini hidup di tengah paradoks. Di satu sisi, kita menyaksikan semakin banyak perempuan yang tampil sebagai pemimpin, akademisi, pekerja profesional, dan penggerak sosial. Namun di sisi lain, batas-batas tak kasatmata masih kokoh mengurung ruang gerak mereka. Batas itu bukan sekadar aturan tertulis atau kebijakan formal, melainkan nilai dan cara pandang yang diwariskan lintas generasi: patriarki. Sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kuasa dan otoritas, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang “seharusnya” menyesuaikan diri.
Patriarki sering kali bekerja secara halus, bahkan dianggap sebagai kewajaran. Ia hadir dalam kalimat sederhana seperti “perempuan sebaiknya di rumah saja”, “jangan terlalu ambisius”, atau “tugas utama perempuan adalah mengurus keluarga”. Kalimat-kalimat ini terdengar ringan, tetapi dampaknya berat: membatasi pilihan hidup perempuan, mengecilkan potensi mereka, dan mengukuhkan ketimpangan yang terus berulang. Artikel ini berpandangan tegas bahwa patriarki bukan sekadar persoalan budaya, melainkan masalah struktural yang nyata membatasi ruang perempuan—di rumah, di ruang publik, di dunia kerja, hingga dalam pengambilan keputusan politik.
Patriarki sebagai Sistem Sosial yang MengakarPatriarki bukan hanya tentang relasi personal antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah sistem sosial yang mengatur pembagian peran, akses terhadap sumber daya, dan legitimasi kekuasaan. Dalam sistem ini, maskulinitas sering diasosiasikan dengan kepemimpinan, rasionalitas, dan otoritas, sementara feminitas dilekatkan pada emosi, pengasuhan, dan ketergantungan. Pembagian ini tidak lahir secara alamiah, tetapi dibentuk melalui proses sosial, pendidikan, dan tradisi yang panjang.
Di Indonesia, patriarki berkelindan dengan adat, tafsir agama, serta praktik sosial sehari-hari. Sejak kecil, anak perempuan kerap diajarkan untuk “rapi”, “penurut”, dan “tidak banyak bicara”, sementara anak laki-laki didorong untuk berani, tegas, dan memimpin. Pola ini tampak sepele, tetapi membentuk kepercayaan diri dan aspirasi sejak dini. Ketika dewasa, perempuan yang vokal sering dicap agresif, sedangkan laki-laki dengan perilaku serupa justru dianggap tegas.
Ruang Domestik dan Beban Ganda PerempuanSalah satu dampak paling nyata dari patriarki adalah pengurungan perempuan di ruang domestik. Perempuan masih dianggap sebagai penanggung jawab utama urusan rumah tangga: memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, dan merawat anggota keluarga. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perempuan Indonesia menghabiskan waktu kerja tidak berbayar jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Beban ini sering kali tidak terlihat, tidak dihitung, dan tidak dihargai, padahal sangat menentukan keberlangsungan keluarga dan masyarakat.
Ketika perempuan juga bekerja di sektor publik, beban itu tidak berkurang. Mereka justru menghadapi beban ganda: bekerja untuk memperoleh penghasilan sekaligus tetap dituntut menjalankan peran domestik secara penuh. Dalam banyak kasus, kelelahan perempuan dianggap sebagai konsekuensi “kodrati”, bukan sebagai ketidakadilan struktural. Sementara itu, keterlibatan laki-laki dalam kerja domestik masih sering diposisikan sebagai bantuan, bukan tanggung jawab bersama.
Dunia Kerja dan Langit-Langit KacaPatriarki juga membatasi ruang perempuan di dunia kerja. Meski tingkat partisipasi kerja perempuan terus meningkat, kesenjangan masih nyata. Perempuan cenderung terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu yang dianggap “sesuai” dengan sifat feminin, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Di sisi lain, posisi pengambil keputusan dan jabatan strategis masih didominasi oleh laki-laki.
Fenomena glass ceiling atau langit-langit kaca menggambarkan batas tak terlihat yang menghambat perempuan mencapai posisi puncak, meskipun mereka memiliki kualifikasi dan kinerja yang setara. Selain itu, kesenjangan upah berbasis gender masih terjadi. Perempuan sering dibayar lebih rendah untuk pekerjaan yang sama nilainya, dengan alasan pengalaman, fleksibilitas, atau asumsi bahwa mereka bukan pencari nafkah utama.
Tak jarang, perempuan juga menghadapi diskriminasi terkait status reproduksi. Pertanyaan tentang rencana menikah atau memiliki anak masih kerap muncul dalam proses rekrutmen. Hal ini mencerminkan anggapan bahwa tubuh dan fungsi reproduksi perempuan adalah risiko bagi produktivitas, sebuah pandangan yang berakar kuat pada patriarki.
Kekerasan Berbasis Gender: Wajah Paling Kasar PatriarkiPembatasan ruang perempuan tidak hanya bersifat simbolik atau ekonomi, tetapi juga fisik. Kekerasan berbasis gender adalah manifestasi paling kasar dari patriarki. Data Komnas Perempuan menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan setiap tahun, baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, maupun kekerasan berbasis teknologi.
Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan. Cara berpakaian, jam keluar rumah, hingga aktivitas di media sosial dijadikan alasan untuk merasionalisasi kekerasan. Pola ini menunjukkan bagaimana patriarki bekerja: melindungi pelaku dan membungkam korban. Ketika perempuan merasa takut untuk melapor, ruang aman mereka semakin menyempit.
Representasi Perempuan dalam Politik dan Pengambilan KeputusanRuang perempuan juga terbatas dalam ranah politik dan pengambilan keputusan publik. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30 persen keterwakilan perempuan telah diterapkan, realitasnya partisipasi perempuan masih menghadapi banyak hambatan. Budaya politik yang maskulin, biaya politik yang tinggi, serta stereotip bahwa politik adalah dunia “keras” bagi perempuan menjadi penghalang serius.
Padahal, kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan bukan sekadar soal angka, melainkan perspektif. Perempuan membawa pengalaman dan sudut pandang yang berbeda, terutama terkait kebijakan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan. Ketika suara perempuan minim, kebijakan publik berisiko bias dan tidak inklusif.
Media dan Normalisasi PatriarkiMedia massa dan media sosial memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik. Sayangnya, patriarki kerap direproduksi melalui representasi perempuan yang stereotipikal. Perempuan lebih sering ditampilkan sebagai objek visual, pelengkap, atau figur emosional, sementara laki-laki diposisikan sebagai subjek utama dan pengambil keputusan.
Narasi semacam ini memperkuat anggapan bahwa nilai perempuan terletak pada penampilan dan peran domestik, bukan pada kapasitas intelektual atau kepemimpinan. Ketika media gagal menghadirkan representasi yang adil, pembatasan ruang perempuan semakin mengakar dalam kesadaran kolektif.
Patriarki Bukan Takdir BudayaPenting untuk ditegaskan bahwa patriarki bukanlah takdir budaya yang tidak bisa diubah. Sejarah menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan selalu mengalami perubahan seiring waktu. Banyak komunitas adat di Nusantara yang mengenal sistem kekerabatan matrilineal atau memberikan ruang kepemimpinan bagi perempuan. Artinya, ketimpangan gender bukan sesuatu yang alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial.
Perubahan juga sudah tampak hari ini. Gerakan perempuan, advokasi kesetaraan gender, serta peningkatan akses pendidikan telah membuka ruang-ruang baru. Namun, perubahan ini sering menghadapi resistensi, terutama ketika dianggap mengancam status quo. Di sinilah pentingnya kesadaran kolektif bahwa kesetaraan gender bukan tentang menggeser dominasi dari satu kelompok ke kelompok lain, melainkan tentang keadilan dan kemanusiaan.
Peran Laki-Laki dalam Membongkar PatriarkiMembongkar patriarki bukan hanya tugas perempuan. Laki-laki memiliki peran kunci sebagai bagian dari sistem yang diuntungkan. Kesadaran laki-laki untuk merefleksikan privilese, berbagi peran domestik, serta menolak stereotip maskulinitas yang toksik adalah langkah penting. Patriarki juga merugikan laki-laki dengan menekan mereka pada standar emosi dan peran yang sempit.
Ketika laki-laki terlibat sebagai sekutu, perubahan menjadi lebih mungkin. Kesetaraan gender bukan permainan menang-kalah, melainkan upaya bersama untuk menciptakan ruang hidup yang adil bagi semua.
Penutup: Membuka Ruang, Meruntuhkan BatasKetika patriarki membatasi ruang perempuan, yang sesungguhnya dirugikan bukan hanya perempuan, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Potensi, gagasan, dan kontribusi yang seharusnya memperkaya kehidupan bersama justru teredam oleh batas-batas yang tidak adil. Dari ruang domestik hingga ruang publik, dari dunia kerja hingga politik, patriarki bekerja membatasi pilihan dan suara perempuan.
Sudah saatnya kita berhenti menganggap ketimpangan sebagai kewajaran. Kesetaraan gender harus dipahami sebagai kebutuhan sosial, bukan tuntutan segelintir kelompok. Pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil memiliki peran masing-masing untuk membuka ruang yang setara. Di tingkat individu, refleksi dan perubahan sikap sehari-hari adalah langkah awal yang nyata.
Masa depan yang adil hanya mungkin terwujud ketika ruang perempuan tidak lagi dibatasi oleh konstruksi patriarki. Membuka ruang itu berarti meruntuhkan batas—batas dalam pikiran, dalam kebijakan, dan dalam praktik sosial. Dari sanalah masyarakat yang lebih inklusif dan manusiawi dapat tumbuh.