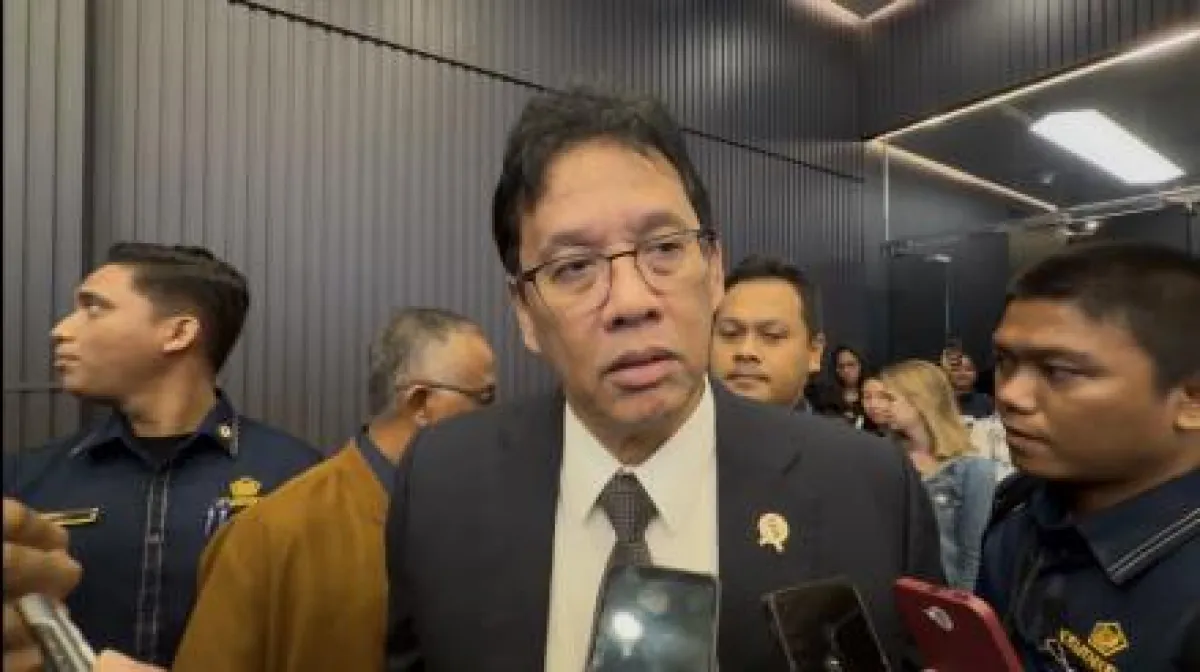Pada Kamis, 5 Februari lalu, BPS mengumumkan angka pertumbuhan triwulanan terakhir sekaligus rekapitulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025. Secara tahunan, ekonomi tumbuh sekitar 5,11%, sedikit di atas ekspektasi berbagai pihak—termasuk Bank Dunia—yang memproyeksikan di kisaran 5%.
Struktur PDB masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 54,5%, diikuti oleh investasi swasta di kisaran 30%, sementara sisanya disumbangkan oleh investasi pemerintah dan net ekspor.
Rilis tersebut juga menunjukkan bahwa tidak banyak perubahan pada komposisi mesin pertumbuhan dari sisi spasial. Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi PDB nasional sebesar 58,7%, di mana DKI Jakarta tetap menempati peringkat teratas dengan sumbangan sebesar 16,5%.
Kondisi ketimpangan ekonomi antarprovinsi memang cenderung menunjukkan pola yang stagnan. Tren Indeks Williamson di 34 provinsi pada dasawarsa terakhir hanya turun tipis: dari 0,767 pada tahun 2015 menjadi sekitar 0,755 pada tahun 2025.
Masalah ketimpangan ini terutama dipicu oleh rendahnya nilai tambah ekonomi di beberapa wilayah, khususnya di luar Pulau Jawa. Rendahnya nilai tambah tersebut dicirikan oleh dominasi sektor pertanian dalam struktur perekonomian wilayah-wilayah tersebut.
Secara nasional, proporsi sektor pertanian dalam PDB berada di angka 12-13%, tetapi rata-rata distribusi sektor ini di Sumatera mencapai 22% dan di Kawasan Timur Indonesia sekitar 21%. Hal ini berbanding terbalik dengan sebaran rata-rata sektor pertanian di Pulau Jawa dan Bali yang hanya sebesar 10%.
Dampak dari ketimpangan ini berpotensi meluas, mulai dari isu kemiskinan hingga kerentanan lingkungan. Kerentanan tersebut merupakan ancaman nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Fenomena backwash effect dan ketidakseimbangan spasial ini berisiko mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan secara permanen.
Pulau Jawa—yang memiliki luas geografis terbatas—akan mengalami titik jenuh karena menyerap sumber daya alam dan manusia dari wilayah lain secara masif. Sebaliknya, wilayah lain berisiko mengalami kerusakan karena sumber dayanya dikeruk dan ditinggalkan tanpa adanya pembangunan yang memadai di dalamnya. Dikarenakan ketimpangan ini berkaitan dengan persepsi tata kelola ekonomi, dibutuhkan pisau analisis dalam melihat akar ketimpangan ini.
Pertumbuhan dan Distribusi dalam Kacamata John RawlsDilema antara mengejar pertumbuhan dan mengatasi ketimpangan merupakan persoalan yang terus menjadi polemik di berbagai negara. Berangkat dari dilema ini, ancaman terhadap terjaganya ritme pembangunan keberlanjutan juga merupakan masalah dari macetnya proses distribusi tersebut, baik secara ruang maupun waktu. Maka, kata kunci keadilan antargenerasi kerap dilekatkan dengan isu pembangunan berkelanjutan.
Dalam magnum opus-nya yang berjudul A Theory of Justice, John Rawls mencoba menantang teori utilitarian, yang menjadi basis teori pertumbuhan, yang selama ini dianggap hegemonik, dan yang lazim ditulis dalam buku teks serta diajarkan oleh hampir seluruh ekonom di ruang-ruang kelas di seluruh dunia.
Karya ini terdiri dari tiga bagian: pembahasan mengenai keadilan secara teoretis, institusi-institusi yang memungkinkan penerapan konsepsi keadilan dalam struktur politik, dan tujuan penegakan keadilan dalam bentuk kebahagiaan maupun stabilitas sosial.
Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1971, di masa yang penuh dengan gejolak sosial, ekonomi, maupun politik, seperti memanasnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Komunis, gerakan sosial persamaan hak (yang dimotori antara lain oleh Martin Luther King Jr.), serta puncak perdebatan antara pendukung kapitalisme murni (pasar bebas) dan negara kesejahteraan (welfare state). Wajar jika buku itu laku keras di masanya.
Sebagaimana diketahui, konsep utilitas yang sering dibahas dalam buku teks biasanya diasumsikan sebagai ukuran kemanfaatan atau kepuasan yang dirasakan seseorang saat mengonsumsi barang atau jasa.
Teori utilitas umumnya digambarkan dalam bentuk kurva indiferen (indifferent curve) yang menunjukkan pola konsumsi atas dua jenis barang atau jasa. Hal ini dilakukan karena kepuasan atau kecenderungan konsumsi adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi bersifat abstrak.
Pembentukan kurva tersebut perlu memenuhi asumsi-asumsi berikut: Pertama, kurva merupakan kombinasi konsumsi antara dua barang/jasa pada masing-masing sumbu yang membentuk pola miring ke bawah (downward slope).
Artinya, setiap penambahan konsumsi satu barang akan mengurangi tingkat konsumsi barang lainnya. Diasumsikan bahwa setiap kombinasi dalam satu kurva yang sama akan memberikan tingkat kepuasan yang setara.
Kedua, kurva bersifat transitif, yang berarti semakin jauh kurva dari titik asal (origin), semakin tinggi pula tingkat utilitas dari kombinasi barang/jasa yang dikonsumsi. Ketiga, karena bersifat transitif, kurva pada tingkat utilitas yang berbeda tidak boleh saling berpotongan.
Dalam pembahasan lebih lanjut, teori utilitas ini biasanya dibenturkan dengan kondisi keterbatasan sumber daya atau anggaran untuk mencapai tingkat utilitas tertinggi. Oleh karena itu, penggunaan instrumen matematis menjadi sangat penting untuk menemukan posisi utilitas yang optimal atas kombinasi konsumsi di tengah batasan anggaran yang ada.
Pemanfaatan teori utilitas ini selanjutnya diterapkan secara luas dalam analisis dan perumusan kebijakan, mulai dari lingkup rumah tangga hingga tingkat negara. Bahkan, perumusan kebijakan mengenai keadilan itu sendiri sering kali menggunakan pendekatan utilitas.
Rawls menekankan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberikan kebebasan maksimal bagi individu, tetapi tetap menjaga agar distribusi sumber daya selalu memihak dan melindungi kelompok yang lemah. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan tingkat konsumsi pada jenis barang dalam kombinasi yang memiliki tingkat konsumsi terkecil.
Oleh karena itu, asumsi kurva indiferen yang digunakan tidak lagi berbentuk miring ke bawah (downward sloping), tetapi berbentuk huruf "L". Dalam bentuk ini, jika hanya salah satu barang dalam kombinasi yang ditingkatkan konsumsinya tanpa menambah konsumsi komponen lainnya, utilitas tetap tidak akan meningkat. Konsep ini dikenal sebagai Maximin (Maximize the Minimum).
Konsep Maximin ini tak berdiri sendiri. Terdapat asumsi dasar lain yang ajukan Rawls dalam membangun teori keadilan, meliputi penetapan posisi asal (Original Position) dan selubung ketidaktahuan (Veil of Ignorance), serta pengutamaan kebebasan dan kesetaraan. Intinya, teori itu mengarahkan agar setting institusi keadilan tersebut berangkat dari objektivitas yang benar-benar murni.
Konsep keadilan ini juga dapat diperluas ke dimensi yang menarik, yaitu keadilan antargenerasi. Perluasan asumsi veil of ignorance mengungkapkan bahwa dalam perspektif keadilan, generasi mendatang adalah kelompok rentan yang tingkat konsumsinya perlu dimaksimalisasi agar tingkat kepuasan agregat dapat dioptimalkan.
Untuk memaksimalisasi konsumsi generasi mendatang, diperlukan upaya "menabung" secara berkeadilan agar konsumsi mereka dapat berjalan berkelanjutan, alih-alih sumber dayanya dikuras habis oleh generasi saat ini.
Upaya menabung tersebut ditempuh melalui penyediaan institusi yang baik, penyediaan modal fisik (infrastruktur), pengembangan modal sosial (pendidikan), dan menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri.
Indikator Berbasis Konsumsi dan Keadilan AntargenerasiMasalah utama dari pembangunan berkualitas adalah penggunaan indikator jangka pendek untuk mengeklaim keberhasilan praktik administrasi suatu rezim politik, padahal keberhasilan tersebut seharusnya diukur dalam jangka panjang.
Dalam konteks pembangunan antargenerasi, klaim keberpihakan mungkin ditunjukkan melalui besaran anggaran urusan lingkungan hidup. Namun, fokus pada indikator jangka pendek ini kerap dibarengi dengan praktik intervensi anggaran yang masif dan tidak efisien, yang justru bertentangan dengan prinsip anggaran yang seharusnya bersifat stimulatif.
Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa indikator pertumbuhan umum—seperti PDB, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, atau alokasi anggaran lingkungan—tidak berguna.
Saya justru berseberangan dengan pihak-pihak yang antipati terhadap indikator tersebut karena hingga saat ini sarana pengukuran yang paling efisien adalah melalui indikator-indikator tersebut.
Di sinilah pengambil kebijakan dituntut berpihak pada posisi yang lemah. Jadi wajar ketika terjadi pengabaian, muncul kritik dari berbagai pihak yang merasa tidak diperlakukan secara adil.
Poin utamanya adalah apakah keberhasilan tersebut juga dievaluasi melalui indikator institusional lainnya yang tecermin dalam prioritas kebijakan, meskipun sekilas tampak tidak berhubungan dengan aspek keadilan antargenerasi.
Dalam konteks pembangunan berkualitas, ketimpangan adalah isu sentral yang kerap tenggelam oleh kebijakan parsial yang hanya memandang kesuksesan dari angka pertumbuhan.
Padahal, penurunan ketimpangan sangat erat kaitannya dengan pembangunan antargenerasi. Sayangnya, isu ini sering terabaikan karena perhatian yang berlebih pada indikator jangka pendek, meskipun keluhan atas masalah institusional tetap ada.
Mengutip data APINDO, biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi, yakni sekitar 14,29% dari PDB. Angka ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia (13%), Filipina dan India (masing-masing 13%), serta Singapura (8%).
Sementara itu, biaya energi nasional untuk industri juga sangat tinggi, yakni sekitar USD 0,099/kWh, atau 32% lebih mahal dibandingkan Vietnam (USD 0,075/kWh). Dari sisi pembiayaan, bunga pinjaman nasional yang mencapai 8-14% jauh melampaui rata-rata negara ASEAN-5 (4-6%).
Berbagai disinsentif ini pada akhirnya memperparah fenomena backwash effect dan ketimpangan, yang pada gilirannya mengganggu impian penciptaan keadilan antargenerasi.
Diperlukan kalibrasi kebijakan; dari yang sekadar mengejar target pertumbuhan tinggi secara agregat dan menyedot anggaran besar menjadi target penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya di luar Pulau Jawa.
Hal ini harus diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana dengan memperhatikan integrasi konektivitas domestik (khususnya wilayah non-Jawa) dan global yang terukur, simetris, dan afirmatif.
Penguatan desain dan tata kelola desentralisasi, serta otonomi daerah mutlak diperlukan untuk mengatasi rendahnya produktivitas di berbagai wilayah Indonesia.
Salah satu kelemahan desain perkotaan saat ini adalah masih terbatasnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memperhatikan risiko bencana tinggi di berbagai wilayah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan yang adil dan berkualitas dapat tercapai.