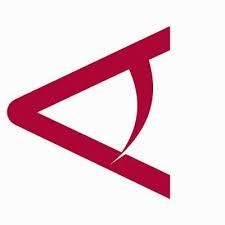Mataram (ANTARA) - Di pagi yang tenang di Teluk Ekas, Lombok Timur, hamparan tali-tali bentangan rumput laut membelah permukaan air yang jernih. Perahu-perahu kecil milik pembudidaya bergerak perlahan, memeriksa ikatan bibit yang digantung di bawah laut.
Pemandangan itu bukan hal baru bagi warga pesisir di Teluk Ekas. Namun, tahun ini ada babak baru yang sedang ditulis. Di teluk yang sama, pemerintah membangun pusat riset rumput laut bertaraf internasional, sebuah langkah yang berpotensi mengubah wajah ekonomi pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bahkan peta industri rumput laut dunia.
Indonesia membangun International Tropical Seaweed Research Center sebagai simpul kolaborasi global. Pilihannya jatuh pada Lombok Timur, wilayah yang selama ini hidup dari laut.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut Indonesia menguasai sekitar 75 persen pasar rumput laut tropis dunia.
Nilai ekonomi globalnya mencapai 12 miliar dolar AS per tahun dan terus tumbuh. Angka itu besar, tetapi ironi juga mengintai. Indonesia masih terlalu sering berhenti sebagai pemasok bahan mentah.
Di sinilah relevansi pusat riset tersebut. Ia tidak sekadar gedung laboratorium, melainkan simbol ambisi untuk naik kelas dari produsen ke inovator.
Paradoks pesisir
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi rumput laut NTB pada 2023 mencapai lebih dari 693 ribu ton dengan nilai sekitar Rp1,65 triliun. Pada 2024, produksi, bahkan tercatat 704.810 ton.
NTB masuk lima besar penghasil nasional. Kabupaten, seperti Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur, menjadi tulang punggung. Teluk Ekas sendiri sejak lama diproyeksikan sebagai sentra ekonomi biru.
Hanya saja, angka produksi yang tinggi belum otomatis menghadirkan kesejahteraan merata. Tantangan klasik masih membelit. Keterbatasan bibit unggul menjadi masalah mendasar.
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mengakui suplai bibit kultur jaringan masih sangat terbatas dan harus dibagi dengan wilayah lain, seperti Bali, NTT hingga Sulawesi. Di sisi lain, perubahan iklim memicu penyakit ice-ice dan menurunkan produksi 10 sampai 20 persen secara nasional.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan bibit tahan panas yang diprediksi mampu menghadapi kenaikan suhu 2 sampai 5 derajat Celcius.
Tetapi riset itu masih dalam skala laboratorium. Ada jarak antara inovasi dan implementasi di lapangan. Petani membutuhkan solusi cepat, bukan sekadar prototipe.
Masalah lain datang dari darat. Alih fungsi lahan pesisir meningkatkan erosi dan kekeruhan air laut. Di beberapa kawasan di Lombok, lokasi budi daya terpaksa dipindahkan karena kualitas perairan menurun.
Rumput laut sangat sensitif terhadap sedimen dan polutan. Tanpa tata ruang pesisir yang disiplin, produktivitas akan terus tergerus.
Paradoks ini memperlihatkan bahwa dominasi pasar global tidak cukup. Indonesia kuat di hulu, tetapi lemah di hilir dan rentan secara ekologis.
Motor inovasi
Kehadiran pusat riset di Teluk Ekas menawarkan peluang untuk memutus siklus tersebut. Dengan dukungan kolaborasi internasional, seperti University of California Berkeley dan Beijing Genomics Institute, serta pendanaan awal miliaran rupiah, pusat ini dirancang bukan sekadar tempat penelitian, tetapi sebagai laboratorium hidup.
Secara ekologis, Teluk Ekas memiliki arus dan sirkulasi air yang relatif baik. Ini ideal untuk uji produktivitas, ketahanan iklim, dan pengembangan biomassa tropis.
Tidak hanya Kappaphycus sebagai bahan baku karagenan, tetapi juga Caulerpa, Ulva, hingga Halymenia yang potensial untuk pangan, farmasi, dan bioplastik.
Di tingkat nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan fokus pada industri rumput laut sebagai bagian dari strategi nilai tambah. Pasar rumput laut nonhidrokoloid, seperti biostimulan dan pakan diproyeksikan mencapai 4,36 miliar dolar AS pada 2024 dan berpotensi melonjak hingga 12,85 miliar dolar AS pada 2034, menurut lembaga riset internasional. Bank Dunia, bahkan memproyeksikan pasar pakan berbasis rumput laut bisa mencapai 6,4 miliar dolar AS pada 2050.
Artinya, peluang hilirisasi terbuka lebar. Rumput laut tidak lagi sekadar bahan baku karagenan, tetapi bisa menjadi suplemen nutrisi, kosmetik, pupuk hayati, hingga kemasan ramah lingkungan. Jika pusat riset mampu menghubungkan laboratorium dengan industri, maka Ekas dapat menjadi episentrum ekonomi biru berbasis pengetahuan.
Hanya saja, riset tanpa ekosistem bisnis hanya akan berakhir sebagai laporan ilmiah. Tantangan terbesar adalah memastikan inovasi mengalir ke pembudidaya dan pelaku usaha mikro kecil menengah.
Kolaborasi dengan Universitas Mataram dan BRIN untuk pendampingan manajemen dan teknologi menjadi krusial. Riset harus menjawab kebutuhan konkret petani, mulai dari bibit unggul, teknik budi daya adaptif, hingga model pemasaran yang memutus mata rantai ijon.
Selain itu, tata kelola kawasan pesisir harus diperkuat. Pusat riset tidak boleh berdiri di tengah degradasi lingkungan. Pengendalian alih fungsi lahan, rehabilitasi pesisir, dan pengawasan kualitas air menjadi prasyarat. Tanpa itu, laboratorium terbaik pun akan kesulitan mencari sampel yang sehat.
Ada pula aspek sosial yang tidak boleh diabaikan. Industrialisasi sering kali memicu konsentrasi modal. Pemerintah daerah perlu memastikan kehadiran industri pengolahan dan investor tetap berpihak pada pembudidaya lokal.
Skema koperasi, kemitraan adil, dan pembiayaan inklusif perlu dirancang sejak awal. Jangan sampai pusat riset bertaraf dunia, justru memperlebar jurang kesejahteraan di kampung nelayan.
Ekonomi biru
Pembangunan pusat riset rumput laut di Teluk Ekas adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Ia selaras dengan visi transformasi ekonomi pesisir dan penguatan kedaulatan pangan laut.
Sejarah panjang pengembangan rumput laut di NTB sejak masuk dalam peta jalan nasional pada 2016 mengajarkan satu hal. Target produksi tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan dan keberlanjutan.
Kini, momentum baru telah tiba. Indonesia ingin menjadi pusat rumput laut dunia, bukan hanya dari sisi volume, tetapi inovasi. Untuk itu, tiga hal perlu dijaga.
Pertama, integrasi riset dan kebijakan. Hasil penelitian harus cepat diadopsi dalam program pembinaan dan perizinan. Kedua, keberlanjutan ekologis sebagai fondasi. Tanpa laut yang sehat, tidak ada industri yang bertahan. Ketiga, keadilan ekonomi bagi masyarakat pesisir sebagai pelaku utama.
Jika ketiganya berjalan beriringan, Teluk Ekas bukan hanya akan dikenal sebagai lokasi laboratorium internasional, tetapi sebagai contoh bagaimana ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kearifan lokal bersatu membangun kemandirian bangsa.
Di atas perairan yang tenang itu, masa depan sedang disemai bersama rumpun-rumpun rumput laut. Pertanyaannya, apakah kita mampu merawatnya hingga benar-benar berbuah nilai tambah bagi negeri.
Pemandangan itu bukan hal baru bagi warga pesisir di Teluk Ekas. Namun, tahun ini ada babak baru yang sedang ditulis. Di teluk yang sama, pemerintah membangun pusat riset rumput laut bertaraf internasional, sebuah langkah yang berpotensi mengubah wajah ekonomi pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bahkan peta industri rumput laut dunia.
Indonesia membangun International Tropical Seaweed Research Center sebagai simpul kolaborasi global. Pilihannya jatuh pada Lombok Timur, wilayah yang selama ini hidup dari laut.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut Indonesia menguasai sekitar 75 persen pasar rumput laut tropis dunia.
Nilai ekonomi globalnya mencapai 12 miliar dolar AS per tahun dan terus tumbuh. Angka itu besar, tetapi ironi juga mengintai. Indonesia masih terlalu sering berhenti sebagai pemasok bahan mentah.
Di sinilah relevansi pusat riset tersebut. Ia tidak sekadar gedung laboratorium, melainkan simbol ambisi untuk naik kelas dari produsen ke inovator.
Paradoks pesisir
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi rumput laut NTB pada 2023 mencapai lebih dari 693 ribu ton dengan nilai sekitar Rp1,65 triliun. Pada 2024, produksi, bahkan tercatat 704.810 ton.
NTB masuk lima besar penghasil nasional. Kabupaten, seperti Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur, menjadi tulang punggung. Teluk Ekas sendiri sejak lama diproyeksikan sebagai sentra ekonomi biru.
Hanya saja, angka produksi yang tinggi belum otomatis menghadirkan kesejahteraan merata. Tantangan klasik masih membelit. Keterbatasan bibit unggul menjadi masalah mendasar.
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mengakui suplai bibit kultur jaringan masih sangat terbatas dan harus dibagi dengan wilayah lain, seperti Bali, NTT hingga Sulawesi. Di sisi lain, perubahan iklim memicu penyakit ice-ice dan menurunkan produksi 10 sampai 20 persen secara nasional.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan bibit tahan panas yang diprediksi mampu menghadapi kenaikan suhu 2 sampai 5 derajat Celcius.
Tetapi riset itu masih dalam skala laboratorium. Ada jarak antara inovasi dan implementasi di lapangan. Petani membutuhkan solusi cepat, bukan sekadar prototipe.
Masalah lain datang dari darat. Alih fungsi lahan pesisir meningkatkan erosi dan kekeruhan air laut. Di beberapa kawasan di Lombok, lokasi budi daya terpaksa dipindahkan karena kualitas perairan menurun.
Rumput laut sangat sensitif terhadap sedimen dan polutan. Tanpa tata ruang pesisir yang disiplin, produktivitas akan terus tergerus.
Paradoks ini memperlihatkan bahwa dominasi pasar global tidak cukup. Indonesia kuat di hulu, tetapi lemah di hilir dan rentan secara ekologis.
Motor inovasi
Kehadiran pusat riset di Teluk Ekas menawarkan peluang untuk memutus siklus tersebut. Dengan dukungan kolaborasi internasional, seperti University of California Berkeley dan Beijing Genomics Institute, serta pendanaan awal miliaran rupiah, pusat ini dirancang bukan sekadar tempat penelitian, tetapi sebagai laboratorium hidup.
Secara ekologis, Teluk Ekas memiliki arus dan sirkulasi air yang relatif baik. Ini ideal untuk uji produktivitas, ketahanan iklim, dan pengembangan biomassa tropis.
Tidak hanya Kappaphycus sebagai bahan baku karagenan, tetapi juga Caulerpa, Ulva, hingga Halymenia yang potensial untuk pangan, farmasi, dan bioplastik.
Di tingkat nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan fokus pada industri rumput laut sebagai bagian dari strategi nilai tambah. Pasar rumput laut nonhidrokoloid, seperti biostimulan dan pakan diproyeksikan mencapai 4,36 miliar dolar AS pada 2024 dan berpotensi melonjak hingga 12,85 miliar dolar AS pada 2034, menurut lembaga riset internasional. Bank Dunia, bahkan memproyeksikan pasar pakan berbasis rumput laut bisa mencapai 6,4 miliar dolar AS pada 2050.
Artinya, peluang hilirisasi terbuka lebar. Rumput laut tidak lagi sekadar bahan baku karagenan, tetapi bisa menjadi suplemen nutrisi, kosmetik, pupuk hayati, hingga kemasan ramah lingkungan. Jika pusat riset mampu menghubungkan laboratorium dengan industri, maka Ekas dapat menjadi episentrum ekonomi biru berbasis pengetahuan.
Hanya saja, riset tanpa ekosistem bisnis hanya akan berakhir sebagai laporan ilmiah. Tantangan terbesar adalah memastikan inovasi mengalir ke pembudidaya dan pelaku usaha mikro kecil menengah.
Kolaborasi dengan Universitas Mataram dan BRIN untuk pendampingan manajemen dan teknologi menjadi krusial. Riset harus menjawab kebutuhan konkret petani, mulai dari bibit unggul, teknik budi daya adaptif, hingga model pemasaran yang memutus mata rantai ijon.
Selain itu, tata kelola kawasan pesisir harus diperkuat. Pusat riset tidak boleh berdiri di tengah degradasi lingkungan. Pengendalian alih fungsi lahan, rehabilitasi pesisir, dan pengawasan kualitas air menjadi prasyarat. Tanpa itu, laboratorium terbaik pun akan kesulitan mencari sampel yang sehat.
Ada pula aspek sosial yang tidak boleh diabaikan. Industrialisasi sering kali memicu konsentrasi modal. Pemerintah daerah perlu memastikan kehadiran industri pengolahan dan investor tetap berpihak pada pembudidaya lokal.
Skema koperasi, kemitraan adil, dan pembiayaan inklusif perlu dirancang sejak awal. Jangan sampai pusat riset bertaraf dunia, justru memperlebar jurang kesejahteraan di kampung nelayan.
Ekonomi biru
Pembangunan pusat riset rumput laut di Teluk Ekas adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Ia selaras dengan visi transformasi ekonomi pesisir dan penguatan kedaulatan pangan laut.
Sejarah panjang pengembangan rumput laut di NTB sejak masuk dalam peta jalan nasional pada 2016 mengajarkan satu hal. Target produksi tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan dan keberlanjutan.
Kini, momentum baru telah tiba. Indonesia ingin menjadi pusat rumput laut dunia, bukan hanya dari sisi volume, tetapi inovasi. Untuk itu, tiga hal perlu dijaga.
Pertama, integrasi riset dan kebijakan. Hasil penelitian harus cepat diadopsi dalam program pembinaan dan perizinan. Kedua, keberlanjutan ekologis sebagai fondasi. Tanpa laut yang sehat, tidak ada industri yang bertahan. Ketiga, keadilan ekonomi bagi masyarakat pesisir sebagai pelaku utama.
Jika ketiganya berjalan beriringan, Teluk Ekas bukan hanya akan dikenal sebagai lokasi laboratorium internasional, tetapi sebagai contoh bagaimana ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kearifan lokal bersatu membangun kemandirian bangsa.
Di atas perairan yang tenang itu, masa depan sedang disemai bersama rumpun-rumpun rumput laut. Pertanyaannya, apakah kita mampu merawatnya hingga benar-benar berbuah nilai tambah bagi negeri.