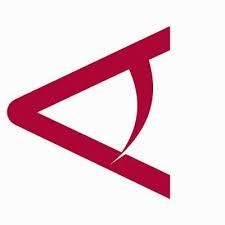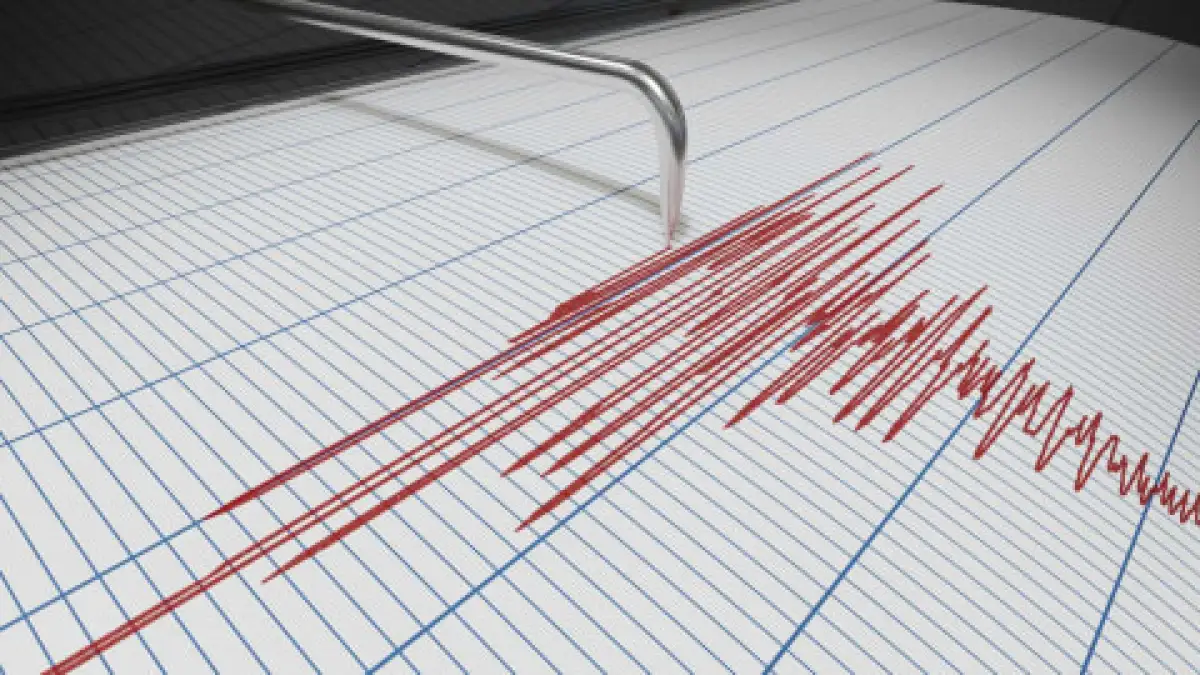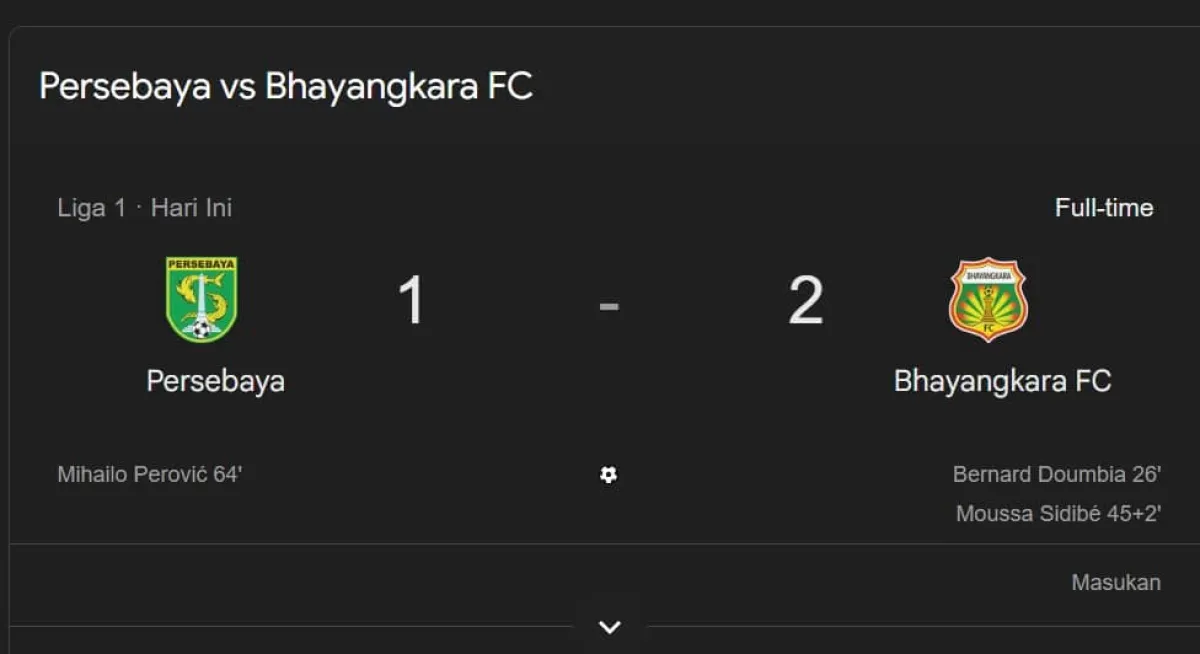Samarinda (ANTARA) - Tak akan ada habisnya jikalau hidup dibatasi pada pagar etnis yang memenjarakan kehidupan bersosial. Betapa kelam situasi bila menuruti ego etnosentris sebagaimana digambarkan secara mencekam dalam film garapan Joko Anwar "Pengepungan di Bukit Duri."
Seperti itulah kecamuk pikiran saat menyusuri Jalan Yos Sudarso, Samarinda, Kalimantan Timur, tepat di depan pelabuhan terbesar Kota Tepian. Kemudian langkah kaki ini menyusuri trotoar berbelok perlahan menuju kawasan Citra Niaga.
Di sini, memori kota seolah diputar ulang. Wali Kota Samarinda Andi Harun, belakangan sering mewacanakan revitalisasi kawasan ini menjadi Little Chinatown. Jauh sebelum Citra Niaga berdiri dengan segala riuh perniagaan, kawasan ini adalah denyut Pecinan Samarinda.
Di sudut lain, tak jauh dari sana, aroma hio menyeruak lembut, menembus udara kota. Kelenteng Thien Le Khong berdiri tegak. Warna merah dan emasnya yang mencolok bukan simbol dominasi, melainkan napas harmoni.
Itu adalah sebuah monumen hidup yang merekam bagaimana etnis Tionghoa dan penduduk lokal, yang mayoritas Banjar, Kutai, dan Bugis, hidup berdampingan tanpa sekat curiga selama berabad-abad.
Di Samarinda, kelenteng tidak perlu bersembunyi di gang sempit. Ia berdiri kokoh di pusat keramaian pada jalan protokol, menjadi bagian integral dari lanskap kota yang majemuk.
“Ketika membahas perihal Tionghoa di Indonesia, ingatan publik nyaris selalu tertuju pada sejarah isu rasialisme,” ujar Muhammad Sarip, sejarawan Kalimantan Timur, membuka percakapan. Pewarta ANTARA menemuinya untuk menggali lebih dalam tentang lapisan sosiologis yang membentuk karakter toleran di Benua Etam.
Sarip menuturkan bahwa sejarah, setragis apa pun peristiwanya, tidak bisa dihapus dalam catatan dan memori kolektif publik.
“Meskipun begitu,” lanjutnya, “memelihara ingatan sejarah memang penting. Tujuannya bukan untuk larut dalam meratapi masa lalu, tapi sebagai sarana introspeksi bagi semua elemen bangsa untuk tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama.”
Sebagaimana digambarkan dalam film "Pengepungan di Bukit Duri", ingatan bangsa ini memang punya luka menganga bernama Mei 1998. Di Jakarta, Solo, dan kota-kota besar di Jawa, etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Toko dijarah, bangunan dibakar, dan martabat manusia direndahkan dalam kekerasan seksual yang memilukan.
Bersyukur, di Kalimantan Timur, itu tak terjadi. Sarip lantas menunjukkan sebuah anomali yang menyejukkan dalam harmoni daerah yang bermajemuk. “Di Samarinda dan kota lainnya di Kalimantan Timur, saat itu warga Tionghoa dengan segala propertinya relatif aman. Tidak tersentuh aksi destruktif,” kata dia.
Fakta sejarah mencatat, di Kaltim pada Mei 1998, tidak ada penjarahan massal. Tidak ada asap hitam membubung dari toko milik Tionghoa. Dan yang paling krusial, tidak ada dugaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa di Samarinda maupun Balikpapan, dua kota metropolis Benua Etam.
“Sejarah panjang relasi penduduk di Samarinda lintas etnis berlangsung dalam suasana yang toleran dan kooperatif,” kata Sarip. Potensi konflik tentu ada, sebagaimana lumrahnya interaksi manusia, namun isu kompetitif di Kaltim tidak pernah berpretensi menjadi chaos berbasis rasial.
Dari Lo A Po
Kembali lagi ke masa silam, sebelum republik ini berdiri, benih toleransi itu sudah disemai lewat relasi bisnis dan darah. Sarip mengajak untuk menengok era Hindia Belanda.
Di masa itu, tokoh Tionghoa bernama Lo A Po sukses mengoperasikan penambangan batu bara di Loa Bukit. Menariknya, lahan itu disewa langsung dari kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara. Hubungan mereka melampaui sekadar kontrak bisnis.
“Jalinan politik dan kultural juga diperkuat melalui ikatan pernikahan antara anggota keluarga Lo A Po dengan kerabat Sultan Kutai,” ungkap Sarip.
Akulturasi ini meninggalkan sebuah monumen yang awet hingga kini. Sebuah rumah antik di kawasan tepian Samarinda, tepatnya di Jalan Yos Sudarso, masih berdiri meski digerus zaman. Dikenal sebagai Villa Annie, rumah dengan arsitektur klasik ini adalah warisan keluarga Lo A Po yang bertahan lebih dari satu abad, menjadi saksi bisu kemesraan hubungan Tionghoa dan aristokrat lokal.
Akan tetapi, kolonialisme tetaplah kolonialisme. Belanda menerapkan stratifikasi sosial yang segregatif. Etnis Tionghoa ditempatkan di lokasi paling strategis, yakni kawasan pelabuhan, sementara warga lokal diposisikan di lapis kedua. Ini adalah devide et impera yang sering memicu kecemburuan sosial.
Di sinilah letak kedewasaan warga lokal Samarinda. “Warga lokal menyikapinya tidak dengan jalan kekerasan,” kata Sarip menekankan.
Orang-orang Banjar, alih-alih membakar toko pesaing, justru membentuk kongsi dagang tandingan. Mereka mendirikan Handel-maatschaappij Borneo Samarinda (HBS). Perusahaan kolektif ini menjadi cikal bakal Kampung HBS, yang di kemudian hari bertransformasi menjadi pusat ekonomi kerakyatan, yakni saat ini dikenal Pasar Pagi.
Secara trivia, Sarip mengingatkan pada figur yang akrab di telinga publik. “Jika publik masa kini mengenal nama Reino Barack sebagai suami artis Syahrini, dia adalah cucu dari Omar Barack," kata Sarip. Omar adalah satu dari beberapa pendiri Kampung HBS zaman kolonial itu. Kompetisi terjadi, tapi bak koridor dagang yang ksatria, bukan di jalanan dengan parang.
Paguyuban Guang Dong di Samarinda yang masih aktif dari era kolonial hingga kini, sebuah dokumentasi sebagai bukti bahwa etnis Tionghoa memiliki peran yang tidak kalah penting dalam sejarah perkembangan Kota Tepian di Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Dok Erwin Lee. Harmoni itu berlanjut ke masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949). Tionghoa di Samarinda tidak duduk diam di balik meja kasir, mereka turun ke gelanggang perjuangan.
Sarip menyebut nama Tan Tjong Tjioe. Sosok ini berkontribusi besar sebagai relawan palang merah. Dedikasinya begitu panjang hingga ia menjabat sebagai Ketua PMI Cabang Samarinda (1951–1975) dan Ketua PMI Kaltim (1975–1986). Kepemimpinan terlama seorang Tionghoa di lembaga kemanusiaan Kaltim.
Dalam bidang pendidikan, ada nama Dorinawati Samalo. Pada tahun 1962, ketika Provinsi Kaltim haus akan institusi pendidikan tinggi, Dorinawati menghibahkan rumahnya yang besar di Jalan Flores. Rumah itulah yang menjadi kampus pertama Universitas Mulawarman, universitas negeri kebanggaan Kaltim.
Namun, contoh paling telak tentang cairnya hubungan antar-etnis di Kaltim ada di panggung politik. Sarip menyebutnya sebagai "anomali" yang bahkan sulit ditemukan di era Reformasi saat ini.
Tan Tjong Tjioe dipercaya menjadi utusan Kaltim di Konstituante, lembaga penyusun Undang-Undang Dasar hasil Pemilu 1955. Yang mengejutkan, Tan Tjong Tjioe tidak diusung oleh partai Tionghoa (Baperki). Dia diusung oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang saat itu didominasi oleh orang-orang Banjar dan Kutai.
Fakta ini adalah tamparan keras bagi narasi rasisme. Seorang Tionghoa, dipilih oleh partai nasionalis yang berisi pribumi, untuk mewakili daerah dalam menyusun konstitusi negara. “Hal ini menunjukkan sentimen rasisme tidak berlaku dalam kultur politik Kaltim masa silam,” kata Sarip.
Gabin lido dan kue keminting
Lantas, kapan sentimen rasial mulai meracuni udara? Sarip menunjuk periode 1960-an sebagai titik balik, terutama saat rezim Orde Baru naik takhta.
“Rezim Soeharto menuduh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara komunis yang terlibat Gerakan 30 September 1965,” kata Sarip. Tuduhan ini menjadi stigma massal. Masyarakat Tionghoa dianggap suporter komunisme, dieliminasi dari kehidupan sosial, budaya, dan politik. Istilah Tionghoa diganti paksa menjadi China yang berkonotasi penghinaan.
Tetapi, di akar rumput Samarinda, propaganda Jakarta tidak sepenuhnya mampu merusak tatanan sosial yang sudah mengakar. Ada satu contoh sederhana sarat filosofis yang diungkapkan Sarip. Contoh ini bukan tentang politik tingkat tinggi, melainkan tentang perut dan rasa, meramu dalam kue keminting dan gabin lido.
Kue keminting adalah camilan tradisional khas Samarinda, berbentuk kecil mirip kemiri (keminting dalam bahasa Banjar), berbahan dasar tepung sagu atau tapioka. Teksturnya keras di luar, namun lumer di mulut.
Kenampakan gabin lido (kiri) dan kue keminting (kanan). ANTARA/Ahmad Rifandi. Kue ini diproduksi massal oleh warga Banjar di kawasan Sungai Karang Mumus. Di dapur-dapur rumah panggung pinggir sungai, ibu-ibu Banjar mengolah adonan ini setiap hari.
Uniknya, kue-kue ini tidak dijual sendiri-sendiri. Kue keminting didrop secara curah tanpa merek ke sebuah toko legendaris milik warga Tionghoa di tepian Mahakam. Toko itu bernama Gabin Lido. Toko ini sejatinya terkenal karena produksi biskuit gabin-nya sendiri.
“Jadilah toko tersebut berperan signifikan sebagai distributor utama kue keminting ke seluruh pelosok,” ujar Sarip.
Di sini terjadi simbiosis yang indah. Produsen muslim Banjar percaya penuh kepada pedagang Tionghoa untuk memasarkan produk mereka. Sebaliknya, Toko Gabin Lido tidak merasa perlu melakukan rebranding atau mengklaim resep. Mereka menjadi etalase bagi karya kuliner tetangga mereka. Orang Samarinda tahu cari keminting enak, ya ke toko Cina Gabin Lido.
Di balik renyahnya kue keminting dan manisnya biskuit gabin, terselip rasa saling percaya yang tidak bisa diruntuhkan oleh propaganda politik sekalipun.
Bunga mei dan jeruk kingkit
Bagi masyarakat umum, perayaan Tahun Baru Imlek mungkin identik dengan kemeriahan barongsai, warna merah yang menyala, dan tentu saja, amplop angpao. Tapi bagi generasi tua Tionghoa di Samarinda, Kalimantan Timur, esensi Imlek tersembunyi dalam diamnya dua tanaman yang wajib hadir di ruang tamu mereka, tiada lain bunga mei (méihuā) dan tanaman jeruk (jīnjú atau jeruk kingkit).
Bagi mereka, kedua tanaman ini bukan sekadar dekorasi. Itu penanda musim, simbol harapan, sekaligus sebuah identitas budaya dipertahankan melintasi rezim yang pernah tidak bersahabat.
Fransisca Haryanto dan Elisa Christiana dalam risetnya di Jurnal Century (2016) bertajuk Pandangan Tionghoa Generasi Tua Samarinda Terhadap Makna Bunga Mei dan Tanaman Jeruk Pada Perayaan Imlek merekam bagaimana para sepuh berusia di atas 65 tahun di Kota Tepian ini memaknai tradisi tersebut.
Sejarah mencatat bahwa etnis Tionghoa di Indonesia pernah melewati masa-masa sulit, terutama di era Orde Baru. Kala itu, segala hal yang berbau kebudayaan dan tradisi Tiongkok dilarang dipertontonkan di ruang publik. Namun, pelarangan itu tidak serta-merta mematikan tradisi di dalam rumah.
Tiga narasumber generasi tua di Samarinda; Hendra, Hermawan, dan Karmila, mengingat masa-masa itu dengan perasaan campur aduk. Meski ada rasa takut, mereka tidak berhenti memajang bunga mei dan pohon jeruk saat Imlek tiba. Strateginya adalah "domestikasi" tradisi: mereka merayakannya secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah, jauh dari pandangan umum.
Menariknya, ada persepsi di kalangan narasumber ini bahwa tekanan politik di Kalimantan kala itu tidak seberat yang dirasakan saudara-saudara mereka di Pulau Jawa. Namun, alasan utama mereka tetap bertahan bukan sekadar karena longgarnya pengawasan, melainkan ketakutan akan hilangnya identitas. Bagi mereka, membuang tradisi sama dengan menghilangkan identitas mereka sebagai orang Tionghoa.
Lantas, mengapa harus bunga mei dan jeruk? Jawabannya terletak pada filosofi alam dan permainan linguistik.
Para orang tua di Samarinda memahami bunga mei sebagai simbol musim semi, kebahagiaan, dan kekuatan. Bunga ini memiliki karakteristik. Ia mekar pertama kali saat musim dingin yang berat, di saat tanaman lain layu atau mati. Kehadirannya menjadi pertanda bahwa musim dingin yang beku akan segera berakhir dan musim semi yang hangat akan tiba.
Dalam konteks kehidupan diaspora Tionghoa yang kerap menghadapi tantangan, bunga mei menjadi metafora yang sempurna. Ia melambangkan keteguhan, kemuliaan, dan semangat untuk tidak mudah menyerah di tengah kesulitan.
Sementara itu, tanaman jeruk atau jīnjú (jeruk kingkit) dipilih karena alasan yang lebih pragmatis. Dalam bahasa Mandarin, pelafalan jeruk (jú) terdengar sangat mirip dengan kata jí, yang berarti mujur atau untung.
Seorang warga bernama A Lie melakukan sembahyang di Kelenteng Thien Le Khong, Jalan Yos Sudarso, Samarinda. ANTARA/Ahmad Rifandi. Matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya jingga di Sungai Mahakam. Dari narasi panjang sejarah yang diceritakan ada kenyataan bahwa kedamaian di Kaltim bukanlah sebuah kebetulan.
Samarinda, sebagai ibu kota Kalimantan Timur, telah memberikan keteladanan. Pola interaksi warganya yang multi-etnik berjalan egaliter, toleran, dan konsisten menjaga kerukunan. Kota ini, dengan segala dinamikanya, tetap nol dari kasus konflik kekerasan berbasis isu SARA.
Revitalisasi Pecinan atau Little Chinatown nanti mungkin akan mengubah wajah fisik kota. Namun, roh persaudaraan yang terjalin antara pembuat kue keminting di Karang Mumus dan penjaga toko Gabin Lido di tepian Mahakam, adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada sekadar bangunan gapura ala pagoda atau lampion merah.
Itu adalah warisan tentang bagaimana menjadi manusia yang memanusiakan sesama, tanpa peduli dari mana nenek moyang mereka berasal.
Seperti itulah kecamuk pikiran saat menyusuri Jalan Yos Sudarso, Samarinda, Kalimantan Timur, tepat di depan pelabuhan terbesar Kota Tepian. Kemudian langkah kaki ini menyusuri trotoar berbelok perlahan menuju kawasan Citra Niaga.
Di sini, memori kota seolah diputar ulang. Wali Kota Samarinda Andi Harun, belakangan sering mewacanakan revitalisasi kawasan ini menjadi Little Chinatown. Jauh sebelum Citra Niaga berdiri dengan segala riuh perniagaan, kawasan ini adalah denyut Pecinan Samarinda.
Di sudut lain, tak jauh dari sana, aroma hio menyeruak lembut, menembus udara kota. Kelenteng Thien Le Khong berdiri tegak. Warna merah dan emasnya yang mencolok bukan simbol dominasi, melainkan napas harmoni.
Itu adalah sebuah monumen hidup yang merekam bagaimana etnis Tionghoa dan penduduk lokal, yang mayoritas Banjar, Kutai, dan Bugis, hidup berdampingan tanpa sekat curiga selama berabad-abad.
Di Samarinda, kelenteng tidak perlu bersembunyi di gang sempit. Ia berdiri kokoh di pusat keramaian pada jalan protokol, menjadi bagian integral dari lanskap kota yang majemuk.
“Ketika membahas perihal Tionghoa di Indonesia, ingatan publik nyaris selalu tertuju pada sejarah isu rasialisme,” ujar Muhammad Sarip, sejarawan Kalimantan Timur, membuka percakapan. Pewarta ANTARA menemuinya untuk menggali lebih dalam tentang lapisan sosiologis yang membentuk karakter toleran di Benua Etam.
Sarip menuturkan bahwa sejarah, setragis apa pun peristiwanya, tidak bisa dihapus dalam catatan dan memori kolektif publik.
“Meskipun begitu,” lanjutnya, “memelihara ingatan sejarah memang penting. Tujuannya bukan untuk larut dalam meratapi masa lalu, tapi sebagai sarana introspeksi bagi semua elemen bangsa untuk tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama.”
Sebagaimana digambarkan dalam film "Pengepungan di Bukit Duri", ingatan bangsa ini memang punya luka menganga bernama Mei 1998. Di Jakarta, Solo, dan kota-kota besar di Jawa, etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Toko dijarah, bangunan dibakar, dan martabat manusia direndahkan dalam kekerasan seksual yang memilukan.
Bersyukur, di Kalimantan Timur, itu tak terjadi. Sarip lantas menunjukkan sebuah anomali yang menyejukkan dalam harmoni daerah yang bermajemuk. “Di Samarinda dan kota lainnya di Kalimantan Timur, saat itu warga Tionghoa dengan segala propertinya relatif aman. Tidak tersentuh aksi destruktif,” kata dia.
Fakta sejarah mencatat, di Kaltim pada Mei 1998, tidak ada penjarahan massal. Tidak ada asap hitam membubung dari toko milik Tionghoa. Dan yang paling krusial, tidak ada dugaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa di Samarinda maupun Balikpapan, dua kota metropolis Benua Etam.
“Sejarah panjang relasi penduduk di Samarinda lintas etnis berlangsung dalam suasana yang toleran dan kooperatif,” kata Sarip. Potensi konflik tentu ada, sebagaimana lumrahnya interaksi manusia, namun isu kompetitif di Kaltim tidak pernah berpretensi menjadi chaos berbasis rasial.
Dari Lo A Po
Kembali lagi ke masa silam, sebelum republik ini berdiri, benih toleransi itu sudah disemai lewat relasi bisnis dan darah. Sarip mengajak untuk menengok era Hindia Belanda.
Di masa itu, tokoh Tionghoa bernama Lo A Po sukses mengoperasikan penambangan batu bara di Loa Bukit. Menariknya, lahan itu disewa langsung dari kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara. Hubungan mereka melampaui sekadar kontrak bisnis.
“Jalinan politik dan kultural juga diperkuat melalui ikatan pernikahan antara anggota keluarga Lo A Po dengan kerabat Sultan Kutai,” ungkap Sarip.
Akulturasi ini meninggalkan sebuah monumen yang awet hingga kini. Sebuah rumah antik di kawasan tepian Samarinda, tepatnya di Jalan Yos Sudarso, masih berdiri meski digerus zaman. Dikenal sebagai Villa Annie, rumah dengan arsitektur klasik ini adalah warisan keluarga Lo A Po yang bertahan lebih dari satu abad, menjadi saksi bisu kemesraan hubungan Tionghoa dan aristokrat lokal.
Akan tetapi, kolonialisme tetaplah kolonialisme. Belanda menerapkan stratifikasi sosial yang segregatif. Etnis Tionghoa ditempatkan di lokasi paling strategis, yakni kawasan pelabuhan, sementara warga lokal diposisikan di lapis kedua. Ini adalah devide et impera yang sering memicu kecemburuan sosial.
Di sinilah letak kedewasaan warga lokal Samarinda. “Warga lokal menyikapinya tidak dengan jalan kekerasan,” kata Sarip menekankan.
Orang-orang Banjar, alih-alih membakar toko pesaing, justru membentuk kongsi dagang tandingan. Mereka mendirikan Handel-maatschaappij Borneo Samarinda (HBS). Perusahaan kolektif ini menjadi cikal bakal Kampung HBS, yang di kemudian hari bertransformasi menjadi pusat ekonomi kerakyatan, yakni saat ini dikenal Pasar Pagi.
Secara trivia, Sarip mengingatkan pada figur yang akrab di telinga publik. “Jika publik masa kini mengenal nama Reino Barack sebagai suami artis Syahrini, dia adalah cucu dari Omar Barack," kata Sarip. Omar adalah satu dari beberapa pendiri Kampung HBS zaman kolonial itu. Kompetisi terjadi, tapi bak koridor dagang yang ksatria, bukan di jalanan dengan parang.
Paguyuban Guang Dong di Samarinda yang masih aktif dari era kolonial hingga kini, sebuah dokumentasi sebagai bukti bahwa etnis Tionghoa memiliki peran yang tidak kalah penting dalam sejarah perkembangan Kota Tepian di Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Dok Erwin Lee. Harmoni itu berlanjut ke masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949). Tionghoa di Samarinda tidak duduk diam di balik meja kasir, mereka turun ke gelanggang perjuangan.
Sarip menyebut nama Tan Tjong Tjioe. Sosok ini berkontribusi besar sebagai relawan palang merah. Dedikasinya begitu panjang hingga ia menjabat sebagai Ketua PMI Cabang Samarinda (1951–1975) dan Ketua PMI Kaltim (1975–1986). Kepemimpinan terlama seorang Tionghoa di lembaga kemanusiaan Kaltim.
Dalam bidang pendidikan, ada nama Dorinawati Samalo. Pada tahun 1962, ketika Provinsi Kaltim haus akan institusi pendidikan tinggi, Dorinawati menghibahkan rumahnya yang besar di Jalan Flores. Rumah itulah yang menjadi kampus pertama Universitas Mulawarman, universitas negeri kebanggaan Kaltim.
Namun, contoh paling telak tentang cairnya hubungan antar-etnis di Kaltim ada di panggung politik. Sarip menyebutnya sebagai "anomali" yang bahkan sulit ditemukan di era Reformasi saat ini.
Tan Tjong Tjioe dipercaya menjadi utusan Kaltim di Konstituante, lembaga penyusun Undang-Undang Dasar hasil Pemilu 1955. Yang mengejutkan, Tan Tjong Tjioe tidak diusung oleh partai Tionghoa (Baperki). Dia diusung oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), partai yang saat itu didominasi oleh orang-orang Banjar dan Kutai.
Fakta ini adalah tamparan keras bagi narasi rasisme. Seorang Tionghoa, dipilih oleh partai nasionalis yang berisi pribumi, untuk mewakili daerah dalam menyusun konstitusi negara. “Hal ini menunjukkan sentimen rasisme tidak berlaku dalam kultur politik Kaltim masa silam,” kata Sarip.
Gabin lido dan kue keminting
Lantas, kapan sentimen rasial mulai meracuni udara? Sarip menunjuk periode 1960-an sebagai titik balik, terutama saat rezim Orde Baru naik takhta.
“Rezim Soeharto menuduh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara komunis yang terlibat Gerakan 30 September 1965,” kata Sarip. Tuduhan ini menjadi stigma massal. Masyarakat Tionghoa dianggap suporter komunisme, dieliminasi dari kehidupan sosial, budaya, dan politik. Istilah Tionghoa diganti paksa menjadi China yang berkonotasi penghinaan.
Tetapi, di akar rumput Samarinda, propaganda Jakarta tidak sepenuhnya mampu merusak tatanan sosial yang sudah mengakar. Ada satu contoh sederhana sarat filosofis yang diungkapkan Sarip. Contoh ini bukan tentang politik tingkat tinggi, melainkan tentang perut dan rasa, meramu dalam kue keminting dan gabin lido.
Kue keminting adalah camilan tradisional khas Samarinda, berbentuk kecil mirip kemiri (keminting dalam bahasa Banjar), berbahan dasar tepung sagu atau tapioka. Teksturnya keras di luar, namun lumer di mulut.
Kenampakan gabin lido (kiri) dan kue keminting (kanan). ANTARA/Ahmad Rifandi. Kue ini diproduksi massal oleh warga Banjar di kawasan Sungai Karang Mumus. Di dapur-dapur rumah panggung pinggir sungai, ibu-ibu Banjar mengolah adonan ini setiap hari.
Uniknya, kue-kue ini tidak dijual sendiri-sendiri. Kue keminting didrop secara curah tanpa merek ke sebuah toko legendaris milik warga Tionghoa di tepian Mahakam. Toko itu bernama Gabin Lido. Toko ini sejatinya terkenal karena produksi biskuit gabin-nya sendiri.
“Jadilah toko tersebut berperan signifikan sebagai distributor utama kue keminting ke seluruh pelosok,” ujar Sarip.
Di sini terjadi simbiosis yang indah. Produsen muslim Banjar percaya penuh kepada pedagang Tionghoa untuk memasarkan produk mereka. Sebaliknya, Toko Gabin Lido tidak merasa perlu melakukan rebranding atau mengklaim resep. Mereka menjadi etalase bagi karya kuliner tetangga mereka. Orang Samarinda tahu cari keminting enak, ya ke toko Cina Gabin Lido.
Di balik renyahnya kue keminting dan manisnya biskuit gabin, terselip rasa saling percaya yang tidak bisa diruntuhkan oleh propaganda politik sekalipun.
Bunga mei dan jeruk kingkit
Bagi masyarakat umum, perayaan Tahun Baru Imlek mungkin identik dengan kemeriahan barongsai, warna merah yang menyala, dan tentu saja, amplop angpao. Tapi bagi generasi tua Tionghoa di Samarinda, Kalimantan Timur, esensi Imlek tersembunyi dalam diamnya dua tanaman yang wajib hadir di ruang tamu mereka, tiada lain bunga mei (méihuā) dan tanaman jeruk (jīnjú atau jeruk kingkit).
Bagi mereka, kedua tanaman ini bukan sekadar dekorasi. Itu penanda musim, simbol harapan, sekaligus sebuah identitas budaya dipertahankan melintasi rezim yang pernah tidak bersahabat.
Fransisca Haryanto dan Elisa Christiana dalam risetnya di Jurnal Century (2016) bertajuk Pandangan Tionghoa Generasi Tua Samarinda Terhadap Makna Bunga Mei dan Tanaman Jeruk Pada Perayaan Imlek merekam bagaimana para sepuh berusia di atas 65 tahun di Kota Tepian ini memaknai tradisi tersebut.
Sejarah mencatat bahwa etnis Tionghoa di Indonesia pernah melewati masa-masa sulit, terutama di era Orde Baru. Kala itu, segala hal yang berbau kebudayaan dan tradisi Tiongkok dilarang dipertontonkan di ruang publik. Namun, pelarangan itu tidak serta-merta mematikan tradisi di dalam rumah.
Tiga narasumber generasi tua di Samarinda; Hendra, Hermawan, dan Karmila, mengingat masa-masa itu dengan perasaan campur aduk. Meski ada rasa takut, mereka tidak berhenti memajang bunga mei dan pohon jeruk saat Imlek tiba. Strateginya adalah "domestikasi" tradisi: mereka merayakannya secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah, jauh dari pandangan umum.
Menariknya, ada persepsi di kalangan narasumber ini bahwa tekanan politik di Kalimantan kala itu tidak seberat yang dirasakan saudara-saudara mereka di Pulau Jawa. Namun, alasan utama mereka tetap bertahan bukan sekadar karena longgarnya pengawasan, melainkan ketakutan akan hilangnya identitas. Bagi mereka, membuang tradisi sama dengan menghilangkan identitas mereka sebagai orang Tionghoa.
Lantas, mengapa harus bunga mei dan jeruk? Jawabannya terletak pada filosofi alam dan permainan linguistik.
Para orang tua di Samarinda memahami bunga mei sebagai simbol musim semi, kebahagiaan, dan kekuatan. Bunga ini memiliki karakteristik. Ia mekar pertama kali saat musim dingin yang berat, di saat tanaman lain layu atau mati. Kehadirannya menjadi pertanda bahwa musim dingin yang beku akan segera berakhir dan musim semi yang hangat akan tiba.
Dalam konteks kehidupan diaspora Tionghoa yang kerap menghadapi tantangan, bunga mei menjadi metafora yang sempurna. Ia melambangkan keteguhan, kemuliaan, dan semangat untuk tidak mudah menyerah di tengah kesulitan.
Sementara itu, tanaman jeruk atau jīnjú (jeruk kingkit) dipilih karena alasan yang lebih pragmatis. Dalam bahasa Mandarin, pelafalan jeruk (jú) terdengar sangat mirip dengan kata jí, yang berarti mujur atau untung.
Seorang warga bernama A Lie melakukan sembahyang di Kelenteng Thien Le Khong, Jalan Yos Sudarso, Samarinda. ANTARA/Ahmad Rifandi. Matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya jingga di Sungai Mahakam. Dari narasi panjang sejarah yang diceritakan ada kenyataan bahwa kedamaian di Kaltim bukanlah sebuah kebetulan.
Samarinda, sebagai ibu kota Kalimantan Timur, telah memberikan keteladanan. Pola interaksi warganya yang multi-etnik berjalan egaliter, toleran, dan konsisten menjaga kerukunan. Kota ini, dengan segala dinamikanya, tetap nol dari kasus konflik kekerasan berbasis isu SARA.
Revitalisasi Pecinan atau Little Chinatown nanti mungkin akan mengubah wajah fisik kota. Namun, roh persaudaraan yang terjalin antara pembuat kue keminting di Karang Mumus dan penjaga toko Gabin Lido di tepian Mahakam, adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada sekadar bangunan gapura ala pagoda atau lampion merah.
Itu adalah warisan tentang bagaimana menjadi manusia yang memanusiakan sesama, tanpa peduli dari mana nenek moyang mereka berasal.