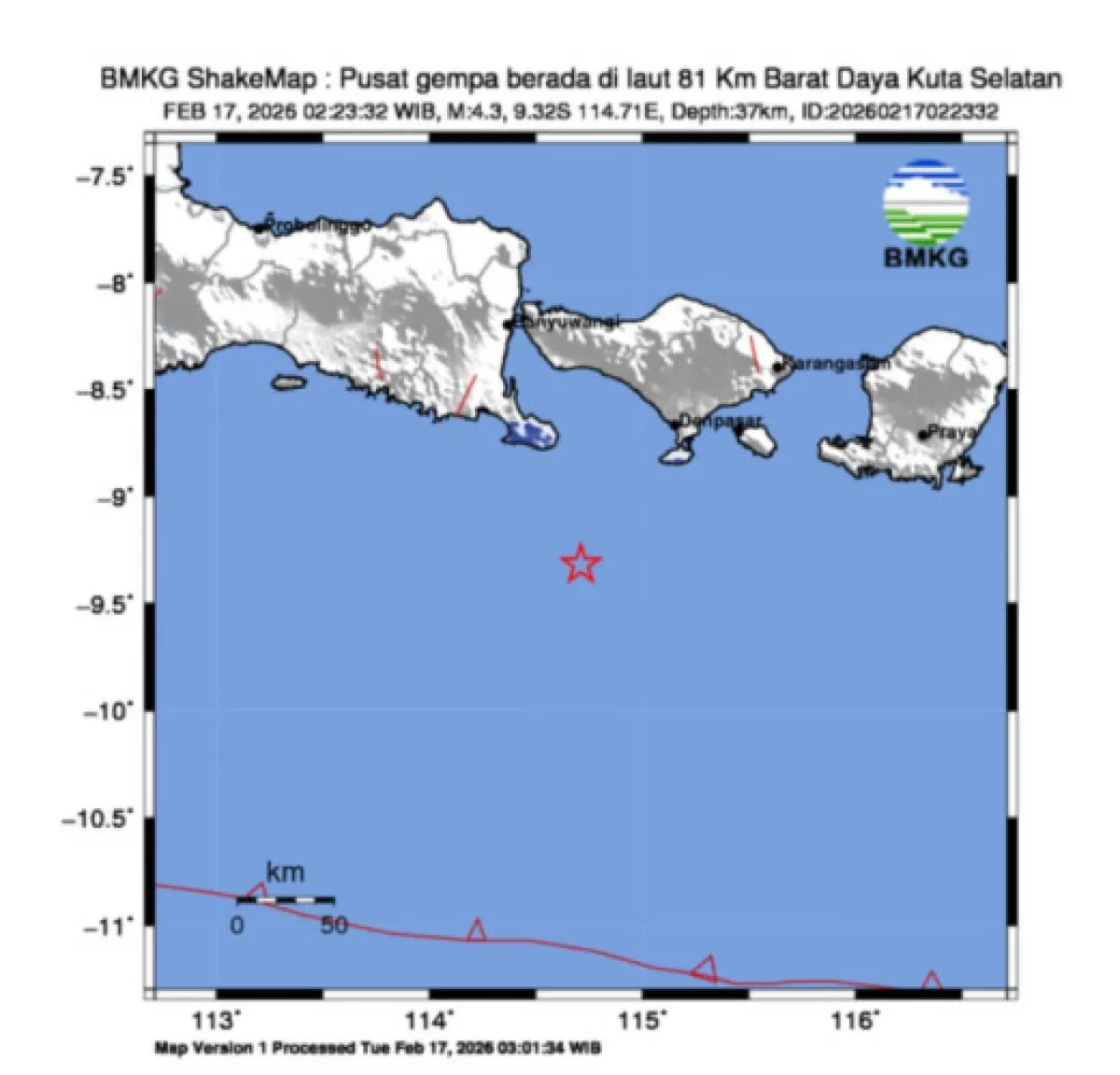Korea Selatan yang kita kenal hari ini adalah sebuah kisah sukses modernitas. Dari k-drama yang mendominasi platform streaming, musik K-Pop yang memenuhi tangga lagu global, hingga perusahaan teknologi seperti Samsung dan Hyundai yang menjadi simbol kekuatan industri Asia Timur, negara ini kerap dipandang sebagai contoh keberhasilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Bagi banyak orang, Korea Selatan adalah contoh negara yang mampu bangkit dari kemiskinan pasca perang menjadi kekuatan budaya dan ekonomi global hanya dalam beberapa dekade.
Namun dibalik berbagai pencapaian manis tersebut, Korea Selatan menyimpan sejarah yang penting. Sebelum dikenal sebagai pusat industri hiburan dunia, negara ini pernah menjadi ruang kekerasan politik. Pada masa awal kemerdekaannya, Korea Selatan tidak langsung menjadi sebuah negara demokrasi, melainkan berada di bawah rezim militer yang silih berganti. Puncaknya terjadi pada Mei 1980 di kota Gwangju, ketika sebuah aksi damai kemudian berakhir tragis dalam peristiwa yang kini dikenang sebagai Tragedi Gwangju.
Tragedi tersebut tidak hanya meninggalkan korban jiwa, tetapi juga menyisakan luka kolektif bagi negara. Selama bertahun-tahun, peristiwa itu disebut sekadar kerusuhan, sementara para penyintas, hidup dengan membawa trauma. Di sinilah novel Mata Malam (Human Acts) karya Han Kang menemukan relevansinya. Han Kang tidak menuliskan kronologi tragedi, melainkan menghadirkan dampaknya, bagaimana sejarah terus hidup di tubuh manusia, jauh setelah kekerasan berhasil dihentikan.
Untuk memahami novel ini, kita harus menilik kembali Korea Selatan tahun 1980. Setelah pembunuhan Presiden Park Chung-hee pada 1979, Korea Selatan memasuki masa transisi politik yang rapuh. Harapan demokratisasi sempat muncul, tetapi pada Desember 1979 Jenderal Chun Doo-hwan melakukan kudeta militer dan mengambil alih kekuasaan. Rezim baru segera memberlakukan darurat militer nasional, universitas ditutup, aktivitas politik dilarang, pers dibungkam, dan aktivis ditangkap. Kota Gwangju kala itu menjadi pusat gerakan mahasiswa. Pada 18 Mei 1980 mahasiswa turun ke jalan menuntut demokrasi, namun negara merespons bukan dengan negosiasi, melainkan pengerahan pasukan khusus.Kekerasan pun terjadi. Selama sepuluh hari Gwangju terisolasi dari dunia luar, informasi diputus, dan kota dikepung. Ketika militer kembali melakukan kekerasan pada 27 Mei 1980, ratusan hingga ribuan warga sipil tewas. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Tragedi Gwangju. Selama bertahun-tahun pemerintah menyebutnya sebagai kerusuhan, dan baru satu dekade kemudian negara mengakui kebenarannya.
Menariknya, dalam buku Mata Malam, Han Kang tidak menulis ulang kronologi tragedi tersebut. Ia tidak menjelaskan strategi militer, tidak menampilkan heroisme revolusi, bahkan tidak menjadikan peristiwa sebagai pusat cerita. Ia memilih sesuatu yang jauh lebih sunyi yakni dampak kemanusiaan setelah kekerasan politik berhenti. Tokoh pertama adalah seorang anak laki-laki yang mencari temannya di antara tumpukan mayat, bukan di medan perang melainkan di gedung olahraga yang berubah menjadi kamar jenazah. Bab-bab berikutnya menghadirkan relawan yang menjaga jenazah agar dapat dikenali keluarga, editor yang menghadapi sensor negara, tahanan yang disiksa, hingga penyintas yang puluhan tahun hidup dalam trauma.
Dalam kajian hubungan internasional, negara sering dipahami sebagai aktor rasional yang bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan nasionalnya. Namun Mata Malam menunjukkan paradoks dari negara modern, dimana negara dapat menjadi ancaman terbesar bagi warganya sendiri. Max Weber mendefinisikan negara sebagai institusi yang memonopoli penggunaan kekerasan yang sah, tetapi legitimasi selalu politis. Di Gwangju, rezim militer menganggap demonstran sebagai ancaman keamanan nasional; dengan definisi itu kekerasan berubah menjadi operasi stabilisasi.
Pentingnya novel ini tidak berhenti pada Korea Selatan semata. Tragedi Gwangju bukan peristiwa yang berdiri sendiri dalam sejarah dunia modern. Banyak negara pernah mengalami momen serupa. Argentina pada era junta militer, Chile di bawah Augusto Pinochet, berbagai tragedi politik di Asia Tenggara, hingga krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di sejumlah negara hari ini menunjukkan pola yang serupa.
Bagi studi hubungan internasional, pola ini menarik karena mengguncang asumsi klasik tentang negara sebagai penyedia keamanan. Dalam teori realisme, negara dipahami sebagai aktor rasional yang berupaya mempertahankan stabilitas dan kelangsungan sistem. Ancaman biasanya datang dari luar, dalam hal ini kerap kali dianggap negara lain, perang, atau intervensi asing. Namun pengalaman sejarah abad ke-20 hingga kini justru memperlihatkan bahwa ancaman terbesar bagi individu seringkali datang dari dalam negeri sendiri. Di titik inilah muncul konsep human security, sebuah pendekatan yang memindahkan fokus keamanan dari negara ke manusia. Pertanyaannya bukan lagi “apakah negara aman?”, melainkan “apakah manusia di dalam negara itu aman?”
Mata Malam memberikan wajah konkret pada konsep tersebut. Ia memperlihatkan bahwa keamanan nasional dan keamanan manusia tidak selalu berjalan beriringan. Rezim militer Korea Selatan saat itu mungkin berhasil mempertahankan kontrol politik, tetapi melakukannya dengan menghancurkan rasa aman warganya sendiri. Dalam bahasa hubungan internasional, negara mempertahankan regime security dengan mengorbankan human security. Novel ini membantu kita memahami bahwa stabilitas politik yang dipaksakan dapat menciptakan ketidakamanan sosial yang jauh lebih panjang daripada kerusuhan itu sendiri.
Di sinilah sastra memiliki posisi yang unik dalam hubungan internasional. Jika diplomasi negara bekerja melalui negosiasi formal, maka sastra bekerja melalui empati lintas batas. Pembaca dari negara mana pun dapat memahami penderitaan warga Gwangju tanpa harus hidup dalam konteks Korea Selatan. Dengan kata lain, novel seperti Mata Malam berfungsi sebagai bentuk diplomasi kemanusiaan, iia membangun solidaritas global terhadap korban kekerasan. Ia mengingatkan bahwa hak asasi manusia bukan hanya norma hukum internasional, tetapi pengalaman manusia yang dapat dirasakan bersama.
Bagi penstudi hubungan internasional, membaca novel ini berarti melihat politik dari perspektif yang jarang dibahas dalam laporan kebijakan.. Kita terbiasa menganalisis negara, sistem internasional, dan kepentingan nasional, tetapi sering melupakan bahwa setiap kebijakan keamanan selalu berujung pada kehidupan individu. Mata Malam memaksa kita menggeser pertanyaan dari “mengapa negara melakukan kekerasan?” menjadi “bagaimana manusia hidup setelah kekerasan itu?” Dan mungkin, pertanyaan kedua jauh lebih penting bagi masa depan perdamaian.