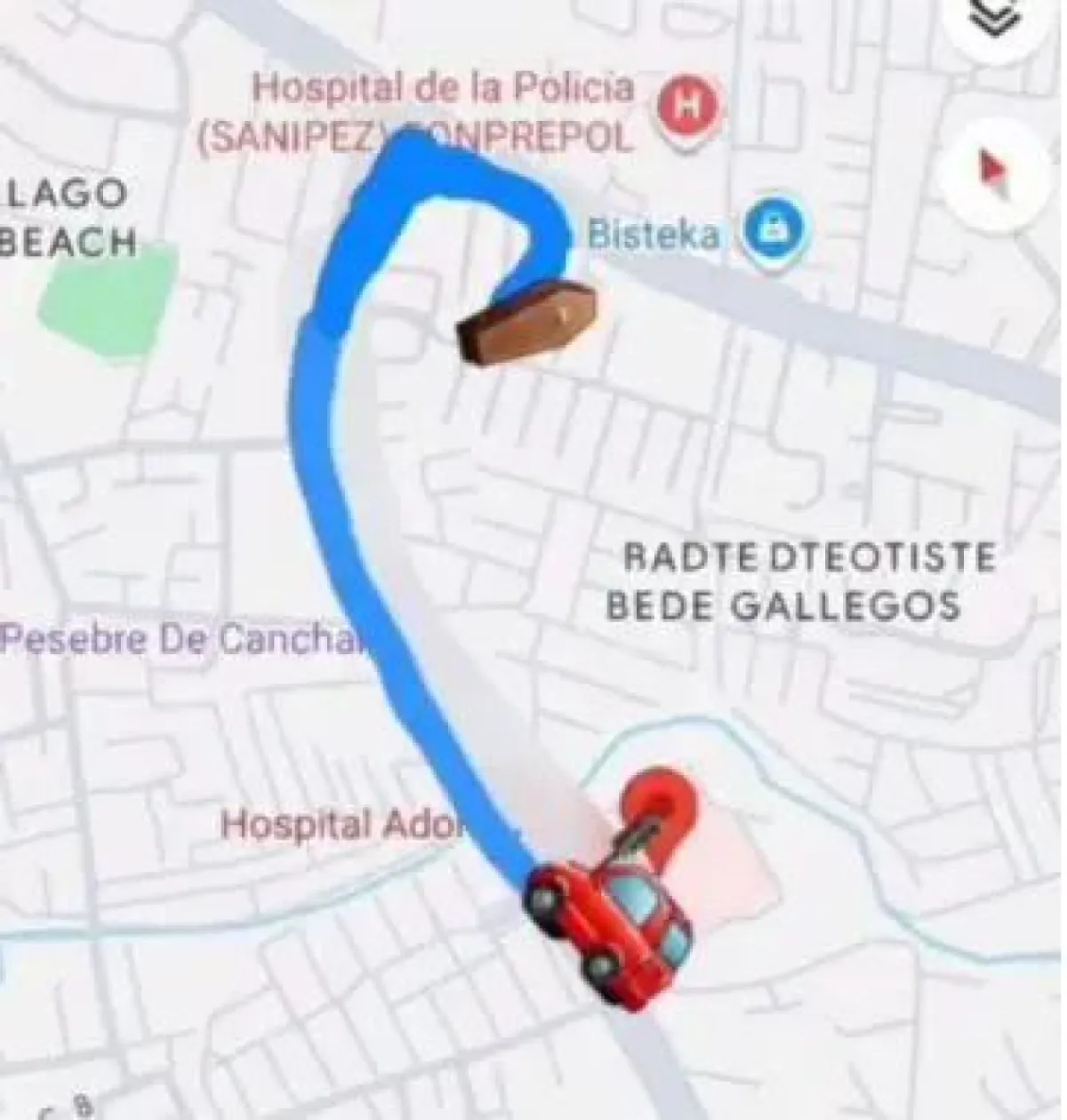Kita pernah berada pada suatu masa ketika setiap mendengar kabar operasi tangkap tangan (OTT) ruang-ruang kekuasaan mendadak sunyi. Telepon berdering lebih pelan. Rapat-rapat terasa tegang. Bukan karena undang-undangnya yang berubah, melainkan karena hukum benar-benar terasa hadir.
Ketika orang berbicara tentang mengembalikan sesuatu kepada yang “asli”, yang dirindukan sesungguhnya bukan sekadar bentuk atau pasal, melainkan juga suasana: suasana ketika kekuasaan bisa disentuh, ketika jabatan bukan perisai, dan ketika negara masih memiliki keberanian untuk menegakkan batas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir dari kegelisahan itu. Ia dibentuk bukan dalam keadaan normal, melainkan di tengah keputusasaan publik terhadap penegakan hukum yang kerap tumpul ke atas. Ketika itu, korupsi bukan lagi penyimpangan sesaat, melainkan telah menjelma menjadi kebiasaan yang seolah dimaklumi. Maka, dibentuklah lembaga dengan kewenangan luar biasa—dan justru karena itu ia memiliki daya gentar.
Daya gentar itu bukan sekadar asumsi. Ia menemukan bentuknya dalam sejumlah peristiwa yang mengguncang kesadaran publik. Pada 2013, Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, ditangkap dalam perkara suap sengketa pilkada. Peristiwa itu bagaikan retakan keras di jantung institusi hukum. Karena untuk pertama kalinya, simbol penjaga konstitusi telah dijerat secara terbuka. Pesannya jelas: tidak ada jabatan yang kebal hukum.
Namun, situasi itu berubah setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Dalam beberapa tahun terakhir, publik tidak lagi merasakan getaran yang sama setiap kali KPK bergerak. Kewenangan penyadapan bukan lagi sepenuhnya berada di ruang internal, penerbitan SP3 dimungkinkan, dan status pegawai beralih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan yang tampak prosedural tersebut membawa dampak psikologis yang tidak kecil.
Sebagai gambaran, pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 30 operasi tangkap tangan (OTT)—angka tertinggi sepanjang sejarah lembaga itu. Namun pada 2020, setahun setelah revisi undang-undang berlaku penuh, jumlah OTT turun menjadi 7 – 8 kasus (Kompas, 15/06/2021).
Penurunan ini tentu memiliki banyak faktor, termasuk pandemi. Namun secara psikologis, publik menangkap satu kesan yang sulit diabaikan: daya gentar KPK itu tidak lagi terasa sekuat sebelumnya.
Dengan adanya penurunan seperti itu, arah perdebatan publik mengenai KPK pun bergeser. Bukan lagi tentang seberapa berani KPK bertindak, melainkan seberapa jauh ia masih dapat bergerak secara independen. Kritik bukan muncul karena lembaga ini terlalu keras, melainkan karena kekhawatiran bahwa ia menjadi terlalu berhati-hati.
Padahal, korupsi sendiri terus bertransformasi. Ia masuk ke ruang digital, bergerak lintas yurisdiksi, bersembunyi di balik perusahaan cangkang, dan menyamar dalam rekayasa regulasi. Jika kejahatan berubah wajah, penegakan hukum tidak bisa sekadar menjaga kenangan tentang masa lalu.
Kerja-kerja penindakan tentu masih berjalan. Perkara ditangani, tersangka ditetapkan, aset dipulihkan. Namun, sebuah lembaga antikorupsi tidak hidup dari statistik semata. Ia hidup dari kepercayaan publik—dari keyakinan bahwa ketika hukum mengetuk, pintu kekuasaan benar-benar terbuka tanpa pandang bulu.
Seruan untuk “mengembalikan KPK asli” sering terdengar seperti nostalgia, seolah ada masa emas yang dapat dipasang ulang. Padahal, bahkan pada masa paling kuatnya, KPK tidak pernah bekerja tanpa tekanan. Keberanian yang hadir saat itu bukanlah hasil situasi yang nyaman, melainkan pilihan sadar untuk tidak tunduk pada risiko politik.
Karena itu, mengembalikan KPK pada fungsi sejatinya bukan sekadar soal legislasi. Undang-undang penting, struktur dapat diperbaiki, dan prosedur bisa disempurnakan. Namun tanpa komitmen etis yang tegas—tanpa dukungan publik yang konsisten dan kepemimpinan yang bersedia menanggung konsekuensi—kewenangan hanya menjadi administrasi dan independensi tinggal slogan.
Pada akhirnya, hal ini bukan semata soal satu lembaga. Ini soal watak bangsa. Apakah kita menginginkan hukum yang membuat penyalahguna kekuasaan berpikir dua kali, atau cukup puas dengan hukum yang tertib di atas kertas, tetapi kehilangan wibawa?
Tidak ada negara yang runtuh karena kekurangan aturan. Negara runtuh ketika hukum berhenti memberi batas kepada yang berkuasa dan berhenti memberi perlindungan kepada warga biasa.
Pertanyaannya sederhana: Apakah kita benar-benar takut pada korupsi, atau hanya takut pada keberanian memberantasnya?
Sebab, sejarah tidak akan mencatat alasan-alasan teknis yang kita buat hari ini; ia hanya akan mencatat apakah kita akan memilih untuk membiarkan keberanian hukum itu surut, atau menjaganya tetap hidup ketika ia paling dibutuhkan.