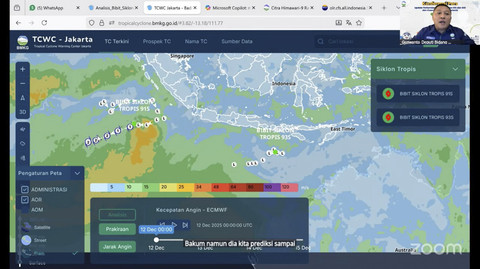Krisis lingkungan yang melanda Indonesia dalam dua dekade terakhir semakin menegaskan bahwa bencana ekologis bukanlah fenomena alamiah yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari keputusan dan praktik manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam.
Banjir, longsor, dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di berbagai wilayah Sumatera—mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat—menjadi bukti nyata bahwa ekspansi industri ekstraktif, lemahnya pengawasan, dan hilangnya tutupan hutan telah memperbesar kerentanan ekologis masyarakat.
WALHI bahkan mencatat bahwa deforestasi di kawasan Sibolga telah mencapai 250.000 hektare, dengan laju kerusakan meningkat 30 persen hanya dalam lima tahun terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan transformasi ekologis yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat di wilayah tersebut.
Isu ini kembali memanas setelah salah satu tokoh NU mengeluarkan pernyataan yang memicu kontroversi mengenai wahabi lingkungan—istilah yang dikaitkan dengan aliran keagamaan tertentu di kalangan umat Islam Indonesia—dan kemudian diarahkan kepada aktivis lingkungan (Kompas TV, 2025).
Kerusakan lingkungan jelas tidak pernah muncul begitu saja. Ia selalu bersumber dari cara manusia membangun relasi dengan alam. Apakah alam dilihat sebagai wilayah sakral yang harus dirawat? Atau dianggap sebagai komoditas yang boleh dieksploitasi atas nama pertumbuhan ekonomi? Dalam konteks Indonesia, ekoteologi—pendekatan yang menelaah hubungan manusia, Tuhan, dan alam—menawarkan dua pendekatan besar: puritanisme dan progresivisme.
Karena itu, keduanya memunculkan pandangan berbeda tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam alam, sekaligus menyoroti ragam cara masyarakat memahami pembangunan dan keberlanjutan.
Ekoteologi Puritanisme: Alam sebagai Entitas SuciEkoteologi puritan dapat dikaitkan dengan cara pandang Islam puritan, yakni tradisi keagamaan yang menekankan pemurnian aqidah dari praktik-praktik yang dianggap sebagai inovasi atau penyimpangan dari ajaran asli Islam (Burhani, 2018).
Dari prinsip tauhid yang menjadi pusat ajaran mereka, lahir pandangan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang memiliki tatanan fitrah: alam sebagaimana adanya, yang telah diciptakan dengan keseimbangan dan keteraturannya sendiri.
Dalam pandangan ini, manusia tidak boleh bertindak secara berlebihan terhadap alam. Eksploitasi yang merusak dipahami sebagai fasad fil-ardh (kerusakan di muka bumi), sebagaimana diperingatkan dalam QS. Al-Baqarah 2:11–12. Karena itu, menjaga alam dipandang sebagai bagian integral dari kesalehan. Perilaku ramah lingkungan sejajar dengan kewajiban spiritual.
Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Karena berfokus pada pelestarian total, ekoteologi puritan terkadang dianggap kurang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi modern.
Di tengah masyarakat yang menghadapi kebutuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, serta tuntutan peningkatan infrastruktur, pandangan puritan sering kali terlihat terlalu konservatif (Keraf, 2014). Ia memberikan dasar moral yang kuat, tetapi kurang memberi ruang bagi adaptasi dan inovasi dalam tata kelola lingkungan.
Ekoteologi Progresivisme: Pembaruan dan Pemanfaatan Rasional AlamBerbeda dengan puritanisme, ekoteologi progresivisme lahir dari pendekatan Islam progresif yang menekankan pentingnya pembaruan, reinterpretasi, dan kontekstualisasi ajaran agama (Abou El Fadl, 2005). Dalam perspektif ini, alam tidak hanya dilihat sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai potensi ekonomi yang perlu dikelola secara rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kelompok progresif—mulai dari pemerintah, pelaku industri ekstraktif, hingga komunitas yang mendukung pembangunan skala besar—melihat pembangunan sebagai indikator utama kemajuan. Pemanfaatan sumber daya alam dianggap sah selama mengikuti regulasi formal, didukung analisis dampak lingkungan, dan diletakkan dalam visi pembangunan jangka panjang (Escobar, 2011).
Namun praktik progresivisme di Indonesia menyimpan paradoks. Konsep “pembangunan berkelanjutan” kerap digunakan sebagai legitimasi proyek industri besar, tetapi regulasi yang lemah sering membuat pengawasan tidak efektif. Ketika kepentingan ekonomi dan politik lebih dominan, pembangunan yang disebut berkelanjutan justru berkontribusi pada kerusakan ekosistem (Monbiot, 2016).
Dalam konteks ini, progresivisme dianggap terlalu utilitarian, menempatkan alam sebagai objek ekonomi semata.
Menjembatani Puritanisme dan Progresivisme: Jalan Tengah Masa Depan Lingkungan IndonesiaKetegangan antara puritanisme dan progresivisme mencerminkan perdebatan fundamental mengenai bagaimana manusia memperlakukan alam. Puritanisme menawarkan etika ekologis berbasis kesucian alam, sementara progresivisme menawarkan etika utilitarian berbasis kebutuhan pembangunan.
Keduanya memiliki dasar rasional masing-masing, tetapi juga membawa kelemahan: puritanisme cenderung mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat, sedangkan progresivisme sering melampaui batas ekologis.
Ekoteologi menawarkan jalan tengah yang mengintegrasikan nilai spiritual puritanisme dengan kepekaan sosial progresivisme (Berry, 1999). Dalam paradigma integratif ini, alam dipandang sebagai ciptaan yang harus dijaga, namun juga dapat dimanfaatkan secara terbatas dan etis, dengan prinsip keadilan ekologis dan tanggung jawab lintas generasi (White, 1967).
Krisis lingkungan di Indonesia—dari deforestasi di Sumatera hingga bencana ekologis yang semakin sering terjadi—mengharuskan kita menata ulang hubungan manusia dengan alam. Ekoteologi puritan memberikan landasan etis dan spiritual, sementara ekoteologi progresif membuka ruang bagi inovasi dan adaptasi.
Dengan mengintegrasikan keduanya, kita dapat membangun kerangka pemikiran ekologis yang lebih kokoh, yang tidak hanya menjaga keberlanjutan alam, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat.
Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan yang tidak mengorbankan alam demi pertumbuhan, dan tidak pula menolak pembangunan demi konservasi total. Paradigma ekologis integratif inilah yang dapat menjadi jalan tengah. Sebuah cara pandang yang melihat alam sebagai amanah, dan pembangunan sebagai tanggung jawab etis.