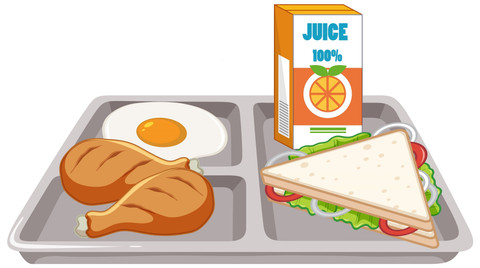Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan gizi anak-anak Indonesia. Di tengah tantangan stunting dan ketimpangan akses pangan, MBG hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat.
Namun, di balik semangat mulia tersebut, muncul pertanyaan mendasar: Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis dan tata kelola yang baik?
Sebagai mahasiswa yang mempelajari etika bisnis, saya melihat bahwa program ini bukan hanya soal distribusi makanan, melainkan juga soal integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ketika negara menjadi “pelaku usaha” dalam konteks pelayanan publik, standar etika bisnis tetap berlaku—bahkan seharusnya lebih tinggi.
Sertifikasi yang Masih MinimData dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025, baru 326 dari 10.700 dapur MBG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Padahal, sertifikasi ini menjadi syarat dasar untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi.
Pemerintah juga mewajibkan dua sertifikat lainnya: halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dari Komite Akreditasi Nasional.
Pertanyaannya: Mengapa mayoritas dapur belum tersertifikasi? Apakah ini soal kapasitas, pengawasan, atau justru kelalaian sistemik? Dalam etika bisnis, ini menyentuh prinsip non-maleficence—jangan sampai niat baik justru membahayakan penerima manfaat.
Jika dapur MBG belum memenuhi standar higienis, risiko kontaminasi makanan menjadi nyata. Ini bukan hanya pelanggaran teknis, melainkan juga pelanggaran etika. Anak-anak yang menjadi sasaran program berhak mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bermartabat.
Transparansi dan Pelaporan: Formalitas atau Substansi?Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan setiap SPPG mengunggah foto dan video operasional sebagai syarat pencairan dana. Ini langkah yang patut diapresiasi. Namun, muncul kekhawatiran bahwa dokumentasi ini bisa dimanipulasi. Jika pelaporan hanya menjadi formalitas administratif tanpa verifikasi lapangan, prinsip akuntabilitas menjadi semu.
Dalam teori etika deontologis (Kantian), kejujuran adalah kewajiban moral, bukan pilihan strategis. Manipulasi data—meski demi tujuan baik—tetaplah pelanggaran etika. Etika bisnis menuntut transparansi yang autentik, bukan sekadar laporan yang indah di atas kertas.
Lebih jauh, sistem pelaporan digital MBG yang terpusat juga perlu diaudit secara berkala. Apakah data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi lapangan? Apakah ada mekanisme koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian? Tanpa sistem pengawasan yang kuat, pelaporan bisa menjadi alat legitimasi semu.
Tenaga Kerja: Unsung Heroes yang TerlupakanIsu lain yang jarang dibahas adalah perlakuan terhadap tenaga kerja dapur MBG. Banyak dari mereka adalah relawan atau pekerja informal yang tidak mendapat perlindungan ketenagakerjaan memadai. Padahal, dalam etika bisnis, memperlakukan pekerja secara adil adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.
Jika negara mengabaikan hak-hak dasar pekerja dalam program sosialnya, bagaimana bisa menuntut sektor swasta untuk patuh? Prinsip human dignity dalam etika bisnis menuntut agar setiap individu diperlakukan dengan hormat, termasuk mereka yang bekerja di balik layar program MBG.
Pemerintah perlu memastikan bahwa tenaga kerja dapur MBG mendapat pelatihan, perlindungan, dan kompensasi yang layak. Jangan sampai semangat gotong royong berubah menjadi eksploitasi terselubung.
Distribusi dan Keadilan SosialEtika bisnis juga menyentuh aspek distribusi. Apakah makanan bergizi benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan? Apakah ada ketimpangan antarwilayah? Apakah kelompok marginal—seperti anak jalanan, anak disabilitas, atau anak di daerah terpencil—turut terlayani?
Teori utilitarianisme menekankan bahwa kebijakan publik harus menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang—tanpa mengorbankan kelompok rentan. Jika MBG hanya menjangkau wilayah tertentu atau kelompok tertentu, prinsip keadilan sosial dilanggar.
Pemerintah perlu membuka data distribusi MBG secara publik. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan bahwa program ini benar-benar inklusif.
Etika Bisnis dalam Pelayanan PublikEtika bisnis bukan hanya milik korporasi. Dalam pelayanan publik, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial tetap relevan. Bahkan, seharusnya lebih ketat. Negara tidak boleh hanya mengejar output, tetapi juga harus menjamin proses yang etis.
Program MBG adalah kebijakan yang sangat potensial. Namun, tanpa etika yang kuat, ia bisa berubah menjadi proyek populis yang rapuh. Kita tidak boleh puas hanya dengan angka-angka distribusi. Kita harus bertanya: Apakah prosesnya adil? Apakah pelaksanaannya jujur? Apakah dampaknya berkelanjutan?
Saatnya Evaluasi EtisSebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab moral untuk mengawal program-program publik agar tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga bermartabat secara etis. Dapur MBG harus menjadi contoh bagaimana negara bisa hadir dengan integritas, bukan sekadar hadir secara fisik.
Etika bukan pelengkap. Ia adalah fondasi. Dan tanpa fondasi yang kokoh, bangunan sebesar apa pun akan mudah runtuh.