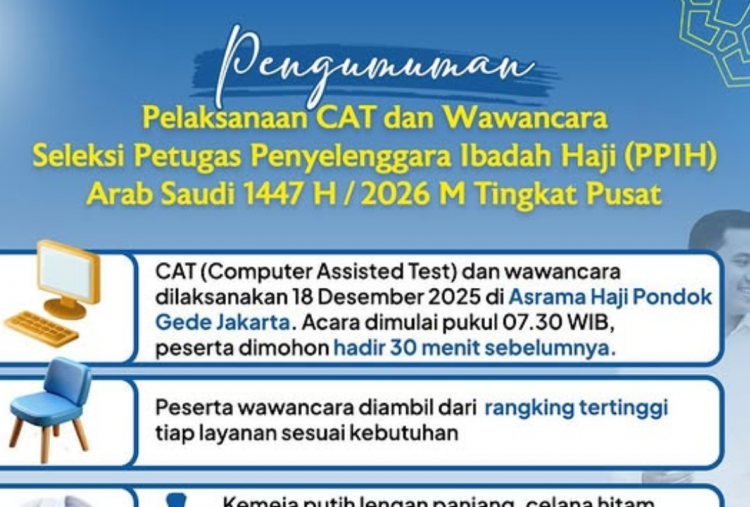Ada satu momen yang selalu terasa berat setiap saya kembali ke ibu kota: tatapan keluarga yang mencoba tegar sambil berkata, “Hati-hati, ya. Selamat sampai tujuan” Pada detik itu, dunia serasa mengecil dan meninggalkan satu ruang kosong di dada. Saya teringat pepatah lama, “Jarak menguji, waktu membuktikan.” Menjalani Long Distance Marriage (LDM) bukan sekadar soal siapa yang pergi dan siapa yang tinggal, tapi tentang bagaimana dua hati menjaga rumah yang tak selalu bisa disentuh, namun selalu bisa diperjuangkan.
Sebagai dosen, saya hidup dalam irama yang tak bisa ditebak. Pendidikan adalah ladang pengabdian, tetapi ladang ini sering menuntut kita untuk mencurahkan energi pada banyak ruang belajar, bukan hanya di rumah sendiri. Ada hari ketika saya merasa menjadi jembatan bagi mahasiswa—mengantar mereka dari kebingungan menuju pemahaman, dari keraguan menuju keberanian. Ironisnya, di saat saya membimbing masa depan orang lain, masa depan keluarga saya justru saya titipkan pada kesabaran dan doa.
LDM membuat kita lebih sering berbicara dengan layar HP daripada memeluk orang-orang yang kita cintai. Namun pekerjaan sebagai dosen memaksa saya percaya bahwa setiap perpisahan kecil memiliki makna. Ada kata bijak yang selalu saya pegang, “Jika ingin melihat masa depan, lihatlah apa yang kamu kerjakan hari ini.” Maka saya memilih percaya bahwa perjalanan ini bukan sekadar pengorbanan, tetapi investasi—investasi pendidikan, karier, dan martabat keluarga.
Di kelas, saya banyak berbicara tentang pertumbuhan dan ketimpangan dalam Ekonomi Pembangunan dan tentang bagaimana memaknai angka-angka dalam Statistik. Tapi LDM mengajari saya teori yang tidak pernah saya temukan di buku: bahwa cinta membutuhkan strategi. Bahwa keteguhan hati adalah kompetensi emosional. Bahwa kesetiaan adalah riset jangka panjang yang bukti empiriknya baru terlihat setelah bertahun-tahun dijalankan.
Menjadi dosen sering disandingkan dengan kata “pengabdian”. Namun di balik itu, ada realitas sosial yang senyap: tuntutan administrasi, akreditasi, penelitian, pembimbingan, pengujian, kepanitiaan, hingga rapat maraton. Kadang saya bertanya dalam hati, “Apakah ini terlalu banyak?” Namun saya juga sadar, tidak ada pendidikan yang lahir dari kemudahan. “Tak ada pelaut ulung lahir dari laut yang tenang,” kata pepatah. Dan mungkin, tidak ada keluarga yang kuat tanpa melewati gelombang rindu yang panjang.
Namun percayalah, bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kalimat bijak. Ada malam ketika lelah mengalahkan logika, ketika suara pada layar HP tidak cukup untuk meredakan penat, ketika jarak terasa lebih keras daripada realita. Pada titik itu, saya menyadari satu hal: masa depan tidak dibangun oleh kehadiran yang sempurna, tetapi oleh komitmen yang tidak patah meski diuji jarak.
Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa bahwa pendidikan adalah proses memperluas dunia. Kini saya belajar bahwa memperjuangkan keluarga adalah proses memperluas hati. Bahwa menjadi dosen bukan hanya pekerjaan intelektual, melainkan juga pekerjaan emosional: menjaga integritas di ruang publik sambil menjaga kehangatan di ruang privat.
Di sela-sela rindu, saya belajar menghargai hal-hal kecil: vcall bersama anak istri, foto yang dikirim untuk memastikan saya tahu bahwa mereka baik-baik saja, atau pesan singkat yang mengatakan, “Jangan lupa makan atau jaga kesehatan disana yaa” Dari situ saya membuat pepatah untuk diri sendiri: “Rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan tempat yang selalu memanggil kita pulang.”
Saya percaya masa depan keluarga saya tidak ditentukan oleh seberapa jauh kami terpisah, tetapi oleh seberapa kuat kami saling menggenggam dalam doa. Pendidikan—baik di kampus maupun di rumah—selalu punya cara membentuk karakter. Dan mungkin inilah pendidikan paling mahal yang sedang saya tempuh: pendidikan tentang sabar, teguh, dan cinta yang tidak takut menempuh jarak.
Kepada siapa pun di luar sana yang sedang menjalani LDM, saya ingin berkata: kita tidak sendirian. Ada banyak hati yang juga menahan rindu, banyak keluarga yang juga sedang berjuang untuk masa depan yang lebih pantas. “Langkah kecil hari ini adalah pondasi besar esok hari.” Bertahanlah. Berdoalah. Tetaplah kuat. Karena suatu hari nanti, semua jarak ini akan terasa seperti kesaksian bahwa kita pernah memperjuangkan sesuatu yang tidak main-main.
Jika ditanya apa yang saya inginkan dari masa depan, jawabannya sederhana: saya ingin pulang tanpa menghitung hari. Saya ingin melihat keluarga saya tumbuh bukan dari layar HP, tetapi dari dekat. Tapi selama waktu itu belum tiba, saya akan terus melangkah—sebab saya percaya, seperti pepatah berkata, “Selama masih ada tujuan, setiap langkah akan menemukan jalannya.”
Dan bagi kita, para pejuang LDM, tujuannya selalu sama: pulang, dan tetap utuh.