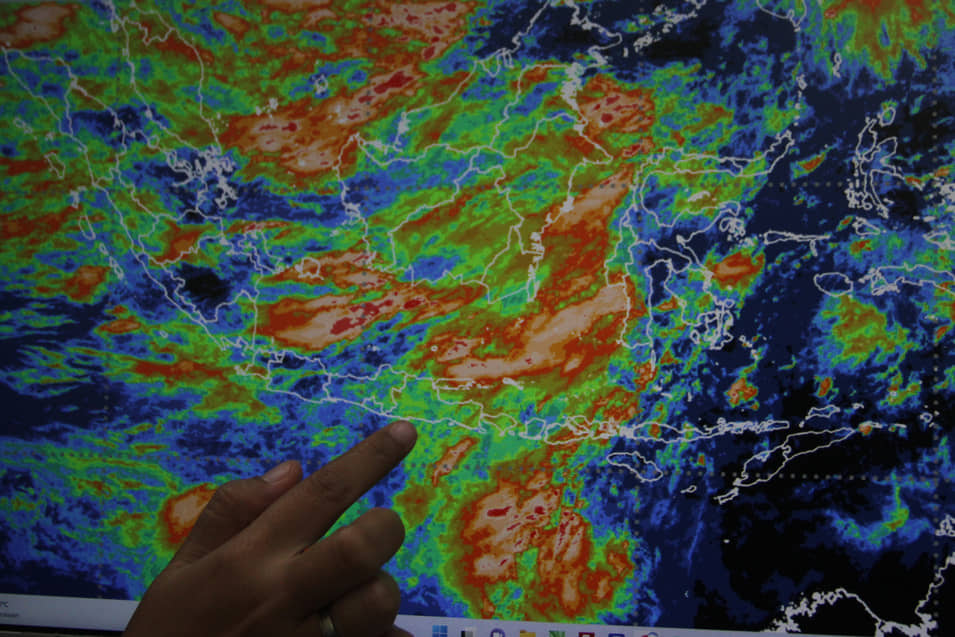Rencana Netflix mengambil alih Warner Bros menandai perubahan besar dalam peta industri hiburan dunia. Jika kesepakatan ini terwujud, Netflix bukan lagi sekadar platform penyalur tontonan, melainkan pusat kendali yang menguasai studio besar, gudang cerita, sekaligus jalur distribusi global. Ini bukan sekadar soal skala bisnis, melainkan pergeseran kekuasaan dalam ekosistem hiburan dan komunikasi.
Pada titik ini, yang patut dipertanyakan bukan hanya efisiensi atau inovasi, melainkan siapa yang memegang kendali atas cerita yang beredar di ruang publik. Ketika produksi, distribusi, dan algoritma berada di satu tangan, kekuatan itu dengan sendirinya melampaui urusan hiburan semata.
Dalam kajian komunikasi massa, Denis McQuail (2010) mengingatkan bahwa konsentrasi kepemilikan media berpotensi melahirkan suara dominan yang perlahan membentuk arah wacana publik. Apa yang dianggap menarik, penting, atau layak dikonsumsi tidak lagi lahir dari keberagaman sudut pandang, tetapi dari keputusan segelintir pemain besar. Akuisisi Netflix–Warner Bros bergerak tepat ke wilayah ini.
Dampak awalnya mungkin terasa di bioskop. Warner Bros selama puluhan tahun menjadi salah satu pemasok utama film layar lebar. Jika Netflix memilih mempercepat distribusi melalui streaming atau mengurangi jatah tayang di bioskop, ruang hidup industri layar lebar akan semakin menyempit. Yang terancam bukan hanya bisnis bioskop, melainkan pengalaman menonton sebagai peristiwa sosial, ruang di mana film dinikmati bersama, didiskusikan, dan menjadi bagian dari kehidupan publik.
Namun, persoalan yang lebih mendalam justru menyentuh keragaman cerita. Netflix bekerja dengan logika data dan algoritma, yang cenderung mendorong konten dengan daya tarik luas dan risiko minimal. Dalam jangka panjang, pola ini berpotensi menyingkirkan cerita-cerita yang tidak sesuai selera pasar global, seperti film lokal, karya eksperimental, atau narasi yang tidak mudah diterjemahkan lintas budaya.
Teori agenda-setting dari McCombs dan Shaw (1972) membantu membaca situasi ini. Media tidak memaksa publik untuk berpikir tertentu, tetapi sangat menentukan isu apa yang layak mendapat perhatian. Ketika satu platform menjadi gerbang utama hiburan, agenda itu semakin terkonsentrasi. Publik tetap merasa bebas memilih, tetapi pilihan yang tersedia sudah lebih dulu disaring.
Bagi negara seperti Indonesia, dampaknya menjadi lebih kompleks. Pasar kita besar dari sisi jumlah penonton, tetapi lemah dari sisi kendali. Platform global bisa dengan mudah menjadi pemain dominan tanpa keterikatan yang seimbang dengan ekosistem produksi lokal.
Jika tidak ada pengaturan yang memadai, pelaku industri nasional hanya akan menjadi penonton di pasar sendiri—menikmati konten global, tetapi sulit menumbuhkan kekuatan lokal.
Konsumen pun berada pada posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. Ketika konten-konten besar terkunci dalam satu ekosistem, ruang memilih menyempit dan soal harga menjadi persoalan waktu.
Dalam kondisi seperti ini, publik tidak dipaksa, tetapi dibiasakan—sebuah situasi yang oleh Noam Chomsky (1988) digambarkan sebagai manufacturing consent: persetujuan yang dibentuk perlahan, bukan lewat larangan, melainkan lewat struktur pilihan.
Tentu, konsolidasi ini tidak sepenuhnya suram. Integrasi antara kemampuan produksi Warner dan teknologi distribusi Netflix berpotensi menghasilkan karya dengan kualitas tinggi dan jangkauan global. Bagi sebagian kreator, hal ini bisa membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Bagi penonton, kemudahan akses dalam satu platform jelas menggoda.
Namun, manfaat itu tidak boleh menutup mata terhadap risiko jangka panjang. Skala besar memang efisien, tetapi efisiensi tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Karena itu, peran negara dan regulator menjadi krusial. Pengawasan persaingan usaha harus memastikan tidak ada penyalahgunaan dominasi pasar.
Dukungan terhadap industri kreatif lokal perlu diwujudkan secara konkret, bukan sekadar jargon ekonomi kreatif. Bioskop pun perlu diposisikan ulang sebagai ruang budaya, bukan sekadar saluran distribusi yang bisa digantikan aplikasi.
Pada akhirnya, rencana akuisisi Netflix terhadap Warner Bros adalah cermin arah zaman, hiburan bergerak menuju pemusatan kendali atau kekuasaan. Pertanyaannya bukan apakah perubahan ini bisa dihentikan, melainkan bagaimana dampaknya dikelola. Apakah layar kita akan dipenuhi oleh satu suara besar, atau tetap memberi ruang bagi banyak cerita untuk tumbuh.
Sebab, hiburan bukan hanya soal tontonan, melainkan juga bagian dari cara masyarakat membangun makna, identitas, dan imajinasi bersama. Dan ruang sepenting itu terlalu berharga untuk diserahkan sepenuhnya pada logika pasar global. Tugas kita sesungguhnya memastikan bahwa arus besar ini tidak membuat dunia hiburan menjadi ruang gema yang hanya memantulkan satu suara saja.