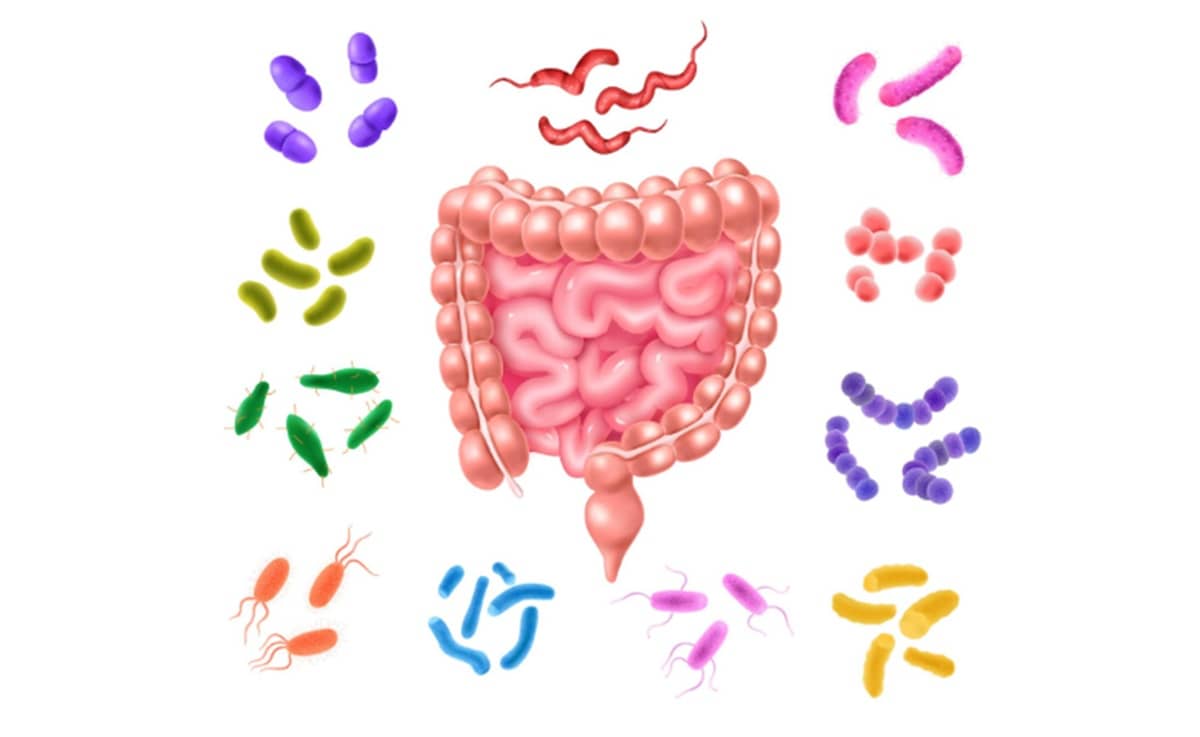Kritik dan demokrasi adalah dua pilar yang tidak terpisahkan dalam memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di atas rel keadilan. Namun, alih-alih merayakan awal tahun dengan optimisme, sebagian masyarakat justru merasa waswas karena menyampaikan aspirasi kini terasa semakin berisiko. Pertanyaan ini mengemuka seiring meningkatnya pelaporan terhadap ekspresi publik, tepat di saat Indonesia memasuki fase baru hukum pidana melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Dalam sistem yang sehat, kritik bukanlah ancaman, melainkan mekanisme koreksi agar kebijakan tidak menimbulkan dampak buruk yang luas bagi masyarakat.
Keresahan publik saat ini tidak lepas dari bayang-bayang sejarah, di mana pembatasan suara kritis sering kali hadir melalui normalisasi ketakutan dan penggunaan instrumen hukum untuk membatasi perbedaan pendapat. Meskipun konteks Indonesia saat ini memiliki pers yang lebih bebas, risiko kemunduran demokrasi tetap nyata jika pembatasan dilakukan melalui jalur legal-formal. Di sinilah relevansi antara aturan hukum dan praktik kritik dan demokrasi menjadi sangat krusial untuk disoroti. Kehadiran Pasal 240 KUHP tentang penyerangan kehormatan pemerintah, misalnya, menciptakan wilayah abu-abu yang bisa menjerat kritik tajam sebagai pelanggaran hukum, tergantung pada sudut pandang penegak hukumnya.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan jika pembaruan hukum tidak dibarengi dengan penguatan perlindungan hak warga negara dalam proses pembuktian. Para ilmuwan politik sering menyebut gejala ini sebagai democratic backsliding, sebuah proses kemunduran di mana kritik dan demokrasi perlahan menjadi mahal harganya secara hukum dan sosial. Ketika warga mulai ragu untuk berpendapat karena takut akan konsekuensi hukum, maka esensi dari kedaulatan rakyat sebenarnya sedang melemah. Negara yang kuat seharusnya bukan negara yang kebal terhadap teguran, melainkan negara yang mampu merespons setiap masukan dengan dewasa.
Sebab, pada akhirnya demokrasi tidak pernah mati dalam satu malam. Ia layu secara perlahan saat kritik dibungkam dan keheningan dianggap sebagai indikator stabilitas. KUHP dan KUHAP baru seharusnya hadir untuk memperkuat keadilan, bukan justru menjadi sumber kecemasan kolektif yang membuat masyarakat memilih untuk diam.