Jakarta (ANTARA) - Momen seratus hari pertama masa kerja kepala daerah menjadi titik awal ekspektasi publik. Di tengah euforia pelantikan, janji-janji kampanye diuji dalam realitas birokrasi dan struktur fiskal yang sempit.
Namun sayangnya, alih-alih menjadi periode akselerasi, banyak kepala daerah justru tersandera pada keraguan, stagnasi, hingga keengganan untuk berinovasi melakukan pembangunan. Bahkan, yang paling menyedihkan, menjelang akhir tahun 2025, publik dipertontonkan dengan fenomena kepala daerah yang justru menjadi buronan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan atas kasus korupsi.
Kalau kita belajar dari pemerintahan di tahun 2025, pemerintah daerah juga sempat mengalami fase “bimbang” dalam menyalurkan belanja dengan beberapa alasan.
Pertama, adanya kekhawatiran kebijakan belanja daerah tidak sejalan atau bertentangan dengan instruksi pemerintah pusat, terutama dalam konteks program direktif dan strategis nasional yang cenderung “top-down.”
Kedua, dinamika regulasi yang cepat berubah tanpa mekanisme transisi yang jelas kerap membuat kepala daerah ragu untuk mengeksekusi program yang bersifat inovatif.
Ketiga, minimnya anggaran karena alokasi fiskal sudah “disetting” lebih dulu untuk membiayai program pusat, membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas.
Apa yang ingin saya sampaikan? Koordinasi antara Kemendagri terhadap seluruh pemerintah daerah seharusnya bukan lagi sekadar ketaatan secara administratif, Kemendagri sebagai instansi pembina utama pemerintah daerah juga perlu membina kepala-kepala daerah dengan memberikan kemampuan teknokratisme sehingga bisa berkreasi meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Jika belanja daerah hanya menjadi alat formalistik untuk menyerap anggaran tanpa strategi pembangunan yang terukur, maka seluruh upaya efisiensi belanja akan kehilangan maknanya. Alih-alih mendorong pertumbuhan, belanja akan kembali ke pola lama: belanja birokrasi dan seremoni, yang cepat habis tapi tidak menyisakan nilai pembangunan jangka panjang.
Situasi ini menuntut lebih dari sekadar kepatuhan administratif. Kepala daerah tidak cukup hanya menjadi manajer program, melainkan juga harus menjadi inovator fiskal. Salah satu agenda penting yang kerap terabaikan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan pada transfer pusat tidak boleh menjadi alibi untuk stagnasi fiskal lokal.
Kreativitas fiskal ini tidak akan tumbuh dalam ruang yang kering akan dukungan teknokratis. Maka dari itu, Kemendagri sebagai pembina utama pemerintah daerah harus bergeser dari sekadar pengawas administratif menjadi agen pemberi vaksin teknokratisme. Kepala daerah harus dibina dan difasilitasi untuk meningkatkan kapasitas perencanaan, manajemen fiskal, hingga tata kelola investasi.
Memulai tahun 2026, maka pertanyaan penting yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah: ke mana arah pemerintahan daerah kita? Bagaimana dengan realisasi janji-janji kampanye yang sudah dilontarkan kepada rakyat? Program apa yang seharusnya benar-benar berdampak dan mendongkrak ekonomi masyarakat?
Pertanyaan ini menjadi penting, karena kita belajar dari tahun 2025 sebagai tahun yang penuh ketidakpastian. Tahun di mana lesunya ekonomi hampir dirasakan oleh semua masyarakat akar rumput.
Baca juga: Menuju kabupaten merdeka fiskal
Baca juga: BSKDN sebut kualitas kepemimpinan kepala daerah tentukan kesejahteraan
Kepala daerah harus memberikan effort lebih keras untuk meningkatkan kapasitas fiskal yang memadai, agar tidak sekadar menjadi “operator” kebijakan pusat.
Hari ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh kepala daerah bukan lagi hanya soal infrastruktur hingga penyediaan layanan publik lainnya, tetapi bagaimana mereka mampu menjadi buffer zone terhadap guncangan ekonomi nasional dan global yang dampaknya perlahan-lahan mempengaruhi kantong rakyat kecil.
Ketika inflasi merangkak naik, daya beli masyarakat tergilas pelan-pelan. Kepala daerah harus sensitif menyadari bila harga bahan-bahan pokok yang melonjak di pasar tradisional, bisa memicu keresahan yang jauh lebih dalam daripada angka statistik yang tertera di kertas laporan.
Terakhir, perlu ditegaskan bahwa seluruh agenda penguatan ekonomi daerah akan menjadi sia-sia jika tidak diiringi oleh pemberantasan korupsi yang nyata dan sistemik. Korupsi di level daerah yang kian membesar, bahkan menyeret banyak kepala daerah aktif, merupakan sinyal buruk bagi stabilitas fiskal dan kepercayaan publik.
Saat ini kita melihat langsung di berbagai media, kasus korupsi di berbagai daerah yang begitu membludak, dari level kepala daerah, kepala dinas, hingga jajaran di level terbawah. Inilah pola-pola dari state capture corruption, ketika korupsi bukan lagi diorkestrasi oleh dua hingga tiga orang saja, namun kondisi sistem pemberantasan korupsi kita lemah akhirnya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan pribadi. Artinya, lagi-lagi kita dihadapkan pada persoalan sistem yang koruptif.
Mengelola pemerintahan daerah di tengah perlambatan ekonomi nasional dan keterbatasan fiskal bukanlah perkara mudah. Namun, justru pada titik inilah kualitas kepemimpinan teknokratik diuji.
Kepala daerah dituntut mampu mentransformasikan ketidakpastian menjadi arah kebijakan yang terukur melalui perumusan agenda fiskal berbasis data, penguatan kualitas belanja, pengendalian risiko korupsi secara sistemik, serta keberanian mendorong inovasi guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dalam konteks ini, praktik salah kaprah efisiensi anggaran sebagaimana kita rakan dalam implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak boleh kembali terulang. Efisiensi seharusnya diarahkan pada pemangkasan belanja birokratis yang tidak produktif, bukan pada pengurangan kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pemerintah pusat juga perlu lebih cermat dalam merancang kebijakan efisiensi anggaran agar tidak berimplikasi kontraproduktif terhadap kinerja pelayanan publik di daerah. Tanpa kehati-hatian, kebijakan tersebut justru berpotensi melemahkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dasarnya.
Jika kondisi ini dibiarkan, penyelenggaraan pemerintahan berisiko terjebak pada rutinitas administratif yang sarat seremoni, namun miskin capaian substantif.
Selain itu, meningkatnya intensitas bencana di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir menuntut kepala daerah untuk melakukan refocusing anggaran secara lebih disiplin, adaptif, dan berbasis risiko.
Baca juga: Mendagri dorong sinergi DPRD-kepala daerah perkuat kemandirian fiskal
Pemerintah daerah perlu menempatkan belanja penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi dan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai belanja prioritas yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah, bukan sekadar respons ad hoc ketika bencana terjadi. Pendekatan ini penting untuk menekan biaya sosial-ekonomi jangka panjang serta meminimalkan kerugian fiskal akibat bencana berulang.
Lebih jauh, kepala daerah dituntut untuk melakukan penataan ulang struktur APBD agar semakin berorientasi pada belanja publik yang produktif dan inklusif. Dominasi belanja birokrasi dan belanja pegawai yang terlalu besar berpotensi menggerus ruang fiskal bagi program-program perlindungan sosial, penguatan infrastruktur dasar, dan peningkatan ketahanan wilayah.
Oleh karena itu, rasionalisasi belanja aparatur harus diimbangi dengan peningkatan kualitas belanja, melalui penguatan belanja berbasis kinerja dan outcome-oriented budgeting.
Dalam kerangka otonomi daerah, kemampuan kepala daerah dalam mengelola prioritas fiskal menjadi indikator penting kualitas kepemimpinan teknokratik. Otonomi tidak semata diukur dari besarnya kewenangan, tetapi dari sejauh mana kewenangan fiskal tersebut dimanfaatkan secara efektif untuk menjawab risiko nyata yang dihadapi masyarakat, termasuk ancaman bencana dan ketimpangan layanan publik.
Oleh karena itu, relasi pusat–daerah perlu bergeser dari sekadar relasi kepatuhan menuju kemitraan strategis yang memberikan ruang, kepercayaan, dan fleksibilitas bagi daerah untuk berinovasi. Otonomi daerah tidak akan bermakna tanpa keberanian untuk mandiri secara fiskal dan kebijakan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan harus diukur dari kemampuannya mendorong mobilitas sosial masyarakat. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu memastikan masyarakat “naik kelas” secara ekonomi dan sosial bukan justru “turun kelas.” Artinya, bukan sekadar bertahan, apalagi terjebak, dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Baca juga: Anggota DPR: Kualitas pilkada tentukan kualitas pemimpin Indonesia
Baca juga: Pilkada serentak diyakini lahirkan kepala daerah kualitas rendah
*) Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Penyuluh Antikorupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK dan Alumni Kebangsaan Lemhannas RI
Namun sayangnya, alih-alih menjadi periode akselerasi, banyak kepala daerah justru tersandera pada keraguan, stagnasi, hingga keengganan untuk berinovasi melakukan pembangunan. Bahkan, yang paling menyedihkan, menjelang akhir tahun 2025, publik dipertontonkan dengan fenomena kepala daerah yang justru menjadi buronan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan atas kasus korupsi.
Kalau kita belajar dari pemerintahan di tahun 2025, pemerintah daerah juga sempat mengalami fase “bimbang” dalam menyalurkan belanja dengan beberapa alasan.
Pertama, adanya kekhawatiran kebijakan belanja daerah tidak sejalan atau bertentangan dengan instruksi pemerintah pusat, terutama dalam konteks program direktif dan strategis nasional yang cenderung “top-down.”
Kedua, dinamika regulasi yang cepat berubah tanpa mekanisme transisi yang jelas kerap membuat kepala daerah ragu untuk mengeksekusi program yang bersifat inovatif.
Ketiga, minimnya anggaran karena alokasi fiskal sudah “disetting” lebih dulu untuk membiayai program pusat, membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas.
Apa yang ingin saya sampaikan? Koordinasi antara Kemendagri terhadap seluruh pemerintah daerah seharusnya bukan lagi sekadar ketaatan secara administratif, Kemendagri sebagai instansi pembina utama pemerintah daerah juga perlu membina kepala-kepala daerah dengan memberikan kemampuan teknokratisme sehingga bisa berkreasi meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Jika belanja daerah hanya menjadi alat formalistik untuk menyerap anggaran tanpa strategi pembangunan yang terukur, maka seluruh upaya efisiensi belanja akan kehilangan maknanya. Alih-alih mendorong pertumbuhan, belanja akan kembali ke pola lama: belanja birokrasi dan seremoni, yang cepat habis tapi tidak menyisakan nilai pembangunan jangka panjang.
Situasi ini menuntut lebih dari sekadar kepatuhan administratif. Kepala daerah tidak cukup hanya menjadi manajer program, melainkan juga harus menjadi inovator fiskal. Salah satu agenda penting yang kerap terabaikan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan pada transfer pusat tidak boleh menjadi alibi untuk stagnasi fiskal lokal.
Kreativitas fiskal ini tidak akan tumbuh dalam ruang yang kering akan dukungan teknokratis. Maka dari itu, Kemendagri sebagai pembina utama pemerintah daerah harus bergeser dari sekadar pengawas administratif menjadi agen pemberi vaksin teknokratisme. Kepala daerah harus dibina dan difasilitasi untuk meningkatkan kapasitas perencanaan, manajemen fiskal, hingga tata kelola investasi.
Memulai tahun 2026, maka pertanyaan penting yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah: ke mana arah pemerintahan daerah kita? Bagaimana dengan realisasi janji-janji kampanye yang sudah dilontarkan kepada rakyat? Program apa yang seharusnya benar-benar berdampak dan mendongkrak ekonomi masyarakat?
Pertanyaan ini menjadi penting, karena kita belajar dari tahun 2025 sebagai tahun yang penuh ketidakpastian. Tahun di mana lesunya ekonomi hampir dirasakan oleh semua masyarakat akar rumput.
Baca juga: Menuju kabupaten merdeka fiskal
Baca juga: BSKDN sebut kualitas kepemimpinan kepala daerah tentukan kesejahteraan
Kepala daerah harus memberikan effort lebih keras untuk meningkatkan kapasitas fiskal yang memadai, agar tidak sekadar menjadi “operator” kebijakan pusat.
Hari ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh kepala daerah bukan lagi hanya soal infrastruktur hingga penyediaan layanan publik lainnya, tetapi bagaimana mereka mampu menjadi buffer zone terhadap guncangan ekonomi nasional dan global yang dampaknya perlahan-lahan mempengaruhi kantong rakyat kecil.
Ketika inflasi merangkak naik, daya beli masyarakat tergilas pelan-pelan. Kepala daerah harus sensitif menyadari bila harga bahan-bahan pokok yang melonjak di pasar tradisional, bisa memicu keresahan yang jauh lebih dalam daripada angka statistik yang tertera di kertas laporan.
Terakhir, perlu ditegaskan bahwa seluruh agenda penguatan ekonomi daerah akan menjadi sia-sia jika tidak diiringi oleh pemberantasan korupsi yang nyata dan sistemik. Korupsi di level daerah yang kian membesar, bahkan menyeret banyak kepala daerah aktif, merupakan sinyal buruk bagi stabilitas fiskal dan kepercayaan publik.
Saat ini kita melihat langsung di berbagai media, kasus korupsi di berbagai daerah yang begitu membludak, dari level kepala daerah, kepala dinas, hingga jajaran di level terbawah. Inilah pola-pola dari state capture corruption, ketika korupsi bukan lagi diorkestrasi oleh dua hingga tiga orang saja, namun kondisi sistem pemberantasan korupsi kita lemah akhirnya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan pribadi. Artinya, lagi-lagi kita dihadapkan pada persoalan sistem yang koruptif.
Mengelola pemerintahan daerah di tengah perlambatan ekonomi nasional dan keterbatasan fiskal bukanlah perkara mudah. Namun, justru pada titik inilah kualitas kepemimpinan teknokratik diuji.
Kepala daerah dituntut mampu mentransformasikan ketidakpastian menjadi arah kebijakan yang terukur melalui perumusan agenda fiskal berbasis data, penguatan kualitas belanja, pengendalian risiko korupsi secara sistemik, serta keberanian mendorong inovasi guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dalam konteks ini, praktik salah kaprah efisiensi anggaran sebagaimana kita rakan dalam implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak boleh kembali terulang. Efisiensi seharusnya diarahkan pada pemangkasan belanja birokratis yang tidak produktif, bukan pada pengurangan kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pemerintah pusat juga perlu lebih cermat dalam merancang kebijakan efisiensi anggaran agar tidak berimplikasi kontraproduktif terhadap kinerja pelayanan publik di daerah. Tanpa kehati-hatian, kebijakan tersebut justru berpotensi melemahkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dasarnya.
Jika kondisi ini dibiarkan, penyelenggaraan pemerintahan berisiko terjebak pada rutinitas administratif yang sarat seremoni, namun miskin capaian substantif.
Selain itu, meningkatnya intensitas bencana di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir menuntut kepala daerah untuk melakukan refocusing anggaran secara lebih disiplin, adaptif, dan berbasis risiko.
Baca juga: Mendagri dorong sinergi DPRD-kepala daerah perkuat kemandirian fiskal
Pemerintah daerah perlu menempatkan belanja penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi dan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai belanja prioritas yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah, bukan sekadar respons ad hoc ketika bencana terjadi. Pendekatan ini penting untuk menekan biaya sosial-ekonomi jangka panjang serta meminimalkan kerugian fiskal akibat bencana berulang.
Lebih jauh, kepala daerah dituntut untuk melakukan penataan ulang struktur APBD agar semakin berorientasi pada belanja publik yang produktif dan inklusif. Dominasi belanja birokrasi dan belanja pegawai yang terlalu besar berpotensi menggerus ruang fiskal bagi program-program perlindungan sosial, penguatan infrastruktur dasar, dan peningkatan ketahanan wilayah.
Oleh karena itu, rasionalisasi belanja aparatur harus diimbangi dengan peningkatan kualitas belanja, melalui penguatan belanja berbasis kinerja dan outcome-oriented budgeting.
Dalam kerangka otonomi daerah, kemampuan kepala daerah dalam mengelola prioritas fiskal menjadi indikator penting kualitas kepemimpinan teknokratik. Otonomi tidak semata diukur dari besarnya kewenangan, tetapi dari sejauh mana kewenangan fiskal tersebut dimanfaatkan secara efektif untuk menjawab risiko nyata yang dihadapi masyarakat, termasuk ancaman bencana dan ketimpangan layanan publik.
Oleh karena itu, relasi pusat–daerah perlu bergeser dari sekadar relasi kepatuhan menuju kemitraan strategis yang memberikan ruang, kepercayaan, dan fleksibilitas bagi daerah untuk berinovasi. Otonomi daerah tidak akan bermakna tanpa keberanian untuk mandiri secara fiskal dan kebijakan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan harus diukur dari kemampuannya mendorong mobilitas sosial masyarakat. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu memastikan masyarakat “naik kelas” secara ekonomi dan sosial bukan justru “turun kelas.” Artinya, bukan sekadar bertahan, apalagi terjebak, dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Baca juga: Anggota DPR: Kualitas pilkada tentukan kualitas pemimpin Indonesia
Baca juga: Pilkada serentak diyakini lahirkan kepala daerah kualitas rendah
*) Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Penyuluh Antikorupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK dan Alumni Kebangsaan Lemhannas RI
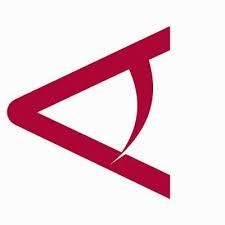



:strip_icc()/kly-media-production/medias/5461740/original/090215100_1767436894-1.jpg)


