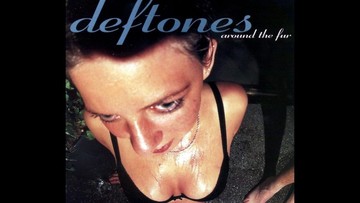FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, turut memberikan pandangannya terkait ketentuan dalam KUHP baru yang mengatur sanksi pidana terhadap praktik nikah siri dan poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum negara.
Cholil menegaskan bahwa dalam perspektif agama, poligami bukanlah sebuah perintah, melainkan solusi dalam kondisi tertentu bagi mereka yang membutuhkan.
Karena itu, menurutnya, praktik poligami tidak semestinya diposisikan sebagai tindakan kriminal.
“Poligami itu bukan perintah tapi jalan keluar bagi yang membutukan,” ujar Cholil di X @cholilnafis (7/1/2026).
Ia juga menyinggung ketentuan yang mensyaratkan adanya izin istri dan izin pengadilan sebagai prasyarat sahnya poligami.
Kata dia, syarat tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan secara agama.
“Jangan memberi syarat sahnya pernikahan itu harus ada izin istri apalagi izin pengadilan,” sebutnya.
Meski demikian, Cholil menganggap pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memastikan pelaku poligami mampu berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.
“Itu untuk memastikan orang yang berpoligami akan mampu berbuat adil,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa poligami tidak boleh dilihat sebagai kejahatan, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial dan kebutuhan kemanusiaan yang dalam kondisi tertentu diakomodasi oleh ajaran agama.
“Poligami itu bukan kejahatan tapi memenuhi hajat kemanusiaan,” kuncinya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar, Dr. Rahman Syamsuddin, menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai upaya negara mengkriminalisasi syariat.
“Banyak narasi beredar seolah negara sedang mengkriminalisasi ajaran agama,” ujar Rahman kepada fajar.co.id, Senin (5/1/2026).
Dikatakan Rahman, jika dikuliti menggunakan teori hukum murni dan perspektif Maqashid Syariah, ancaman pidana ini justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk memuliakan institusi perkawinan yang sering direduksi sekadar urusan biologis semata.
“Dalam kacamata teori hukum, terjadi pergeseran paradigma yang fundamental dari Wetboek van Strafrecht (WvS) lama ke KUHP Baru,” sebutnya.
Ia kemudian mengajak ke belakang, mengingat bahwa sebelumnya pasal-pasal kesusilaan kental dengan nuansa menjaga ketertiban umum, kini semangatnya bergeser pada perlindungan hak individu dan kepastian hukum.
“Ancaman pidana 6 tahun (yang merujuk pada substansi larangan melangsungkan perkawinan padahal ada penghalang yang sah) tidak menyasar ibadah nikahnya. Yang disasar adalah mens rea (niat jahat) berupa penyelundupan hukum,” tukasnya.
Rahman menarik contoh kasus, ketika seorang suami melakukan poligami secara siri tanpa izin pengadilan dan sepengetahuan istri pertama, ia telah dianggap sedang melakukan penipuan administratif.
“Dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum pidana di sini berfungsi sebagai ultimum remedium (obat terakhir) untuk memaksa suami agar tidak sewenang-wenang menggunakan hak agama (poligami) dengan cara menginjak-injak hak hukum (hak persetujuan istri pertama dan hak keperdataan calon istri kedua/anak),” imbuhnya.
Ia mengakui bahwa kritik yang membenturkan KUHP baru dengan hukum Islam seringkali luput melihat esensi syariat itu sendiri.
“Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar Mitsaqan Ghalizan (perjanjian agung) di hadapan Tuhan, tapi juga kontrak sosial (muamalah) yang melahirkan hak dan kewajiban,” jelasnya.
(Muhsin/fajar)