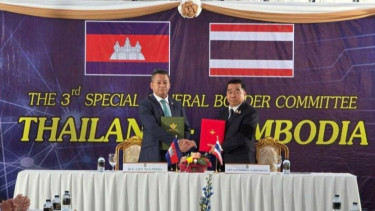Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan ketentuan hukum yang mengatur persentase minimum perolehan suara partai politik agar dapat diikutsertakan dalam penghitungan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan ini memiliki dampak langsung terhadap tingkat keterwakilan politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Secara sederhana, partai politik yang memperoleh suara di bawah ambang batas tersebut tidak berhak mendapatkan kursi di parlemen. Mekanisme ini berfungsi sebagai alat penyaringan jumlah partai politik yang dapat masuk ke lembaga legislatif, dengan tujuan menciptakan sistem politik yang lebih efektif dan stabil.
Di Indonesia, peraturan mengenai parliamentary threshold tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan undang-undang tersebut, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen dari total suara sah secara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Ketentuan ini menjadi salah satu elemen penting dalam sistem kepemiluan nasional.
Penerapan parliamentary threshold di Indonesia dimulai sejak Pemilu 2009, dengan besaran yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 2009, ambang batas ditetapkan sebesar 2,5 persen. Angka ini kemudian meningkat menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014 dan kembali dinaikkan menjadi 4 persen pada Pemilu 2019 serta Pemilu 2024.
Dalam konteks sistem multipartai yang dianut Indonesia, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi fragmentasi politik serta menciptakan struktur parlemen yang lebih stabil dan efektif.
Akan tetapi, bukankah penerapan parliamentary threshold ini justru bertentangan dengan konsep demokrasi itu sendiri?
Salah satu prinsip utama dalam demokrasi modern adalah political equality, yakni kesetaraan nilai setiap suara pemilih. Penerapan ambang batas parlemen berpotensi menimbulkan fenomena wasted votes atau suara terbuang, yaitu suara sah yang diberikan kepada partai politik, tetapi tidak berkontribusi dalam perolehan kursi parlemen.
Data menunjukkan bahwa jumlah suara terbuang akibat parliamentary threshold cukup signifikan.
Berdasarkan data Databoks (2019), pada Pemilu 2009 terdapat sekitar 19,05 juta suara atau sekitar 18 persen dari total suara sah tidak terkonversi menjadi kursi parlemen. Pada Pemilu 2014, jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 2,96 juta suara atau 2,4 persen.
Namun, pada Pemilu 2019, angka suara terbuang kembali meningkat menjadi sekitar 13,6 juta suara atau 9,7 persen dari total suara sah nasional. Tren serupa juga terlihat pada Pemilu 2024. Berdasarkan laporan Metrotvnews (2024), sekitar 17,3 juta suara atau 11,3 persen dari total suara sah nasional tidak berkontribusi terhadap alokasi kursi DPR akibat penerapan ambang batas parlemen.
Suara yang diberikan kepada partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak diperhitungkan dalam pembagian kursi, sehingga tidak menghasilkan representasi politik di parlemen.
Dalam perspektif teori demokrasi representatif, keberadaan parliamentary threshold memang menempatkan efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik sebagai prioritas utama. Namun, hal tersebut tidak selalu sejalan dengan prinsip keterwakilan politik secara maksimal.
Demokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan sistem politik menghasilkan pemerintahan yang stabil, tetapi juga dari sejauh mana suara warga negara dapat terartikulasikan secara adil dalam lembaga perwakilan. Ketika sejumlah besar suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi parlemen akibat ambang batas, terjadi kesenjangan antara kehendak rakyat dan komposisi parlemen yang terbentuk.
Kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi representasi politik, khususnya bagi kelompok pemilih yang suaranya tidak terakomodasi. Hal tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara efisiensi sistem kepartaian dan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia.
Oleh karena itu, perdebatan mengenai parliamentary threshold seharusnya tidak berhenti pada soal perlu atau tidaknya ambang batas parlemen, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut dapat dirancang dan dievaluasi agar tidak mengorbankan prinsip dasar demokrasi. Menemukan titik keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan keadilan representasi menjadi pekerjaan rumah yang terus relevan dalam perjalanan demokrasi Indonesia.