Suasana Indonesia belakangan ini penuh duka dan panas. Bukan hanya karena bencana alam yang terjadi, melainkan karena "bencana komunikasi" yang diciptakan oleh para pemangku kebijakan. Gelombang amarah publik yang kita saksikan di media sosial bukan muncul tanpa sebab. Jika ditelusuri, akar dari gejolak ini mengerucut pada satu titik api: lidah para pejabat publik.
Pernyataan-pernyataan yang arogan, elitis, dan miskin empati dari pejabat daerah maupun pusat saat menanggapi krisis sering kali menjadi bensin yang menyiram api kemarahan warga. Fenomena ini terlihat jelas dalam penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra beberapa waktu yang lalu.
Di tengah duka mendalam akibat ratusan ribu rumah hancur dan ribuan nyawa melayang, publik justru disuguhi narasi pejabat yang menyalahkan curah hujan atau bahkan menganggap bencana tersebut masih biasa saja, tanpa diimbangi pengakuan jujur akan kegagalan mitigasi dan tata ruang.
Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa dalam politik, komunikasi bukan sekadar pelengkap. Di era kecepatan informasi, setiap kata pejabat memiliki konsekuensi fatal. Untuk membedah fenomena ini, teori retorika kuno dari Aristoteles—Ethos, Pathos, dan Logos—menjadi pisau analisis yang sangat relevan untuk menelanjangi inkompetensi komunikasi para pemimpin kita.
Pilar pertama, Ethos, merujuk pada kredibilitas dan karakter moral pembicara. Seorang pejabat dengan ethos kuat akan didengar karena integritasnya. Namun, apa yang terjadi di lapangan dalam kasus bencana di Sumatra, ethos pemerintah runtuh ketika narasi yang dibangun bertolak belakang dengan fakta.
Pejabat yang datang ke lokasi bencana dengan pengawalan ketat, pakaian "necis", lalu memberikan pernyataan normatif tanpa solusi konkret, seketika kehilangan otoritas moralnya. Publik melihat rekam jejak: izin tambang ilegal dan pembalakan liar yang dibiarkan bertahun-tahun berkontribusi pada bencana ini.
Ketika pejabat tersebut berbicara tentang "cobaan alam", tanpa mengakui andil kelalaian pengawasan ekologis, ia tidak lagi dilihat sebagai pelayan publik, tetapi sebagai penguasa yang lari dari tanggung jawab. Ethos-nya hancur; ucapannya disambut sinisme, bukan kepatuhan.
Pilar kedua, Logos, yaitu logika, data, dan fakta. Dalam komunikasi bencana, Logos berarti transparansi mengenai penyebab bencana dan rencana mitigasi yang masuk akal. Sayangnya, aspek ini sering kali dimanipulasi.
Alih-alih menyajikan data transparan mengenai kerusakan sistem peringatan dini (early warning system) yang tidak berfungsi optimal, pejabat kerap bersembunyi di balik istilah teknis atau data makro ekonomi, mengabaikan fakta lapangan bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi evakuasi yang memadai.
Kegagalan menjelaskan secara runut mengapa bencana ini berdampak begitu fatal dan bagaimana langkah taktis perbaikannya membuat publik merasa tidak dilibatkan. Kebijakan relokasi yang ditawarkan pun akhirnya sering ditolak karena dianggap tidak logis secara sosiologis dan ekonomi bagi warga terdampak.
Pilar terakhir—dan yang paling fatal kerusakannya saat ini—adalah Pathos, kemampuan terhubung secara emosional. Pathos bukan manipulasi air mata, melainkan empati tulus: validasi atas rasa takut, kehilangan, dan trauma korban.
Pernyataan pejabat yang meminta warga "bersabar" atau "introspeksi diri" saat jenazah keluarga mereka belum ditemukan adalah contoh kematian Pathos. Blunder komunikasi ini melukai hati rakyat lebih dalam daripada bencana itu sendiri.
Seorang pemimpin yang menguasai Pathos seharusnya "berhenti bicara" sejenak, turun ke lapangan, merasakan lumpur yang diinjak korban, dan berkata, "Kami gagal melindungi kalian dan kami akan memperbaikinya." Tanpa Pathos, bantuan logistik sebanyak apa pun akan terasa hambar. Tanpa validasi emosi, Logos (penjelasan teknis) akan terdengar seperti omong kosong teknokratis yang angkuh.
Mempelajari trilogi Aristoteles bukan untuk gagah-gagahan akademis, melainkan syarat mutlak bertahan sebagai pemimpin di negara demokrasi yang rawan bencana. Kerusakan infrastruktur bisa diperbaiki, tetapi kepercayaan publik yang hancur akibat "salah ucap" membutuhkan waktu generasi untuk pulih.
Sudah saatnya elite politik berhenti meremehkan kekuatan diksi. Lidah yang tak bertulang bisa menjadi senjata pemusnah massal bagi karier politik mereka sendiri dan stabilitas sosial bangsa.
Dalam konteks bencana Sumatra dan bencana-bencana lainnya, rakyat merindukan pemimpin yang memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan (Pathos), kejujuran untuk membuka data (Logos), dan integritas untuk bertanggung jawab (Ethos). Tanpa itu, pejabat publik hanyalah turis bencana yang menabur garam di atas luka rakyatnya sendiri.


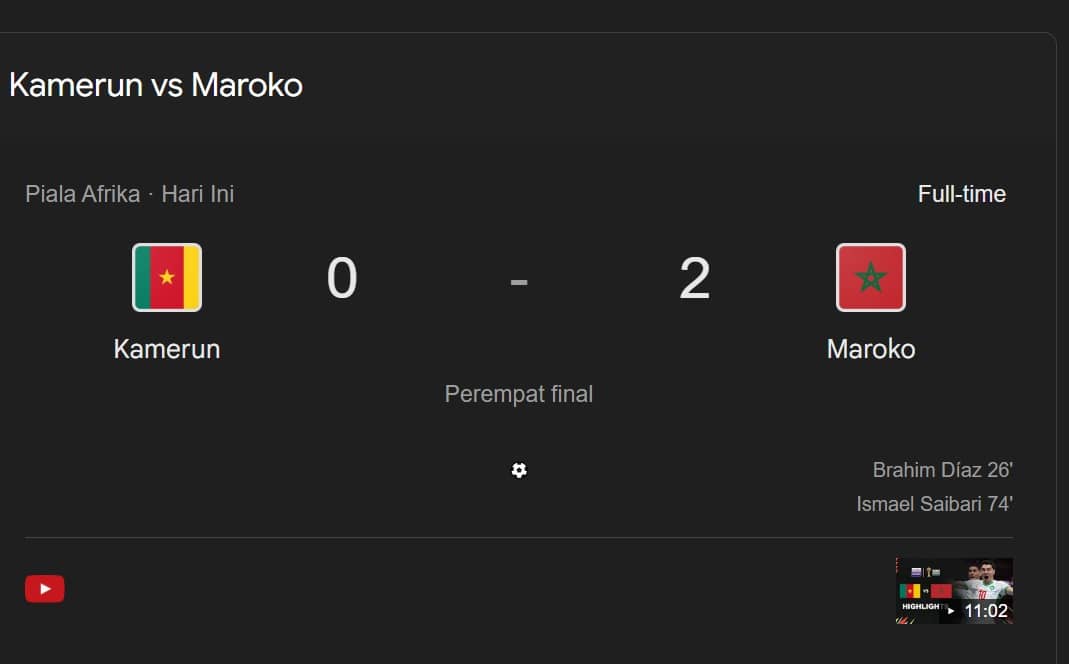



/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fphoto%2Fori%2F2025%2F01%2F02%2F9bac899f-5227-4d69-9a0d-1d41e13736f0.jpg)
