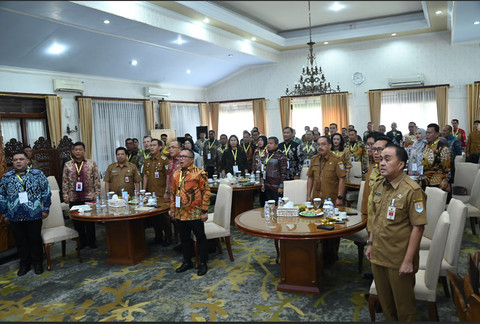Ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa “incorrect data can lead to financial waste”, ia sesungguhnya sedang mengingatkan satu hal mendasar: kesalahan data berarti kesalahan kebijakan. Masalahnya, di banyak instansi, data sebenarnya sudah tersedia, sistem sudah terbangun, tetapi kapasitas ASN untuk berpikir berbasis data masih tertinggal. Di sinilah diklat ASN seharusnya mengambil peran strategis.
Di banyak instansi, data tidak digunakan untuk mengambil keputusan, melainkan untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat.
Selama ini, diklat ASN lebih banyak diposisikan sebagai sarana peningkatan kompetensi administratif: memahami regulasi, menguasai aplikasi, atau memenuhi kewajiban jam pelatihan. Dalam kerangka ini, data sering diperlakukan sebagai objek teknis—sekadar sesuatu yang harus diinput, dilaporkan, dan disajikan dalam bentuk dashboard. Padahal, dalam konteks negara berbasis data, tantangan utamanya bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada kemampuan menafsirkan makna di balik data tersebut.
Yang dominan hari ini bukan kepemimpinan berbasis data, melainkan kepemimpinan berbasis slide. Keputusan ditentukan oleh siapa yang presentasinya paling meyakinkan, bukan oleh siapa yang datanya paling valid. Negara terlihat semakin digital, tetapi proses berpikir di balik kebijakan sering kali masih analog.
Negara berbasis data sejatinya adalah negara yang mampu belajar dari realitasnya sendiri. Data bukan tujuan, melainkan bahan baku untuk membangun pengetahuan, dan pada akhirnya kebijakan. Namun tanpa kapasitas analitis yang memadai, data justru berisiko menjadi ilusi objektivitas: terlihat ilmiah, tetapi tidak benar-benar digunakan untuk memahami masalah publik secara lebih dalam.
Di titik ini, diklat ASN tidak lagi cukup berfokus pada penguasaan tools atau aplikasi. Yang dibutuhkan adalah pergeseran paradigma: dari training menuju learning. Dari sekadar transfer materi menuju pembentukan cara berpikir. ASN perlu dilatih untuk mengajukan pertanyaan berbasis data: apa pola yang muncul, apa anomali yang perlu dicurigai, apa implikasi kebijakan dari angka-angka yang ada.
Ironisnya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin jarang ia bersentuhan langsung dengan data mentah. Informasi yang sampai kepadanya sudah melalui berlapis filter: staf, laporan, ringkasan, dan slide. Akibatnya, banyak pemimpin publik justru mengambil keputusan paling strategis dengan pemahaman paling dangkal terhadap realitas yang diwakili oleh data.
Dalam banyak rapat, kalimat “berdasarkan pengalaman saya” sering mengalahkan temuan data. Pengalaman personal menjadi otoritas kebenaran, seolah realitas sosial cukup dibaca dari ingatan individu, bukan dari pola empiris. Di sini, intuisi sering diperlakukan lebih sakral daripada evidensi.
Artinya, substansi diklat juga harus berubah. Literasi data, analisis kebijakan, systems thinking, dan kemampuan membaca konteks sosial dari data seharusnya menjadi kompetensi inti. Bukan sebagai mata pelajaran tambahan, tetapi sebagai fondasi cara kerja birokrasi modern. Tanpa itu, negara berbasis data hanya akan menghasilkan birokrasi yang sibuk mengelola informasi, tetapi miskin pengetahuan.
Lebih jauh, indikator keberhasilan diklat pun perlu diredefinisi. Bukan lagi berapa banyak peserta yang lulus, atau berapa sertifikat yang diterbitkan, melainkan apa yang berubah di organisasi: apakah kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, apakah anggaran lebih efisien, apakah layanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ironisnya, capaian nilai SPBE yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat literasi data para pimpinan instansi. Banyak organisasi pemerintah berhasil memperoleh skor baik dalam evaluasi SPBE—sistem terintegrasi, aplikasi berjalan, dashboard tersedia—namun dalam praktiknya, keputusan strategis masih lebih sering ditentukan oleh intuisi, pengalaman personal, atau pertimbangan politis. Dashboard dibuka di awal rapat, tetapi ditutup saat keputusan diambil.
SPBE, dalam banyak kasus, berhenti sebagai indikator kesiapan teknologi, bukan indikator kematangan cara berpikir. Negara terlihat semakin digital, tetapi belum tentu semakin data-driven. Yang terjadi justru paradoks: birokrasi semakin canggih secara sistem, tetapi tetap bekerja dengan logika lama dalam proses pengambilan kebijakan.
Namun, membangun pemimpin yang melek data tidak berarti mengubah mereka menjadi analis teknis, apalagi programmer. Kepemimpinan berbasis data bukan tentang kemampuan menulis kode, mengolah dataset, atau membuat visualisasi kompleks. Itu adalah ranah teknis yang penting, tetapi bukan inti dari peran kepemimpinan.
Yang dibutuhkan dari seorang pemimpin di era negara berbasis data adalah kemampuan kognitif dan strategis: mengajukan pertanyaan yang tepat terhadap data, memahami konteks di balik angka, mengenali bias dan keterbatasan informasi, serta menggunakan data sebagai dasar pertimbangan kebijakan—bukan sekadar legitimasi keputusan yang sudah diambil sebelumnya.
Sebagai ilustrasi, seorang pimpinan yang melek data tidak harus mampu mengolah dataset secara langsung. Ketika melihat angka kemiskinan meningkat, ia tidak langsung menyimpulkan kegagalan kebijakan, tetapi menelusuri apakah kenaikan tersebut disebabkan oleh perubahan metodologi pendataan, perluasan cakupan survei, atau memang terjadi penurunan kesejahteraan.
Sebaliknya, tidak jarang rapat kebijakan dimulai dengan paparan data 20 slide, tetapi ditutup dengan satu kalimat penentu: “di lapangan rasanya tidak seperti itu”. Pada titik itu, data berubah fungsi dari alat analisis menjadi sekadar ornamen presentasi.
Dalam pengalaman penulis sendiri, paradoks kepemimpinan berbasis data justru terasa sangat nyata. Suatu kali, penulis terlibat dalam pengembangan aplikasi Makarti 5.0, sebuah aplikasi visualisasi dalam bentuk dashboard kinerja SKP transformasional yang menampilkan capaian unit kerja—mulai dari aspek branding, inovasi, networking, hingga learning. Secara konseptual, dashboard ini dirancang untuk membantu pimpinan membaca kinerja organisasi secara lebih utuh dan merumuskan arah pengembangan yang lebih strategis.
Namun yang terjadi justru cukup ironis. Alih-alih mendiskusikan pola kinerja yang muncul dari data—misalnya unit mana yang unggul dalam inovasi, unit mana yang lemah dalam kolaborasi, atau area mana yang perlu diperkuat—fokus utama pimpinan justru pada satu hal: unit kerja mana yang belum mengisi data. Perhatian bergeser dari membaca makna data menjadi memastikan kepatuhan pengisian.
Momen itu menyadarkan satu hal penting: persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya sistem, melainkan pada cara berpikir terhadap data itu sendiri. Ketika data dipahami semata sebagai kewajiban administratif, dashboard secanggih apa pun tidak akan pernah benar-benar menjadi alat pengambilan keputusan. Ia hanya berubah menjadi instrumen kontrol, bukan instrumen pembelajaran organisasi.
Situasi semacam ini menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan berbasis data bukan terletak pada ketersediaan informasi, melainkan pada distribusi kapasitas berpikir. Struktur organisasi tetap hierarkis, tetapi proses berpikir justru terbalik: yang memahami realitas berada di bawah, sementara yang memegang otoritas keputusan berada di atas, tanpa cukup literasi untuk menafsirkan realitas tersebut secara mandiri.
Fenomena serupa juga terlihat dalam praktik manajemen talenta birokrasi, misalnya dalam proses pemilihan pejabat melalui Baperjakat. Idealnya, proses ini berbasis pada data kinerja, rekam jejak, hasil asesmen kompetensi, serta pemetaan potensi seperti nine box talent matrix. Namun dalam praktiknya, keputusan sering kali lebih dipengaruhi oleh persepsi subjektif, aduan informal, atau narasi personal yang sulit diverifikasi secara data.
Di titik inilah literasi data kepemimpinan menjadi krusial. Tanpa kemampuan membaca dan mempercayai data secara kritis, instrumen-instrumen manajemen ASN yang berbasis sistem—mulai dari e-kinerja, talent pool, hingga asesmen kompetensi—berisiko hanya menjadi ritual administratif. Sistem sudah dibangun, indikator sudah tersedia, tetapi keputusan strategis tetap berjalan dengan logika lama: intuisi, kedekatan, dan kompromi kekuasaan.
Pada akhirnya, negara berbasis data akan selalu gagal jika dipimpin oleh elite yang lebih percaya pada intuisi daripada evidensi. Transformasi digital tanpa transformasi cara berpikir hanya akan melahirkan birokrasi yang tampak modern di layar, tetapi feodal di ruang rapat. Dan di situlah, diklat kepemimpinan ASN seharusnya tidak lagi sekadar mencetak pejabat yang patuh prosedur, melainkan pemimpin yang mampu berpikir jernih di tengah banjir data.